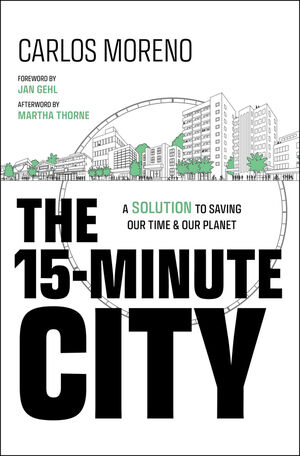Sustainability 17A #49
5 Juni 2024
Perayaan yang Muram,
Bagi Bumi yang Lebam
Dwi R. Muhtaman,
sustainability partner
We are Generation Restoration.
Together, let’s build a sustainable future
for land, and for humanity.
–António Guterres
Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, 5 Juni 2024, adalah “Restorasi Lahan, Penggurunan, dan Ketahanan terhadap Kekeringan.”
António Guterres, Sekjen PBB dalam pesan lingkungannya mengatakan, “Kemanusiaan bergantung pada tanah. Namun, di seluruh dunia, dampak buruk polusi, kekacauan iklim, dan musnahnya keanekaragaman hayati telah mengubah lahan sehat menjadi gurun, dan ekosistem yang subur menjadi zona mati.” Inilah potret bumi kita hari ini dalam 52 tahun terakhir ini sejak Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kalinya dicanangkan, 1972 di Swedia pada acara Stockholm Conference on Human Environment. Pada saat yang bersamaan sebuah resolusi yang diadopsi The UN General Assembly untuk pembentukan UNEP (United Nations Environmental Programme).
Kecemasan atas nasib bumi ini juga tercermin dari Overshoot Day 2024. Tanggal 1 Agustus 2024 menandai Hari Overshoot Bumi tahun ini. Artinya, mulai tanggal 1 Januari hingga 1 Agustus, umat manusia telah menggunakan sumber daya alam sebanyak yang dapat diperbarui oleh ekosistem bumi sepanjang tahun ini, berdasarkan perhitungan terbaru dari Global Footprint Network. Dengan kata lain, hanya dalam 7 bulan, umat manusia menggunakan waktu yang dibutuhkan Bumi untuk beregenerasi selama 12 bulan.
David Lin, Direktur Sains Global Footprint Network, menekankan bahwa: Terus menerus terjadi overshoot, selama lebih dari setengah abad, telah menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, kelebihan gas rumah kaca di atmosfer, dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pangan dan energi. Gejalanya menjadi lebih nyata dengan adanya gelombang panas yang tidak biasa, kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir. Pada 2023 Umat manusia 8.1 milyar orang) membutuhkan barang dan jasa dari alam sekitar 20,8 miliar hektar global untuk memperbaruinya. Jumlah ini lebih dari 12,2 miliar hektar global kawasan produktif biologis (atau biokapasitas/bio-capacity) yang tersedia di planet ini. Permintaan yang berlebihan berarti bahwa umat manusia saat ini menggunakan 1,7 kali lebih banyak dari jumlah yang diperbarui oleh biosfer saat ini. Beberapa orang menggambarkan tingkat konsumsi ini sebagai penggunaan 1,7 Bumi. Untuk menjaga keanekaragaman hayati dan iklim yang kuat, para ahli ekologi memperkirakan bahwa kebutuhan manusia tidak boleh lebih dari setengah kapasitas hayati yang ada di Bumi, atau 3 kali lebih sedikit dari kebutuhan saat ini. Tetapi kenyataannya tidak. Kita telah menggunakan sumberdaya bumi dari tahun ke tahun selalu melebihi apa yang tersedia.
Bahkan dalam hal mengurangi emisi karbon “Negara-negara G-7 secara besar-besaran memperluas produksi bahan bakar fosil di dalam negeri dan menginvestasikan miliaran dolar untuk lebih banyak infrastruktur bahan bakar fosil di luar negeri,” kata organisasi advokasi Oil Change International dalam sebuah laporan.
Laporan ini muncul menjelang pertemuan puncak tahunan ke-50 Kelompok Tujuh (G7) pada minggu depan, di mana kepala negara dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat akan bertemu untuk membahas isu-isu yang kemungkinan besar mencakup perubahan iklim.
Pada bulan April, para menteri iklim, energi dan lingkungan hidup G-7 menyatakan keprihatinannya terhadap “tiga krisis” yang terdiri dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Mereka berjanji untuk melakukan upaya intensif untuk mengurangi permintaan dan penggunaan bahan bakar fosil, termasuk dengan meningkatkan teknologi ramah lingkungan secara cepat.
Namun Oil Change International mengklaim mereka tidak melakukan apa-apa dan terus mendanai pengembangan minyak dan gas. Mereka terlalu banyak omong daripada bertindak. Negara-negara berkembang, sebaliknya, menjadi sasaran tuduhan kerusakan sumberdaya alam dan harus tunduk pada kebijakan global untuk melindungi hutan dan mengurangi emisi.
Perubahan iklim yang jangkauan dampaknya jangka panjang tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Negara-negara kaya harus bertanggungjawab atas perubahan iklim saat ini yang dihadapi dunia. Termasuk juga adanya perbedaan dalam kemampuan menghadapi kerentanan antara penghasil emisi tertinggi dan terendah. Laurie Parsons (2023) dalam bukunya membandingkan perbedaan itu seperti ‘perokok pasif’ karena kemampuannya dalam menimbulkan dampak buruk pada mereka yang tidak ada hubungannya dengan perokok sebagai produksinya.
Mari kita periksa kembali tentang emisi. Perjanjian Paris tahun 2016 merupakan hasil dari proses perjanjian jangka panjang. Serangkaian perjanjian internasional dilakukan untuk mebatasi emisi yang berbahaya. Dari Konferensi Iklim Dunia yang pertama pada tahun 1979, melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 1992, Kyoto pada tahun 1999, Kopenhagen pada tahun 2009, dan terakhir Paris pada tahun 2016, perjanjian menjadi lebih spesifik bersifat spesifik dan mengikat seiring berjalannya waktu. Namun pada saat yang sama, konsentrasi CO2 di atmosfer terus meningkat.
Dengan mengutip berbagai sumber, Parsons menguraikan bahwa pada saat Konferensi Iklim Dunia pertama, CO2 di atmosfer tetap ada pada 339 bagian per juta; pada saat pendirian UNFCCC, 13 tahun kemudian, jumlahnya menjadi 358. Saat kembang api booming di Paris, jumlahnya menjadi 402 bagian per juta; dan hari ini berada di 421. Kurangnya dampak yang dicapai oleh berbagai perjanjian ini telah menimbulkan sesuatu yang membingungkan bagi penggiat lingkungan hidup. Setiap pertemuan, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, memiliki kerangka kerja dan kebijakan yang disepakati oleh negara-negara dengan emisi terberat di dunia, negara-negara yang diharapkan dapat mengurangi emisi karbon. Memang, data menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, berdampak pada berkurangnya emisi. Emisi bersih UE turun 5,6 miliar ton CO2 pada tahun 1990 menjadi 4,2 miliar pada tahun 2018, sementara klaim Inggris – yang secara historis merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di Uni Eropa, pengurangan emisi sebesar 44 persen sejak tahun 1990.
Bahkan Amerika Serikat, negara yang upayanya dianggap ‘sangat tidak memadai’ oleh para pemantau, telah mencapai sedikit penurunan, dari 7,1 miliar ton pada tahun 1998 menjadi 6,7 miliar saat ini. Tiongkok, salah satu penghasil karbon terbesar dan paling pesat pertumbuhan-nya di dunia beberapa dekade terakhir, telah mulai memperlambat laju peningkatan, dengan emisi diproyeksikan akan stabil selama lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya rencana nasional untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.
“Lalu, apa yang melatarbelakangi kesenjangan ini?,” tanya Parsons. Rupanya ini disebabkan oleh tatacara penghitungan emisi. Emisi dari negara-negara besar sedang turun atau stabil, namun peningkatan emisi karbon global yang tiada henti terus berlanjut, tanpa berkurang. Apakah para penghasil emisi besar tidak jujur mengenai emisi mereka? “Tidak dalam arti langsung,” tulisnya. Sebaliknya, ini adalah pengurangan diri mereka sendiri yang bersifat ilusi. Produk dari sistem karbon akuntansi yang tetap bersifat nasional dan terbatas di dalam dunia yang semakin global dan saling terhubung.
Sederhananya ketika negara-negara kaya semakin mengurangi pangsa mereka dalam industri global, melakukan outsourcing (pengalihdayaan) dengan margin yang lebih rendah dan peningkatan proses yang berdampak buruk pada lingkungan hidup di negara-negara Selatan, maka emisi yang terkait dengan proses-proses tersebut – bukan merupakan bagian emisi negara-negara maju itu.
Secara total, emisi impor – emisi yang terjadi di negara selain tempat penggunaannya – sekarang diperhitungkan sejumlah seperempat emisi CO2 global, sebuah angka skala kemampuan negara-negara kaya untuk menghilangkan emisi dari catatan lingkungan hidup mereka. Bahkan ada istilah menarik untuk praktik seperti ini.
Kemampuan untuk secara efektif melakukan outsourcing emisi dari negara kaya ke negara-negara miskin digambarkan sebagai ‘carbon colonialism’ (kolonialisme karbon): sebuah istilah yang menekankan hubungan kekuasaan historis yang mendasari pin akuntansi karbon. Negara-negara yang lebih kaya, sangat banyak bertanggung jawab atas perubahan iklim baik secara historis maupun saat ini, telah menetapkan ketentuan mitigasi karbon di meja perundingan.
Tentu saja, istilah-istilah ini menguntungkan penghasil emisi terbesar, sehingga memungkinkan
negara-negara besar ke proses produksi lepas pantai ke negara-negara yang lebih kecil yang lain, sambil mempertahankan hasil ekonomi dari produksi tersebut. Skala outsourcing ini sangat besar, dalam beberapa kasus sepenuhnya melemahkan klaim nasional terhadap kemajuan pengelolaan lingkungan hidup.
Ambil contoh di Inggris. Ini adalah negara yang berhasil dalam kepemimpinan hijau globalnya, seperti yang dicontohkan oleh angka pengurangan emisi karbon sebesar 44 persen yang selalu ada sejak tahun 1990. Namun, jika kita melihat gambaran yang lebih besar, sebagian besar capaian ini hilang. Nilai impor Inggris mencapai lebih dari dua kali lipat dalam dua dekade terakhir, dengan peraturan lingkungan hidup Eksportir UE menyumbang proporsi yang menurun dari jumlah tersebut.
Dengan banyaknya produksi Inggris yang kini dilakukan di luar negeri perbatasan kita, semakin banyak karbon yang digunakan orang-orang Inggris setiap hari malah dipindahkan dan ditambahkan ke dalam anggaran karbon negara lain, bukan anggaran Inggris sendiri.
Demikianlah bumi kita saat ini. Negara-negara maju yang secara historis telah menghancurkan sumberdaya alam dan menimpakan beban pemulihannya pada negara maju. Sementara mereka tetap melanjutkan praktek-praktek buruknya dengan cara-cara yang baru.
Dari sisi pangan kita mengalami kecemasan sejak lama. Lester R. Brown dalam bukunya Full Planet, Empty Plates menuliskan: “Antara tahun 2007 dan pertengahan tahun 2008, harga biji-bijian dan kedelai dunia meningkat lebih dari dua kali lipat. Ketika harga pangan naik di mana-mana, beberapa negara pengekspor mulai membatasi pengiriman biji-bijian dalam upaya membatasi inflasi harga pangan di dalam negeri. Negara-negara pengimpor panik. Beberapa pihak mencoba menegosiasikan perjanjian pasokan biji-bijian jangka panjang dengan negara-negara pengekspor, namun di pasar penjual, hanya sedikit yang berhasil. Tampaknya dalam sekejap, negara-negara pengimpor menyadari bahwa salah satu dari sedikit pilihan mereka adalah mencari lahan di negara lain untuk memproduksi pangan bagi mereka sendiri.”
Mencari tanah di luar negeri bukanlah hal baru. Imperialis berkembang melalui akuisisi teritorial, dan kekuasaan kolonial mendirikan perkebunan, dan perusahaan agribisnis mencoba memperluas jangkauan mereka. Analis pertanian Derek Byerlee yang dikutip Brown, menelusuri investasi yang didorong oleh pasar pada lahan asing sejak pertengahan abad kesembilan belas. Selama 150 tahun terakhir, investasi pertanian skala besar dari negara-negara industri terkonsentrasi terutama pada produk-produk tropis seperti tebu, teh, karet, dan pisang.
“Yang baru saat ini adalah perebutan lahan di luar negeri untuk mendapatkan lebih banyak bahan pangan pokok dan tanaman pakan ternak—termasuk gandum, beras, jagung, dan kedelai—dan untuk biofuel. Akuisisi lahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, atau sering disebut dengan “perampasan lahan/land grab”, mewakili tahap baru dalam munculnya geopolitik kelangkaan pangan. Hal ini terjadi dalam skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Menurut FAO dalam The State of Food and Agriculture 2023 “Sistem pangan pertanian menghasilkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, termasuk pangan yang menyehatkan kita serta lapangan kerja dan penghidupan bagi lebih dari satu miliar orang. Namun, dampak negatifnya akibat aktivitas dan praktik bisnis seperti biasa yang tidak berkelanjutan berkontribusi terhadap perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan tidak terjangkaunya pola makan sehat. Mengatasi dampak negatif ini merupakan suatu tantangan, karena masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya tidak memiliki gambaran lengkap tentang bagaimana aktivitas mereka mempengaruhi kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan ketika mereka mengambil keputusan sehari-hari.” Edisi The State of Food and Agriculture kali ini berfokus pada dampak sebenarnya dari sistem pertanian pangan. Dengan memperkenalkan konsep biaya dan manfaat tersembunyi dari sistem pangan pertanian dan memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai hal ini, laporan ini bertujuan untuk memulai suatu proses yang akan lebih mempersiapkan para pengambil keputusan dalam mengambil tindakan untuk mengarahkan sistem pangan pertanian ke arah lingkungan, sosial dan ekonomi. keberlanjutan.
The 2024 Environmental Performance Index (EPI) menegaskan keprihatinan yang mendalam tentang kesehatan tubuh bumi kita. Pada siaran pers yang diterbitkan bersamaan dengan peluncuran EPI 2024 itu disebutkan: Semakin banyak bukti yang menyoroti degradasi sistem pendukung kehidupan di planet ini yang menjadi sandaran umat manusia. Perekonomian dunia yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil mengakibatkan polusi udara dan air yang terus berlanjut, pengasaman lautan, dan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Perubahan-perubahan ini mengancam kelangsungan hidup spesies yang sudah menderita akibat hilangnya habitat secara luas, dan mendorong mereka semakin dekat dengan kepunahan. Analisis terbaru menunjukkan bahwa umat manusia telah melampaui enam dari sembilan batas planet (Planet Boundary) yang menentukan ruang aman bagi bumi untuk beroperasi – dan hampir melewati batas ketujuh.
Disebutkan pula bahwa sebenarnya ada secercah harapan ketika pada tahun 2022, pada COP 15 di Montreal, lebih dari 190 negara membuat apa yang disebut sebagai “komitmen konservasi terbesar yang pernah ada di dunia.” Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal menyerukan perlindungan dan pengelolaan yang efektif terhadap 30% daratan, perairan pedalaman, serta wilayah pesisir dan laut dunia pada tahun 2030 – yang umumnya dikenal sebagai target 30×30. Meskipun terdapat kemajuan dalam mencapai tujuan ambisius untuk melindungi 30% daratan dan lautan di atas kertas, Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) 2024 yang dirilis ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perlindungan tersebut gagal menghentikan hilangnya ekosistem atau mengurangi praktik-praktik yang merusak lingkungan.
Sebuah metrik baru yang menilai seberapa baik negara-negara melindungi ekosistem penting menunjukkan bahwa meskipun negara-negara telah mencapai kemajuan dalam melindungi daratan dan lautan, banyak dari wilayah tersebut merupakan “taman kertas” di mana aktivitas komersial seperti pertambangan dan pukat terus dilakukan – terkadang pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan di kawasan yang tidak dilindungi. Analisis EPI menunjukkan bahwa di 23 negara, lebih dari 10 % lahan yang dilindungi ditutupi oleh lahan pertanian dan bangunan, dan di 35 negara terdapat lebih banyak aktivitas penangkapan ikan di dalam kawasan perlindungan laut dibandingkan di luar kawasan perlindungan laut.
EPI juga menemukan bahwa banyak negara yang memimpin tujuan keberlanjutan telah tertinggal atau terhenti. Hal ini menggambarkan tantangan pengurangan emisi di industri yang sulit melakukan dekarbonisasi dan sektor yang resisten seperti pertanian. Di beberapa negara, penurunan emisi rumah kaca pertanian baru-baru ini disebabkan oleh kondisi eksternal, bukan kebijakan. Misalnya, di Albania, gangguan rantai pasok menyebabkan harga pakan ternak menjadi lebih mahal sehingga mengakibatkan penurunan tajam jumlah sapi dan, akibatnya, emisi dinitrogen oksida dan metana.
“Indeks Kinerja Lingkungan tahun 2024 menyoroti serangkaian tantangan keberlanjutan yang penting mulai dari perubahan iklim hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan seterusnya – dan mengungkapkan tren yang menunjukkan bahwa negara-negara di seluruh dunia perlu melipatgandakan upaya mereka untuk melindungi ekosistem penting dan vitalitas planet kita,” kata Daniel Esty, Profesor Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hillhouse dan direktur YCELP (Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University).
Indonesia pada tingkat global menduduki peringkat 162 (dari 180 negara) dengan skor 33.8 (dari 100). Sementara itu pada tingkat regional Indonesia menduduki peringkat nomor 20 dari (dari 25 negara) di bawah China yang menduduki peringkat 19 dan jauh di bawah Jepang yang bercokol pada peringkat 1. Bahkan pada indikator Environmental Health, Indonesia hanya menduduki peringkat 22 dengan skor 25.7.
Pada indikator Climate Change, Indonesia di tingkat regional mendapatkan skor 32.1 pada peringkat 20, sedangkan pada tingkat global lumayan membaik pada peringkat 143. Peringkat ini hanya lebih baik sedikit dari indikator Ecosystem Vitality, pada peringkat 144 pada tingkat global. Sedangkan pada tingkat regional skor Ecosystem Vitality Indonesia masih cukup baik pada peringkat 13 dengan skor 39.3.
Pekerjaan rumah kita masih sangat banyak dan berat.
Kita memusnahkan hutan dan padang rumput, serta melemahkan kekuatan lahan untuk mendukung ekosistem, pertanian, dan masyarakat. Akibatnya para petani gagal panen, kita kehilangan sumber air, perekonomian melemah, dan masyarakat terancam – dan kelompok masyarakat termiskinlah yang paling terkena dampaknya, demikian tulis Guteres.
“Karena degradasi lahan dan penggurunan berdampak pada lebih dari tiga miliar orang. Ekosistem air tawar juga terdegradasi, sehingga semakin sulit bercocok tanam dan beternak.
Hal ini secara tidak proporsional berdampak pada petani kecil dan, tentu saja, masyarakat miskin pedesaan,” tulis UNEP Executive Director Inger Andersen dalam pesannya pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Pembangunan berkelanjutan kini menjadi sebuah penderitaan. Dan kita terjebak dalam siklus yang mematikan – penggunaan lahan bertanggung jawab atas sebelas persen emisi karbon dioksida yang memanaskan planet kita. Karena itu, demikian kata Sekjen PBB yang merupakan diplomat dan politisi Portugal dan Perdana Menteri Portugal periode 1995 to 2002 ini, saatnya untuk membebaskan diri–sesuatu yang secara retorika telah menjadi klise tetapi pada kenyataannya begitu sulit dilakukan. Bumi yang makin buruk adalah cermin kegagalan dalam membebaskan diri.
Tentu saja “Negara-negara harus memenuhi seluruh komitmen mereka untuk memulihkan ekosistem dan lahan yang terdegradasi, dan seluruh Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Mereka harus menggunakan rencana aksi iklim nasional mereka yang baru untuk menentukan bagaimana mereka akan menghentikan dan membalikkan deforestasi pada tahun 2030. Dan kita harus secara drastis meningkatkan pendanaan untuk mendukung negara-negara berkembang beradaptasi terhadap cuaca buruk, melindungi alam, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.”
Menurut Andersen, yang menyuarakan rasa optimis, dengan memulihkan ekosistem, kita dapat memperlambat tiga krisis yang terjadi di planet ini: krisis perubahan iklim, krisis alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, termasuk penggurunan, serta krisis polusi dan limbah. Kami dapat membantu membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030, sejalan dengan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global. Dan kita bisa membatasi kenaikan suhu global sesuai dengan Perjanjian Paris dengan meningkatkan penyimpanan karbon, termasuk di lahan gambut. Dan kita dapat mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan, sejalan dengan SDGs.
Namun berbagai peristiwa buruk yang dimulai dengan pandemi the coronavirus disease (COVID-19) perang Ukraina dan juga penjajahan yang tiada henti di tanah air Palestina memaksa kita untuk “Saatnya membunyikan alarm.” Menurut penilaian Sustainable Development Report (2023), pada pertengahan menuju tahun 2030, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berada dalam masalah besar. Penilaian terhadap sekitar 140 target yang data trennya tersedia menunjukkan bahwa sekitar setengahnya dari target itu tidak tercapai. Dan lebih dari 30% hanya stagnan atau malah turun di bawah baseline 2015.
Kita tidak bisa terus melakukan hal yang sama yang terbukti buruk dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kita tidak bisa bertahan dengan sistem keuangan yang bangkrut secara moral dan mengharapkan negara-negara berkembang untuk memenuhi target yang telah dicapai negara-negara maju dengan kendala yang jauh lebih sedikit.
Agenda 2030 menyatakan bahwa generasi saat ini akan mampu menjadi generasi pertama yang berhasil mengentaskan kemiskinan – dan menjadi orang terakhir yang mempunyai peluang untuk menyelamatkan bumi. Meski nampak sebuah harapan yang berlebihan, namun hanya harapan itulah yang akan menjadi tantangan untuk menghadapi segala penghambat mencapaian Agenda 2030. Diperlukan upaya yang terus menerus baik oleh masing-masing Pemerintah, non pemerintah, swasta dan berbagai stakeholders di seluruh komunitas internasional dan aliansi global. Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan kerjasama di bidang bisnis, masyarakat sipil, ilmu pengetahuan, generasi muda, otoritas lokal, dan banyak lagi.
Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global dan pembelajaran sejak tahun 2015, laporan ini mengidentifikasi serangkaian tindakan mendesak yang perlu dipertimbangkan dalam lima bidang utama.
Berdasarkan tren yang ada saat ini, 575 juta orang masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030, dan hanya sekitar sepertiga negara yang mampu memenuhi target pengurangan separuh tingkat kemiskinan nasional. Yang mengejutkan, dunia kembali mengalami tingkat kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 2005, dan harga pangan di banyak negara tetap lebih tinggi dibandingkan periode 2015–2019. Saat ini, diperlukan waktu 286 tahun untuk menutup kesenjangan gender dalam perlindungan hukum dan menghapus undang-undang yang diskriminatif. Dan di bidang pendidikan, dampak dari kurangnya investasi dan hilangnya pembelajaran selama bertahun-tahun sedemikian rupa sehingga, pada tahun 2030, sekitar 84 juta anak akan putus sekolah dan 300 juta anak atau remaja yang bersekolah tidak akan mampu membaca dan menulis.
Berdiam diri tanpa aksi justru akan menimbulkan biaya yang jauh lebih mahal. Padahal jangka panjang tindakan kini yang cepat dan tepat justru masuk akal secara ekonomi. Tetapi perubahan yang drastis memerlukan kepemimpinan yang radikal dan komitmen kuat untuk dilaksanakan. Menurut Guteres, setiap dolar yang diinvestasikan dalam restorasi ekosistem menghasilkan manfaat ekonomi hingga tiga puluh dolar.
Pesan Guteres: “Kami adalah Generasi Restorasi. Bersama-sama, mari kita membangun masa depan yang berkelanjutan bagi lahan dan umat manusia.”
Tapi alam tangguh.
Dengan memulihkan ekosistem, kita dapat memperlambat tiga krisis yang terjadi di planet ini: krisis perubahan iklim, krisis alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, termasuk penggurunan, serta krisis polusi dan limbah. Restorasi lahan dapat menjadi benang emas yang menyatukan hal-hal tersebut, menyatukan tindakan dan ambisi di ketiga pertemuan penting ini.
Tanah kami adalah masa depan kami.
Dan kita harus melindunginya.
Retorika selalu baik. Melaksanakannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Inilah tantangan terbesar. Bicara itu mudah.
“Hanya perubahan besar dalam pemikiran moral, dengan komitmen yang lebih besar yang diberikan pada sisa hidup, yang dapat menjawab tantangan terbesar abad ini,” tulis naturalis Edward O. Wilson pada buku Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life. Pesan Wilson bagi kita adalah bahwa “Wildlands adalah tempat kelahiran kita. Peradaban kita dibangun dari mereka. Makanan kita dan sebagian besar tempat tinggal serta kendaraan kita berasal dari mereka. Dewa-dewa kita tinggal di tengah-tengah mereka. Alam di alam liar adalah hak asasi semua orang di Bumi. Jutaan spesies yang kita biarkan bertahan hidup di sana, namun terus terancam, adalah kerabat filogenetik kita. Sejarah jangka panjang mereka adalah sejarah jangka panjang kita. Terlepas dari semua kepura-puraan dan khayalan kita, kita selalu dan akan tetap menjadi spesies biologis yang terikat pada dunia biologis tertentu. Evolusi jutaan tahun tersimpan secara tak terhapuskan dalam gen kita. Sejarah tanpa alam liar bukanlah sejarah sama sekali.”
Kita tidak ingin mengalami perayaan yang muram bagi bumi yang lebam. Karena itu dalam rangka merenungkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini ada baiknya “..kita harus selalu ingat bahwa dunia indah yang diwarisi spesies kita membutuhkan waktu 3,8 miliar tahun untuk membangun biosfer. Kita hanya mengetahui sebagian kerumitan spesiesnya, dan cara mereka bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan berkelanjutan yang baru mulai kita pahami. Suka atau tidak, dan siap atau tidak, kita adalah pikiran dan pengelola dunia kehidupan. Masa depan akhir kita bergantung pada pemahaman itu. Kita telah menempuh perjalanan yang sangat jauh melalui masa barbar yang masih kita jalani, dan sekarang saya yakin kita telah cukup belajar untuk mengadopsi ajaran moral yang transenden mengenai sisa hidup. Sederhana dan mudah untuk mengatakan: Jangan melakukan kerusakan lebih lanjut terhadap biosfer.”