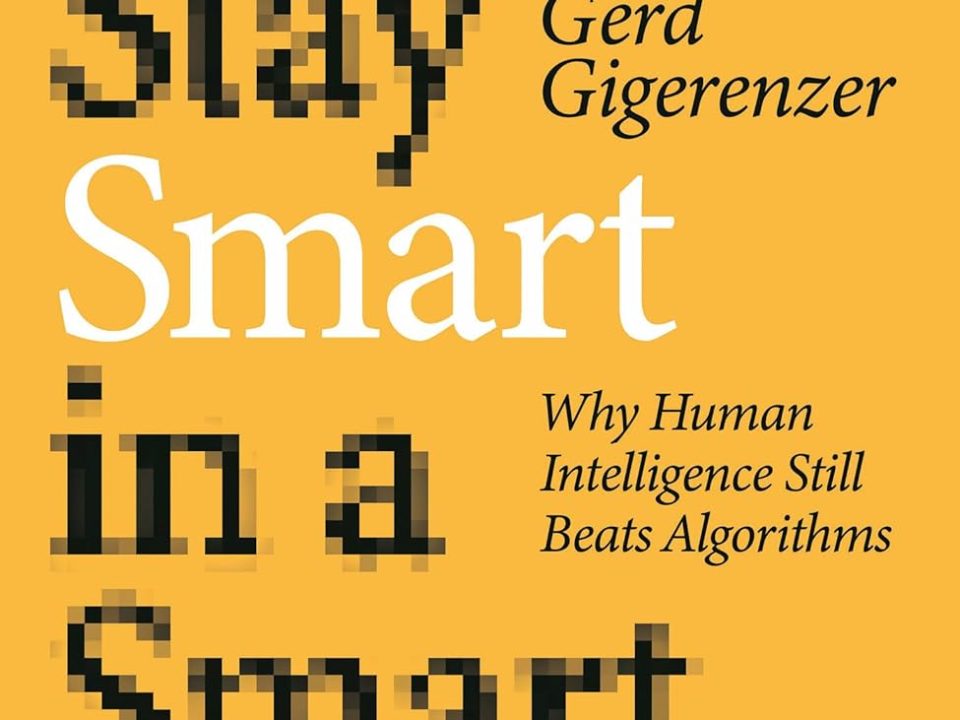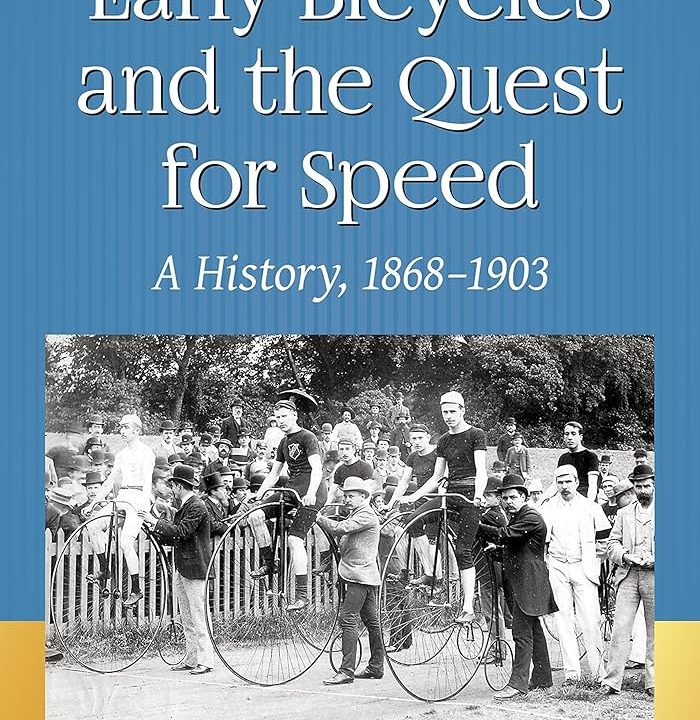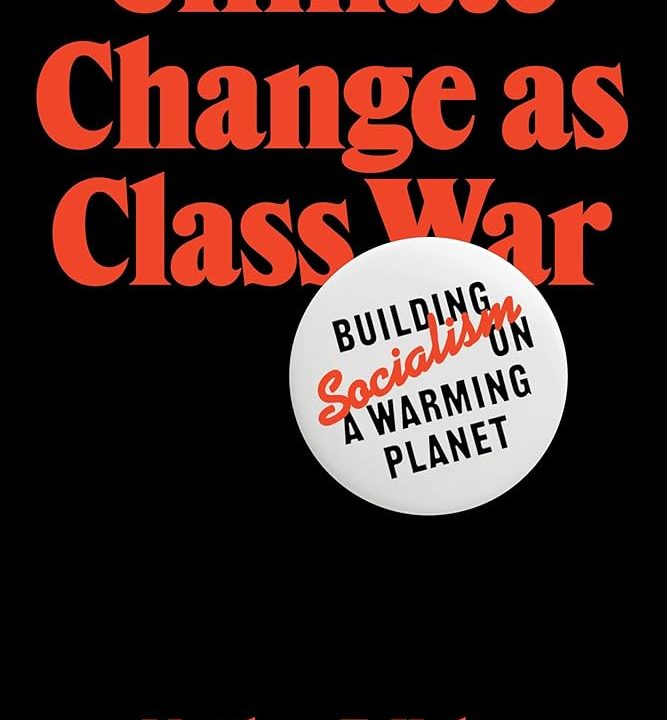Rubarubu #11
Melawan Penjajahan Iklim Menuju Keadilan Iklim
Pada suatu pagi pasang tinggi melanda desa pesisir — air asin menyusup ke sumur, ladang menjadi payau, dan perahu yang dulu menopang keluarga kini kosong karena ikan berpindah jauh. Di sebuah pertemuan komunitas, seorang perempuan tua berkata bahwa tanah nenek-moyang mereka terasa “diambil lagi”: pertama oleh penjajah, kini oleh kebijakan dan pasar yang menganggarkan alam sebagai komoditas — ia meratapi bukan sekadar kehilangan lahan, melainkan kehilangan cara hidup dan suara dalam pengambilan keputusan. Kisah ini menangkap inti yang digarisbawahi di awal buku Confronting Climate Coloniality: Decolonizing Pathways for Climate Justice (ed. Farhana Sultana): bahwa krisis iklim bukan hanya masalah atmosfer atau emisi, melainkan sebuah kelanjutan historis dari kolonialitas—struktur kuasa, ekonomi, epistemik, dan kegawatan yang memposisikan sebagian dunia sebagai yang boleh dieksploitasi dan dibuang. Farhana Sultana membuka koleksi ini dengan nada mendesak: climate coloniality menimbang hidup manusia dan bumi, dan panggilan dekolonisasi adalah panggilan untuk rekonstruksi etis-politik. Routledge+1
Confronting Climate Coloniality dimulai dengan pemaparan kerangka teori dengan menempat-kan climate coloniality sebagai konsep sentral: bukan hanya warisan kolonial formal tetapi praktik kontemporer (neoliberalisme, kapitalisme rasial, penjarahan sumber daya, penghapus-an hak-hak masyarakat adat) yang memperparah ketidakadilan iklim. Kontributor di bagian ini memetakan bagaimana wacana internasional — dari mekanisme offset karbon sampai agenda ‘green growth’ — mereproduksi ketidak-seimbangan historis dengan menyamarkan hutang iklim Utara ke Selatan dan mengeksklusi pengetahuan lokal. Penekanan utama adalah dua macam ketidakadilan: material (kehilangan tanah, akses terhadap sumber daya, risiko bencana) dan epistemik (pengabaian pengetahuan lokal, marginalisasi suara yang terdampak). Sultana dan rekan menekankan bahwa dekolonisasi bukan hanya menambah representasi tetapi merombak struktur pengetahuan, institusi, dan hak atas keputusan. Routledge+1
Climate coloniality sebagai struktur historis dan institusional yang terus mereproduksi ketidakadilan iklim. Pembukaan Farhana Sultana (preface & bab pengantar) menegaskan bahwa isu iklim tidak sekadar teknis; ia adalah produk hubungan kuasa yang berakar pada kolonialisme, imperialisme, kapitalisme rasial, dan patriarki—yang semuanya membentuk kebijakan, lembaga internasional (seperti UNFCCC), dan pasar iklim.
Konsep Climate apartheid—ide bahwa distribusi dampak dan perlindungan iklim mengikuti garis kolonial dan rasial—dengan praktik kontemporer yang menormalisasi eksklusi pasti ada hubungannya. Joshua Long (Bab 2: The Coloniality of Climate Apartheid) menelusuri bagaimana kebijakan pembangunan dan diskursus ‘resilience’ sering mereduksi komunitas yang rentan menjadi objek intervensi, bukan subjek berdaulat. Intinya: tanpa pengakuan hak, redistribusi, dan mekanisme reparatif, kebijakan iklim akan terus menciptakan “zona expendable” yang mirip dengan logika kolonial. Ini menempatkan konsep apartheid iklim sebagai alat analitis untuk mengkritik kebijakan internasional yang tampak netral. Routledge+1
Jamie Haverkamp (Bab 3: The De/Coloniality of Global Climate Governance and Indigenous Politics within the UNFCCC) membedah UNFCCC dan arena diplomasi iklim: meskipun ada peningkatan representasi masyarakat adat, struktur prosedural dan relasi kuasa tetap mereproduksi ketergantungan. Haverkamp menunjukkan titik-titik di mana partisipasi simbolis (tokenism) menggantikan kewenangan nyata—mis. menjadi penasihat tanpa akses ke agenda-setting, atau dimasukkan di bawah mekanisme sukarela yang mengabaikan hak-hak kolektif. Ia menuntut pengakuan institusional yang lebih kuat atas kedaulatan adat dan penyesuaian aturan internasional yang selama ini menguntungkan negara dan entitas kaya. (Bab tersedia secara ringkasan di platform penerbit). Taylor & Francis+1
Ketergantungan yang mendarah daging pada bahan bakar fosil telah melahirkan apa yang disebut Bernardo Jurema dan Elias König sebagai fossil imperialism. Bab 4: State Power and Capital in the Climate Crisis: A Theory of Fossil Imperialism) merek amemperkenalkan istilah itu.
Dijelaskaan konsepual yang menautkan kapasitas negara-negara industri dan korporasi besar untuk mengekspor eksternalitas (emisi, degradasi, risiko) ke wilayah Global South sambil mempertahankan akses ke sumber daya. Mereka menekankan interplay antara kekuatan negara, modal finansial, dan struktur geopolitik yang memungkinkan model pertumbuhan berbasis fosil bertahan—meskipun secara ekologis destruktif. Implikasi kebijakan: perlu pembongkaran rantai akumulasi yang menguntungkan aktor-aktor ini, bukan sekadar pajak karbon atau offset yang memperkuat status quo. Taylor & Francis+1
Pemikiran ini bisa ditemukan pada Naomi Klein, Vandana Shiva, dan Amitav Ghosh—yang memberi pujian di halaman penerbit—yang menegaskan bahwa solusi teknis tanpa pertimbangan keadilan struktural berisiko menjadi “perpanjangan” kolonialisasi melalui pasar. Kutipan singkat dari Sultana (dari tulisan sebelumnya) menggarisbawahi: “international climate negotiations falter … without meaningfully reducing fossil fuel dependency, growth models, and hyper-consumption.” Ini menguatkan argumen Bagian I bahwa tata kelola iklim harus mengubah prioritas sistemik, bukan hanya memodifikasi instrumen yang ada. Routledge+1
Bagian II — Confronting and Decolonizing Climate Framings and Policies bergerak dari teori ke empiris: studi kasus lintas benua yang menunjukkan manifestasi climate coloniality dalam praktik—misalnya perampasan lahan untuk proyek ‘green’ atau infrastruktur, dampak kebijakan adaptasi/top-down yang mengabaikan hak masyarakat adat, dan bagaimana mekanisme internasional (seperti pasar karbon) sering menjadi alat baru akumulasi untuk aktor kuat. Kontributor menelaah kasus spesifik—dari wilayah pesisir, hutan hujan tropis, hingga tambang mineral kritis—menunjukkan pola yang sama: solusi teknokratik dan pasar yang diimpor menghapus konteks lokal dan menguntungkan kapital besar. Bagian ini juga menelusuri dimensi gender dan rasisme—bagaimana perempuan, komunitas etnis marginal, dan masyarakat nelayan menanggung beban paling berat. Bukti-bukti empirisnya memperkuat tuntutan agar kebijakan iklim menjadi redistributif, reparatif, dan berbasis partisipasi sejati. Routledge+1
Bagian II membahas bagaimana isu iklim dibingkai (framing) dan bagaimana kebijakan dibentuk — dari level lokal hingga global — lalu menunjukkan bagaimana framing-framing dominan sering memarginalkan pengetahuan lokal dan memperkuat solusi pasar. Bab-babnya me-nyodorkan bukti empiris dan kritik teoritis terhadap narasi yang tampak ‘netral’ namun sangat bernilai politik. (Garis besar di TOC Routledge). Routledge
Diren Valayden (Bab 5: The Politics of “Heaviness” in Climate Emergency) mengeksplorasi bagaimana retorika “darurat” bisa dipolitisasi: sementara narasi emergency memaksa tindakan cepat, ia juga dapat digunakan untuk membenarkan tindakan otoriter atau proyek-besar yang merampas lahan atas nama kecepatan adaptasi/mitigasi. Valayden memperingatkan bahwa bahasa darurat tanpa mekanisme pengawasan dan hak akan membiarkan masyarakat rentan semakin tak berdaya. (Argumen ini relevan dengan fenomena ‘fast-track’ pembangunan hijau). Routledge
Bilal Butt (Bab 6: Buying the Dead, Burying the Poor: Climate Change and Pastoral Drought Coping Strategies in East Africa) menyajikan studi kasus yang kuat: pasar mekanistik (mis. kompensasi/penjualan karbon) sering mengabaikan biaya sosial dari solusi yang tampak ekonomis. Dalam konteks pastoral di Afrika Timur, strategi adaptasi yang diarahkan luar (donor/NGO) kerap memaksakan model sedentary, mengikis cara hidup nomadik dan sumber mata pencaharian tradisional—mengilustrasikan bagaimana ‘solusi’ global merusak struktur sosial lokal. Butt menunjukkan pentingnya solusi berbasis komunitas dan pengakuan terhadap strategi adaptasi lokal. Routledge
Aby L. Sène (Bab 7: Towards an African Epistemic Site for Biodiversity Conservation and Climate Action) mengusulkan pluralisasi epistemik: membangun ruang epistemik Afrika untuk konservasi dan aksi iklim—bukan sekadar menerjemahkan pengetahuan barat ke konteks Afrika. Sène menekankan nilai pengetahuan lokal, praktik tradisional, dan sistem moral komunitas dalam membentuk strategi konservasi yang adil dan efektif. Ini adalah argumen dekolonial yang menekankan rekonstruksi cara produksi pengetahuan dan penggunaan bukti ilmiah yang lebih inklusif. Routledge
“Blue carbon”—proyek karbon biru yang sering menjadi alat akumulasi dan kontrol atas wilayah pesisir dan laut mendapat perhatian Andrew Kalani Carlson (Bab 8: AlterNatives to Blue Carbon Coloniality: An ʻŌiwi Perspective on Redirecting Funding to Indigenous Stewardship). Dari perspektif ʻŌiwi (penduduk asli Hawaiʻi), Carlson menuntut alokasi dana yang mengutamakan steward lokal, pengakuan hak teritorial laut, dan mekanisme pendanaan yang tidak mengubah komunitas menjadi penyedia jasa karbon semata.
Carlson menekankan bahwa pandangan dunia dan sistem pengetahuan adat yang memungkin-kan pengelolaan sosial-ekologis berakar sangat dalam dan tidak dapat ditiru oleh orang atau organisasi non-adat yang berpura-pura menjadi sekutu yang berpikiran adil. Ini bukan sekadar kekhawatiran hipotetis, karena para pendatang terus memposisikan diri sebagai ahli dalam topik-topik adat, termasuk Pengetahuan Ekologis Tradisional. Di Hawaiʻi, hal ini termanifestasi sebagai perpanjangan dari kolonialisme pendatang Asia di mana sebagian ilmuwan biokultural terus memposisikan diri sebagai ahli pengetahuan dan budaya Kanaka ʻŌiwi, atau bahkan mengaburkan posisionalitas mereka sendiri untuk secara menipu menyiratkan bahwa mereka adalah Kanaka ʻŌiwi itu sendiri.
Sebagai gantinya, menurut Carlson, pendanaan untuk proyek-proyek Blue Carbon kolonial harus dialihkan ke akuakultur setempat sebagai alternatif praktis untuk kolonialitas iklim. Praktik akuakultur Pribumi dan budidaya pesisir telah bertahan dan sedang direvitalisasi, namun kolonialitas prioritas dan persyaratan pendanaan terus menjadi batasan utama bagi pemulihan lebih lanjut sistem sosial-ekologis yang berdaulat. Karena Blue Carbon dan layanan ekosistem lainnya harus dianggap sebagai manfaat bersama dari pengelolaan dan restorasi Pribumi, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi layanan ekosistem (MRV) tidak seharusnya menjadi persyaratan untuk menerima pendanaan.
Catatan terakhir Carlson sangat menarik. Ia mengingatkan kembali ʻōlelo noʻeau yang tentang meruntuhkan perlawanan, dikombinasikan dengan satu pepatah tradisional: “Nahā ka mākāhā, lele ka ʻupena,” “Jika pintu air [tambak] itu jebol, jaring pun segera diturunkan [untuk menangkap ikan yang lolos].” (Pukui 1983, ʻŌlelo Noʻeau 2088). Dari refleksi ini, ia menawarkan sebuah ʻōlelo noʻeau baru yang diturunkan untuk merangkum inti dari bab ini:
“Nahā ka pali paʻa, lele ka ʻāina”
“Pīpī holo kaʻao” (Pukui 1983,ʻŌlelo Noʻeau 2658).
“Begitu tembok tegak [kolonialitas iklim] pecah,
terpancarlah tanah dan air yang menghidupkan.”
Bab ini menyoroti bagaimana pendekatan karbon biru dapat direformulasi menjadi praktek yang menegakkan kedaulatan. Routledge
Kritik terhadap offsets, net-zero, dan mekanisme berbasis pasar datang dari banyak penulis (mis. Naomi Klein, Amitav Ghosh)—mereka memperingatkan bahwa tanpa perubahan struktural, mekanisme pasar hanya memindahkan tanggung jawab. Di ranah agama/etika, tokoh Muslim seperti Fazlun Khalid mengingatkan: konsep khalifah (stewardship) dan amanah dapat menjadi landasan moral untuk menolak ekstraksi semata dan menegakkan tanggung jawab kolektif terhadap ciptaan—suatu cara untuk menjembatani moral lokal/religius dengan tuntutan dekolonial terhadap kebijakan iklim. Routledge+1
Bagian III — Confronting and Decolonizing Climate Responses and Praxis mengusulkan pathways dekolonial—prinsip-prinsip dan strategi praktik yang memprioritaskan keadilan: reparasi (climate reparations), pengakuan hak tanah dan kedaulatan pangan, pluralisasi epistemik (mengangkat pengetahuan lokal/indigenous), pembatasan peran pasar dalam solusi iklim, dan pembuatan kebijakan yang berbasis hak serta partisipasi penuh kelompok yang terdampak. Kontributor mendesak perlunya solidaritas transnasional antara gerakan akar rumput Global South dan elemen progresif di Utara, serta reformasi lembaga internasional yang selama ini melegitimasi ketidaksetaraan. Buku ini menekankan bahwa transformasi memerlukan pendekatan multidimensi—hukum, ekonomi, kultural, dan epistemik—bukan sekadar koreksi teknis atau funding tambahan. Routledge+1
Bagian III berfokus pada praktik, resistensi, dan upaya di lapangan—bagaimana orang-orang, komunitas, dan gerakan menentang praktik kolonial iklim dan merancang alternatif. Di sini kita menemukan analisis tentang performative environmentalism, resistensi teritorial, rasisme dalam risiko banjir, dan transformasi energi di wilayah poskolonial. Bab-babnya memberi contoh konkret strategi praktik dan tantangan implementasi. (TOC dan bab akhir/afterword oleh Mimi Sheller menutup rangkaian). Routledge
Manisha Anantharaman (Bab 9: Performative Environmentalism and the Everyday Legitimization of Climate Coloniality) mengkritik tindakan lingkungan “simbolik”—kampanye atau sertifikasi yang memberi legitimasi pada korporasi tanpa mengubah praktik dasar. Dia menggambarkan bagaimana greenwashing menjadi wacana sehari-hari yang mereduksi ketidakadilan menjadi masalah citra. Anantharaman mendorong audit sosial dan kebijakan akuntabilitas yang mengaitkan klaim lingkungan dengan hak dan pengawasan masyarakat. Routledge Contoh unik: perjuangan menolak proyek ruang angkasa yang menempati lahan publik dan komunitas lokal—kasus ini menghubungkan kolonialisme ruang dengan kolonialitas iklim dituliskan oleh Rivera & Breder (Bab 10: Fuera SpaceX: Resisting Climate Coloniality via Terra Nullius within Contested Boca Chica State Park). Mereka menegaskan bahwa ekspansi teknologi tinggi (mis. infrastruktur peluncuran) sering mengabaikan hak komunitas lokal dan menciptakan zona-zona “terra nullius” modern. Ini memperluas pemahaman climate coloniality ke ranah infrastruktur teknologi dan frontier ekonomi baru. Routledge
Michael Lomotey (Bab 11: Antiblackness in Flood Risk in Hull: The Afterlife of Colonialism) dan tim Bab 12 (studi kasus Puerto Rico tentang energi) menegaskan bahwa pengalaman banjir, transformasi energi, dan respons bencana tidak netral rasial—antiblackness dan struktur kolonial membentuk siapa yang dilihat sebagai prioritas. Puerto Rico menunjukkan bagaimana alih energi atau ‘green recovery’ tanpa kontrol lokal dapat memperkuat ketergantungan dan vulnerabilitas. Penekanan pada solidaritas transnasional dan pembangunan kapasitas lokal muncul sebagai rekomendasi kuat. Routledge
Secara tematik, buku ini menonjolkan beberapa gagasan kuat: (1) climate debt — bahwa negara-negara dan korporasi kaya memiliki hutang historis atas emisi dan keuntungan dari kolonialisme; (2) epistemic repair — perlunya mengembalikan suara dan pengetahuan yang dihapus; dan (3) kritik terhadap solusi berbasis pasar (offsets, net-zero) yang sering jadi “penutup luka” tanpa perubahan struktural. Sultana menulis sebelumnya tentang “the unbearable heaviness of climate coloniality,” menautkan rasa kehilangan, kemarahan, dan tuntutan keadilan di arena global (contoh: kritik terhadap COP sebagai panggung di mana kepentingan besar sering menang). Kutipan kunci dari tulisan Sultana memperingatkan bahwa “international climate negotiations falter in addressing climate change without meaningfully reducing fossil fuel dependency, growth models, and hyper-consumption.” Ini menegaskan bahwa akar masalahnya sistemik, bukan sekadar teknis. climatehealth.utoronto.ca+1
Ulasan kritikus umumnya memuji buku ini sebagai kontribusi penting yang memadukan teori dan kasus guna memajukan wacana climate justice yang benar-benar dekolonial. Beberapa pengamat memuji keberanian editor mengumpulkan pluralitas suara dari Global South dan hubungan antara gender, ras, dan ekonomi politik iklim; misalnya tinjauan di Blue Community dan peluncuran buku yang menekankan kebutuhan strategi transformatif. Kritik yang muncul — dari sebagian pembaca akademis — adalah bahwa rekomendasi strukturalnya radikal sehingga menimbulkan pertanyaan implementasi: bagaimana membiayai reparasi besar atau merombak institusi global yang berakar kuat? Namun kritik semacam ini sering justru mempertegas bahwa transformasi yang diusulkan memang menuntut konfrontasi dengan kekuatan yang mapan. Blue Community+1
Relevansi global buku ini hari ini sangat tinggi: era setelah berbagai COP dan kegagalan nyata dalam mengamankan pengurangan emisi yang adil membuat argumen dekolonial menjadi pusat. Di tengah terus berlanjutnya greenwashing, ekstensifikasi proyek ekstraktif (mis. mineral untuk transisi) dan pembajakan solusi oleh aktor kuat, pemahaman Sultana menyediakan alat kritis untuk mengevaluasi kebijakan iklim. Sejalan dengan analisis ini, gerakan lingkungan dan advokasi di banyak negara menuntut agar NDC, pendanaan adaptasi, dan mekanisme loss-and-damage memasukkan kewajiban historis, partisipasi komunitas, dan perlindungan hak tanah—hal yang buku ini dorong secara teoretik dan praktis. Routledge+1
Dalam konteks Indonesia, gagasan climate coloniality sangat relevan dan berbahaya bila diabaikan. Indonesia menghadapi kombinasi: lahan gambut yang menyimpan karbon besar dan rentan kebakaran; deforestasi untuk sawit dan tambang; serta pesisir dan kota besar (Jakarta) yang terancam banjir, penurunan tanah, dan perubahan iklim. Banyak kebijakan yang mem-promosikan pembangunan ekstraktif atau proyek ‘hijau’ berskala besar tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat adat dan komunitas lokal — pola yang persis diperingatkan oleh buku ini. Laporan-laporan tentang kebakaran lahan 2023, strategi pengelolaan lahan gambut, dan risiko Jakarta memperlihatkan bahwa tanpa pendekatan berbasis keadilan—yang mengakui hak, reparasi, dan pengetahuan lokal—solusi semata teknokratis atau pasar dapat memper-dalam ketidakadilan. Oleh karena itu, penerimaan ide-ide Sultana di Indonesia akan menuntut reformasi kebijakan kehutanan, agraria, pengakuan hak adat, dan alokasi pendanaan iklim yang pro-rakyat. Greenpeace+2MDPI+2
Catatan Akhir
Buku ini bukan hanya ajakan akademis — ia adalah panggilan moral dan politis. Mengutip Frantz Fanon yang terkenal, “Decolonization is the veritable creation of new men,” inti dari dekolonisasi adalah lahirnya manusia-manusia baru. Kita diingatkan bahwa proses dekolonial mengubah subjek dan struktur; demikian pula dekolonisasi iklim menuntut penciptaan ulang institusi, bahasa, dan hubungan sosial yang adil. Sultana menggabungkan data, narasi, dan tuntutan kebijakan untuk menunjukkan bahwa keadilan iklim harus bersifat reparatif, plural, dan berbasis hak. Kritik-kritik yang menilai rekomendasi terlalu radikal justru menegaskan bahwa persis itulah titik perubahan yang diperlukan. Bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan akademisi di Indonesia dan global, buku ini menawarkan kerangka yang kuat untuk bergerak dari retorika ke tindakan yang membongkar warisan kolonialitas—menuju masa depan yang lebih adil bagi banyak generasi. climatehealth.utoronto.ca+1
Bagi Farhana Sultana perundingan iklim internasional gagal mengatasi perubahan iklim jika tanpa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, model pertumbuhan, dan hiper-konsumsi secara bermakna. climatehealth.utoronto.ca
Mimi Sheller, penulis buku “Island Futures: Caribbean Survival in the Anthropocene (2020) dan Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes (2018), menutup dengan menekankan perlunya ekologi politik mobilitas, perhatian terhadap ruang/territori, dan advokasi transformasi institusional. Sheller mengajak pembaca untuk melihat climate justice sebagai proyek multidimensional yang memerlukan aliansi global dan rekonstruksi norma.
Vandana Shiva, aktifis yang puluhan tahun mengritik pembangunan ‘modern,’ (pada halaman penerbit) menyoroti hubungan kolonialisme, patriarki, dan enclosure; mendorong solidaritas dan praktik kearifan lokal. Sementara Amitav Ghosh/Naomi Klein (kutipan di halaman penerbit) menekankan bahwa tidak cukup narasi teknis tanpa akuntabilitas historis.
Serupa juga yang dicatat oleh Fazlun Khalid, Pendiri Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES), yang menegaskan konsep khalifah/amanah—menyatakan bahwa perlindungan lingkungan adalah kewajiban moral yang dapat dijadikan basis lokal/ religius untuk mendukung dekolonial climate justice. Seyyed Hossein Nasr, seorang intelektual, filsuf, dan akademisi terkemuka dari Iran yang dikenal sebagai ahli studi Islam, perbandingan agama, sejarah sains, dan spiritualitas, menekankan dimensi spiritual dan etika sebagai fondasi solusi yang berkelanjutan. CRCC+1
Bogor-Bandung, 16 November 2025.
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Blue Community. (2025, July 9). Review: Confronting Climate Coloniality. Blue Community. Blue Community
- Critical.eco. (2025). Book Launch: Confronting Climate Coloniality. Critical
- Choy, Y. K. (2025). The tropical peatlands in Indonesia and global significance (summary). MDPI (journal listing). MDPI
- Fanon, F. (1963). The Wretched of the Earth (excerpt). commons.princeton.edu
- Greenpeace. (2024). Indonesia’s chronic forest fires 2023 (report). Greenpeace
- Haverkamp, J. (2024). The De/Coloniality of Global Climate Governance and Indigenous Politics within the UNFCCC (chapter). In F. Sultana (Ed.), Confronting Climate Coloniality. Taylor & Francis. Taylor & Francis
- Jurema, B., & König, E. (2025). State Power and Capital in the Climate Crisis: A Theory of Fossil Imperialism (chapter). In F. Sultana (Ed.), Confronting Climate Coloniality. Taylor & Francis. research.utwente.nl
- Sultana, F. (Ed.). (2024). Confronting Climate Coloniality: Decolonizing Pathways for Climate Justice. Routledge. Routledge
- Sultana, F. (2022). The unbearable heaviness of climate coloniality. Political Geography, 99, Article 102638. (Reprinted online PDF consulted). climatehealth.utoronto.ca
- VitalSource / eText listing for Confronting Climate Coloniality. VitalSource
- WRI Indonesia / studies on Jakarta flooding and subsidence (various reports). wri-indonesia.org+1