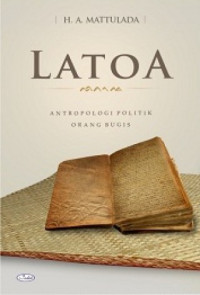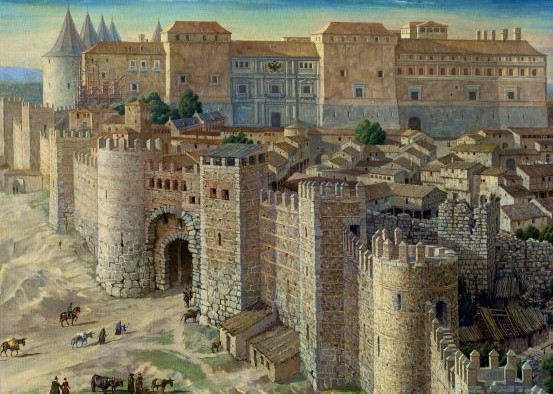halaman drm #43
Latoa: Kitab Bagi Pemimpin Bangsa
Dwi R. Muhtaman
Daftar Isi
…..
Berkata To-riolo, yang disebut niat yang benar 1
ialah yang bersandar pada keberanian, dan
adapun keberanian ialah yang bersandar pada niat yang benar,
maka perbuatan yang dua macam itu barulah baik kalau
ditegakkan di atas kejujuran.
…..
Bisik Hikmah dari Tanah Bugis untuk Pemimpin yang Adil
Bayangkan empat abad yang lalu. Sungai Walennae (Bone) mengalir hening seperti sebuah dansa tanpa suara. Dari batas kaki langit Pesisir Teluk Bone berombak tenang seperti hendak mendengarkan dengan hikmat suara dari ruang istana yang mengalunkan kata demi kata dari lembar kebijaksanaan lama. Di antara hamparan padi Bone yang keemasan, di mana Sungai Walennae membisikkan hukum-hukum Latoa, seorang pemimpin belajar menjadi manusia—bukan dengan mahkota, tapi dengan cangkul dan keberanian.
Di bawah langit sore yang memerah di istana Watampone, Sulawesi Selatan, yang dikelilingi sawah dan sungai, tempat Latoa pertama kali dibacakan untuk calon pemimpin, seorang bangsawan Bugis tua duduk bersila di depan naskah lontar yang telah usang. Jarinya yang berurat menelusuri tulisan kuno beraksara Lontara, sambil berkata: “La Tommu Toja, La Mappasessu Ri Dewata—Manusia mulia adalah yang taat pada kebenaran Illahi.” Itulah inti kitab Latoa, panduan kepemimpinan Bugis yang ditulis pada abad ke-17, tetapi relevansinya abadi.
Pemimpin dalam Latoa adalah pelayan, bukan penguasa. Kitab ini menegaskan: “Pemimpin yang baik ibarat akar pohon beringin—kokoh menjunjung tinggi, tetapi tak terlihat, karena seluruh hidupnya untuk menopang rakyat.” (Latoa, Pasal III.2, naskah koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan). Seperti pesan Sawerigading dalam La Galigo:2
“Lautku dalam berombak,
tapi lebih dalam hati perantau.
Padi menguning di sawah,
tapi lebih kuning cahaya kebijaksanaan.”
Pemimpin harus mempunya cahaya kebijaksanaan. Karena menjadi pemimpin bukan hanya melangkah dengan menggunakan logika tetapi juga mempertimbangkan aneka kebijkasanaan yang seringkali tidak tertulis dalam hukum-hukum formal. Pemimpin harus sensitif terhadap rasa dan suara rakyatnya dan menggunakan apa yang dirasakan dan didengar dari rakyat untuk mengambil tindakan yang bijak, melampaui hukum-hukum yang dituliskan.
Kitab Latoa memaparkan beberapa karakter pemimpin ideal. Pertama, Acca (Bijaksana). Seperti kisah Arung Palakka, pemimpin Bone yang legendaris, yang selalu memutuskan hukum setelah mendengar suara rakyat kecil terlebih dahulu. “Kebenaran bukan milik raja, tetapi milik bersama,” tulis Latoa.3 Kedua, Lempu (Jujur): Latoa menceritakan seorang bupati yang menolak hadiah emas dari pedagang asing, seraya berkata: “Kekayaan sejati adalah kepercayaan rakyat.” 4 Ketiga, Getteng (Tegas tapi Adil). Dalam salah satu pasalnya, Latoa mengingatkan: “Hukumlah pemeras rakyat seberat-beratnya, tetapi beri pengampunan bagi yang menyesal.”
Indonesia mempunyai kekayaan spiritual, filosofi dan kebijaksanaan yang luar biasa. Barangkali hampir setiap sudut-sudut komunitas di hamparan Nusantara ini catatan-catatan kebijaksanaan itu tersedia. Kita beruntung mempunyai Latoa dan juga La Galigo dari khasanah peradaban Bugis yang hingga saat ini tersimpan dengan baik. Meskipun kita perlu mengambil sebesar-besarnya hikmah kebijaksanaan itu dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga naskah yang tersimpan tidak hanya menjadi benda mati tetapi ia menjadi hidup karena digunakan sebagai panduan dalam kehidupan yang baik.
Latoa menolak kepemimpinan yang hanya mengandalkan kekuasaan. Keadilan yang diperjuangkan harus juga mampu menjadi jalan untuk menyejahterakan. “Negara akan hancur jika penguasanya sibuk mengumpulkan harta, sementara rakyat makan sekali sehari,” tulisnya. Sebaliknya, pemimpin harus:5
- Membangun “siri’ na pacce” (harga diri dan solidaritas) dengan mendahulukan kepentingan publik.
- Mengadakan “awang” (musyawarah terbuka) sebelum mengambil keputusan besar.
Warisan yang Tak Pernah Usang
Ketika malam tiba, sang bangsawan menutup lontar sambil berbisik: “Pemimpin sejati adalah yang kakinya berlumpur di sawah, bukan yang duduk di singgasana emas.” Latoa mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan soal kuasa, tetapi pengorbanan. Seperti kata puisi dari Bugis yang entah siapa yang menuliskannya:
“Di mana pun kau memerintah,
jadikanlah air mata rakyat sebagai cerminmu,
dan suara mereka sebagai petunjuk jalanmu.”
Atau seperti petikan dari La Galigo (terjemahan Prof. Nurhayati Rahman (2015), “Epos La Galigo: Suntingan Teks”, hlm. 134),
“Riak na tasik na mulino,
namaraja ri dewata,
tau na makkedao mali,
nasaba ri siri’ na pacce.”
Arti:
“Gelombang laut yang bergulung,
ditaklukkan oleh dewata,
tetapi manusia yang takluk,
karena harga diri dan solidaritas.”
Harga diri dan solidaritas adalah bagian penting dari nilai-nilai kepemimpinan.
Sejarah Singkat Latoa
Asal usul Latoa tidak diketahui secara pasti, namun diyakini bahwa naskah ini muncul pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Bugis, terutama pada abad ke-16 hingga ke-17. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan seperti Bone, Gowa, dan Wajo sering terlibat dalam konflik dan aliansi yang rumit. Latoa diyakini ditulis sebagai respons terhadap kebutuhan para penguasa Bugis untuk membimbing mereka dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana, serta untuk meminimalisasi perselisihan internal dan eksternal.
Latoa sering dianggap sebagai karya kolektif, yang berkembang melalui tradisi lisan dan kemudian dituliskan. Dalam tradisi Bugis, Latoa tidak hanya menjadi panduan untuk urusan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bugis. Naskah ini memberikan panduan tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dalam situasi tertentu, baik dalam masa damai maupun perang.
Makna Penting dalam Sejarah Masyarakat Bugis
Latoa memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah dan budaya Bugis karena beberapa alasan:
- Panduan Kepemimpinan: Naskah ini memberikan nasihat yang mendalam bagi para raja dan bangsawan tentang bagaimana memimpin dengan bijaksana dan adil. Nasihat dalam Latoa sering kali berfokus pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, serta menghormati hukum adat dan hak rakyat.
- Pemeliharaan Perdamaian: Latoa juga mempromosikan perdamaian dan diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, seperti yang terlihat dalam perjanjian damai antara Bone dan Gowa pada 1565 (Perjanjian Caeppa). Naskah ini mendorong para pemimpin Bugis untuk mencari solusi damai daripada mengandalkan peperangan.
- Pentingnya Hukum Adat: Latoa menekankan pentingnya menjaga dan menghormati hukum adat (pangadereng) sebagai fondasi tatanan sosial Bugis. Hukum adat ini mencakup norma-norma yang mengatur perilaku individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyat dan penguasa.
- Pewarisan Budaya: Melalui Latoa, masyarakat Bugis dapat melestarikan nilai-nilai budaya mereka dari generasi ke generasi. Naskah ini menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat Bugis, yang membantu mereka menjaga tradisi dan kebanggaan terhadap sejarah mereka.
Latoa adalah naskah yang tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan dan panduan kepemimpinan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Sulawesi Selatan. Dalam konteks yang lebih luas, Latoamenunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional Bugis seperti keadilan, kebijaksanaan, dan perdamaian tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, baik di masa lalu maupun masa kini.
Referensi lebih lanjut tentang Latoa dapat ditemukan dalam buku “Latoa: Satu Kajian Sastra Bugis” oleh Muhammad Salim, serta kajian lain tentang sejarah hukum adat dan kebijakan politik di Sulawesi Selatan.
Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan memiliki dua karya kanonik yang sangat penting, yaitu La Galigo dan Latoa. Keduanya merupakan warisan budaya yang tak ternilai dan mengandung kebijaksanaan leluhur Bugis yang diwariskan turun-temurun. Meskipun demikian, kedua karya ini berbeda dalam hal tema, konteks sejarah, dan peran di dalam masyarakat Bugis.
1. La Galigo
La Galigo adalah sebuah epik yang dianggap sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Karya ini diperkirakan mulai muncul antara abad ke-14 dan ke-15, awalnya sebagai bagian dari tradisi lisan masyarakat Bugis dan kemudian ditulis. Epik ini menceritakan sejarah mitologis orang Bugis, tentang penciptaan dunia dan petualangan dewa, setengah dewa, dan pahlawan legendaris, khususnya tokoh Sawerigading, seorang pahlawan dalam mitologi Bugis.
- Tema dan Isi: La Galigo adalah narasi kosmologis yang mencerminkan pemahaman Bugis tentang alam semesta, tatanan sosial, dan eksistensi manusia. Karya ini membahas penciptaan dunia, hubungan ilahi, petualangan heroik, dan memberikan pelajaran moral tentang kehidupan, kepemimpinan, dan masyarakat. Namun, La Galigo lebih merupakan landasan mitologis daripada panduan sosial atau politik langsung.
- Pengaruh Budaya: La Galigo sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan dunia masyarakat Bugis. Karya ini digunakan dalam berbagai ritual dan upacara adat, terutama di pusat-pusat kerajaan seperti Luwu, yang merupakan kerajaan penting dalam budaya Bugis. Karya ini ditulis dalam aksara Lontara, sistem penulisan tradisional Bugis.
- Pengarang: La Galigo tidak memiliki satu penulis yang jelas karena merupakan bagian dari tradisi lisan kolektif. Karya ini berkembang selama berabad-abad melalui kontribusi dari banyak individu, terutama para pendongeng lisan yang dikenal sebagai to-Galigo, sebelum akhirnya ditulis.
2. Latoa
Latoa merupakan sebuah karya yang lebih bersifat filosofis tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Berbeda dengan La Galigo yang bersifat mitologis, Latoa memberikan panduan langsung tentang etika, keadilan sosial, dan kepemimpinan yang efektif. Karya ini berisi kumpulan diskursus politik dan etika yang memberikan nasihat kepada para penguasa, dengan fokus pada tanggung jawab kepemimpinan dan pentingnya menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.
- Tema dan Isi: Latoa membahas isu-isu politik dan sosial nyata, menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Karya ini juga memberikan wawasan tentang cara mengelola konflik, membimbing masyarakat, dan memastikan hubungan yang seimbang antara penguasa dan rakyat. Latoa dipandang sebagai refleksi dari filsafat hukum dan politik Bugis, yang banyak terinspirasi dari ajaran Islam yang masuk ke Sulawesi Selatan sekitar abad ke-17.
- Pengaruh Budaya: Latoa lebih erat kaitannya dengan pemerintahan dan kepemimpinan di masyarakat Bugis, terutama di kalangan bangsawan dan mereka yang terlibat dalam politik. Latoa masih sering dirujuk dalam diskusi tentang pemerintahan tradisional Bugis dan resolusi konflik.
- Pengarang: Tidak seperti La Galigo, Latoa lebih memiliki asal-usul sejarah yang jelas. Meskipun penulis spesifiknya tidak dikenal secara luas, Latoa biasanya dikaitkan dengan para cendekiawan dan pemimpin Bugis yang terlibat dalam struktur politik dan sosial pada masanya. Karya ini juga dipengaruhi oleh pemikiran politik Islam.
Perbandingan dan Pengaruh
- La Galigo memberikan landasan kosmis dan mitologis yang menghubungkan masyarakat Bugis dengan asal-usul ilahi mereka dan memberi mereka rasa identitas dan tujuan. Karya ini lebih menekankan pada idealisme heroik dan tatanan moral alam semesta.
- Latoa, sebaliknya, lebih fokus pada aspek praktis pemerintahan, kepemimpinan, dan keadilan sosial. Karya ini berfungsi sebagai panduan bagi para pemimpin tentang cara menjalankan kekuasaan politik dan sosial.
Kedua karya ini sangat penting bagi budaya Bugis, meskipun peran mereka berbeda. La Galigo lebih berpengaruh secara spiritual dan mitologis, sementara Latoa berperan langsung dalam kepemimpinan dan pemerintahan di masyarakat Bugis. Kedua naskah ini juga mempunya pengaruh geografis yang berbeda. La Galigo: Secara luas dirujuk di seluruh Sulawesi Selatan, terutama di Luwu, yang merupakan pusat kerajaan dan kebudayaan Bugis. Sementara Latoa lebih banyak dirujuk dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan di wilayah Bugis, khususnya dalam kaitannya dengan tradisi dan politik Islam. Kedua karya ini adalah harta sastra Bugis yang menawarkan wawasan tak ternilai tentang kehidupan spiritual dan politik masyarakat Bugis.
Sebagai sebuah karya kanonik, Latoa mengandung begitu banyak hal yang diatur. Soal kepemimpinan adalah salah satu sisi diantara sisi-sisi kehidupan lainnya. Menurut Mattulada,
semua ide, pikiran dan sikap hidup yang tercantum dalam Latoa, pada bagian-bagian yang belum memperoleh pengaruh Islam, sudah ada pada zaman Kajao Laliddo dalam abad ke-XVI, dan telah berperan dengan nyata sebagai landasan aktivitas kenegaraan dan pergaulan hidup antara orang-orang dan negara-negara Bugis. Sampai sekarang pun masih tampak pengaruhnya dalam menghadapi usaha-usaha pembangunan dan pembaharuan di segala bidang kemasyarakatan. Garis besar isi Latoa, adalah kumpulan ucapan-ucapan, petuah-petuah dari beberapa raja dan orang-orang bijaksana (sekitar abad ke-XVI), mengenai berbagai hal,
terutama kewajiban-kewajiban raja dan abdi raja terhadap negara dan rakyatnya, di samping hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap raja dan rakyatnya, di samping hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap raja dan negaranya.
Adapun raja-raja dan orang-orang bijaksana yang buah pikiran, petuah-petuah, dan petunjuk-petunjuk terdapat dalam Latoa ini ialah:
- Kajao Laliddo, pada alinea 1 s/d 31 dan 160, semuanya 32 alinea. Pada alinea 1 s/ 31 itu, Kajao Laliddo berdialog dengan Arumpone. Arumpone yang berdialog dengan Kajao Laliddo itu, pastilah salah satu di antara dua Arumpone yang berkuasa pada saat Kajao Laliddo masih hidup, yaitu La Ulio BoteE, MatinroE ri Terrung, Raja Bone ke-6 (* 1535-1560) dan La Tenrirawe Bongkannge, Raja Bone ke-7 ($ 1560-1578). Baginda wafat dalam tahun 1584, dan Kajao Laliddo meninggal dalam tahun 1586 (Noorduyn, 1955 : 77-78).
- Tau-riolo, yang dimaksud dengan kata itu, ialah orang dahulu kala, tak disebutkan namanya. Buah pikiran Tau-riolo berasal dari leluhur yang tetap dijadikan pedoman pada saat Latoa dituliskan. Tau-riolo itu niscaya adalah mereka yang hidup sebelum datangnya agama Islam di Bone. Menurut kebiasaan orang Bugis, petuah-petuah yang berasal dari Tau-riolo itu disebut paseng (amanat) yang diwariskan dari generasi ke generasi. Buah-buahan pikiran Tau-riolo itu, menempati alinea 32 s/d 55, berjumlah 24 alinea.
- MatinroE ri Tanana, ialah raja kerajaan Sopeng, atau Datu Soppeng ke-9 (# 1602-1646), bernama La Manusa Toakka, MatinroE ri Tanana. Buah-buah pikiran baginda, tersebut pada alinea 56, 57, 58, 59.
- Petta Maddarennge, salah seorang di antara tiga orang raja yang mendampingi Arung Matoa Wajo’. Siapa orangnya dan bila waktunya, tak diperoleh keterangan. Buah-buah pikiran Petta Maddanrengge, terdapat pada alinea 60, 61, 62.
- Arung Bila, salah seorang raja di Soppeng ($ abad ke-15). Buah pikiran beliau terdapat pada alinea-alinea yang panjang, yaitu alinea 69.90, sejumlah 27 buah alinea.
- Nabi Munammad (Rasul Allah), disebut pada alinea 91 s/d 93. Memperhatikan maksud (isi) aline-alinea tersebut mengingatkan kita kepada Hadist Nabi Muhammad. Hadis-hadis Nabi Muhammad yang mendekati apa yang tersebut dalam latoa tak lain dari penyesuaian demikian rupa, sehingga menggambarkan suasana Tana-Ugi’ dan para penguasanya dengan merubah istilah-istilah pejabatnya. Misalnya untuk “pemerintah” digantikan dengan Arung Mangkau’ dan sebagainya. Akan tetapi isi dan tujuannya tetap dipertahankan.
- Lukmanul Hakim, seorang ahli hikmah (filsuf). Menurut keterangan beberapa orang ahli tafsir, Lukmanul Hakim berasal dari negeri Habsya (Ethiopia). Ada yang menghubungkannya dengan Acsop, filsuf Yunani, mengingat persamaan hikmah. Buah pikiran Lukmanul Hakim tersebut dimuat pada alinea 94 s/d 103, ada sembilan alinea. Tokoh ini, termasuk salah satu ulama Islam zaman dahul, yang banyak diikuti jalan pikirannya dalam perkembangan Islam di kalangan orang Bugis-Makassar.
- KaraEtta ri Cenrana. salah seorang bangsawan Bugis terkemuka. Buah pikirannya mengenai pendirian yang benar, tersebut pada alinea 104.
- Petta MatinroE Lariang-banngi. Salah seorang bangsawan dan pembesar Tana-Bone, yang wafat di Makassar (kampung Lariang-banngi), berbicara tentang tata tertib menghadap raja. Buah tuturnya dapat diikuti pada alinea 105 s/d 138, sejumlah 33 buah alinea. Sebagai rangkaian paseng (amanat) beliau kepada Petta Tomarilaleng PawelaiE ri Lempu. Alinea 139 dan selanjutnya tak jelas siapa yang mengucapkannya. Akan tetapi sesuai dengan urutannya, ada kemungkinan bahwa yang mengucapkan- nya adalah Petta MatinroE ri Lariang-bangi juga.
- Puang ri Maggalatung, Arung Matoa Wajo’ (1798-1828), disebut dalam alinea 160.
- KaraEng MatoaE Raja Tallo merangkap Mangkubumi Kerajaan Gowa, disebut juga dalam alinea 160.
- Arumpone MatinroE ri-Addenenna, La Ica, Raja Bone ke-8, tersebut dalam alinea 211. Baginda dijadikan rapang (ibarat) seorang raja yang dibunuh karena melanggar panngaderreng.
Manurut catatan Mattulada jelas bahwa semua tokoh yang terlibat dalam Latoa adalah
tokoh-tokoh sekitar abad ke-XV dan XVI, zaman tergenting yang dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan. Genting karena timbulnya peperangan yang berkecamuk antara kerajaan-kerajaan dalam wilayah sendiri, juga karena menghadapi arus kekuatan kolonial dari dunia Barat. Pada zaman itu berlangsunglah kontak dengan dunia Islam, yang sudah mulai berakar di bagian barat Nusantara dan pulau Jawa. Sulawesi Selatan pada saat-saat tu mengalami masa peralihan yang amat dahsyat yang sampai sekarang tetap mewarnai kehidupan sosial-budaya orang Bugis-Makassar.
Demikianlah catatan pengantar untuk menyerap Latoa sebagai Kitab Bagi Pemimpin Bangsa. Meskipun tentu saja hikmah kebijaksanaan tentang kepemimpinan yang tertuang dalam Latoa ini bisa berlaku dan relevan untuk semua pemimpin dimanapun dan bentuk organisasinya apapun. Setidaknya bisa menjadi rujukan gaya dan mandat kepemimpinan. Catatan pengantar ini ditulis sebagai bagian dari merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Sebagai catatan akhir membaca Latoa ini, saya tuliskan ulang sebagian kecil naskah Latoa yang saya kutip dari buku Latoa karya Prof Mattulada. Ditulis dengan gaya puisi. Puisi sudah ditulis pada 2024.
Cirebon, 17 Agustus 2025
Latoa: Kitab Bagi Pemimpin Bangsa6
1/
Musim yang gelisah, musim semi abad 16.
Langit bergolak. Bumi cemas.
Kekuasaan merayap melintasi batas-batas.
Kerajaan Cana adalah Gowa, kekuasan yang perkasa. Makin berjaya.
Pesisir Selatan jazirah Sulawesi Selatan takluk di bawah kekuasannya.
Bentang sayap kerajaan menjangkau jauh
hingga negeri-negeri tetangga, tempat menambat sauh.
Bayang-bayang cengekeramannya membekuk siapa saja.
Semua kerajaan dan negeri merdeka di Sulawesi Selatan berlutut
satu demi satu. Putus asa.
Dengan lembut, atau dengan carutmarut.
Hanya kerajaan Bone nan tegak sendiri
berdaulat dari politik ofensif Gowa.
Menjaga martabat di bumi negeri
melawan kuasa tanpa tawar jiwa.
Bak batu karang di lautan, badai dan ombak
selalu datang menghantam, mengepung, menggempur
Bone dari segala penjuru mata angin dan matahari
hantaman dan tekanan-tekanan politis bergelegak,
gempuran strategi pertahanan, juga
tekanan psikologis yang tak pernah habis.
Bone tak tergoyahkan. Bertahan dengan kekuatan mandiri
dan teguh membentengi jatidiri.
Pemerintah dan rakyat Bone cemas,
selalu waspada, menjaga tapal batas dengan tegas.
“Tindakan harus segera diambil,” seru para pemimpin.
—Kekuatan-kekuatan di seluruh negeri harus dihimpun,
menjaga kehormatan di dalam dan di luar,
maka semua orang pandai dan terkemuka,
pemuda yang berani dan kuat terpanggil untuk membela
dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.
Musim datang dan pergi, dan
tersebutlah pada tarikh 1560,
dalam masa pemerintahan raja Bone ke-7, LaTenrirawe Bongkannge,
diangkatlah La Mellong To Sualle, alias Kajao Laliddo
menjadi penasihat dan duta keliling kerajaan Bone.
Dengan gagah, penuh hormat, melangkahlah Ia
pada panggilan penguasa untuk tugas negara.
To Sualle Kajao Laliddo membuka lorong-lorong terjal diplomatik
yang mengokohkan dinding-dinding pengaruh kerajaan Bone,
— pembelian Pitumpanua dari kerajaan Luwu,
— perjanjian perdamaian Caeppa antara Bone dengan Gowa
dalam tahun 1565, perjanjian yang membahagiakan pihak Bone
dan kerajaan-kerajaan Bugis
: Wajo’, Soppeng, Lamatti dan Bulo-Bulo.7
Kerajaan Gowa menyambutnya sebagai perdamaian yang terhormat.
Kebijaksanaan dan kepandaian Kajao Laliddo sangat mengesankan,
perjanjian yang menegakkan iklim perdamaian
antara Bone dengan Gowa sebagai dua kerajaan bersahabat,
penuh persaudaraan erat.
Selama tiga abad kata-kata bijak kaum pandai dan penguasa bijaksana,
jadi cahaya bagi rakyat dan para pemimpinnya.
Sebab bagi manusia Bugis, inilah pangaderreng 8—
—manusia itu, apa pun dan bagaimanapun tingkat atau derajat sosialnya
adalah makhluk yang sama derajatnya sebagai ciptaan Tuhan.
—manusia itu, dalam tujuan hidupnya berhasrat untuk selalu berbuat kebajikan.
—manusia itu, dalam membangun nilai-nilai dan pranata-pranata sosial kebudayaannya selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan bersama dengan kepentingan individunya.
Maka pada pagi yang teduh, matahari menyala perlahan,
bayang-bayangnya menarikan daun-daun rindang pepohonan
di pelataran pondok istana, dan angin dari pantai samudra menari-nari memainkan,
gelombang ombak yang udara hempasannya tiba di pintu kerajaan,
berbincanglah Kajaolaliddo dan Arumpone:
Berkatalah Kajaolaliddo, apa gerangan, hai Arumpone,
yang kau sebut tak membiarkan robohnya kemuliaan,
yang mengekalkan tegaknya kemuliaan yang kau punyai,
yang tidak mencerai-beraikan rakyatmu,
yang tidak menghambur-hamburkan harta yang kau punyai.
Berkata Arumpone, kejujuran9 itu, Kajao, bersama kepandaian.
Berkata Kajaolaliddo, memang itu, tapi juga bukan itu10
Berkata Arumpone, lantas manakah gerangan hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, adapun induk harta-benda itu, hai Arumpone,
ialah tak membiarkan rakyatmu tercerai-berai,
tak tidur raja siang maupun malam merenungkan kesejahteraan negaranya 11,
dipandangnya muka dan belakang12 perbuatan itu, baru diperbuatnya;
yang ke-dua, Arummangkau’ harus pandai membangun kalimat13;
yang ketiga, Arummakau’ harus pandai mengucapkan kalimat;
keempat, tidak alpa suronya14 mengatakan apa yang benar.
Berkata Arumpone, manakah yang disebut pandai membangun kalimat, Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, adapun hai Arumpone yang disebut pandai
membangun kalimat ialah orang yang kukuh memegang pangaderreng15
Berkata Arumpone, manakah yang disebut pandai mengucapkan kalimat, hai Kajao.
Berkata Kajaolalio, adapun hai Arumpone yang disebut mengucapkan kalimat
ialah orang yang tak salah pada rapang. 16
Berkata Arumpone, manakah yang disebut orang tak alpa dutanya
pada perkataan yang benar, hai Kajao.
Berkata Kajalaliddo, adapun hai Arumpone, yang disebut orang tak alpa dutanya pada perkataan yang benar ialah orang tak alpa dari bicara.17
Berkata Arumpone, apa sumbernya kepandaian itu, hai Kajao
Berkata Kajaolaliddo, kejujuran,18 hai Arumpone
Berkata Arumpone, apa saksinya kejujuran itu, hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, obbie 19itu, hai Arumpone.
Berkata Arumpone, apakah (yang) diserukan, hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, adapun yang diserukan, hai Arumpone,
ialah: jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu;
jangan mengambil harta-benda yang bukan harta-bendamu, bukan pula pusakamu;
jangan mengeluarkan kerbau (dari kandangnya) kalau bukan kerbaumu,
serta kuda yang bukan kudamu; jangan mengambil kayu yang tersandar, kalau bukan engkau yang menyandarkannya, juga
jangan mengambil kayu yang kedua ujungnya tertetak kalau
bukan engkau yang menetaknya.
Berkata Arumpone, apa saksinya kepandaian itu, hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, perbuatan20 itulah saksi kepandaian, hai Arumpone.
Berkata Arumpone, apakah yang diperbuat, hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, yang diperbuat, hai Arumpone,
ialah tak menghiraukan perkataan buruk dan perkataan baik.
2/
Berkata Arumpone, apakah tanda akan hancurnya suatu 21negara besar, hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, tanda akan binasanya negara besar itu, hai Arum-pone,
ialah kecerobohan,22
kedua, apabila raja tak mau diperingati,
ketiga, apabila tak ada orang pandai dalam negeri,
keempat, Tomabbi-carae 23 dinaiki harta,24
kelima, apabila berkecamuk perbuatan jahat di dalam negeri,
keenam, apabila raja tak mengasihi abdinya.25
Berkata Arumpone, apa tandanya Negara akan jaya, hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, tandanya ada dua. Negara akan jaya, Arumpone,
apabila pertama, Arummangkau jujur dan pandai,
kedua kalau tak ada persengketaan di dalam negeri.
Berkata Arumpone, apakah nakas-tahunan26 itu, hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, adapun yang menyebabkan nakas-tahunan, hai Arumpone,
pertama, jika besar nafsu27 Arummangkau’ itu,
kedua, jika Tomabbicara disogok,
ketiga, jika orang di dalam negeri bersengketa,
itu jugalah tandanya kesuburan padi, hai Kajao.
Berkata Arumpone, apa tandanya kesuburan padi, hai Kajao.
Berkata Kajaolaliddo, tiga tandanya, maka jadi padi itu, hai Arumpone,
pertama, bila jujur 28 Arummangkau’ itu,
kedua, bila pantangan ditaati (oleh) Arummangkau’ beserta Tomabbicara,
bersatu-padu orang di dalam negeri.
Berkata selanjutnya Kajaolaliddo, adapun ade29 itu, hai Arumpone,
mengokohkan kebesaran Ammangkau,
ia jugalah yang menghalangi perbuatan para penjahat,
ia jugalah tempatnya bersandar orang lemah.
Dan adapun bicara30 (peradilan) itulah yang menyelesaikan
perselisihan orang yang bersengketa.
Dan adapun rapang 31 itu,32 ialah yang membangun
kekeluargaan negara yang sekeluarga33 dan bila telah rusak, hai Arumpone,
ade itu, maka tidak kokoh lagi kebesaran Arummangkau’,
rusak pulalah Negara bila tak ditegakkan lagi bicara34 itu,
rusaklah rakyat banyak bila tak ditegakkan lagi rapang itu,
itulah hai Arumpone yang menjadi sumber persengketaan.
Sengketa itulah yang menjadi sumber perang,
perang itulah yang menjadi pangkal saling bunuh membunuh.
Oleh karena itulah, hai Arumpone, maka dikehendaki,
pelihara/jagalah ade itu, juga bicara itu,
serta rapang itu, bersama wari 35itu.
Berkata pula Kajaolaliddo, adapun pangkal ade 36, hai Arumpone,
ialah perbuatan mappasilasa’e 37,
dan adapun pangkal bicara 38
ialah perbuatan mappasisaue 39,
serta perkataan siariwawonnge 40, dan adapun pangkal rapang
ialah perbuatan yang mappassenrupae 41 dan adapun pangkal wari
ialah perbuatan mappalla-isennge. 42
Hari telah turun. Temaram menguasai langit merah jingga.
Desir pasir pantai terdengar lelah.
Percakapan Kajaolaliddo dan Arumpone perlahan lelap,
terukir dalam lontara yang hidup dalam tiga abad,
diucapkan bergantian, diperbuat dalam panutan.
3/
Bergantian terdengar percakapan antara
To-riolo atau To-matoa43 yang mengingatkan
pikiran, sikap dan tindakan yang harus ditegakkan
agar tegak pula kemaslahan orang banyak dan kejayaan negara.
tentang adab pemimpin itu:
Berkata To-riolo, yang disebut niat yang benar44
ialah yang bersandar pada keberanian, dan
adapun keberanian ialah yang bersandar pada niat yang benar,
maka perbuatan yang dua macam itu barulah baik kalau
ditegakkan di atas kejujuran.
Berkata pula To-riolo, apabila engkau menghendaki agar
sesuatu dikerjakan oleh orang banyak, umpamakanlah perahu.
Jika engkau suka menaikinya, itulah yang engkau muati orang lain,
yang demikianlah yang disebut jujur45
Berkata pula To-Matoa, kalau ada perbuatan yang
engkau hendak lakukan dan tak disukai oleh nafsumu,
tetapi disukai oleh pertimbangan (= akalmu), maka lakukanlah
walaupun ada keburukannya, karena tidak ada samasekali
kebaikan bagi orang yang menuruti nafsunya,
kecuali sesuai akal-budinya barulah ia benar.
Berkata pula To-Matoa, peliharalah hatimu, arahnya,
jangan engkau meniatkan sesamamu manusia kepada keburukan,
karena pastilah engkau nanti yang buruk, walaupun baik perbuatanmu,
karena terbawa-bawa perbuatan yang baik itu kepada hati yang buruk.
Tidaklah tercipta hati yang baik dari perbuatan buruk.
Maka jika hatimu buruk, sampai kepada keturunanmulah 46 keburukannya.
Berkata To-Matoa, jika engkau sudah beranak,
jujurkan sangatlah dirimu, karena apa yang disebut perbuatan buruk,
akan diwarisi oleh keturunanmu. Apabila perbuatanmu buruk,
itulah yang dijadikan cermin oleh anakmu.
Kecuali engkau jujurkan dirimu, engkau perbaiki perbuatanmu,
engkau habiskan nasihat-nasihat kepada anakmu,
dan ia juga tetap melakukan perbuatan yang buruk itu,
maka begitulah ketentuan Allah Taala kepada anakmu.
Berkata To-Matoa, empat hal47 yang memburukkan niat.48
Pertama, kemauan 49,
kedua, ketakutan,
ketiga, keengganan,
keempat, kemarahan.
Empat hal itulah yang memburukkan niat, juga memburukkan perkataan.50
Ditambahkannya, lihatlah kepada orang yang memberi,
jangan kepada pemberiannya, karena sesungguhnya sebaik-baiknya
perbuatan ialah yang sewajarnya51
Berkata pula To-Riolo, adapun yang membuat
negara jaya ada sebelas hal.
Pertama, perkataan baik52 ,
kedua, tingkah-laku yang baik,
ketiga, bicara yang jujur,
keempat, janji tak terlupakan, dan uluada 53(= persetujuan; ikrar) yang tak diingkari,
kelima, ade yang tak diragukan 54,
ke-enam, rapang yang kokoh,
ketujuh, wari (= batas-batas) yang terpelihara,
kedelapan, kesepakatan dalam negeri,
kesembilan, pertimbangan yang tak berselish,
kesepuluh, siakkasiriseng55 (= saling menghargai) dalam negeri,
kesebelas tidak saling tidak bersetia sesama warga negeri56,
apa-pula terhadap sanak-keluarganya, karena sesungguhnya,
perbuatan baik itu, serta bicara yang jujur
memasukkan rezeki tahunan (= berhasil baik tanaman padi).
Berkata pula To-Riolo, empat macam penyakit keras
(= ancaman kebinasaan) dari negara:
pertama Arungmangkau yang berang sebelum menyelidiki,
kedua, joa (= pengikut)57 yang lancang dan aniaya58,
ke-tiga, Pabbicara yang menerima sogok,
keempat, suro (duta; suruhan) yang meringkaskan atau memanjangkan kata.
Berkata pula To-Riolo, semua perbuatan barulah baik kalau tertib.
Pertama, ketahuilah yang buruk, pahamilah yang baik,
kedua, ketahuilah yang rampung,
ketiga, ketahuilah yang benar, pahamilah yang yang disebut tertib, tak benar,
keempat, ketahuilah yang culas, pahamilah yang jujur, itulah yang disebut tertib.
Berkata pula To-Riolo, apabila engkau berkata,
ingatlah (akan) ade dan rapang59 serta perbuatan
yang engkau anggap benar.
Itulah yang engkau tekankan dalam berkata-kata,
hubungkan pangkal dan jung dari kata-kata itu
sebelum mengucapkannya, karena adapun perkataan serta perbuatan yang baik,
barulah baik dan benar kalau ade tempat berpijaknya. 60
Tempatkanlah perbuatan semua pada tempatnya,
lagipula kata-katamu, walaupun engkau mengganggap perbuatan
serta kata-katamu banar tapi tidak pada tempatnya, salah jugalah ia.
Berkata pula To-Riolo, apabila engkau menjawab kata,
pahamilah lebih dahulu kata itu.
Carikan perbuatan yang sesuai dengan ade dan sara!
juga rapang, yang dapat memenuhi perkataan orang 61
dan itulah yang menegakkan lawan kata (= jawaban),
karena sesungguhnya apabila bukan jawaban dari
kata orang engkau jawabkan, diketawainyalah eng-kau,
disebutnya juga bahwa tak ada orang pandai dalam negeri.
Maka sepatutnyalah sudah Arummangkau
serta Pabbicara sungguh-sungguh memahami rapang, ade,
juga wari, sungguh-sungguh mengingat perbuatan yang baik,
serta kata yang benar, karena itulah yang
menjadi jaminan pada orang pandai.62
Jangan mereka lupa membiasakan diri pada perbuatan yang benar,
juga pada kata yang benar.
Demikian pula halnya dengan suro,
karena akan sangat menertawakan jika suro
dari Aummangkau itu tak tahu berbicara.
Berkata pula To-Riolo, ada tiga hal yang mengecilkan negara besar.
Pertama, Arummangkau dikuasai oleh kehendak (= ambisi),
kedua, To Mabbicara menetapkan bicara berdasar pilih kasih,
ketiga, benci (yang) menetapkan (= menjadi dasar) bicara dari To-Mabbicara,
Tiga hal pula yang membesarkan negara kecil.
Pertama, bicara tongetellu63 = keputusan hukum yang didasarkan atas tiga kebenaran);
kedua, bicara situru’e (= keputusan hukum yang serasi)64,
ketiga, bicara dope (=penundaan keputusan hukum)65.
Adapun yang disebut bicara tongettellu
ialah kalau terputus sudah semua akarnya,
keempat-empat-bicara itu, mengangguklah
pikiran orang yang benar kebenarannya, mengangguk
pulalah pikiran orang yang salah pada kesalahannya,
maka betullah jalannya To-Mabbicara itu.
Dan adapun yang disebut bicara situru,
walaupun hanya gembala yang mengucapkan perkataan,
namun hanya dengan kebulatan persepakatanlah (dari) orang orang itu,
sepakat membaringkannya, barulah ia dibaringkan.
Dan adapun yang disebut bicara dope ialah jika sudah sama panjang,
sama lebar letak perbuatan kedua pihak, kecermatan kedua pihak,
saksi kedua pihak, maka ditempatkanlah dirinya dalam keseimbangan Pabbicara itu, diperhadapkannya kepada Dewata
dan apalah yang diberikan kepadanya oleh Dewata,
mewadahi Bicara itu, diputuskannya, begitulah yang disebut bicara yang lurus (= jujur).
Berkata pula To-Riolo, ada tiga macam yang menjadi pangkal kebajikan di dunia ini.
Pertama, yang mencegah mulutnya menyebut kata yang buruk,
kedua, yang mencegah pikirannya memikirkan yang jahat,
ketiga yang mencegah dirinya berbuat yang jahat.
Juga ada tiga macam yang membangun dunia,
pertama ade,
kedua bicara,
ketiga rapang, dan ada-pun kejujuran itu,
tak mudah melaksanakannya.
Oleh karena itu biasakanlah diri berbuat jujur,
karena adapun kejujuran itu, bagai burung liar,
tak dapat kita menangkapnya jika kita tidak tahu
cara pemeliharaannya.
Dan cara pemeliharaannya ialah tak berputus-asa,
dan makanannya ialah kecermatan (= kehematan),
dan sangkarnya ialah kewaspadaan.
Begitulah ibaratnya perbuatan yang jujur.
Jika orang menghayati ketiga perbuatan itu,
dimisalkan ia berdiam dalam kurungan besi,
tak ada lagi yang sanggup mengganggunya.
la jugalah yang selalu didinding (= dijaga) oleh Allah Taala.
4/
Berkata pula To-Riolo, ada empat pagar negeri yang
membuatnya tak dapat dimasuki oleh orang yang
berbuat sewenang-wenang.66
Pertama, jujur sejalan dengan ade,
kedua rapang sejalan dengan kepastian,
keti-ga, keberanian sejalan dengan kepandaian,
keempat, dermawan sejalan dengan hati terbuka67 (= toleransi).
Dan adapun yang disebut jujur68 tiga macamnya,
pertama, kejujuran tuan kepada hambanya,
kedua, kejujuran anak (= hamba) kepada tuannya,
ketiga, yang menjadikan tauladan atas dirinya,
artinya menjadikan dirinya contoh untuk sesama-nya.
Dan adapun kejujuran tuan kepada hambanya ialah
tak dibalasnya perbuatan baik hambanya dengan perbuatan buruk,
melainkan dengan kebaikan jugalah ia membalasnya.
Dan adapun kejujuran hamba kepada tuannya
ialah mengerjakan amanat tuannya, apa yang diamanatkan,
itulah yang dilaksanakannya.
Ada empat macam hal yang memperbaiki hubungan kekeluargaan69
Pertama, kasih sayang berkeluarga,
kedua, saling memaalkan secara kekal,
ketiga, tak segan saling memberi pengorbanan pada silasanae70 (=sewajarnya),
keempat, saling memperingati untuk berbuat kebajikan dan kepada kebaikan.
Berkata pula To-Riolo, hanya empat macam hal
yang memperbaiki negara dan barulah dicukupkan
lima ketika syareat Islam diterima.
Pertama ade,
kedua, rapang,
ketiga, wari,
keempat bicara71, adapun ade itu ialah yang memperbaiki rakyat,
rapang itu, ialah yang mengokohkan kerajaan,
wari itu, ialah yang memperkuat kekeluargaan negara yang sekeluarga,
dan adapun bicara itu, ialah yang memagari perbuatan sewenang-wenang
dari orang yang berbuat sewenang-wenang,
dan adapun sara itu, ialah sandarannya orang lemah yang jujur.
Bila ade tidak dipelihara lagi, rusaklah rakyat.
Bila rapang tak dipelihara lagi, lemahlah kerajaan.
Bila wari hilang, tak bersepakatlah rakyat itu.
Dan bila sara tak ada lagi, berbuat sewenang-wenanglah semua orang,
bila bicara tiada lagi, rusaklah hubungan kekeluargaan
negara-negara yang sekeluarga.
Itulah nanti yang menjadi sumber pertikaian,
dan adapun pertikaian itu, berujung pada perang,
dan barang siapa yang mengingari rapang akan
didatangkan baginya lawan yang kuat oleh Allah Taala.
Bila bicara tak dijalani lagi, saling membinasakanlah orang,
karena tidak ditakutinya lagi perbuatan yang bersumber dari kekuatan.
Begitulah maka dikehendaki oleh To-Riolo agar ade diperteguh,
rapang dipelihara dengan cermat, dan bersama-sama menegakkan kepastian bicara,
agar dirobohkanlah perlindungan terhadap orang lemah.72
Berkata pula To-Riolo, ada lima macam pagar negeri
sehingga tak bisa dimasuki oleh orang yang berbuat sewenang-wenang.
Pertama, jujur sejalan dengan ade;
kedua, rapang sejalan dengan kepastian;
ketiga, berani sejalan dengan kepandaian;
keempat, dermawan sejalan dengan lapang dada;
kelima, senantiasa dipersiapkan alat peperangan
diiringi oleh kata-kata yang baik dan lemah lembut,
tak boleh dijerumuskan oleh ikrar (=perjanjian dengan lawan-lawan kita. 73
Itulah perbuatan yang lima macamnya,
dipagarkan kepada negeri, jangan sampai negara terancam bencana. 74
Inilah perbuatan macamnya, dipagarkan kepada negeri,
jangan yang tujuh macamnya, camkan sungguh-sungguh,
sungguh-sungguh, jangan hilangkan dari hatimu jika herdak bertuat sesuatu,
Pertama, lihat kesudahan perbuatan itu dan perialasan Allah Taala, barulah mengerjakannya, kedua, takutlah (= seganlah) kepada orang jujur;
ketiga, jangan mengingkari janji;
keempal, jangan takut mendengar berita, jadikan pertimbangan begitu pula orang yang membawa berita;
kelima, rajinlah mendengarkan peringatan;
keenam, hendaknya janganlah engkau memulai perbuatan yang sukar,
jangan pula mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati orang,
ketujuh, rajinlah meminta pertimbangan To-Mabbicaramu75
sebelum melakukan apa yang disebut oleh jori (garis ketentuan),
mudah-mudahan engkau terhindar dari kejahatan lawanmu.
Bila hendak memperoleh kebaikan dunia dan akhirat
janganlah engkau biarkan yang buruk mere-sapi yang baik.76
Jangan sampai terlintas di hatimu,
bahwa ada hal yang tak diketahui Allah Taala.
Jangan pula terdapat dalam angan-anganmu
bahwa ada perkataan yang tak didengar oleh Allah Taala.
Jangan pula menduga bahwa ada angan-angan yang
tak diketahui oleh Allah Taala, apabila engkau melihat
orang berbuat aniaya (= sewenang-wenang),
buruk angan-angannya (akan tetapi) baik juga
kedudukan dunianya, niscaya kemurkaanlah adanya,
alamat akan ditimpakan oleh oleh Tuhan bala kepadanya,
atau di akhirat nanti akan dibalas perbuatannya.
Bila rahmat yang baik akan didatangkan oleh
Allah Taala kepada hambanya, maka perbuatan yang baik
serta pikiran yang benarlah yang diperbuat oleh orang,
dan itulah titiannya, maka bahagia kehidupan dunianya.
Oleh karena itu diharapkan agar engkau tanamkan
dalam hati dan perbuatanmu pikiran yang baik
serta perbuatan yang benar, karena apabila Allah Taala
hendak melimpahkan kepada hamba-Nya,
apakah hal yang baik atau yang buruk,
tak dapat tiada hal itu bersumber dari niat hati dan perbuatan.
Seperti pada ajaran, perbuatan baik yang ditanam di hati seseorang,
perbuatan baik pulalah buahnya, perbuatan buruk yang di hati seseorang,
pebuatan buruk pulalah yang dibuahkannya.
Itulah yang dimaksudkan oleh para ulama ketika
dikatannya bahwa adapun hati itu adalah
wadah yang disediakan oleh Allah Taala.
Apabila hal yang buruk yang engkau tempatkan ke dalam hatimu,
maka yang buruk itu pulalah diisikannya ke dalam hatimu.
Apabila hal yang baik engkau tempatkan ke dalam hatimu,
maka hal yang baik itu pulalah yang diisikannya.
Oleh karena itu diharapkan agar dimliki dengan sungguh-sungguh sikap hati 77
yang baik terhadap sesama manusia.
5/
Berkata pula To-Riolo bahwa mereka yang
diangkat menjadi parewa. it-tanae (= alat kekuasaan negara)78,
artinya pakkatenni ade (= pemegang kekuasaan)79
ialah mereka yang memilki empat sarat.
Pertama, mempunyai karsa (= inisiatip)80;
kedua, jujur 81;
ketiga, berani;
keem-pat, kaya.
Dan adapun tanda orang yang mempunyai karsa,
empat pula macamnya:
pertama, takut kepada dewata (= taqwa);
kedua, takut ber-kata yang buruk;
ketiga takut berbuat aniaya;
keempat, takut mengambil cekka (berbuat tak jujur)82.
Dan adapun tanda kejujuran itu ada empat juga macamnya.
Pertama, berbuat dengan cermat;
kedua, melakukan perbuatan yang benar;
ketiga, melakukan hal yang baik;
keempat mela-kukan hal yang sungguh-sungguh.
Dan adapun tanda orang yang berani ada empat juga macamnya.
Pertama, tak takut ia dikedepankan;
kedua tak takut ia dikebelakangkan83;
ketiga, tak takut ia mendengar berita;
keempat, tak takut ia menjumpai lawan.
Dan adapun tanda orang kaya ada empat juga macamnya.
Pertama, tak habis-habisnya karsanya84;
kedua, tak berkekurangan jawaban
dan jawaban yang tepat yang diper-gunakannya;
ketiga, dimahirinya semua pekerjaan;
keempat, tak berke-kurangan dalam semua karya85
Berkata pula To-Riolo, ada dua macam perbuatan (hal) yang
saling mencari dan bersua, yakni perbuatan baik,
serta perbuatan yang sewa-arnya.
Barulah ia itu menjadi baik, jika keduanya bersua.
Dan adapun cara menemukan kebaikan itu,
ialah membiasakan diri berbuat baik.
Walaupun sukar, biasakanlah dirimu melakukannya.
Kedua, rendahkanlah dirimu pada silasana (=kepatutan).
Harapkanlah balas kasih sewajarnya.
Keempat bekerjalah dengan ikhlas.
Kalau menemui semuk-semuk (rintangan), kembalilah.86
Keenam, melalui jalan, waspadalah dan berserah diri pada Dewata.
Perbuatan yang enal macamnya itulah jalan menuju kebajikan.
Berkata To-Riolo, janganlah dicela oleh ade87,
jangan dihina oleh bicaro, Jangan pula dicibir
oleh rapang dan jangan pula ditertawakan bicen wari.
Peliharalah perbuatan yang empat macamnya.
Yang empat ini jugalah yang disebut sung-baruga (= sudut balai pertemuan)88.
Usahakanlah menduduki sunna-barugae (sudutnya balai pertemuan),
walau satu saja, apalagi bila engkau dapat menduduki.
Pertama, yang disebut sung-baruga ialah jangan engkau
mau terpandang sebelah mata89 ditengah-tengah orang banyak;
kedua, pandai membangun kalimat, serasi jawabannya
dan memberi jawaban sesuai dengan pertanyaan;
ketiga, menyambung kalimat dan sambungan kalimat itu pada tempatnya;
keempat, malu-malu itu tak nampak oleh kejantanan90,
walaupun bukan juga towa-rani (= pemberani/perwira).
Karena diinjak oleh sesamamu laki-laki tak akan
bisa kau tanggungkan, kau akan diketawai orang.
Apalagi bila engkau sungguh-sungguh berani,
sempurnalah kebaikannya. Jika engkau
tidak duduki (= kuasai) satu pun sung-baruga itu,
maka diketawailah engkau oleh wari,
dan juga oleh ade, dicibirlah engkau oleh rapang,
dihinakanlah engkau (oleh) bicara.
Berkata pula To-Riolo, ada empat macamnya aju-tabu (kayu rapuh)91
dan jangan mencoba-coba menyandarinya.
Pertama, aju-tabu yang percaya semata-mata kepada kepintarannya,
tanpa mengingat kekuasaan Allah Taala;
kedua, yang percaya kepada kekayaannya;
ketiga, terlalu mengandalkan diri sebagai bangsawan tinggi92;
keempat, menganggap dirinya to-warani,
padahal tidak dicapainya. Itulah yang disebut
aju-tabu yang empat macamnya.
Dan adapun tanda kecelakaan itu dua juga
pertama, jangan bercemburu terhadap orang yang beruntung;
kedua, jangan ketawai pemberian (= kehendak) Dewata93.
Berkata pula To-Riolo, dua macamnya perbuatan
yang orang tak mampu berdiri di depannya (= melawannya).
Pertama, kebenaran;
kedua, keunggulan.
Pancaran cahaya dari tanah-tanah Bone memberi terang
jalan di darat dan lautan,
Kerajaan Gowa dan kerajaan-kerajaan sekitarnya,
menikmati segala bijak dan nasihat,
menjadikannya petunjuk untuk membangun manusia,
seutuhnya, rakyat dan penguasa.
Selalu terngiang,
—manusia itu, makhluk yang sama derajatnya sebagai ciptaan Tuhan.
—manusia itu, tujuan hidupnya berhasrat selalu berbuat kebajikan.
—manusia itu, selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan bersama dengan kepentingan individunya.
Itulah Latoa
: Kitab Bagi Pemimpin Bangsa.
Bogor-Silangit-Siborongborong,
September-Oktober 2024
Dwi Rahmad Muhtaman
1 Mawa-nawapatuju: “pikiran yang benar”
2 La Galigo Edisi standar oleh Prof. Nurhayati Rahman (UNHAS, 2015) mencantumkan contoh pantun dalam konteks kisah Sawerigading (hlm. 217).
3 Pelras, C. (1996). “The Bugis” (hlm. 213). Blackwell Publishers.
4 Mattulada (1985). “Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis” (hlm. 57). Universitas Hasanuddin.
5 Naskah Lontara Latoa, transliterasi oleh Prof. Nurhayati Rahman (2010), Pusat Studi Bugis-Makassar UNHAS. Baca juga Rahman, N. (2010). Transliterasi Lontara Latoa. Makassar: Pusat Studi Bugis-Makassar.
6 Saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai buku karya Prof. Mattulada, Latoa yang terbit tahun 1985 (Gadjah Mada University Press). Buku ini saya peroleh dari koleksi kakak saya waktu itu yang belajar di Jurusan Antropologi, FISIP, Universitas Udayana. Dibaca berkali-kali bolak-balik, cari rujukan-rujukan nasihat. Saya sangat terkesan dengan karya kanonik Latoa ini sehingga mendorong saya untuk menuliskan dan mengutipnya dalam bentuknya yang saya sukai: sajak. Buku ini merupakan bentuk populer dari karya desertasi doktoral Prof. Mattulada. Dari buku inilah saya mendapatkan inspirasi untuk menulis ulang dalam bentuk yang saya inginkan. Penulisan dengan mengutip buku Latoa ini saya lakukan karena kekaguman saya atas karya kanonik Latoa dari Suku Bugis di Bone yang luar biasa, yang hampir setara dengan karya Suku Bugis lainnya yakni La Galigonya. Bentuk baru ini saya tulis tanpa ijin dari Prof Mattulada. Semoga Prof. Mattulada berkenan. Sebagian besar dari materi yang ada dalam sajak ini saya kutip langsung (khususnya semua percakapan) dari Buku Latoa tersebut, termasuk catatan akhir (endnote). Tulisan ini saya sadur dan gubah dari bagian yang ada pada buku tersebut khususnya pada halaman 79-125. Semua perubahan yang saya lakukan, baik sebagian kata, penambahan paragraf, struktur penulisannya dan hal-hal lain, adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.
Seperti ditulis Mattulada bahwa dalam BKI. No. 103-1946, Ph.S. van Ronkel, mengarang Aanvulling der Beschriving den Malaische en Minangkabausche Handschriften, Benevens een Atjehsch Handschrift, in het Bezit van het Kon. Institut voor de Taal, Land-en Volkenkunde van Nederlands-Indie (Tambahan Deskripsi Naskah Melayu dan Minangkabau, serta sebuah Naskah Aceh, yang Dimiliki oleh Institut Kerajaan untuk Bahasa, Tanah, dan Budaya Rakyat Hindia Belanda). la menyebut berbagai kutipan tentang Latoa, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di antaranya No. XCVII Hikayat Batara Guru, disebut sebagai berikut”……opgenomen in de Kroniek van Latowa XCVII en volgende. Kroniek van Latowa folio 94 blz. 62 r. Lat. schrift typewritten. Alleen de linkerhelft der blz. is bes-chreven. Het HS. is verdeoold in 13 hoofdstukken. Deel I blz. 1-95, is het verhaal vam Kadjaolaliddong en Aroempone, den Vorst van Bone. Vertaling van de complete Latowa van Dr. B.F. Matthes door Toepoe Daeng Mappoeli, oud Hoofd-onderwijzer, in samenweking met H.R. Rookmaker, Controleur van Bone, October 1918. (BKI 103-1946, p. 560)” (“Dikutip dalam Kronik Latowa XCVII dan seterusnya. Kronik Latowa folio 94 halaman 62 r. Tulisan Latin diketik. Hanya separuh kiri halaman yang ditulis. Naskah ini dibagi menjadi 13 bab. Bagian I, halaman 1-95, adalah kisah Kadjaolaliddong dan Aroempone, penguasa Bone. Terjemahan lengkap Latowa oleh Dr. B.F. Matthes dilakukan oleh Toepoe Daeng Mappoeli, mantan Kepala Guru, bekerja sama dengan H.R. Rookmaker, Kontrolir Bone, pada Oktober 1918. (BKI 103-1946, hlm. 560).” Beberapa kata-kata penting atau kalimat dalam terjemahan Toeppoe Daeng Mappoeli dan H.R. Rookmaker, berbeda dari terjemahan ini, dictat dalam note.
Latoa adalah sebuah naskah atau kitab kuno yang menjadi salah satu warisan budaya terpenting dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Naskah ini berisi kumpulan nasihat, panduan etika, dan kebijaksanaan politik yang disampaikan melalui dialog dan cerita tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Latoa sering dianggap sebagai panduan moral dan politik bagi para pemimpin, terutama raja-raja Bugis, yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Bugis seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesetiaan.
7 Perjanjian Caeppa adalah perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa pada tahun 1565. Perjanjian ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah hubungan antara kedua kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama karena mengakhiri konflik yang berkepanjangan di antara mereka dan membawa kebahagiaan bagi Kerajaan Bone serta kerajaan-kerajaan Bugis lainnya.
Latar Belakang Perjanjian
Pada abad ke-16, Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa sering terlibat dalam perselisihan dan peperangan, yang didorong oleh persaingan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh masing-masing. Gowa, yang merupakan kerajaan besar dengan pengaruh kuat di wilayah pesisir, berusaha untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Bugis, termasuk Bone, yang merupakan salah satu kerajaan Bugis yang terkemuka di wilayah daratan.
Isi dan Dampak Perjanjian
Perjanjian Caeppa pada tahun 1565 dianggap sebagai peristiwa yang membahagiakan bagi Bone dan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya karena menandai berakhirnya konflik dengan Gowa. Perjanjian ini memungkinkan Bone dan kerajaan-kerajaan Bugis untuk mempertahankan kedaulatan dan otonomi mereka, sekaligus mengurangi tekanan dari Gowa yang ingin memperluas kekuasaannya di wilayah Bugis.
Dalam Latoa, sebuah naskah penting yang mencatat sejarah dan kebijaksanaan politik para raja Bugis, perjanjian ini disebut sebagai momen penting yang mencerminkan upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Sulawesi Selatan. Latoa mencatat bahwa perjanjian tersebut disambut dengan sukacita oleh masyarakat Bugis karena menciptakan suasana damai yang memungkinkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di antara kerajaan-kerajaan Bugis.
Sumber-Sumber Sejarah
Perjanjian Caeppa menjadi bagian penting dalam narasi Latoa, yang menyoroti bagaimana para raja pada masa itu berusaha mencari solusi damai untuk menghindari peperangan yang merusak. Hal ini menunjukkan kecerdasan politik dan kemampuan diplomasi para pemimpin Bugis dalam mempertahankan kedaulatan mereka di tengah dinamika kekuasaan yang rumit di wilayah tersebut.
Sebagai referensi lebih lanjut, karya “Latoa: Satu Kajian Sastra Bugis” oleh Muhammad Salim memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana Latoa mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting seperti Perjanjian Caeppa dan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi tatanan sosial politik di Sulawesi Selatan.
Dalam buku Latoa, Prof. Mattulada, disebutkan Latoa adalah sejenis lontara dalam kepustakaan berbahasa Bugis dari Tana-Bone. Penulisan Latoa diduga pada zaman raja Bone ke-7 yang bernama La Tenrirawe Bongkannge (1560-1578). Baginda mempunyai seorang penasehat, orang bijaksana bernama La Mellong, anak seorang Kepala Desa di sebuah desa yang bernama Laliddong, dalam wanua (daerah) Cina, Tana-Bone. La Mellong inilah yang pada masa tuanya terkenal dengan sebutan Kajao Laliddo, yang berarti orang pandai (bijaksana) dari Laliddo atau orang-tua dari Laliddo.
Menurut anggapan umum di kalangan orang Bugis, Latoa berisi pembicaraan antara Kajao Laliddo dengan Arumpone (Raja Bone). Anggapan umum tersebut tidak seluruhnya benar, dan karena itu pula tidak seluruhnya salah. Menurut batasan yang lebih terurai, kita dapat mengemukakan bahwa Latoa adalah lontara’ dalam kepustakaan orang Bugis yang berisi kumpulan dari berbagai ucapan dan petuah raja-raja dan orang-orang Bugis-Makassar yang bijaksana dari zaman dahul (termasuk Kajao Laliddo) mengenai berbagai masalah, terutama berkenaan dengan kewajiban-kewajiban raja terhadap rakyat dan sebaliknya. Latoa dijadikan tuntunan bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan. Persamaan dengan “rapang” orang Makassar dikemukakan Matthes (1872 : halaman 109) dalam MChr. pada halaman 456 s/d 460 dan halaman 471 s/d 480.
Latoa yang termuat dalam B. CHr. atas usaha B.F. Matthes dan dicetak dalam tahun 1872 adalah salinan lontara tulisan tangan (Hansdschrift – HS) Arung Pancana, yang khusus disalin dengan indah buat Matthes. Lontara HS yang berasal dari Arung Pancana Tua (La Paga lipue Colli pujie) tersebut sebagian
- Lihat daftar raja-raja Bone, pada Bab I.
- Laliddo, sebutan sesungguhnya dahulu adalah Laliddong. Sekarang orang Bugs umumnya, menyebutnya dengan Laliddo saja.
8 Ketiga pola sikap umum yang mendasari alam pikiran yang dituangkan dalam Latoa ini memberikan bentuk perwujudan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sosial-budaya, yang disebut pangaderreng. Inilah yang menjadi ukuran tingkah-laku sosial dan budaya. Kalau kita memperhatikan sekian buah pikiran dalam Latoa sebagai himpunan pedoman tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah normatif yang ideal bagi orang Bugis pada zamannya, kita akan menjumpai bahwa pola-pikir itu telah memberikan tempat terhormat kepada manusia sebagai makhluk yang bermartabat, sederajat dengan sesamanya, apapun kedudukan sosial dan asal keturunannya. Pola sikap yang demikian itulah yang dipergunakan oleh orang Bugis dalam nenyongsong kedatangan Islam dan menghadapi orang Barat yang dianggap sangat berlainan dengan pandangan hidupnya karena terutama ditujukan untuk mencari keuntungan-keuntungan ekonomi dan kekuasaan. Pertemuan dua cara berpikir yang berbeda, yang satu didorong olat kehendak praktis menguasai dan yang lain didorong oleh keinginan berbuat kebaikan kepada semua orang berdasarkan prinsip persamaan, akhirnya mengakibatkan kalahnya pola pikir yang berkehendak berbuat kebajikan (Mattulada, hal. 87).
Penaklukan atas fitrat berbuat kebajikan ini, menyebabkan timbulnya, ekses-ekses yang jauh dalam sikap hidup menghadapi lingkungannya. la menjadi liar, menjadi sangat curiga kepada tiap hal yang baru, menjadi pengecut dan selalu dapat berbuat eksplosif, seolah-olah lahir dari emosi yang tak terkendali. Keadaan jiwa demikianlah yang diwarisi orang Bugis, yang bekas-bekasnya rupanya mash berbuntut sampai pada hari ini. Pada zaman itu, penguasa di Tana-Ugi’ telah menjadikan kaidah positif untuk memberikan tempat kepada milik seseorang dan menghormatinya (Mattulada, hal. 88).
Setiap orang tak akan mengganggu milik orang lain, dan menghormati prinsip itu sebagai tata-hidup yang benar (Latoa, al. 17). Dapatkah hal ini dianggap suatu ide yang terbelakang pada zaman itu? Bilamana sudah dihargai adanya milik perorangan, bukankah pemiliknya berarti mendapat penghargaan yang lebih patut lagi? Rasionalisasi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, berarti membebaskan pikiran orang dari belenggu anggapan bahwa raja adalah penitisan dewa-dewa yang sanggup memberikan kebahagiaan pada rakyanya hanya karena berkat kedewataannya atau berkat namanya atau kharismanya. Anggapan demikian telah ditolak pada zaman itu dalam sistem pangaderreng orang Bugis. Hal itu tak dipercaya lagi! Bukankah ini suatu sikap rasional yang sesungguhnya, yang berarti bahwa raja atau apapun kedudukannya, hanyalah manusia biasa. la dapat membuat negara yang dipimpinnya runtuh kalau ia ceroboh, kalau ia tak mau lagi diperingatkan, kalau ia tak lagi menghormati peranan orang berilmu, dan kalau ia menerima sogok (Latoa, al. 23). Bahwa negara sungguh-sungguh dapat dijadikan negara yang jaya di mana rakyat berbahagia, bukan karena penguasa itu keturunan dewa-dewa yang bermana melainkan karena kecakapan dan kejujuran penguasa itu (Latoa, al. 25). Keakapan itu bukanlah sesuatu yang terwujud begitu diucapkan; ia harus dapat dinyatakan dalam perbuatan (Latoa, al. 19 dalam Mattulada, hal. 88).
Kekuasaan atas rakyat harus dijalankan atas dasar niat yang benar. Niat yang benar harus bersandar pada keberanian, dan keberanian bertolak dari niat yang benar. Niat yang benar dan keberanian lahir dari kejujuran (Latoa, al 32). Sebelum menjalankan kekuasaan yang ada padaya, penguasa (raja) pertama-tama harus diperhadapkan kepada kekuasaan itu. Jika ia sanggup memikulnya, barulah kekuasaan itu dijalankan atas orang lain (Latoa, al. 33). Raja atau penguasa sesungguhnya adalah manusia yang bertekad berbuat kebajikan bagi sesamanya manusia, dan tiap orang punya kehendak yang sama terhadap sesamanya manusia. Nilai-nilai inilah yang menandai orang Bugis di zaman Latoa, tiga atau empat abad yang lampau. Seperti digambarkan oleh von Schimd (1932), di Eropa Barat dalam abad-abad pertengahan, khususnya abad XVIXVII, yang umum berlaku.
9 Lempu,
”keadilan”, menurut kami kejujuran.
10 lato taniato, “setengah benar”
11 Tanana, “negerinya”
12 (= sebab dan akibat)
13 (= menjawab)
14 (= Duta)
15 Panngaderreng, “Raad Adat”, sehingga kalimat “Tettassalae ri Pangaderreng”, diterjemahkan dengan, “Yang selamanya menegakkan Raad-Adat”.
16 Rapang, dalam kalimat ‘Tettassalae ri rapannge”, “yang selamanya menetapkan raad Adat”.
17 Bicara, dalam kalimat “Tettakkalupae ri bicarae”, : “yang tidak melupakan perkara”
18 Lempu e: “Keadilan”
19 (= seruan)
20 Gaue: “Kelakuan itu”, menurut kami perbuatan
21 Tanra cinna matena tanaE, “alamat negeri besar akan kena bencana”.
22 Ling-lingae, “khianat”, menurut kami, kecerobohan.
23 (= hakim)
24 (= disogok)
25 Atanna, “rakyatnya” menurut kami, abdinya.
26 Tula pattaungeng, Menulak pertahuan (membinasakan hasil tanah).
27 Matanre cinnai,
”amat menyukai atas barang sesuatu”.
28 Komalepu’i, “Adil hukumnya”.
29 Ade e, “Raad adat”.
30 Bicara, “zaak”.
31 Rapang, “undang-undang”.
32 (= ibarat)
33 Passeajinggi tana masseajinnge, “meneguhkan persahabatan negeri yang bersahabat”
34 Temmagettenni bicarae, “bicara itu tidak tetap”
35 Wari! “Aturan perbedaan pangkat kebangsaan”.
36 Appongenna ade e : “Asal tumbuhnya raad-adat itu”.
37 Mappasilasa e: “Perihal mematutkan (menimbang) perkara”. (= memberikan keseimbangan)
38 Appengenna bicarae :
”Asal tumbuhnya bicara (zaak) itu”
39 Mappassane : “Adu-mengadu perinal dan perkataan perkataan.” (= saling menyembuhkan)
40 Siariwawonnge : “Yang tingi dan yang rendah”
41 Mappasenrupae : “Perihal menyerupakan suatu perkara dengan yang lain.” (= saling menghormati), (menserupakan)
42 Mappallatengnge “Peel meyer derant (pangkai tiap bangsa). (= yang tahu membedakan)
43 Dalam khasanah Latoa—sebuah teks sastra dan panduan etika dalam tradisi Bugis—terdapat dua konsep penting yang terkait dengan struktur kepemimpinan, yaitu To-riolo dan To-matoa. Keduanya merujuk pada tokoh atau golongan yang memiliki peran penting dalam masyarakat dan sistem politik Bugis.
1. To-riolo
To-riolo secara harfiah berarti “orang-orang terdahulu” atau “leluhur.” Dalam konteks Latoa dan masyarakat Bugis, To-riolo merujuk kepada para leluhur atau pendahulu yang dianggap sebagai tokoh bijaksana dan memiliki kewibawaan tinggi. Mereka adalah sosok-sosok yang dihormati karena kebijaksanaan, pengalaman, dan pengaruh besar mereka dalam membentuk norma-norma dan adat-istiadat masyarakat Bugis.
Peran To-riolo bukan hanya sekedar figur historis, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya. Mereka dihormati dan sering kali menjadi sumber kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan besar di masyarakat. Sosok To-riolo juga menjadi representasi dari warisan sejarah yang harus dijaga dan dihormati oleh generasi berikutnya.
Dalam Latoa, To-riolo memiliki pengaruh penting dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Nasihat dan nilai-nilai yang mereka wariskan menjadi pedoman moral bagi para pemimpin Bugis yang memegang kekuasaan.
2. To-matoa
To-matoa dalam bahasa Bugis berarti “orang tua” atau “yang dituakan.” Dalam struktur sosial dan politik Bugis, To-matoaadalah sosok-sosok yang memiliki posisi tinggi karena usia, kebijaksanaan, dan pengaruhnya. Mereka dianggap sebagai pemimpin informal dalam masyarakat, orang yang dihormati karena pengalaman hidupnya dan kedalaman pemahamannya tentang adat istiadat.
Dalam Latoa, To-matoa berfungsi sebagai penasihat utama bagi para penguasa atau raja. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat bijak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, etika, dan hubungan antar-kerajaan. Kedudukan mereka tidak hanya didasarkan pada otoritas formal, tetapi juga pada kebijaksanaan moral dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.
To-matoa sering kali menjadi mediator dalam konflik, baik di dalam kerajaan maupun antar-kerajaan. Peran mereka yang netral dan dihormati menjadikan mereka sebagai tokoh yang dapat menyeimbangkan kekuasaan dan menjaga stabilitas sosial serta politik.
Makna dalam Konteks Latoa
Baik To-riolo maupun To-matoa memiliki peran sentral dalam mempertahankan tatanan sosial dan menjaga keberlangsungan adat Bugis yang kaya akan nilai-nilai etika dan moral. Keduanya menjadi simbol penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas politik, serta menjadi referensi moral bagi para pemimpin dan masyarakat Bugis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Latoa sendiri merupakan salah satu karya sastra yang memuat nilai-nilai dan kebijaksanaan yang berasal dari tokoh-tokoh seperti To-riolo dan To-matoa. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelindung adat, tetapi juga sebagai penuntun dalam memimpin masyarakat yang lebih besar.
Secara keseluruhan, To-riolo dan To-matoa adalah figur sentral dalam masyarakat Bugis yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga tatanan dan etika kehidupan Bugis, terutama dalam konteks pemerintahan dan hubungan sosial.
44 Mawa-nawapatuju: “pikiran yang benar”
45 Lempu: “Adil”
46 to-rimmurimmu: “anak cucumu”
47 eppa rupanna: “empat bahagian”.
48 mappasala nawa-nawa: “menghilangkan pikiran”.
49 elo e: “kehendak yang amat sangat”.
50 mappasalatoi passu ada: “menjalankan perkataan”.
51 gau situju-tujue: “perihal yang sedang itu”
52 ada madecennge: “perkataan yang manis”.
53 ula-ada: “perkataan”.
54 ade tenriabata-batae: “adat-istiadat (gewoonte) yang tetap”.
55 siaksiriseng ri lalempanua; “tiada memalui seorang dengan yang lain dalam negeri”.
56 lessimelekiannge ininnawa ri sempanuanna; “tidak sampai hati seorang dengan yang lain kepada senegerinya itu”
57 jowa; “hamba raja”
58 madancannga; “menganiaya kepada anak negeri”.
59 ingerangi ade e enrennge rapannge; “Ingatlah olehmu undang-undang”.
60 ode pa natestong hendal rap arse; englan turan”
61 mottonngenngi adanna taue; “yang dapat menindis perkataan orang itu”
62 addanrenngeng ri to maccae; “sandaran daripada orang bijaksana”.
63 Bicara rongettellue; tak diteriemahkan oleh Toeppoe dan kawan-kawannya.
64 Bicara situru e;
”bicara bersepakat”
65 Bicara dope; “bicara yang didiamkan beberapa hari”.
66 toppegau bawang; “sipenganiaya”
67 labo sialong palece; “kemurahan dengan membujuk” naia riasennge lempu; “adapun keadilan itu”.
68 naia riasennge lempu: “adapun keadilan itu.”
69 asseajingennge; “persanak-saudaraan”
70 tessicirinnaiannge ri silasanae; “tidak kikir seorang dengan yang lain atas barang sepatutnya”.
71 ade = “adat (raad adat)”; rapang= “undang-undang”: wari = “aturan perbedaan pangkat kebangsaan”; bicara =
“bicara”; sara = “syara”
72 Bara kuammeng parirebba fo-mauarannge, naripeutangi t-madodonnge = “mudah-mudahan lemah orang yang kuat dan kuat orang yang lemah.”
73 Aja nawedding naottong ulu-ada balta= “mudah-mudahan musuh kita”.
74 Aja naengka salibanana tal-ada “supaya negara itu sentausa adanya”.
75 Mapatanga ri to-mahicaame = “merinta pikiran (pertimbangan) kepada pegawaimu”.
76 naselung anu mo-m abbi rade = me yang halal jangan engkau campurkan dengan yang riba
77 Sikki ati madaceng; “akal budi yang baik”.
78 Parewa ri tanae = “pegawai dalam negeri”
79 Toeppoe Dg. Mappoei, menyamakan saja dengan “Pegawai dalam negeri”.
80 kenawa-nawapi = “akal-budi”
81 malempu = “adil”
82 matau mala cekka = “takut berkesalahan”.
83 Tematau i pariolo, tenuter es parimunni – “tidak takur berjalan ke hadapan, tidak takut ditinggalkan dibelakang”
84 tekkuranggi nawa-naunan – “tidak kekurangan akal-budi:
85 tennakurangiwi ri sininna pattujunnge = tiada kekurangan daripada pikiran yang berguna”
86 mole roppe pareue = “berjalan ke semak-semak maka la kembali artinya: Jika pekerjaan itu, bakal menjadi kejahatan pada akhirnya, baiklah dihentikan pekerjaan itu”.
87 nacacca ade = “dicela raad ade”.
88 sung baruga atau su baruga = “penjuru balairung”.
89 rita wiring – “diabaikan atau dimulai”.
90 tenrita alongkorennge ri aoroanengennge = :Jangan sampaik mau dimulai atas nama laki-laki itu.”
91 aju-tabu = “kayu gaba-gaba”.
92 Arummatase – “raja bangsawan”
93 taro dewata = “kehendak Dewata, yakni orang buta, timpang, dan sebagainya