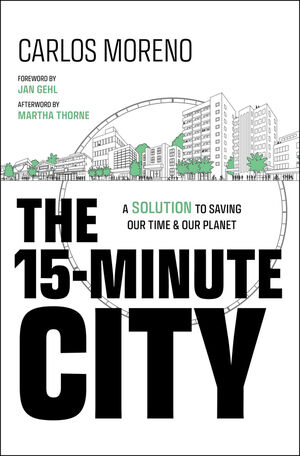Sustainability 17A #62
Menjalin Kembali Kekuatan Kolaborasi
Ekspedisi LATIN ke Kuningan dan Garut
Sebuah Catatan Ekspedisi1
Dwi R. Muhtaman,
Sustainability Partner
“Saya ingin membangkitkan
kesadaran anak muda desa
agar tidak melulu memimpikan
kehidupan kota.
…, kampung pun bisa memberi masa depan.”
Samsul, pemilik dan pengelola
Kafe Es Kopian, Majalengka
Daftar Isi
Sosial Forestri 2045 Kabupaten Kuningan
Ruang pertemuan itu pada Senin, 25 April 2022, penuh dengan semangat yang ditebarkan oleh semua yang hadir. Seperti berjumpa dengan sahabat lama yang merindukan perbincangan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan lebih dari 20 tahun lalu. Aula BAPPEDA Kabupaten Kuningan ini menjadi saksi pentingnya menjalin kembali kolaborasi untuk menjadikan sosial forestri sebagai jalan baru masa depan. Karena itulah dengan antusiasme yang sama Tim ekspedisi LATIN mengunjungi kembali jejak-jejak sejarah yang pernah digoreskan di Kabupaten Kuningan.
LATIN menawarkan Diskusi Sosial Forestri 2045 yang mendapatkan sambutan dengan semangat itu. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti BAPPEDA, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Perhutani Kuningan, LSM KANOPI, serta tokoh-tokoh penggerak kehutanan masyarakat. Forum ini membahas situasi mutakhir perhutanan sosial di wilayah Kuningan, terutama setelah sebagian kawasan hutan produksi berubah menjadi kawasan konservasi. Diskusi juga menggali dampak perubahan tersebut terhadap kelembagaan lokal yang sebelumnya aktif dalam skema PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).
Propinsi Jawa Barat merupakan wilayah bagi Perhutanan Sosial seluas 86.556,64 Ha dengan melibatkan 53.506 keluarga dan mendapatkan 390 Surat Keputusan. Kabupaten Kuningan, yang terletak di kaki Gunung Ciremai, merupakan wilayah dengan kekayaan ekosistem hutan yang penting bagi penyangga kehidupan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap sumber daya hutan di daerah ini semakin meningkat seiring bertambahnya kebutuhan ekonomi penduduk. Namun, alih-alih terus menerus menghadapi konflik kepentingan antara konservasi dan pemanfaatan, masyarakat dan negara mencoba membangun jembatan kolaboratif melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH).
Sementara itu Kabupaten Kuningan sedikitnya terdapat 60 Kelompok Tani Hutan (KTH). Total anggota bervariasi, namun banyak KTH yang beranggotakan 20–50 orang terdiri dari petani, tokoh masyarakat, dan pemuda desa. Dalam konteks ini, hutan tidak lagi dipandang sebagai entitas terpisah, tetapi menjadi bagian dari sistem kehidupan lokal yang bisa dikelola bersama secara adil dan berkelanjutan. Mereka bekerja wilayah antara desa-desa seperti Cileuya, Garajati, Cikadu, Karanganyar, Ciberung, dan lainnya. Mayoritas kelompok beroperasi dalam skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)—sebuah pendekatan yang memungkinkan masyarakat sekitar hutan untuk berperan langsung dalam menjaga, memelihara, sekaligus memanfaatkan hutan secara lestari.
Kegiatan kelompok sangat beragam, mulai dari penanaman pohon kayu dan buah-buahan, pemeliharaan tanaman kehutanan, agroforestri, hingga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu, bambu, dan kopi. Beberapa kelompok bahkan mulai menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lokal dan koperasi desa untuk memperkuat rantai nilai dari produk hutan mereka.
Yang menarik, sejumlah kelompok didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Kanopi, yang berperan sebagai fasilitator, pendamping hukum, hingga penyambung lidah antara masyarakat dan Perhutani. Kehadiran LSM ini terbukti mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan KTH, baik dalam perencanaan kegiatan maupun dalam partisipasi masyarakat pada tataran implementasi.
Model kolaborasi ini menjadi contoh nyata bahwa konservasi tidak harus berarti pelarangan, dan penghidupan tidak selalu identik dengan eksploitasi. Justru, ketika masyarakat diberi ruang untuk berperan dan merasa memiliki, hutan dapat menjadi sumber kesejahteraan sekaligus kekuatan ekologis yang lestari.
Secara umum, KTH di Kuningan menunjukkan wajah kehutanan yang inklusif, di mana nilai-nilai gotong royong, kearifan lokal, dan prinsip keberlanjutan berusaha dijalankan secara nyata dalam pengelolaan hutan negara.
Jejak Kanopi Kuningan dan LATIN
Tentu saja keadaan yang terlihat saat ini bukan tanpa perjuangan awal. LATIN dengan mitra lokal Kanopi Kuningan memprakarsai PHBM pada tahun 2000, ketika PHBM masih belum mendapatkan perhatian dalam aspek kebijakan pemerintah. LATIN melihat PHBM sebagai sebuah pendekatan yang penting karena membuka ruang dan hak kewajiban yang lebar bagi masyarakat untuk mengelola hutan sebagai bagian dari ruang kelola kehidupan. Perhutani mengeluarkan kebijakan PHBM resmi berdasarkan Keputusan Direksi PT Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Program PHBM merupakan inisiatif dari Perum Perhutani yang dirancang untuk mengatasi berbagai konflik yang muncul dalam aktivitas pengelolaan hutan. Keberhasilan implementasi PHBM sangat bergantung pada keberadaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian hutan serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan Perum Perhutani (Theresia, 2008). Namun demikian, perlu dipahami bahwa perbedaan karakteristik antar-stakeholder dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat menjadi pemicu munculnya konflik. Bila konflik ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif, baik bagi para stakeholder maupun terhadap kelangsungan sumber daya hutan itu sendiri (Hidayah, 2012).
Berdasarkan Keputusan Direksi PT Perhutani, PHBM merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan, serta/atau melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sistem ini dibangun atas semangat berbagi (sharing spirit) untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan proporsional.
Tujuan utama dari pelaksanaan PHBM adalah memberikan arah dalam pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan secara seimbang aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara profesional. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, serta pihak-pihak terkait lainnya terhadap keberlanjutan sumber daya hutan.
Secara lebih rinci, tujuan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
- Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- Memperluas akses masyarakat desa hutan terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya hutan.
- Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dengan pembangunan wilayah, sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- Meningkatkan usaha-usaha produktif yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa hutan dalam rangka mendukung terciptanya hutan yang lestari.
PHBM dilaksanakan berbasis pada wilayah Desa Hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, mencakup ruang lingkup berbasis lahan maupun non-lahan. Perencanaan dilakukan secara partisipatif, dengan mempertimbangkan skala prioritas. Penting untuk ditegaskan bahwa pelaksanaan PHBM tidak mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan, maupun status tanah milik perusahaan.
Selain sebagai pendekatan pengelolaan, konsep PHBM juga dapat dimaknai sebagai suatu resolusi konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hidayah (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa PHBM dapat menjadi mekanisme resolusi konflik melalui program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut mencakup peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya hutan, penguatan interaksi antar-stakeholder, serta peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan.
Rintisan kerja Kanopi Kuningan dan LATIN dalam program Perhutanan Sosial di Kabupaten Kuningan adalah di Desa Cileuya dan Desa Sukasari. Keduanya menjadi model praktik lapangan dari kolaborasi tripartit antara masyarakat, Perhutani, dan Pemerintah Daerah. Dari wilayah inilah benih harapan bagi kehutanan partisipatif tumbuh secara lebih konkret.
Cileuya merupakan salah satu desa awal yang mengembangkan pola PHBM sejak tahun 2000-an. Dengan pembentukan Kelompok Tani Hutan, masyarakat mulai aktif dalam penanaman pohon, menjaga kawasan, hingga berbagi hasil secara adil dengan Perhutani. Studi terdahulu (Kusumaningtyas, 2003) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Cileuya tergolong tinggi, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan PHBM.
Masyarakat tidak hanya hadir sebagai pekerja lapangan, tetapi terlibat dalam pengambilan keputusan—seperti penentuan jenis tanaman, pola tanam, hingga pembagian lahan. Peran LSM Kanopi dalam mendampingi kelompok juga tidak bisa dikesampingkan. Sebagai fasilitator, mereka memperkuat posisi tawar masyarakat dalam negosiasi dan membangun kesadaran ekologis yang lebih luas.
Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa meskipun partisipasi tinggi, peningkatan pendapatan belum selalu signifikan. Artinya, perlu penguatan aspek ekonomi seperti akses pasar, pendampingan agribisnis, dan pengolahan hasil hutan untuk menjadikan PHBM benar-benar menguntungkan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Desa Sukasari—yang juga memiliki KTH aktif menunjukkan pergeseran paradigma masyarakat terhadap hutan. Sebelumnya, pembalakan liar dan penjarahan menjadi fenomena umum akibat minimnya akses legal terhadap sumber daya hutan. Kini, dengan keikutsertaan dalam PHBM, masyarakat mendapatkan legalitas, pendampingan, dan kepastian berbagi hasil dari lahan yang mereka kelola.
Anggota KTH di Sukasari tidak hanya melakukan penanaman kayu keras seperti mahoni dan jati, tetapi juga membangun kebun agroforestri dengan tanaman sela seperti palawija dan pisang. Dengan jenis palawija (di 0-4 thn awal saat tanaman pokok jati & mahoni belum tinggi), dan buah-buahan seperti pisang, petai, mangga. Ini menciptakan skema penghasilan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan.
Program ini juga menjadi arena transfer pengetahuan antar generasi, di mana anak-anak muda desa ikut belajar cara menanam, menjaga hutan, dan berorganisasi dalam kelompok tani yang demokratis.
Kegiatan Utama LATIN
Pada saat pertama kali LATIN menginjakkan kakinya di Kabupaten Kuningan, LSM Kanopi adalah mitra strategis. Adalah merupakan strategi LATIN yang selalu menggaet stakeholder lokal sebagai mitra kerja. Pendekatan dengan kolaborasi bersama mitra lokal ini penting karena pada dasarnya setiap kegiatan-kegiatan di manapun harus ada organisasi setempat yang bisa melanjutkan kegiatan LATIN agar apa yang dirintis terus bis aberkembang dan berdampak jangka menengah dan panjang.
Bersama Kanopi LATIN mengembangkan sedikitnya tiga kegiatan utama, yakni Pertama, Pendampingan Masyarakat. Pelatihan PHBM dan agroforestri untuk mengurangi ketergantungan pada eksploitasi hutan. Pembentukan lembaga adat/kelompok tani pengelola hutan. Kemudian kedua, Advokasi Kebijakan. Kebijakan yang mendukung kegiatan-kegiatan ini harus dilahirkan agar jamninan masa depannya tersedia. Karena kegiatan PHBM ini menyangkut kawasan hutan yang menjadi otoritas pemerintah. Advokasi kebijakan ini misalnya dengan memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Mendukung pengakuan hutan adat atau hutan desa. Ketiga, Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Pengembangan ekonomi ini disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia baik secara bahan alamnya maupun keahlian. Pengembangan ekonomi selalu dilandaskan pada apa yang tersedia di wilayah setempat. Pelatihan kerajinan dari hasil hutan non-kayu (e.g., madu hutan, buah).
Kegiatan PHBM di kedua desa ini tidak hanya kegiatan fisik/teknis penanaman & pengamanan, tetapi juga termasuk penguatan kelembagaan, pemetaan lahan, inventarisasi potensi, dan perencanaan hutan secara partisipatif.
Selama berkegiatan di Kuningan, LATIN dan Kanopi memfasilitasi terbentuknya kelompok tani hutan dengan izin pengelolaan dari TNGC. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui agroforestri kopi dan usaha lainnya. Adanya Perdes (Peraturan Desa) tentang PHBM di beberapa desa.
Dukungan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan juga tidak kalah pentingnya.
Pemerintah Kabupaten Kuningan secara resmi telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Sejumlah kebijakan dan dukungan yang diberikan antara lain:
Integrasi PHBM dalam RPJMD Kabupaten: PHBM tidak lagi dianggap sebagai program sektoral semata, tetapi diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam sektor lingkungan hidup dan pertanian. Penyediaan anggaran fasilitasi: Pemda Kuningan mengalokasikan dana untuk pelatihan, studi banding, dan penyuluhan terkait PHBM, termasuk bantuan bibit dan alat tanam. Kemitraan dengan LSM dan perguruan tinggi: Pemda membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan pihak ketiga dalam mendampingi KTH, sehingga proses pemberdayaan tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah atau Perhutani.
Pembentukan Forum Komunikasi Perhutanan Sosial: Forum ini menjadi wadah koordinasi antar-KTH, Pemda, Perhutani, dan stakeholder lain agar pengelolaan hutan lebih terkoordinasi dan adil.
Desa Cileuya dan Sukasari telah membuktikan bahwa hutan bukan hanya wilayah larangan, melainkan ruang hidup yang bisa dikelola secara lestari ketika masyarakat diberi tempat untuk berpartisipasi. Melalui dukungan kebijakan yang konsisten dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, program PHBM dan Perhutanan Sosial bukan hanya menjadi jargon, melainkan jalan konkret menuju keberlanjutan ekologi dan kemandirian ekonomi desa. Meskipun demikian tantangan ke depan masih besar. Penelitian yang dilakukan Deny Rusdianto, Ir. San Afri Awang, M.Sc. ditemukan “..secara umum di dalam proses tersebut, partisipasi masyarakat masih dalam konteks keterwakilan belum pada partisipasi aktif karena masih adanya dominasi dari elit desa atau tokoh masyarakat bahkan dalam membangun kesepakatan, Perhutani nampak mendominasi. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat adalah Perhutani dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan meskipun hanya formalitas, masyarakat meliputi penggarap, tokoh masyarakat dan pemerintah desa sedangkan LSM Kanopi dibantu oleh LSM LATIN sebagai fasilitator. Respon yang berkembang pasca kesepakatan adalah adanya inkonsistensi Perhutani dalam melaksanakan kesepakatan dan masih adanya ketergantungan masyarakat pada pihak luar. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan PHBM di Desa Cileuya kurang dapat berkembang secara dinamis.”2
Ekspedisi ke Kuningan ini dimaksudkan untuk menjalin kembali kolaborasi baru untuk mewujudkan Sosial Forestri 2045. Menjajagi berbagai kemungkinan kolaborasi masa depan dengan generasi-generasi baru di Kab Kuningan.
Pada pertemuan April 2022 itu disepakati perlunya kolaborasi yang baru dengan melihat perkembangan baru dan tantangan baru yang di hadapi. Pemerintah Kabupaten Kuningan yang mendukung dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan, termasuk di dalam soal alokasi anggaran, Perhutani juga menyambut dengan baik jika ada gagasan-gagasan baru kolaboratif ada masa mendatang. Secara spesifik belum dirumuskan. Tetapi dengan berpegang pada Sosial Forestri 2045 maka Kabupaten Kuningan adalah tempat yang baik dan tepat untuk menjadi bagian gerakan Sosial Forestri 2045.
Sosial Forestri 2045 Kabupaten Garut
Jalan berliku yang melelahkan dari Kabupaten Kuningan menuju Garut terbayar dengan persinggahan di sebuah Kafe mungil, di pojok jalan utama tepian Kabupaten Majalengka. Kami singgah menikmati secangkir dua cangkir kopi di Kafe Eskopian.
Pada suatu sore itu, kami berbincang dengan seorang anak muda inspiratif bernama Samsul Arifin. Ia berasal dari Desa Manis Kidul, sebuah desa kecil di perbatasan Majalengka, Ciamis, dan Kuningan, Jawa Barat. Meski berlatar belakang pendidikan ilmu komputer yang ditempuh di Bandung, Samsul memilih kembali ke kampung halamannya dan mendirikan sebuah usaha kopi yang dinamainya “Es Kopian”.
Kisahnya bermula saat ia baru lulus kuliah. Ia sempat menganggur selama empat bulan, bingung mencari pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang sulit pasca pandemi. Dalam kebingungan itu, ia mulai memperhatikan pohon-pohon kopi di kampungnya yang selama ini diabaikan masyarakat. Kopi-kopi itu ditanam sejak dua dekade silam, namun nyaris tak pernah dipanen, apalagi diolah. Tak ada pasar, tak ada ilmu pengolahan. Petani hanya membiarkan buah kopi jatuh begitu saja.
Samsul tidak tinggal diam. Ia mulai belajar tentang kopi. Ia menyambangi petani-petani di Kuningan, Ciamis, hingga kawasan Gunung Cakrabuana, Garut untuk menyerap pengetahuan tentang penanaman, panen, dan pascapanen kopi. Setelah cukup memahami prosesnya, ia kembali ke desa dan mulai menyuluh para petani kopi di desanya. Ia mengedukasi tentang pentingnya memetik buah kopi merah yang matang, merawat pohon, serta cara mengolah kopi agar bernilai jual tinggi. Ia pun bersedia membeli hasil panen mereka, memotong satu mata rantai besar dalam sistem perdagangan kopi yang selama ini tak terjangkau oleh petani kecil.
Kini, sekitar 10–20 petani di desa mulai kembali bersemangat menanam dan merawat pohon kopi mereka. Samsul menampung hasil panen, mengolahnya secara alami (dijemur karena belum ada mesin pengering), dan mendistribusikannya ke berbagai kafe di Majalengka, Kuningan, hingga ke luar negeri seperti Abu Dhabi dan Kairo. Bahkan ia menyebut bahwa setiap bulan bisa mengekspor kopi hingga 200 kg dalam bentuk bubuk kopi hasil giling (grinding).
Jenis kopi yang tumbuh di Desa Manis Kidul antara lain robusta dan arabika. Dengan ketinggian sekitar 1.200–1.500 meter di atas permukaan laut, desa ini cocok menjadi habitat arabika yang berkualitas tinggi. Yang menarik, banyak petani mengombinasikan pohon kopi mereka dengan tanaman lain seperti lemon dan jahe. Alhasil, kopi yang dihasilkan pun memiliki cita rasa khas, misalnya rasa lemon yang kuat dari pohon-pohon lemon di sekitarnya.
Kafe milik Samsul, “Es Kopian”, menjadi tempat nongkrong favorit warga. Letaknya strategis di tikungan jalan, dengan pemandangan sawah dan hutan yang memanjakan mata. Sekitar 50 gelas kopi terjual setiap hari. Tak hanya tempat menikmati kopi, Es Kopian juga menjadi ruang inspirasi bagi anak-anak muda di desa yang mulai merasakan manfaat ekonomi dari hasil bumi sendiri.
Misi besar Samsul tidak sekadar menjual kopi. Ia ingin membangkitkan kesadaran anak muda desa agar tidak melulu memimpikan kehidupan kota. Menurutnya, kampung pun bisa memberi masa depan. Ia berharap anak-anak para petani bisa terlibat dalam seluruh rantai kopi: dari penanaman, pengolahan, hingga penjualan.
Saat ditanya tentang masa depan, Samsul menjawab dengan semangat, “Harapan saya, kopi dari kampung ini bisa tersebar ke seluruh Jawa Barat dulu. Saya ingin makin banyak produk lokal khas yang kita hasilkan, bukan hanya kopi, tapi juga olahan lain seperti lemon dan camilan tradisional.” Samsul juga membuka peluang untuk mengembangkan makanan-makanan lokal berbasis bahan kampung seperti singkong, kelapa, atau gula aren. Ia percaya potensi desa sangat besar dan belum tergali sepenuhnya.
Perbincangan diakhiri dengan pesan sederhana namun kuat dari Samsul: “Tetap semangat menjalani apa yang ingin dicapai. Semua butuh proses. Jangan cepat puas dengan keadaan sekarang. Teruslah bermimpi lebih tinggi.”3
Apa yang digeluti Samsul adalah bentuk-bentuk Sosial Forestri 2045. Anak muda yang melihat desa dengan hutannya sebagai sebuah modal alam, sebagai kekayaan yang perlu mendapatkan sentuhan yang tepat. Dan Samsul melakukannya. Perjalanan ke Garut membawa pesan penting dari Samsul bahwa desa dengan segala kekayaan alam dan manusianya bisa menjadi jalan hidup yang membahagiakan. Masa depan yang cerah tidaklah jauh. Ada di kampung halaman.
Berbeda dengan Kabupaten Kuningan, pengalaman LATIN di wilayah Kabupaten Garut sangat terbatas. LATIN tidak punya kegiatan apapun selain jaringan-jaringan aktifis yang senantiasa dibangun. Karena itu ekspedisi LATIN ke Garut pada dasarnya berbagi visi LATIN Sosial Forestri 2045 dengan mereka dan mengeksplorasi potensi-potensi masa depan yang bisa dikolaborasikan. Sosial Forestri 2045 memerlukan kolaborasi yang amat luas untuk mewujudkannya. Sosial Forestri 2045 adalah visi bersama, bukan visi LATIN semata. Karena selama kunjungan ke Garut LATIN menemui para aktifis yang beraktifitas dalam dunia sosial forestri.
Pesantren Ekologi At Thariq 4
Di kaki pegunungan Garut, tepatnya di Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong, berdiri sebuah pesantren yang tidak biasa: Pesantren Ekologi At Thariq. Didirikan pada tahun 2008 oleh Nisa Wargadipura, seorang aktivis lingkungan yang kemudian memilih jalan sunyi sebagai pendidik dan penggerak ekologi, pesantren ini menjadi rumah bagi pengetahuan agroekologi dan spiritualitas Islam yang berpijak pada nilai rahmatan lil alamin.
Sejak awal, At Thariq tidak hanya menawarkan pendidikan agama. Ia juga menanamkan nilai-nilai cinta bumi, kedaulatan pangan, dan keberlanjutan ekosistem. Nisa dan para santrinya belajar mengolah tanah, menanam, memanen, dan mengolah hasil pertanian mereka sendiri. Namun yang paling menarik, semua itu dilakukan dalam semangat kolaboratif—dengan kaum muda, masyarakat sekitar, pesantren lain, bahkan perguruan tinggi dan lembaga pemberdayaan.
Kurikulumnya pun tak biasa. Santri di At Thariq tidak dipersiapkan untuk “pergi ke kota”, melainkan untuk kembali ke desa, menggali dan mengembangkan potensi kampung halaman mereka sendiri. Di pesantren ini, belajar berarti menyatu dengan tanah, menyerap nilai-nilai spiritual Islam sambil menyemai tanaman, menyulam ekologi dan iman dalam praktik sehari-hari. “Islam yang kami ajarkan adalah Islam yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan, yang toleran, dan berpihak pada keadilan sosial serta keadilan lingkungan,” ujar Nisa dalam salah satu wawancaranya.
Bagi Nisa, pertanian bukan sekadar urusan produksi pangan. Ia adalah jalan hidup, terapi jiwa, sekaligus bentuk ibadah. Itulah mengapa ia menyebut pendekatannya sebagai agroekologi—sebuah sistem bertani berbasis keragaman hayati, kebijaksanaan lokal, dan pengetahuan ekologis. Pendekatan ini, menurutnya, bukan hanya mencegah gagal panen, tapi juga membangun kesadaran bahwa bumi harus dirawat sebagaimana kita merawat diri sendiri.
Meski sempat terdampak pandemi hingga tak lagi menerima santri tetap, At Thariq terus melanjutkan program belajar terbuka yang disebut “santri kalong”—siapa pun boleh datang, belajar, dan tinggal sejenak di pesantren dengan membuat janji kepada pengelola. Di sinilah rombongan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum berdatangan tiap pekan. Mereka belajar tentang pertanian dari hulu ke hilir: dari cara menanam, memanen, hingga mengolah hasil panen menjadi produk bernilai.
Seorang peserta, Muhammad Sholeh, mengaku pengalaman di At Thariq membangkitkan kembali semangatnya terhadap pertanian. Ia menyadari bahwa pertanian bukan sekadar urusan menanam, tapi juga soal menjaga lingkungan dari pencemaran, meminimalkan plastik, dan menciptakan sistem pangan berkelanjutan. Seorang mahasiswa agroteknologi lain bahkan menjadikan At Thariq sebagai laboratorium hidupnya, tempat ia menemukan inspirasi bagi tugas akhir kuliahnya.
Yang menarik, pesantren ini tidak pernah memungut biaya dari santri yang mondok. Nisa dan timnya mengandalkan hasil panen dari sawah, kebun, peternakan ayam, dan kolam ikan. Mereka juga memproduksi berbagai produk, mulai dari teh herbal hingga masker wajah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Cita-cita besar Nisa tidak hanya membangun pesantren, tapi juga menciptakan pusat penyebaran pengetahuan agroekologi yang terintegrasi dengan ayat-ayat Alquran dan nilai-nilai ekoteologi Islam. Visi ini pula yang membawa At Thariq mendapat pengakuan sebagai Representative of Family Farming Decade oleh FAO PBB, berlaku hingga 2028.
Bagi Nisa, pertanian masa depan Indonesia harus berbasis pada pengetahuan yang berpihak pada pemulihan alam. “Yang paling benar dalam sistem pertanian,” katanya, “adalah pertanian yang berbasis pada kearifan lokal dan pengetahuan yang menyelamatkan alam, juga menyelamatkan manusia.”
Tim Ekspedisi LATIN berbincang seharian di Pesantren Ekologi dan menikmati hidangan yang diambil dari kebun Pesantren. Pemaparan dan diskusi tentang Sosial Forestri 2045 cukup membuat para undangan antusias bertanya dan memberi komentar. Ini adalah pertukaran gagasan dan pemikiran yang sejalan dengan misi agroekologi Pesantren Ekologi. Kedaulatan pangan desa, dan optimalisasi sumebrdaya alam dengan membangun ekosistem yang memadai di desa maka akan mampu menciptakan desa yang makmur dan mandiri. Itulah yang juga menjadi cita-cita Sosial Forestri 2045.
Dari Garut Tim Ekspedisi LATIN melaju menuju Kampung Naga di Tasikmalaya, sekitar dua jam perjalanan.
Kampung Naga, Model Desa Wakanda?
Kampung ini dikenal dengan nama Kampung Naga. Meski namanya menyebut kata “naga,” kampung ini sama sekali tidak memiliki kaitan dengan makhluk mitos tersebut. Nama “Kampung Naga” berasal dari istilah “Nagawir”, yang berarti kampung di bawah tebing. Jadi, nama “Naga” bukanlah merujuk pada makhluk mitologi, melainkan pada letak geografisnya yang berada di bawah bukit curam.
Kampung Naga bukan hanya tempat tinggal, melainkan sebuah peradaban kecil yang hidup dalam keselarasan, kearifan, dan keberlanjutan.
Nama itu hanya merupakan sebutan yang telah melekat sejak lama.5 Statusnya adalah sebagai Kampung Adat
Kampung Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Warga menyebut sejarah kampung ini dengan istilah parim obor, yang jika diterjemahkan secara bebas berarti “padamnya penerangan.” —sebuah metafora bahwa jejak sejarah mereka lenyap dan tak diketahui. Namun, masyarakat meyakini bahwa Kampung Naga merupakan bagian dari jejak Kerajaan Galunggung yang pernah berjaya di Tasikmalaya.6 Ada juga yang merujuk pada hilangnya catatan sejarah kampung akibat terbakarnya arsip-arsip penting saat kampung dibakar oleh gerakan DI/TII Kartosuwiryo di masa lalu. Hingga kini, asal usul Kampung Naga tetap menjadi misteri bagi warganya sendiri.
Kampung ini dikelilingi dua hutan: Hutan Larangan di sebelah timur dan hutan keramat di bagian atas kampung yang menjadi tempat makam leluhur mereka. Hutan Larangan tidak boleh dimasuki atau diambil hasil hutannya. Larangan ini dijaga ketat demi kelestarian adat dan lingkungan.7 Di sebelah selatan terbentang sawah-sawah milik warga, sementara di utara dan timur mengalir Sungai Ciwulan (atau Kaliwulan), yang turut memberi kehidupan bagi kampung tersebut.
Rumah-rumah di Kampung Naga memiliki bentuk yang khas dan mengikuti aturan adat. Semua rumah berbentuk rumah panggung, dibangun dari bambu dan kayu. Atap rumah harus terbuat dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang. Lantainya dibuat dari bambu atau papan kayu. Selain itu, setiap rumah wajib menghadap ke arah utara atau selatan, dengan memanjang ke arah barat–timur. Ini adalah bentuk konsistensi warga Kampung Naga dalam menjaga dan merawat warisan budaya leluhur mereka.8
Untuk mencapai kawasan inti kampung, pengunjung harus menuruni lebih dari 400 anak tangga. Begitu sampai di bawah, kita akan disambut suasana kampung adat yang masih memegang teguh warisan nenek moyang.
Penduduk Kampung Naga menyebut diri mereka sebagai “Sak Naga”, atau warga asli yang mengikuti adat. Karena luas kampung hanya sekitar 1,5 hektar, sebagian warga tinggal di luar area inti kampung, namun tetap memegang nilai dan tradisi yang sama.
Menariknya, Kampung Naga tidak ingin disebut sebagai objek wisata. Bagi mereka, kampung adat bukan tontonan, melainkan tuntunan. Mereka menerima kunjungan orang luar, tetapi dengan syarat mengikuti tata aturan yang berlaku. Pengunjung harus menghormati adat dan batasan yang sudah diwariskan secara turun-temurun.
Jumlah kepala keluarga di Kampung Naga ada sekitar 102 KK, dengan jumlah penduduk 282 jiwa. Terdapat 110 bangunan, termasuk tiga sarana umum: masjid, balai kampung, dan lumbung padi. Namun, hanya 102 rumah yang dihuni. Di kampung ini, tidak diperkenankan menggunakan listrik atau membangun rumah permanen. Larangan tersebut ditafsirkan sebagai cara menjaga keaslian adat. Jika listrik diperbolehkan, maka persaingan gaya hidup bisa timbul dan merusak keselarasan.
Setiap rumah harus menghadap ke utara atau selatan, tidak boleh ke arah matahari terbit atau terbenam. Bahkan kamar mandi tidak boleh berada di dalam rumah. Semua fasilitas sanitasi ditempatkan di luar, di atas kolam, sebagai simbol pemisahan antara ruang bersih dan ruang kotor.
Struktur sosial di Kampung Naga dipimpin oleh lembaga adat yang terdiri dari Kuncen (pemimpin adat sekaligus pemimpin ritual), Lebe adat (bertugas di bidang keagamaan), dan Punduh adat (urusan hubungan luar/humas). Semuanya ditunjuk secara turun-temurun, bukan dipilih oleh warga.
Mata pencaharian utama warga adalah bertani. Setiap keluarga biasanya memiliki sawah sendiri dan mengikuti sistem pertanian tradisional—menanam padi hanya dua kali setahun, yaitu pada Januari dan Juli. Selain bertani, banyak warga juga membuat kerajinan tangan atau bekerja di kota.
Di dalam kampung, rumah-rumah dibangun dengan tiang dari kayu albasi atau manglid, beratap ijuk atau tepus, dan berdinding bambu. Lantai dapur terbuat dari bambu, agar sisa makanan bisa langsung diberikan kepada ayam yang berada di bawah rumah—sengaja dipelihara untuk mengendalikan rayap.
Penerangan di malam hari hanya menggunakan lampu tempel berbahan bakar minyak tanah, yang khusus disubsidi oleh Pertamina untuk warga Kampung Naga.
Salah satu bangunan penting adalah lesung penumbuk padi, yang dibangun di atas kolam agar kulit padi bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Proses menumbuk dan menyimpan padi masih dilakukan dengan cara tradisional.
Kerajinan tangan juga menjadi bagian penting dari kehidupan warga, seperti pembuatan tempat makanan, piring dari bambu, hingga hasil hutan seperti kapulaga yang dijual ke pasar.
Tim Ekspedisi LATIN berkunjung ke Kampung Naga untuk mengambil teladan bahwa masyarakat desa sebetulnya dengan kemampuan dan keahlian yang dibangun berpuluh generasi mampu hidup dalam ekosistem yang harmoni. Sumberdaya alam yang menjadi penopang kehidupan terjaga dengan baik. Karena mereka paham bahwa kerusakan alam akan merusak kehidupan mereka sendiri. LATIN percaya hal serupa. Sosial Forestri adalah sebuah kekayaan yang cukup untuk bisa merawat komunitas dalam sebuah wilayah secara berkelanjutan sepanjang hubungan antara manusia (sosial) dan alam (forestri) berjalan dengan baik.
Memang masyarakat di Kampung Naga membatasi yang namanya teknologi termasuk listrik sebagai sumber enerji bagi berbagai teknologi. Kesadaran ini memang masih bertahan pada kalangan tetua mereka. Generasi muda dengan paparan sekolah di luar kampung meungkin akan menghadapi dilema. Kebutuhan-kebutuhan baru bermunculan. Ekosistem Kampung Naga tidak bisa memenuhinya. Ataukah akan ada adaptasi atas perubahan ekternal pada Kampung Naga. Perubahan apa yang diperlukan yang tidak merusak tatanan, teknologi apa yang sesuai dengan perkembangan dan dasar peradaban Kampung Naga? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh kaum muda.
Sosial Forestri 2045 memberi ruang perubahan dan adaptasi pada kemajuan-kemajuan di luar komunitas desa, jika memang masyarakat desa berkehendak untuk mengikuti perubahan itu.
Apakah Kampung Naga merupakan salah satu tipologi model Desa Wakanda?
1 Tulisan ini aslinya adalah tulisan yang telah dimuat sebagai Laporan Kegiatan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) untuk Ford Foundation. Tulisan ini juga telah ditayangkan di website LATIN (latin.or.id). Pemuatan ulang dalam rubrik Sustainability 17A seijin LATIN. Tim Ekspedisi LATIN terdiri dari Annisa Aliviani, Taufik Saifulloh, Firman Dwi Yulianto, Sutjie Shinto dan Dwi Rahmad Muhtaman.
2 Rusdianto, D., & Awang, S. A. (2005). Analisis proses perencanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (Studi kasus di Desa Cileuya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan) (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada Repository. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/230706
3 Perbincangan lengkap dengan Samsul Arifin, pemilik Kafe Eskopian bisa dinikmati pada tautan ini: https://youtu.be/VmVlJO37ukY?si=uJG8smiPMr5B4zrF
4 https://www.youtube.com/watch?v=IW1mqIFpsSY
5 https://www.youtube.com/watch?v=YGJg-eIcWw0
6 https://www.youtube.com/watch?v=eKM5l0qeoQU
7 https://www.youtube.com/watch?v=413I3eoyjR0
8 https://www.youtube.com/watch?v=eKM5l0qeoQU