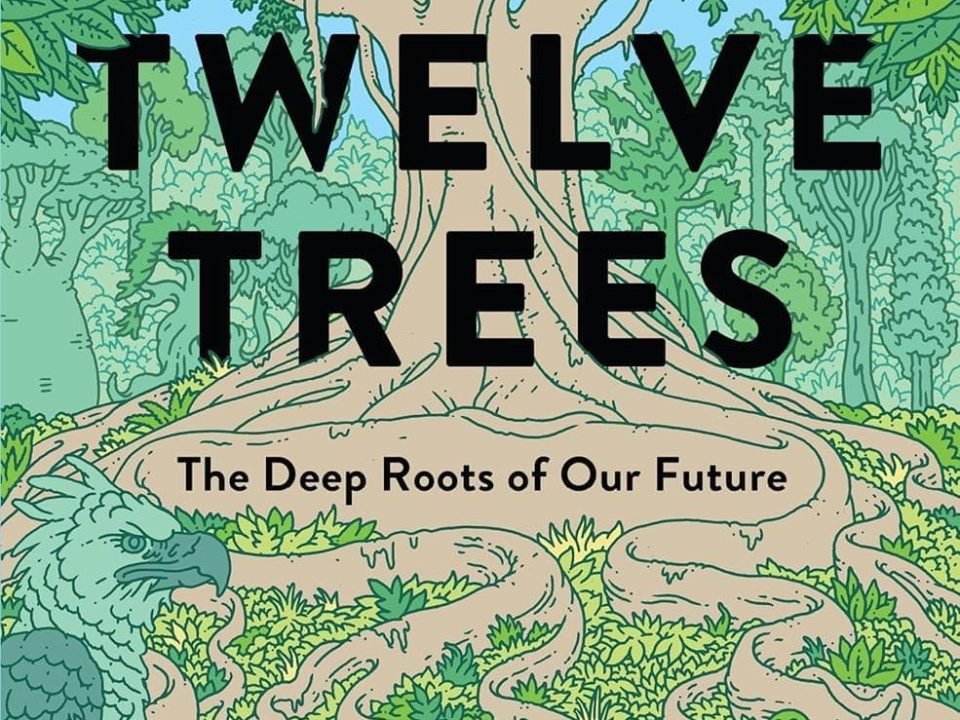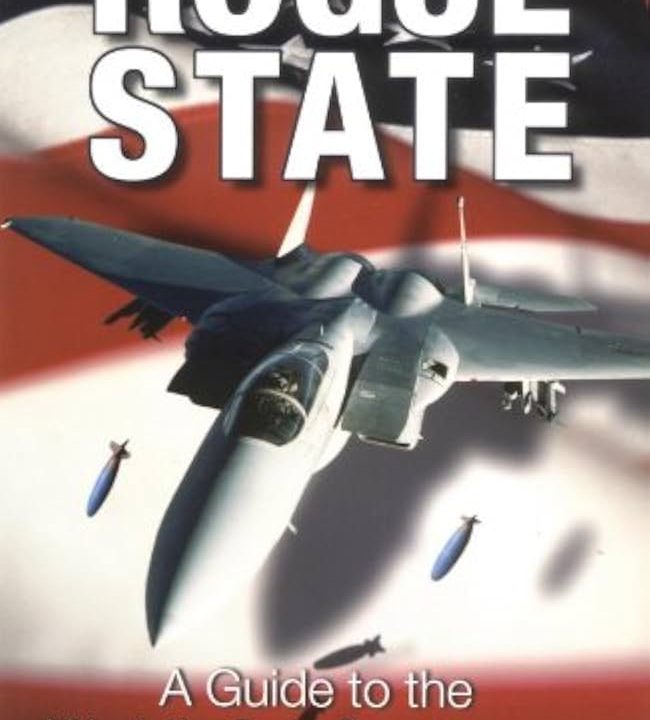Rubarubu #10
Imperialism in the Twenty-First Century: Wajah yang Busuk
Runtuhnya Rana Plaza, sebuah gedung delapan lantai yang menampung beberapa pabrik tekstil, sebuah bank, dan beberapa toko di distrik industri di utara Dhaka, ibu kota Bangladesh, pada 24 April 2013, menewaskan 1.133 pekerja garmen dan melukai 2.500, adalah salah satu bencana tempat kerja terburuk dalam sejarah yang tercatat. Bencana ini, serta kesedihan, kemarahan, dan tuntutan keadilan para pekerja garmen, membangkitkan perasaan simpati dan solidaritas dari rakyat pekerja di seluruh dunia—dan sebuah bencana yang dilakukan perusahaan-perusahaan raksasa yang mengandalkan pabrik-pabrik Bangladesh untuk produk mereka. Namun menyangkal segala tanggung jawab atas upah, kehidupan, dan kondisi kerja yang mengerikan dari mereka yang memproduksi semua barang mereka.
Jyrki Raina, sekretaris jenderal IndustriALL, sebuah federasi serikat pekerja internasional, menyebut peristiwa itu sebagai “pembantaian industri massal.” Jeritan ribuan orang yang terperangkap dan hancur saat beton dan mesin-mesin berjatuhan menimpa mereka melepaskan gelombang kejut dan lolongan kesedihan jutaan orang di seluruh dunia. Musibah itu langsung menjadi berita utama. Konsumen pakaian yang dibuat di pabrik-pabrik garmen Bangladesh dihadapkan pada hubungan nyata mereka dengan orang-orang yang tangannya membuat pakaian mereka, dan tentang keberadaan mereka yang menyedihkan di bumi ini.
Seperti sinar-X yang intens, gelombang kejut dari Rana Plaza menyinari struktur internal ekonomi global, menyoroti dengan tajam fakta mendasar tentang kapitalisme global yang biasanya disembunyikan dan dijauhkan dari pikiran: kesehatan baiknya bergantung pada tingkat eksploitasi pekerja yang ekstrem di negara-negara berupah rendah di mana produksi barang konsumsi dan input perantara telah dipindahkan. Perhatian dunia terpaku pada upah kemiskinan Bangladesh—upah pabrik terendah dari pengekspor besar mana pun di dunia, bahkan setelah kenaikan gaji 77 persen pada November 2013; pada pabrik-pabrik perangkap kematiannya—hanya lima bulan sebelumnya kebakaran di Tazreen Fashions di dekatnya menewaskan 112 pekerja, yang terperangkap di belakang jendela berjeruji dan pintu terkunci saat bekerja hingga larut malam; ini adalah bentuk-bentuk penindasan kekerasan terhadap hak-hak serikat pekerja—aktivis serikat pekerja secara rutin masuk daftar hitam, dipukuli, dan ditangkap secara sewenang-wenang; dan pada hubungan yang terlalu akrab antara pemilik pabrik, politisi, dan kepala polisi di Bangladesh—tidak ada majikan di industri garmen Bangladesh yang pernah dihukum karena melanggar undang-undang kesehatan dan keselamatan.
Yang membuat semua ini sangat relevan dengan buku Smith, Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis, bahwa industri garmen adalah “contoh utama dari rantai komoditas yang digerakkan oleh pembeli . . . [di mana] pembeli global menentukan apa yang akan diproduksi, di mana, oleh siapa, dan pada harga berapa.”
Dengan demikian, industri garmen Bangladesh menyaring strategi industrialisasi berorientasi ekspor yang dijalankan oleh pemerintah kapitalis di seluruh Global Selatan. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Pekerja Inggris Frances O’Grady menanggapi bencana Rana Plaza, “Kehilangan nyawa yang mengerikan ini membuktikan bahwa, dalam perlombaan global ke bawah mengenai kondisi kerja, garis finisnya adalah Bangladesh.”
Upah kelaparan, pabrik perangkap kematian, dan permukiman kumuh yang busuk di Bangladesh mewakili kondisi yang dialami oleh ratusan juta rakyat pekerja di seluruh Global Selatan, sumber nilai lebih yang menopang profit dan memberi makan konsumsi berlebihan yang tidak berkelanjutan di negara-negara imperialis. Rakyat Bangladesh juga berada di garis depan konsekuensi malapetaka lain dari eksploitasi tenaga kerja hidup dan alam yang sembrono oleh kapitalisme: “perubahan iklim,” yang lebih akurat digambarkan sebagai kehancuran alam oleh kapitalis. Sebagian besar Bangladesh adalah dataran rendah, dan seiring naiknya permukaan laut dan muson menjadi lebih energetik, lahan pertanian semakin sering tergenang air asin, mempercepat migrasi ke kota-kota.
Kisah tragis Rana Plaza menjadi pintu masuk yang pas untuk membaca John Smith: bagaimana gaya hidup konsumtif dan rantai nilai global — yang direkayasa oleh modal besar dan negara kuat — mengubah hidup komunitas paling rentan. Smith menempatkan fenomena semacam pulau tadi ke dalam kerangka imperialisme modern: bukan hanya penguasaan teritori, tetapi penataan ulang tenaga kerja dan alam melalui mekanisme “globalisasi” yang membuat eksploitasi baru — super-exploitation — menjadi inti akumulasi kapital kontemporer (Baca: Rubarubu #08 -Pulau-pulau Antroposen: Menyibak Dunia yang Saling Terjalin.
John Smith membuka bukunya, Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis (Monthly Review Press, 2016) dengan pertanyaan besar: mengapa, setelah tiga dekade neoliberalisme dan globalisasi, ketimpangan global semakin menjulang dan krisis ekonomi berulang? Jawabannya, menurut Smith, adalah bahwa imperialisme tidak hilang — ia berevolusi. Jika Lenin pernah menyatakan bahwa “imperialism is the highest stage of capitalism,” Smith berargumen bahwa abad XXI melihat bentuk baru imperialisme yang menggabungkan deregulasi finansial, fleksibilisasi tenaga kerja, integrasi rantai pasok multinasional, dan kontrol geopolitik untuk menekan upah dan mengekstrak nilai lebih besar dari pekerja di Selatan. Konsep sentralnya adalah super-exploitation: kerja upah sangat rendah, jam panjang, precariousness, tanpa jaminan sosial, yang membuat profit margin perusahaan pusat tetap tinggi meski krisis berkepanjangan. Jika saja iPhone diproduksi di Amerika Serikat (Made in USA) maka harganya akan mencapai USD30,000.
Imperialisme sebagai Wajah Sejati Globalisasi
Bagi Smith “globalisasi” yang disebut sebagai era keterhubungan yang setara adalah mitos. Ia menegaskan bahwa globalisasi sebenarnya adalah nama baru bagi imperialisme ekonomi, di mana perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju memindahkan produksi ke negara-negara berupah rendah untuk meningkatkan keuntungan melalui super-exploitation. Ia mem-beri contoh kasus industri garmen Bangladesh, pekerja elektronik di China, dan pekerja migran di Timur Tengah — menunjukkan bahwa “kemajuan global” dibangun di atas penderita-an yang tak terlihat. Situasi serupa terjadi juga di Indonesia: buruh pabrik di Bekasi, pekerja tambang di Sulawesi, dan TKI di luar negeri yang bekerja dalam kondisi minim perlindungan, semuanya bagian dari rantai nilai global imperialistik.
Bagian awal buku mengurai mekanika super-exploitation: bagaimana perusahaan transnasional, dalam pencarian biaya terendah, memecah produksi menjadi fragmen global — rantai nilai yang memisahkan pekerjaan terampil di negara pusat dari kerja kasar di perifer. Smith me-maparkan bukti empiris: sektor tekstil, pertambangan, agribisnis, dan manufaktur elektronik menggunakan kombinasi deregulasi, outsourcing, dan represi serikat untuk menekan upah. Negara-negara penerima investasi sering dipaksa memilih antara “investasi” dan perlindungan tenaga kerja; pilihan itu, kata Smith, berakhir pada subordinasi jangka panjang: modal memindahkan pabrik, bukan memperkuat hak pekerja.
Paragraf berikutnya membahas peran finansialisasi dan hutang: Smith menyorot bagaimana krisis 2008 bukan gangguan sementara, melainkan pengingat bahwa kapital finansial terus menekan akumulasi riil sambil mengekspor biaya akibat krisis ke negara dan pekerja lewat penghematan, privatisasi, dan restrukturisasi hutang. Mekanisme pembiayaan global—bank, hedge funds, rating agencies—menjadi instrumen baru imperialisme karena mereka menentu-kan akses negara pada modal, memaksa kebijakan pro-kapital yang melemahkan kedaulatan fiskal. Hasilnya adalah negara terperangkap: harus menjaga iklim investasi internasional dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Smith tidak menutup mata pada sisi kekuatan negara dan militer: imperialisme abad ke-21 juga dioperasikan melalui campur tangan geopolitik—perjanjian keamanan, pangkalan militer, dan dukungan rezim yang “patuh” pada kepentingan korporasi pusat. Ia mengaitkan intervensi geopolitik modern dengan perlindungan jalur pasokan, hak atas sumber daya strategis (mineral, energi), dan stabilitas rezim yang memfasilitasi ekstraksi. Di sini ia beresonansi dengan analisis kritis lain yang melihat bahwa “globalisasi” sering dipadukan dengan hegemoni militer—sebuah kombinasi yang memaksa subordinasi politik di banyak negara periferi.
Satu bagian penting yang menarik untuk masa kini adalah pembahasan Smith tentang hubungan antara imperialisme dan krisis lingkungan. Smith menunjukkan bahwa logika akumulasi—dorongan untuk menurunkan biaya dan memaksimalkan ektraksi—mendorong eksploitasi sumber daya secara bertanggung jawab rendah: deforestasi, perusakan ekosistem pesisir, polusi tambang, dan overfishing. Di sinilah kaitan dengan Anthropocene Islands muncul kuat: pulau-pulau dan komunitas pesisir menjadi korban ganda—super-eksploitasi tenaga kerja sekaligus kolonialisasi ekologis. Smith mengingatkan bahwa solusi teknis untuk krisis iklim tanpa mengatasi relasi kuasa ekonomi hanya akan mereproduksi “green colonialism” — pola ekstraktif yang berpakaian hijau.
Apa relevansi keseluruhan gagasan Smith untuk dunia sekarang dan khususnya untuk Indonesia? Sangat besar. Indonesia menjadi contoh yang relevan: negara kaya sumber daya yang menarik investasi asing, sekaligus menghadapi fenomena kerja precarious (ketidakstabilan merujuk pada situasi kerja yang tidak aman, tidak stabil, dan rentan) di sektor perkebunan, tambang, dan manufaktur; tekanan hutang untuk proyek infrastruktur; serta konflik agraria yang mengorbankan komunitas adat. Smith memberi amunisi analitis: solusi harus melampaui perbaikan teknis—diperlukan rekonstruksi relasi produksi (mis. kontrol rantai nilai, industrial policy berdaulat, perlindungan pekerja) dan penguatan kedaulatan fiskal untuk menolak kondisi ketergantungan. Juga, kebijakan iklim harus berpihak pada keadilan sosial agar tidak menjadi topeng bagi ekstraksi baru.
Buku ini mendapat pujian karena menggabungkan analisis ekonomi klasik tentang imperialisme dengan data empiris kontemporer—menunjukkan kontinuitas struktur kuasa sekaligus inovasi modal. Kritikus memuji keberanian Smith menolak narasi optimistis tentang “globalisasi yang mengangkat semua orang.” Namun ada pula catatan: beberapa pengulas menilai Smith cenderung deterministik—memperlihatkan struktur yang menindas tanpa memberikan roadmap tindakan politik detail selain seruan umum untuk solidaritas dan rekonstruksi ekonomi. Lainnya mengeluhkan kurangnya pembahasan tentang fenomena perubahan politik di Asia Timur (mis. peran perusahaan negara Cina) yang menuntut nuansa lebih kompleks.
Beberapa kutipan dan resonansi intelektual memperkaya ringkasan ini. Lenin: “Imperialism is the highest stage of capitalism” (kita pakai sebagai latar sejarah teori). Dari tradisi pemikir non-Muslim kontemporer, David Harvey menulis tentang “spatial fix” kapital—cara kapital mengatasi krisis lewat relokasi ruang produksi—yang sejalan dengan analisis Smith tentang outsourcing. Dari ranah pemikir Muslim, Fazlun Khalid menekankan etika amanah: bahwa bumi bukan untuk dieksploitasi semata—sebuah perspektif moral yang berkesesuaian dengan kritik Smith terhadap kolonialisme lingkungan. Dari penyair/aktivis seperti Mahmoud Darwish atau Pramoedya Ananta Toer: seni dan literatur menjadi ruang menegaskan martabat melawan narasi dominan; Smith sendiri menegaskan bahwa perjuangan melawan imperialisme harus mencakup budaya, hukum, dan ekonomi.
Outsourcing
Sebagai fondasi konseptual Smith menjelaskan bagaimana outsourcing memungkinkan modal global memisahkan produksi dari konsumsi: barang diproduksi di Selatan, namun nilai dan keuntungan tetap mengalir ke Utara. Ia memperkenalkan konsep super-exploitation — situasi di mana pekerja dibayar jauh di bawah nilai tenaga kerja mereka, bukan sekadar “lebih rendah.” Dengan data statistik, ia membuktikan bahwa perbedaan upah internasional adalah sumber keuntungan utama bagi kapital global. Smith memperbarui teori Lenin tentang imperialisme. Jika Lenin menekankan dominasi finansial, Smith menyoroti dominasi relasi produksi global. Indonesia mengalami hal ini lewat dominasi perusahaan asing dalam industri elektronik, tekstil, dan agribisnis, di mana tenaga kerja lokal hanya menjadi “perantara murah” bagi pasar dunia.
Menurut Smith sifat komoditas dalam ekonomi dunia hari ini: barang tidak lagi sederhana produk lokal tetapi “global commodities” yang melewati rantai nilai panjang—desain, komponen, perakitan, distribusi—yang diatur oleh perusahaan transnasional. Bab 1 — The Global Commodity ini menekankan bahwa nilai komoditas (surplus value) diproduksi secara spasial: bagian bernilai tinggi tersentral di negara-negara inti (R&D, merek, finansial) sementara produksi bernilai rendah terjadi di perifer. Konsekuensinya: pertumbuhan produksi dunia tidak serta-merta berarti kenaikan kesejahteraan pekerja di negara penerima investasi; malah, keuntungan menumpuk di ujung rantai.
Di Indonesia: ekspor komoditas primer dan perakitan elektronik menunjukkan pola ini—meskipun produksi tumbuh, capture nilai oleh aktor lokal sering rendah kecuali ada kebijakan local content, transfer teknologi dan kontrol rantai nilai.
Maka outsourcing menjadi mekanisme utama globalisasi produksi: perusahaan pusat memecah proses produksi dan memindahkan potongan-potongan yang intensif tenaga kerja ke lokasi berupah rendah. Smith mendetailkan berbagai model kontrak (kontrak OEM/ODM, subkontrak berantai) dan bagaimana teknologi komunikasi & logistik memungkinkan fragmentasi produksi. Ia menggarisbawahi bahwa outsourcing bukan sekadar teknis efisiensi, melainkan strategi akumulasi yang membangun hubungan ketergantungan struktural antara inti dan perifer.
Itu terjadi pada banyak sektor manufaktur dan tekstil di Indonesia beroperasi sebagai bagian rantai outsourcing; kebijakan investasi yang hanya menarik modal tanpa mengatur struktur kontrak memperkuat ketergantungan.
Smith membedakan dua bentuk outsourcing utama: (a) arm’s-length (pembelian komponen atau kontrak satu tahap), dan (b) hierarchical/vertical control (integrasi jaringan pemasok yang dikontrol ketat oleh perusahaan pusat melalui kualitas, IP, dan teknologi). Bab ini penting karena bentuk hubungan menentukan ruang manuver pekerja dan negara: arm’s-length sering berarti persaingan tekanan harga; hierarchical control memungkinkan perusahaan pusat mempertahankan kontrol kualitas sekaligus kemampuan mengekstrak nilai.
Implikasinya negara dan pekerja menghadapi modalitas yang berbeda — strategi politik industrial dan serikat pekerja harus menyesuaikan dengan bentuk outsourcing yang dominan.
Smith mengkritik narasi neoliberal bahwa industrialisasi di Selatan adalah tanda kemajuan. Ia menunjukkan bahwa produksi global tidak berarti industrialisasi sejati, karena nilai tambah tetap diserap oleh perusahaan di negara maju. Ia mencontohkan iPhone: walau dirakit di Tiongkok, 90% nilai keuntungannya mengalir ke Apple dan pemasok teknologi tinggi di AS, Jepang, dan Eropa. Investasi asing yang hadir di Indonesia sering dipuji sebagai “pembangunan” padahal struktur kepemilikan, transfer teknologi, dan rantai nilai tetap timpang. Seperti dikatakan Smith, “produksi global memperdalam ketergantungan, bukan membebaskannya.”
Imperialism in the Twenty-First Century menantang pembedaan klasik inti/perifer yang pasif: sekarang tenaga kerja Selatan menjadi subyek strategis—bukan sekadar penyedia upah murah tetapi kunci akumulasi global. Ia menunjukkan bagaimana kumpulan tenaga kerja besar di Tiongkok, Asia Tenggara, dan India memberi modal ruang untuk “global wage arbitrage.” Namun ini juga membuka posisi tawar baru bila pekerja bisa berorganisasi atau bila negara menerapkan kebijakan industrial pro-pekerja. Karena itu kelas pekerja urban dan buruh pabrik—jika terorganisir transnasional—memiliki potensi menegosiasikan ketentuan yang lebih baik; namun represi serikat dan fleksibilitas kerja melemahkan peluang itu.
Pada Bab 5 — Global Wage Trends in the Neoliberal Era, Smith menyajikan data tren upah global: upah riil stagnan atau menurun di banyak negara pusat sejak 1980-an, sementara di beberapa negara perifer naik relatif tetapi tetap jauh di bawah standar inti. Ia menekankan peran neoliberalisme—deregulasi, precarization, serangan pada serikat—dalam menekan upah sehingga keuntungan korporasi terjaga. Bab ini menghubungkan statistik upah dengan distribusi surplus global dan ketimpangan. Bagi Indonesia, meski upah nominal naik di beberapa sektor, kenaikan produktivitas, jaminan sosial, dan distribusi keuntungan sering tidak seimbang—menjaga legitimasi sosial kerja butuh kebijakan upah minimum, jaminan, dan industrial policy.
Bab ini membahas dua fenomena yang tampak paradoksal: (1) purchasing power anomaly — peningkatan output tidak selalu mendorong konsumsi massa di negara pusat karena upah tidak naik; dan (2) productivity paradox — produktivitas meningkat tapi tidak tercermin pada kenaikan pendapatan pekerja. Ia menjelaskan, Pada Bab 6 ini, bagaimana akumulasi finansial dan distribusi pendapatan yang miring menciptakan pasar yang rapuh: permintaan efektif melemah walau produksi besar.
Implikasi makro: permintaan global lemah memperparah krisis overproduction; bagi Indonesia, strategi pembangunan harus menyeimbangkan produksi ekspor dengan penguatan pasar domestik berpendapatan.
Bab 7 — Global Labor Arbitrage: The Key Driver of the Globalization of Production buku ini memusatkan tema inti: labor arbitrage (perbedaan biaya tenaga kerja antar wilayah) adalah motor utama relokasi produksi global. Smith menunjukkan bagaimana kapital memaksimalkan selisih upah, hak, dan ketentuan antara lokasi; mekanisme yang dipakai termasuk ancaman relokasi, penggunaan kontraktor, dan pembatasan serikat. Bab ini menghubungkan labor arbitrage dengan strategi korporasi untuk mempertahankan margin profit di tengah stagnasi.
Indonesia berkompetisi dengan negara lain untuk menarik investasi berbasis upah rendah — solusi jangka panjangnya harus menolak rasionalitas perang upah dan fokus pada nilai tambah serta hak-hak pekerja.
Setelah 1980-an, lembaga keuangan global (IMF, Bank Dunia, WTO) memaksakan liberalisasi dan privatisasi. Utang negara-negara Selatan digunakan sebagai alat kontrol politik dan ekonomi — menuntut reformasi struktural yang memperlemah negara dan memperkuat korporasi asing. Situasi ini masih nyata di Indonesia: ketergantungan pada pembiayaan eksternal (utang luar negeri dan investasi asing) membuat negara rentan terhadap tekanan kebijakan. Ketika negara mengutamakan “iklim investasi,” buruh dan lingkungan sering menjadi korban.
Smith menguraikan paradoks besar kapitalisme modern: kemampuan menghasilkan lebih banyak dari yang dapat dijual dengan untung. Untuk mengatasi krisis ini, kapital memindahkan produksi ke Selatan dan menciptakan pasar keuangan spekulatif. Namun strategi ini hanya menunda krisis, bukan menyelesaikannya. Hasilnya adalah krisis ganda: ekonomi (overproduksi dan stagnasi) dan ekologi (eksploitasi alam berlebihan). Pada situasi pasca-pandemi dan krisis iklim: dunia menghadapi kelebihan produksi dan kelebihan karbon sekaligus. Smith dengan tajam menulis, “Capitalism’s survival strategy is its suicide note.”
Smith kembali ke teori marxis: ia mengurai bagaimana Law of Value (nilai kerja) beroperasi dalam dunia berantai global—nilai lebih diekstrak di lokasi produksi murah dan direalisasi lewat pasar dunia. Bab ini juga menjelaskan distorsi: nilai tak lagi terlokalisasi, sehingga hubungan sosial produksi menjadi lintas-negara. Smith menunjukkan bahwa imperialisme modern adalah cara kapital untuk mengatasi krisis nilai melalui spasial expansion (geographical fixes).
Buku ini menegaskan relevansi teori nilai kerja klasik dalam menjelaskan ketimpangan global kontemporer; bagi pembuat kebijakan Indonesia, pemahaman ini penting untuk merancang kontrol rantai nilai dan kebijakan fiskal yang memperbaiki capture nilai domestik.
Penggunaan GDP sebagai indikator kesejahteraan juga dikritik: GDP tumbuh sementara kesejahteraan pekerja, distribusi pendapatan, dan kualitas hidup bisa stagnan atau merosot. Ia memaparkan bagaimana ekspor dan produksi yang terintegrasi secara global dapat menaikkan GDP tanpa memperbaiki kondisi massal—karena keuntungan direpatriasi. Bab ini mendorong pembacaan alternatif: indikator distribusi, pendapatan riil, dan kualitas hidup harus jadi tolok ukur pembangunan.
Catatan Akhir
Bab penutup, Bab 10 — All Roads Lead into the Crisis, mengikat semua tema: akumulasi melalui super-exploitation, finansialisasi, krisis permintaan, dan destruksi ekologis membawa kapital ke jalan kebuntuan—krisis berkepanjangan yang sifatnya sistemik. Smith menegaskan bahwa tanpa arah radikal (redistribusi nilai, kontrol atas rantai global, hak pekerja, demokrasi ekonomi), kapitalisme imperial akan terus memproduksi krisis. Ia juga menyinggung kemungkinan dan syarat alternatif: solidaritas transnasional pekerja, kebijakan industri berdaulat, pembatalan hutang, dan transisi ekologi adil.
John Smith memperbarui teori klasik tentang imperialisme. Dan menegaskan bahwa “imperialisme abad ke-21 adalah wajah manusiawi dari perbudakan modern.” Ia adalah wajah yang busuk disembunyikan dibalik kosmetik tebal yang bernama globalisasi. Ia menggabung-kan analisis ekonomi Marxian, teori ketergantungan Latin Amerika, dan kritik ekologi politik. Dengan gaya argumentatif tajam dan bukti empiris kuat, Smith menunjukkan bahwa globalisasi neoliberal bukan akhir dari imperialisme — melainkan puncaknya.
Buku ini mengingatkan bahwa perjuangan untuk keadilan sosial dan ekologis bukan sekadar lokal atau nasional, melainkan global dan struktural.
Bagi Indonesia, menghadapi “jalan krisis” berarti membangun strategi berdaulat—industrial policy, peraturan investasi yang kuat, kekuatan serikat, dan kebijakan iklim yang adil.
Bogor-Bandung, 14 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Khalid, F. (2019). Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis. Islamic Foundation.
Smith, J. (2016). Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis. Monthly Review Press.
Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press.
Pugh, J., & Chandler, D. (2021). Anthropocene Islands: Entangled Worlds. University of Westminster Press.