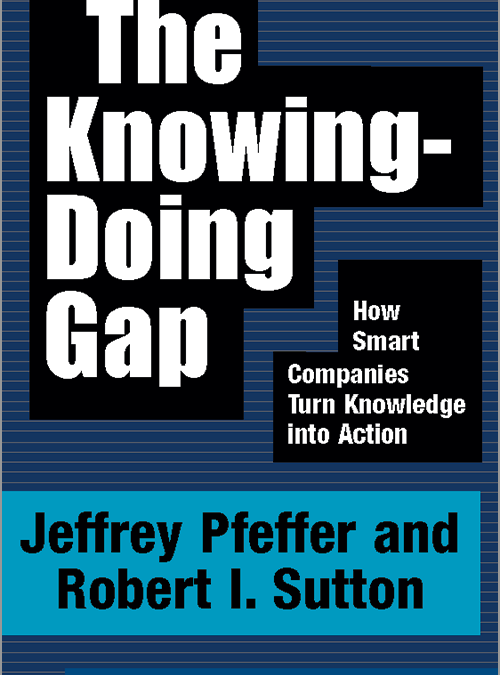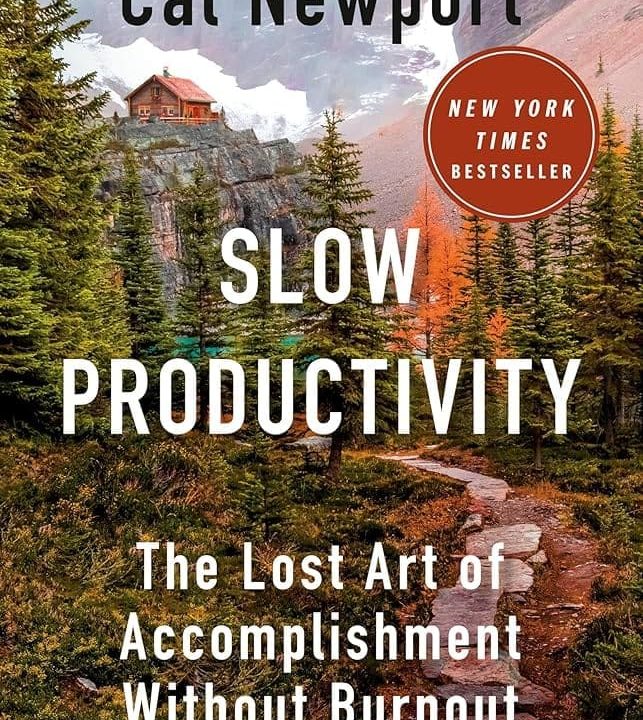Rubarubu #26
The Knowing-Doing Gap:
Mengubah Pengetahuan Menjadi Tindakan
Paradoks Perusahaan yang Terlalu Pintar untuk Bertindak
Bayangkan sebuah perusahaan teknologi yang menghabiskan jutaan dolar untuk mengirim para manajernya ke program pelatihan kepemimpinan terbaik. Mereka mendatangkan guru manajemen ternama, perpustakaan perusahaan penuh dengan buku-buku tentang inovasi, dan semua orang bisa memaparkan teori “transformasi digital” dengan fasih. Namun, ketika seorang karyawan muda mengajukan ide sederhana untuk memperbaiki proses yang sudah usang, ide itu tenggelam dalam rapat demi rapat. Formulir harus diisi, persetujuan dari lima atasan harus didapat, dan akhirnya, semangat itu pun padam. Perusahaan itu tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih gesit, tetapi mereka tidak melakukannya.
Kisah ini adalah gambaran sempurna dari fenomena yang diinvestigasi oleh Jeffrey Pfeffer dan Robert I. Sutton dalam buku mereka yang groundbreaking, “The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action” (2000). Buku ini bukan tentang apa yang harus kita ketahui, tetapi tentang mengapa kita sering kali gagal mengubah pengetahuan itu menjadi tindakan, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa mengatasinya. “The central message of this book is that transforming knowledge into action is one of the greatest challenges—and opportunities—facing organizations today. There is often a huge and damning difference between what firms know and what they do.” (Pfeffer & Sutton, 2000, p. 6) [1].
Di dunia yang dipenuhi dengan informasi, konsultan, dan “best practices,” mengapa begitu banyak organisasi yang masih terjebak dalam ketidakaktifan? Pfeffer dan Sutton berargumen bahwa masalahnya bukan pada kekurangan pengetahuan, tetapi pada penyakit sosial dan organisasiyang secara sistematis mencekik tindakan.
Membongkar Penyebab dan Menemukan Obat
Buku ini dibangun dengan kerangka yang jelas: pertama, mendiagnosis akar penyebab “Knowing-Doing Gap,” dan kedua, memberikan resep untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan. Mengapa “knowing” tidak menjadi “doing”? – Penulis berpendapat ada beberapa penghalang utama. Penulis mengidentifikasi lima penghalang utama yang membuat organisasi terjebak dalam “pengetahuan kosong”.
1. Ketika Talk Merupakan Pengganti untuk Action (When Talk Substitutes for Action)
Dalam banyak organisasi, proses pembicaraan—rapat, presentasi, perencanaan—sering kali disalahartikan sebagai kemajuan. Perusahaan menghabiskan begitu banyak energi untuk berbicaratentang apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada energi yang tersisa untuk melakukannya. “In many organizations, the process of talking about what to do and planning what to do becomes a substitute for actually doing it.” (Pfeffer & Sutton, 2000, p. 42) [1].
- Relevansi Masa Kini: “Analysis paralysis” di era Big Data dan budaya rapat yang tidak produktif dalam kerja hybrid adalah manifestasi modern dari masalah ini.
2. Ketika Memory Merupakan Pengganti untuk Thinking (When Memory Substitutes for Thinking)
Organisasi sering terperangkap oleh kesuksesan masa lalu. Mereka menerapkan “best practices” lama secara membabi buta tanpa mempertimbangkan konteks yang berubah. Prosedur dan kebijakan yang sudah ketinggalan zaman menjadi “cara kami melakukan sesuatu di sini” yang suci dan tidak boleh dipertanyakan.
- Relevansi Masa Depan: Dalam era disrupsi, ketergantungan pada memori masa lalu adalah resep untuk keusangan. Organisasi perlu menjadi pembelajar yang lincah, bukan museum prosedur.
3. Ketika Fear Menghalangi Action (When Fear Prevents Action)
Budaya ketakutan adalah pembunuh terbesar dari tindakan. Ketika orang takut disalahkan, dipermalukan, atau dipecat karena mencoba hal baru dan gagal, mereka akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Ketakutan mendorong orang untuk bermain aman, mengikuti aturan, dan menghindari risiko.
- Relevansi Masa Kini: Inovasi—kunci untuk bertahan di dunia modern—tidak mungkin tumbuh dalam tanah yang dipupuk dengan ketakutan.
4. Pengukuran yang Menghambat (When Measurement Obstructs Good Judgment)
Manajemen berdasarkan angka (management by numbers) bisa menjadi bumerang. Ketika orang terobsesi dengan metrik (seperti kepuasan pelanggan yang diukur dengan skor 1-10), mereka akan mengoptimalkan angka tersebut, seringkali dengan mengorbankan substansi yang sebenarnya diinginkan—yaitu, pelanggan yang benar-benar bahagia.
- Relevansi Masa Depan: Dengan kemajuan AI dan analitik, godaan untuk mengukur segalanya akan semakin besar. Kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang tidak boleh diukur akan menjadi sangat berharga.
5. Ketika Internal Competition Menjadi Lebih Penting daripada External Competition
Persaingan internal yang kejam, sistem reward yang mendorong orang untuk saling mengalahkan, dan politik kantor memecah belah organisasi. Alih-alih bekerja sama untuk melawan pesaing di pasar, energi habis untuk pertarungan internal.
“Internal competition turns colleagues into competitors, causing people to hoard knowledge, not share it; to undermine others’ efforts, not support them.” (Pfeffer & Sutton, 2000, p. 109) [1].
Bagaimana Menutup Kesenjangan – Prinsip untuk Bertindak
Setelah mendiagnosis penyakitnya, penulis menawarkan obatnya. Mereka menyajikan seperangkat prinsip yang dianut oleh perusahaan yang berhasil mengubah pengetahuan menjadi tindakan.
1. Why Before How: Filosofi itu Penting
Orang tidak akan bertindak dengan komitmen penuh jika mereka tidak memahami mengapa suatu tindakan diperlukan. Perusahaan yang sukses memastikan setiap orang memahami konteks dan tujuan di balik suatu tindakan, bukan hanya diajari bagaimana melakukannya. Ini mengingatkan pada tulisan Simon Sinek: “Orang tidak membeli APA yang Anda lakukan, mereka membeli MENGAPA Anda melakukannya.” [2].
2. Knowledge (and Action) Comes from Doing
Cara terbaik untuk belajar adalah dengan melakukan. Daripada hanya mendengarkan ceramah atau membaca manual, perusahaan-perusahaan ini menciptakan pengalaman langsung, prototipe, dan pilot project.
- Contoh: Alih-alih membuat rencana 5 tahun untuk transformasi digital, sebuah perusahaan mungkin memilih satu tim untuk mencoba alat kolaborasi baru selama sebulan dan belajar dari sana.
3. Action Counts More than Elegant Plans and Concepts
Nilai ada pada eksekusi, bukan pada kesempurnaan rencana. Perusahaan yang berfokus pada tindakan lebih memilih untuk bergerak cepat dengan sesuatu yang “cukup baik” dan memperbaikinya di jalan, daripada menunggu solusi yang sempurna.
Kutipan Kunci: “In a knowing-doing organization, there is a bias for action. The motto is ‘Ready, fire, aim’—not ‘Ready, aim, aim, aim…” (Pfeffer & Sutton, 2000, p. 244) [1].
4. There is No Doing without Mistakes… or without Learning
Perusahaan yang berhasil menutup kesenjangan melihat kegagalan sebagai sumber pembelajaran yang vital, bukan sebagai sesuatu yang harus dihukum. Mereka menciptakan “ruang aman” untuk bereksperimen.
5. Drive Out Fear, Build Trust
Ini adalah fondasinya. Tanpa lingkungan yang aman secara psikologis, di mana orang percaya bahwa mereka tidak akan dihukum karena berbicara atau mencoba, semua prinsip lainnya akan runtuh. Prinsip ini bergema dengan ajaran Nelson Mandela: “Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemenangan atasnya.” [3]. Sebuah organisasi harus membantu orang-orangnya untuk menaklukkan ketakutan mereka agar bisa bertindak.
Sementara itu Bab 4: Musuh Tak Terlihat dari Inovasi dan Tindakan (When Fear Prevents Acting on Knowledge) membahas salah satu penghalang paling kuat dan merusak dalam mengubah pengetahuan menjadi tindakan: rasa takut. Pfeffer dan Sutton berargumen bahwa dalam banyak organisasi, budaya ketakutan bukanlah sebuah gejala sampingan, melainkan sebuah penyakit inti yang melumpuhkan. Ketika orang takut akan konsekuensi negatif dari bertindak—terutama jika tindakan itu melibatkan risiko atau menyimpang dari norma—mereka akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa, sekalipun mereka tahu apa yang seharusnya dilakukan.
“Fear does more than discourage potential action; it prevents the acquisition of new knowledge in the first place, teaches people to keep their heads down and not make waves, and breeds an environment of internal competition and politics that is antithetical to learning and cooperation.” (Pfeffer & Sutton, 2000, p. 105) [1].
Bab ini menguraikan bagaimana ketakutan diciptakan, dipelihara, dan dampak destruktifnya terhadap organisasi.
Tabel di bawah ini merangkum perbedaan mendasar antara dua jenis lingkungan kerja ini dan bagaimana mereka mempengaruhi “Knowing-Doing Gap”.
Tabel Perbandingan: Organisasi yang Dipimpin oleh
Rasa Takut vs. Organisasi yang Dipimpin oleh Kepercayaan
| Aspek Organisasi | Organisasi yang Dipimpin Rasa Takut (Fear-Based) | Organisasi yang Dipimpin Kepercayaan (Trust-Based) | Dampak pada Knowing-Doing Gap |
| 1. Pengambilan Risiko & Inovasi | Penghindaran Risiko Total. Karyawan hanya melakukan apa yang diperintahkan dan mengikuti prosedur secara membabi buta. Eksperimen dan penyimpangan dilarang. | Eksperimen yang Terkelola. Karyawan didorong untuk mencoba hal baru. Kegagalan dilihat sebagai biaya pembelajaran, bukan alasan untuk dihukum. | Gap Lebar: Pengetahuan tentang perlunya inovasi ada, tetapi tindakan diredam oleh ketakutan. |
| 2. Komunikasi & Umpan Balik | Informasi Disembunyikan. Pesan buruk disembunyikan, kesalahan ditutupi. “Shoot the messenger” adalah norma. Percakapan jujur dan kritis dihindari. | Transparansi & Kejujuran. Masalah didiskusikan secara terbuka. Umpan balik diberikan dan diterima dengan konstruktif untuk perbaikan. | Gap Lebar: Pengetahuan tentang masalah nyata tidak pernah muncul ke permukaan, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. |
| 3. Penyelesaian Masalah | Mencari Kambing Hitam. Fokusnya adalah pada siapa yang salah, bukan apa yang salah. Ini mendorong perilaku defensif dan saling menyalahkan. | Fokus pada Sistem & Proses. Masalah dilihat sebagai kegagalan sistem, bukan kegagalan individu. Fokusnya pada perbaikan root cause. | Gap Lebar: Energi dihabiskan untuk menyelamatkan diri sendiri, bukan untuk menyelesaikan masalah. |
| 4. Pembelajaran & Pengembangan | Pembelajaran Mandek. Orang menyembunyikan ketidaktahuan mereka dan enggan mengajukan pertanyaan. Tidak ada ruang untuk belajar dari kesalahan. | Pembelajaran Berkelanjutan. Kerentanan diterima. Orang merasa aman untuk bertanya, “Saya tidak tahu,” dan “Bisakah Anda membantu saya?” | Gap Lebar: Pengetahuan baru tidak bisa berkembang karena orang takut terlihat bodoh. |
| 5. Kepatuhan vs. Komitmen | Kepatuhan Kosong (Compliance). Orang patuh karena takut dihukum. Mereka melakukan minimum yang diperlukan. | Komitmen Tulus (Commitment). Orang bertindak karena mereka percaya pada tujuan dan merasa memiliki. Mereka memberikan usaha terbaik. | Gap Lebar: Tindakan hanya bersifat superficial dan transaksional, bukan didorong oleh pemahaman yang mendalam. |
| 6. Alokasi Energi | Energi untuk Politik & Pertahanan Diri. Banyak waktu dan pikiran dihabiskan untuk mengelola kesan, membangun aliansi politik, dan melindungi diri dari serangan. | Energi untuk Pelanggan & Hasil. Energi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi dan melayani pelanggan. | Gap Lebar: Sumber daya intelektual dan emosional yang seharusnya untuk bertindak, justru habis untuk bertahan hidup. |
Anatomi Ketakutan di Tempat Kerja
Pfeffer dan Sutton mendetailkan mekanisme spesifik bagaimana ketakutan mencekik tindakan.
1. Takut akan Hukuman atas Kegagalan (Fear of Punishment for Failure)
Ini adalah sumber ketakutan yang paling langsung. Jika organisasi memiliki sejarah memecat, menurunkan jabatan, atau mempermalukan orang yang gagal, maka pesannya jelas: jangan mengambil risiko.
- Contoh: Seorang insinyur yang tahu bahwa sebuah proses produksi bisa ditingkatkan mungkin akan diam saja. Jika dia mengusulkan perubahan dan gagal, karirnya bisa hancur. Jika dia diam dan proses yang buruk terus berjalan, tidak ada yang akan menyalahkannya. Dalam kalkulus rasa takut, diam adalah pilihan yang lebih aman.
2. Takut akan Ketidakpastian dan Ambiguitas (Fear of Uncertainty and Ambiguity)
Tindakan, terutama yang inovatif, selalu melibatkan ketidakpastian. Budaya birokrasi yang kaku sering kali diciptakan untuk meminimalkan ketidakpastian ini. Ketika orang terbiasa dengan aturan yang jelas dan prosedur yang tetap, mereka menjadi takut untuk beroperasi di luar zona nyaman mereka, bahkan ketika pengetahuan mereka mengatakan bahwa aturan itu sudah usang.
3. Takut Terlihat Bodoh (Fear of Looking Ignorant)
Dalam budaya yang terlalu menekankan pada “pemimpin yang serba tahu” atau “kecerdasan individual,” mengakui bahwa Anda tidak tahu sesuatu dianggap sebagai kelemahan. Ketakutan ini mencegah orang untuk bertanya, mencari bantuan, atau mengakui bahwa mereka perlu belajar, yang pada akhirnya menghambat akuisisi pengetahuan baru dan penerapannya.
4. Takut akan Konflik dan Konfrontasi (Fear of Conflict and Confrontation)
Bertindak berdasarkan pengetahuan baru seringkali berarti menantang status quo atau mengkritik praktik yang sudah mapan. Hal ini dapat menimbulkan konflik dengan mereka yang memiliki kepentingan dalam menjaga keadaan yang ada. Banyak orang lebih memilih untuk tetap damai dan menghindari konfrontasi yang tidak menyenangkan, meskipun hal itu berarti mengorbankan kinerja organisasi.
5. Takut Kehilangan Sumber Daya atau Status (Fear of Losing Resources or Status)
Dalam organisasi yang sangat kompetitif secara internal, tindakan yang dilakukan oleh satu unit atau individu dapat dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain. Ketakutan bahwa kesuksesan orang lain akan berarti kegagalan bagi diri sendiri mendorong orang untuk menghalangi, bukan membantu, tindakan orang lain.
Kutipan Filsuf dan Pemikir yang Relevan
Masalah ketakutan ini telah dibahas oleh para pemikir sepanjang sejarah.
- Francis Bacon (Filsuf Inggris): “Knowledge itself is power.” (Pengetahuan itu sendiri adalah kekuatan). Namun, Pfeffer dan Sutton akan menambahkan: “Tetapi ketakutan dapat melucuti kekuatan itu.” Dalam organisasi yang penuh ketakutan, kekuatan pengetahuan menjadi tidak berguna karena tidak ada yang berani menggunakannya.
- Nelson Mandela (Aktivis dan Mantan Presiden Afrika Selatan): “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.” (Saya belajar bahwa keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemenangan atasnya. Orang yang berani bukanlah dia yang tidak merasa takut, tetapi dia yang menaklukkan rasa takut itu) [2]. Sebuah organisasi yang bijak tidak mengharapkan orangnya untuk tidak memiliki rasa takut, tetapi menciptakan kondisi di mana orang merasa cukup aman untuk menaklukkan rasa takut mereka dan bertindak.
Kesimpulan Bab: Membangun Jembatan dari Pengetahuan ke Tindakan dengan Keberanian
Bab ini menyimpulkan bahwa memerangi ketakutan bukanlah sebuah “program pelatihan” tambahan, melainkan tugas fundamental dari kepemimpinan.
“The most important responsibility of a leader is to create an environment where it is safe for people to tell the truth, to experiment, and to occasionally fail—an environment that rewards doing instead of just knowing.” (Pfeffer & Sutton, 2000, p. 132) [1].
Pemimpin harus secara aktif “mengusir ketakutan” dari organisasi dengan:
- Menghargai dan Melindungi Pembawa Kabar Buruk.
- Merayakan Kegagalan yang Terpelajar (intelligent failures) sebagai bukti bahwa orang sedang mencoba hal baru.
- Menghukum Perilaku Politik dan Menyalahkan, bukan menghukum kegagalan yang jujur.
- Mendemonstrasikan kerentanan mereka sendiri dengan mengakui ketidaktahuan dan kesalahan.
Dengan demikian, menutup “Knowing-Doing Gap” yang disebabkan oleh rasa takut membutuhkan lebih dari sekadar analisis yang brilian; hal ini membutuhkan keberanian moral dari para pemimpinuntuk membangun budaya kepercayaan di mana pengetahuan tidak hanya disimpan, tetapi juga dijalankan dengan percaya diri.
Setelah melalui tujuh bab sebelumnya yang mendiagnosis akar penyebab “Knowing-Doing Gap”—seperti ketika pembicaraan menggantikan tindakan, ketika memori menggantikan pemikiran, dan ketika ketakutan mencegah aksi—Bab 8: Dari Diagnosis ke Resep – Prinsip untuk Menutup Kesenjangan (Turning Knowledge into Action) berfungsi sebagai puncak dari buku ini. Di sini, Pfeffer dan Sutton beralih dari “apa yang salah” ke “bagaimana memperbaiki-nya”.
Bab ini adalah jantung dari solusi. Penulis tidak menawarkan daftar periksa yang kaku atau program “cara terbaik” yang generik. Sebaliknya, mereka menyajikan serangkaian prinsip panduan yang saling terkait yang, ketika diterapkan bersama, menciptakan lingkungan di mana pengetahuan secara alami dan konsisten diubah menjadi tindakan yang efektif. “The knowing-doing problem is not primarily about the lack of intelligence or knowledge. It’s about a failure to translate that knowledge into action. The principles we outline here provide a foundation for building organizations that act on what they know.” (Pfeffer & Sutton, 2000, p. 235) [1].
Elaborasi Mendalam tentang Prinsip-Prinsip untuk Bertindak
Berikut adalah uraian lengkap dari setiap prinsip yang dijelaskan dalam bab ini, beserta logika dan penerapannya.
Prinsip 1: Why Before How: Filosofi itu Penting
- Konsep Inti: Orang tidak akan bertindak dengan komitmen dan pemahaman yang penuh jika mereka hanya diajari bagaimana melakukan sesuatu tanpa memahami mengapa hal itu harus dilakukan. Penjelasan filosofis dan kontekstual harus mendahului instruksi teknis.
- Mengapa Ini Penting: Memahami “mengapa” memberikan makna. Itu memberdayakan orang untuk menggunakan penilaian mereka sendiri ketika mereka menghadapi situasi yang tidak terduga, alih-alih hanya mengikuti prosedur secara membabi buta. Ini mengubah kepatuhan buta menjadi komitmen yang cerdas.
- Contoh Penerapan: Alih-alih hanya memerintahkan teller bank untuk mengucapkan “Terima kasih telah menggunakan layanan kami,” sebuah bank yang menerapkan prinsip ini akan terlebih dahulu menjelaskan mengapa pengalaman pelanggan yang positif sangat penting untuk loyalitas dan bisnis jangka panjang. Dengan memahami “mengapa”-nya, para teller akan lebih tulus dan kreatif dalam menciptakan pengalaman itu.
- Kaitan dengan Pemikiran Lain: Prinsip ini sangat selaras dengan Golden Circle Simon Sinek, yang mempopulerkan ide untuk “Start With Why”. Sinek berargumen bahwa para pemimpin dan organisasi yang paling inspiratif mulai dengan menjelaskan tujuan dan keyakinan mereka sebelum menjelaskan produk atau proses mereka [2].
Prinsip 2: Knowing Comes from Doing, and Teaching Others How
- Konsep Inti: Cara terbaik untuk mempelajari sesuatu—dan untuk memastikan pengetahuan itu tertanam—adalah dengan melakukannya secara langsung dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Pengetahuan prosedural (know-how) jauh lebih berharga daripada pengetahuan deklaratif (know-what).
- Mengapa Ini Penting: Pelatihan dan ceramah konvensional seringkali hanya menciptakan pengetahuan yang pasif. Ketika orang secara aktif terlibat dalam sebuah tugas dan kemudian harus mengartikulasikan apa yang telah mereka pelajari kepada orang lain, pemahaman mereka menjadi lebih dalam dan lebih melekat.
- Contoh Penerapan: Daripada menyelenggarakan lokakarya tentang “manajemen proyek yang gesit,” sebuah perusahaan mungkin meminta sebuah tim untuk langsung menggunakan metodologi agile dalam sebuah proyek kecil. Setelah proyek selesai, tim tersebut kemudian ditugaskan untuk membimbing tim lain yang ingin menerapkan agile. Proses membimbing ini akan memaksa tim pertama untuk menyusun dan menyempurnakan pengetahuan mereka.
- Kaitan dengan Filsafat: Ini adalah penerapan langsung dari pedagogi experiential learning(pembelajaran pengalaman) yang dikemukakan oleh John Dewey, yang menekankan bahwa belajar melalui pengalaman langsung adalah bentuk pendidikan yang paling efektif.
Prinsip 3: Action Counts More than Elegant Plans and Concepts
- Konsep Inti: Nilai sebenarnya terletak pada eksekusi, bukan pada kesempurnaan rencana. Organisasi yang berhasil menutup kesenjangan memiliki bias untuk bertindak. Mereka lebih memilih untuk bergerak cepat dengan sesuatu yang “cukup baik” dan belajar serta beradaptasi sepanjang jalan.
- Mengapa Ini Penting: Pencarian tanpa henti akan rencana yang sempurna—sering kali didorong oleh rasa takut akan kegagalan—adalah salah satu bentuk paling umum dari “pembicaraan yang menggantikan tindakan.” Dalam dunia yang berubah dengan cepat, sebuah keputusan yang baik yang dijalankan hari ini lebih baik daripada sebuah keputusan sempurna yang dijalankan enam bulan kemudian.
- Contoh Penerapan: Sebuah tim pengembangan produk mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merencanakan setiap fitur dengan sempurna. Sebaliknya, tim yang berorientasi pada tindakan akan membuat minimum viable product (MVP) dalam beberapa minggu, mengujinya dengan pengguna, dan mengulang berdasarkan umpan balik nyata.
- Kutipan Kunci: “In a knowing-doing organization, there is a bias for action. The motto is ‘Ready, fire, aim’—not ‘Ready, aim, aim, aim…’” (Pfeffer & Sutton, 2000, p. 244) [1].
Prinsip 4: There is No Doing without Mistakes… or without Learning
- Konsep Inti: Kegagalan adalah produk sampingan yang tak terhindarkan dari tindakan dan eksperimen. Organisasi harus melihat kegagalan yang “terpelajar” (intelligent failures)—kegagalan yang terjadi karena mencoba hal baru—sebagai sumber pengetahuan yang vital, bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau dihukum.
- Mengapa Ini Penting: Sebuah budaya yang menghukum kegagalan akan secara efektif mematikan semua tindakan yang berisiko, yang pada dasarnya adalah semua tindakan inovatif. Untuk mendorong prinsip “action counts more,” organisasi harus secara bersamaan mendorong prinsip “learning from failure.”
- Contoh Penerapan: Sebuah perusahaan dapat menyelenggarakan “pesta kegagalan” di mana tim berbagi cerita tentang proyek yang gagal dan pelajaran berharga yang mereka petik. Ini secara simbolis dan praktis mengubah kegagalan dari sebuah aib menjadi sebuah aset.
- Kaitan dengan Pemikiran Lain: Prinsip ini adalah fondasi dari konsep modern seperti fail fastdalam dunia startup dan psychological safety yang dipopulerkan oleh Amy Edmondson, yang didefinisikan sebagai keyakinan bahwa seseorang tidak akan dihukum atau dipermalukan karena mengemukakan ide, pertanyaan, kekhawatiran, atau kesalahan [6].
Prinsip 5: Drive Out Fear, Build Trust
- Konsep Inti: Ini adalah prinsip yang paling mendasar, yang memperkuat keempat prinsip lainnya. Tanpa lingkungan yang aman secara psikologis, di mana orang percaya bahwa mereka tidak akan dihukum karena berbicara jujur, mencoba hal baru, atau gagal, semua prinsip lainnya akan runtuh.
- Mengapa Ini Penting: Ketakutan mendorong orang untuk menyembunyikan pengetahuan, menghindari tindakan, dan menyalahkan orang lain. Kepercayaan memungkinkan kolaborasi, eksperimen, dan komunikasi yang jujur—bahan bakar yang diperlukan untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan.
- Contoh Penerapan: Seorang pemimpin secara terbuka mengakui kesalahan strategisnya sendiri dalam rapat seluruh perusahaan. Dengan menunjukkan kerentanannya, dia mengirim pesan yang kuat bahwa adalah aman untuk mengakui ketidaktahuan dan kegagalan, sehingga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.
- Kaitan dengan Filsafat: Prinsip ini adalah inti dari ajaran Lao Tzu dalam Tao Te Ching: “Pemimpin terbaik adalah mereka yang hampir tidak diketahui oleh orang-orang… Ketika pekerjaan mereka selesai, tujuan mereka terpenuhi, mereka semua akan berkata, ‘Kami melakukannya sendiri.'” Sebuah organisasi yang bebas dari rasa takut adalah organisasi di mana setiap orang merasa diberdayakan untuk bertindak, seolah-olah mereka adalah pemiliknya.
Sintesis: Sebuah Sistem yang Saling Terkait
Kekuatan bab ini terletak pada bagaimana kelima prinsip ini saling memperkuat:
- Memahami “Why” (Prinsip 1) memberikan motivasi untuk “Doing” (Prinsip 2).
- Fokus pada “Action” (Prinsip 3) secara alami akan menghasilkan beberapa “Mistakes” (Prinsip 4).
- Untuk belajar dari kesalahan tersebut, Anda membutuhkan lingkungan yang bebas dari “Fear”(Prinsip 5).
- Lingkungan yang aman (Prinsip 5) memungkinkan orang untuk lebih terbuka dalam “Teaching”(Prinsip 2) apa yang telah mereka pelajari.
Dengan demikian, “Turning Knowledge into Action” bukanlah tentang menemukan satu trik ajaib. Ini tentang membangun sebuah sistem organisasi—sebuah budaya dan serangkaian proses—yang secara konsisten memprioritaskan dan memungkinkan eksekusi atas perencanaan, pembelajaran atas penyembunyian, dan kepercayaan atas ketakutan. Bab ini memberikan peta jalan yang kuat untuk melakukan hal tersebut.
Relevansi dengan Dunia Saat Ini dan Masa Depan
- Era Disrupsi Digital: Kecepatan adalah segalanya. Perusahaan yang terjebak dalam “knowing-doing gap” akan punah karena mereka terlalu lambat dalam beradaptasi dan berinovasi.
- Budak “Best Practices”: Buku ini adalah peringatan terhadap penerapan “cara orang lain” secara membabi buta. Konteks adalah raja. Pengetahuan harus disesuaikan dan diuji melalui tindakan di lingkungan sendiri.
- Krisis Inovasi: Banyak perusahaan mengeluh mereka tidak bisa berinovasi. Masalahnya seringkali bukan pada kurangnya ide (knowing), tetapi pada budaya dan struktur yang menghambat eksekusi (doing).
Relevansi dengan Konteks Indonesia
Temuan buku ini sangat kontekstual untuk menganalisis tantangan pembangunan dan bisnis di Indonesia.
- Birokrasi Pemerintahan: “Knowing-Doing Gap” mungkin adalah definisi dari birokrasi Indonesia. Prosedur dan perencanaan (talk, memory) sering kali menjadi tujuan itu sendiri, bukan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (action). Ketakutan untuk mengambil keputusan tanpa “payung hukum” yang sempurna melumpuhkan tindakan.
- Budaya Kekuasaan yang Tinggi (High Power Distance): Budaya yang hierarkis dan penuh rasa sungkan dapat memperkuat penghalang “Fear”. Bawahan sering kali takut untuk mengambil inisiatif atau menyampaikan ide yang bertentangan dengan atasan, sehingga banyak pengetahuan di level bawah yang tidak pernah ditindaklanjuti.
- Kearifan Lokal “Trial and Error” sebagai Kekuatan: Prinsip “Knowledge Comes from Doing” sebenarnya selaras dengan semangat wirausaha dan pragmatisme banyak pelaku UMKM Indonesia. Mereka sering kali langsung terjun (doing) dan belajar dari pasar. Kekuatan ini perlu dibawa ke dalam organisasi yang lebih besar.
- Pembangunan Infrastruktur: Buku ini menjelaskan mengapa suatu daerah bisa tahu bahwa mereka membutuhkan jalan yang baik untuk mengangkut hasil pertanian (knowing), tetapi gagal memobilisasi sumber daya dan koordinasi untuk benar-benar membangun jalan tersebut (doing), karena politik lokal, korupsi, atau prosedur yang berbelit.
Kritik dan Apresiasi
- Apresiasi: Buku ini dipuji karena mengidentifikasi masalah mendasar yang sering diabaikan. Sebuah ulasan di Harvard Business Review menyebutnya “sebuah diagnosis yang brilian tentang penyakit organisasi yang paling tersebar luas.” [4]. Buku ini berhasil menggabungkan penelitian akademis yang rigor dengan contoh-contoh bisnis yang praktis.
- Kritik:
- Kurangnya “How” yang Spesifik: Beberapa kritikus berpendapat bahwa meskipun diagnosisnya kuat, resepnya (prinsip-prinsipnya) masih cukup tinggi levelnya dan tidak selalu mudah untuk diterjemahkan menjadi langkah-langkah operasional yang konkret dalam setiap konteks.
- Mengabaikan Kompleksitas Perubahan: Mengubah budaya dari yang penuh ketakutan menjadi penuh kepercayaan adalah proses yang sangat sulit dan memakan waktu lama, yang mungkin diremehkan dalam buku ini.
- Tidak Membahas Peran Teknologi Secara Mendalam: Buku ini terbit di tahun 2000, sebelum ledakan media sosial dan alat kolaborasi cloud. Peran teknologi sebagai enabler atau justru disabler tindakan bisa dieksplorasi lebih dalam.
Catatan Akhir: Keberanian dan Kebijaksanaan Praktis
“The Knowing-Doing Gap” pada akhirnya adalah lebih dari sekadar buku manajemen; ini adalah sebuah panggilan untuk mengutamakan kebijaksanaan praktis (phronesis) atas pengetahuan teknis (episteme).
Buku ini mengajak kita untuk bergeser dari obsesi pada “apa yang kita tahu” ke fokus pada “apa yang akhirnya kita lakukan”. Di dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kemampuan untuk bertindak—untuk bereksperimen, belajar, dan beradaptasi—adalah satu-satunya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Bagi Indonesia, mengatasi “Knowing-Doing Gap” bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Dengan memberdayakan orang-orangnya untuk bertindak, membangun kepercayaan, dan belajar dari pengalaman langsung, Indonesia dapat mengubah pengetahuan kolektifnya tentang potensi yang besar menjadi sebuah realitas kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah Cina kuno: “Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.” [5]. Buku ini mengingatkan kita bahwa langkah pertama itulah yang paling sering terhambat, dan paling penting untuk diambil.
Cirebon, 27 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
[1] Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2000). The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action. Harvard Business School Press.
[2] Sinek, S. (2009). Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Portfolio.
[3] Mandela, N. (1994). Long Walk to Freedom. Little, Brown and Company.
[4] Ghoshal, S. (2000). [Review of the book The Knowing-Doing Gap, by J. Pfeffer & R.I. Sutton]. Harvard Business Review.
[5] Attributed to Lao Tzu. Tao Te Ching.
[6] Edmondson, A. C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.