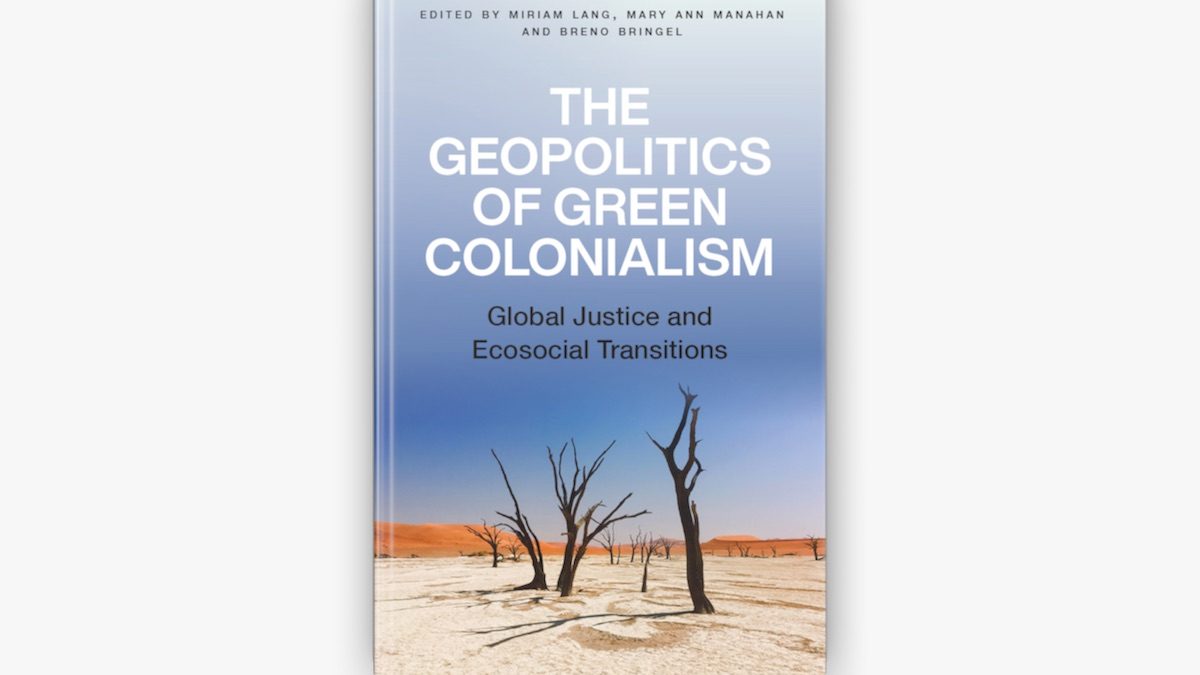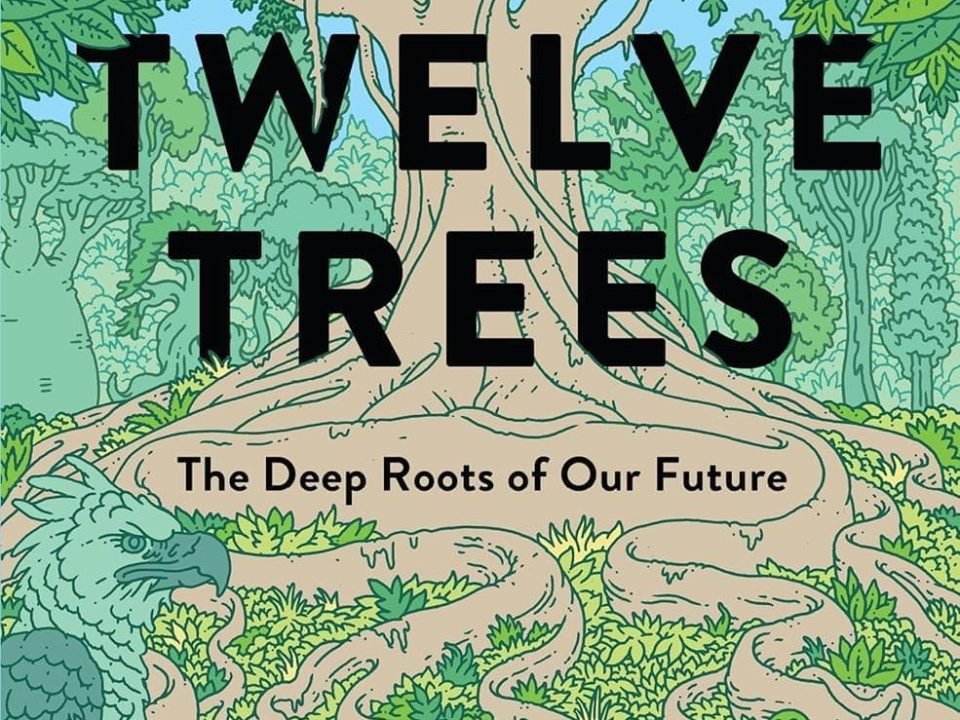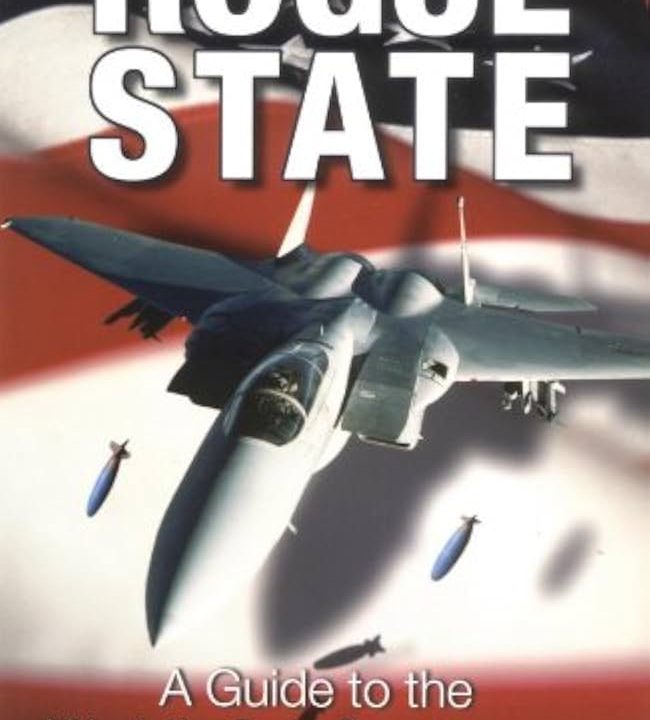# 07 Rubarubu
The Geopolitics of Green Colonialism
Pada suatu petang di sebuah desa di Andes, para petani asli menatap ladang garam dan air yang makin surut. Mereka sedang berjuang melawan izin tambang lithium yang diklaim sebagai ‘energi hijau untuk masa depan dunia’. Namun, para petani itu merasa bahwa transisi hijau global membuat mereka jadi “zona pengorbanan” untuk kebutuhan teknologi negara-Negara Utara.
Laporan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) menyebutkan aktivitas tambang dan smelter di Konawe Utara menyebabkan pencemaran air laut dan udara. Limbah tailing yang dibuang ke laut diduga kuat merusak terumbu karang dan ekosistem pesisir yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Data WALHI Sulawesi Tenggara mencatat izin tambang nikel telah menggerus kawasan hutan, termasuk hutan lindung. Di Kabupaten Konawe sendiri, alih fungsi hutan untuk tambang mencapai puluhan ribu hektar. Hilangnya hutan ini memicu banjir bandang dan longsor pada musim hujan, serta kekeringan di musim kemarau.
Mongabay Indonesia melaporkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat di Konawe Utara. Masyarakat adat Moronene di Konawe Utara kehilangan akses terhadap sumber daya hutan yang menjadi sumber pangan dan mata pencaharian mereka (sagu, rotan, hasil hutan bukan kayu). Tanah ulayat mereka beralih fungsi menjadi lubang-lubang tambang tanpa persetujuan yang benar-benar bebas dan diinformasikan sebelumnya (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). The Gecko Project dan Tirto.id menulis bahwa masyarakat seringkali didesak untuk melepaskan tanahnya dengan harga yang sangat murah. Setelah tanah mereka habis ditambang, mereka kehilangan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, tanpa memiliki keahlian untuk bekerja di sektor tambang.
Kemiskinan yang semakin memburuk dan kerusakan tata sosial. Kehadiran tambang justru memunculkan kesenjangan yang mencolok. Meski perusahaan mengklaim membuka lapangan kerja, lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat lokal seringkali bersifat sementara, berupah rendah, dan tidak terampil. Sementara itu, kehidupan sosial menjadi rentan dengan maraknya prostitusi dan peredaran minuman keras di sekitar area tambang.
“Demam nikel justru menjadi kutukan bagi masyarakat lokal. Mereka kehilangan tanah, air, dan masa depan. Kedaulatan energi hijau Indonesia tidak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat di wilayah tambang.”
Bukti-bukti dari lapangan menunjukkan bahwa “kemajuan” industri nikel nasional justru berbanding terbalik dengan nasib rakyat di Konawe dan kabupaten penghasil nikel lainnya di Sultra. Mereka mengalami kerugian ganda: kehilangan sumber kehidupan (lahan dan laut) sekaligus harus menghadapi dampak buruknya kualitas lingkungan dan kesehatan. Klaim-klaim perusahaan tentang pembangunan dan CSR seringkali tidak sebanding dengan kerusakan permanen yang ditimbulkan, menciptakan lanskap sosial-ekologis yang terluka di jantung pusat nikel Indonesia.
Kisah ini menjadi benang merah buku ini: bahwa di balik jargon “energi bersih”, “net-zero”, dan “green economy” sering tersembunyi relasi kuasa yang lama — kolonialisme, ekstraksi, dan ketidakadilan global. Buku ini mengundang pembaca untuk melihat transisi ekologi bukan hanya sebagai teknis tetapi sebagai geopolitik: siapa yang mengambil keuntungan, siapa yang dipinggirkan, dan bagaimana konsep “keadilan lingkungan” diredefinisi dalam era baru.
Buku The Geopolitics of Green Colonialism: Global Justice and Eco social Transitions (Penyunting: Miriam Lang, Mary Ann Manahan & Breno Bringel; Pluto Press, 2024) mengupas dengan pisau yang tajam fenomena Green Colonialism ini.
Bagian pembuka ini menjelaskan tentang hegemonic transitions and the geopolitics of power sebuah narasi kolonialisme purba. Lang, Manahan & Bringel membuka halaman pertama dengan menguraikan bagaimana transisi hijau global dipimpin oleh yang para penyunting sebut sebagai “decarbonisation consensus” — koalisi institusi, negara kaya, korporasi besar yang menyepakati bahwa solusi terhadap perubahan iklim adalah melalui teknologi, pasar karbon, dan konsumsi yang “bersih”. Pengulas menyatakan bahwa: “The world is undergoing a new hegemonic phase of tech-based and corporate-led green colonial capitalism.” Intl Spectator+1
Bab-bab di Bagian I menelusuri bagaimana kebijakan hijau di Global Utara mendorong ekstraksi besar di Global Selatan: misalnya lithium di Amerika Latin, lahan untuk panel surya di Afrika Utara, dan penggunaan wilayah “kosong” di Selatan sebagai lokasi proyek energi nol-karbon yang melayani konsumsi Utara. Dan tentu saja seperti dipaparkan pada bagian di atas: demam nikel di Indonesia. Degrowth+1 Analisis ini memperlihatkan bahwa meskipun wacana hijau berbicara tentang keberlanjutan, realitasnya memperkuat struktur lama: konsumsi Utara, ekstraksi Selatan, peran subordinasi. Untuk dunia saat ini, bagian ini relevan karena memperingatkan bahwa transisi teknologi saja tidak cukup—harus disertai transformasi struktural. Untuk Indonesia, relevansinya jelas: sebagai negara tropis dengan banyak sumber mineral dan pulau-pulau, Indonesia bisa jadi lokasi “ekspansi hijau” global — sehingga perlu waspada agar tidak menjadi korban kolonialisme hijau.
Hamza Hamouchene, seorang peneliti-aktivis Aljazair dan anggota pendiri Jaringan Kedaulatan Pangan Afrika Utara, menulis artikel dengan judul “Decolonising the Energy Transition in North Africa” (Bagian I, Bab 3). Hamouchene yang telah banyak menulis tentang ekstraktivisme energi, demokrasi, perjuangan anti-kolonial, dan keadilan iklim di Afrika Utara, membuka bab ini dengan analisis tajam tentang bagaimana proyek transisi energi di Afrika Utara—seperti Desertec, ladang surya di Sahara, dan proyek hidrogen hijau di Maroko dan Tunisia—sebenarnya memperluas relasi kolonial lama. Ia menyebut bahwa “the energy transition in the region is being imposed rather than proposed,” menyoroti bagaimana kepentingan Eropa terhadap energi bersih mengubah gurun dan wilayah adat menjadi “zona energi” bagi kebutuhan industri utara. Dalam pandangan Hamouchene, ini adalah bentuk baru dari “energi kolonialisme”, di mana produksi energi tidak diarahkan untuk kebutuhan lokal tetapi untuk ekspor menuju pusat kapital global.
Bab ini memperlihatkan bahwa jargon “clean energy” menutupi praktik eksklusi dan ketimpangan: komunitas lokal sering tidak mendapat listrik atau kompensasi, sementara lahan mereka diambil untuk proyek energi hijau ekspor. Hamouchene juga menyoroti bahwa institusi keuangan internasional (EU Investment Bank, World Bank) mendikte model pembangunan, memperkuat “dependensi energi” daripada “kedaulatan energi.” Ia menegaskan bahwa “to decolonise the energy transition means to reclaim the right to energy as a public good, not a market commodity,” tulis Koordinator program Afrika Utara di Transnational Institute ini.
Bagi Indonesia, gagasan Hamouchene relevan karena mencerminkan dilema yang sama dalam kebijakan energi: bagaimana mendorong transisi ke energi bersih tanpa jatuh pada logika pasar dan kolonialisme baru. Saat Indonesia mendorong investasi besar-besaran untuk nikel dan panel surya, bab ini mengingatkan agar arah transisi tidak dikuasai oleh kapital global, tetapi ditentukan oleh kepentingan rakyat dan komunitas lokal yang terdampak langsung.
Pertanyaan menarik, sebagai judul artikelnya, diajukan oleh John Feffer & Edgardo Lander— “Can the Greatest Polluters Save the Planet? Decarbonisation Policies in the US, EU and China” (Bagian I, Bab 4). Feffer dan Lander menelusuri paradoks besar abad 21: negara-negara yang paling banyak mencemari bumi kini memosisikan diri sebagai pemimpin transisi hijau. Mereka bertanya secara retoris: “Can the same structures that created ecological crisis now solve it?” Analisis mereka menyoroti bagaimana kebijakan dekarbonisasi di AS, Uni Eropa, dan Tiongkok cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi hijau, bukan keadilan ekologis. Feffer menunjukkan bahwa “green industrial policy” di negara maju kerap dimaksudkan untuk mempertahankan supremasi geopolitik dan keuntungan teknologi.
Bab ini memperlihatkan pola “green protectionism”: subsidi besar untuk industri hijau domestik, tetapi tetap mengandalkan bahan mentah dari Selatan—nikel, lithium, dan kobalt—yang diekstraksi dengan biaya sosial dan ekologis tinggi. Lander menegaskan bahwa ini bukan transformasi, tetapi “a greening of empire.” Ia menulis, “Carbon neutrality targets do not question over-consumption, they merely repaint it in green.” Para penulis menyerukan perlunya eco-social transition yang menantang fondasi kapitalisme global, bukan sekadar mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan dalam struktur yang sama.
Bagi Indonesia, bab ini relevan sebagai cermin untuk menilai arah kebijakan transisi energi nasional yang sangat bergantung pada ekspor mineral ke tiga kekuatan besar itu. Ia menimbulkan pertanyaan etis: apakah Indonesia sedang berkontribusi pada penyelamatan planet, atau justru memperpanjang struktur ketimpangan ekologis global?
Struktur Kolonial Dan Ekonomi
Bagian kedua dengan tema besar “Structural Dependencies & the Continuation of Power Asymmetries” mengeksplorasi bagaimana struktur kolonial dan ekonomi masih hidup dalam transisi hijau—melalui berbagai mekanisme: perdagangan global, hutang ekologis dan keuangan, ketergantungan pada ekspor komoditas kritis, dan regulasi yang sering diimpor dari Utara ke Selatan tanpa partisipasi lokal. Pengulas menyebut: “A new subordination in the global energy economy prevents societies in the South from developing sovereign strategies to foster a dignified life.” Goodreads+1
Bab-bab di bagian ini menggunakan kerangka teoritik seperti ekonomi politik, pandangan dekolonial dan feminis untuk memaparkan bahwa transisi hijau tetap dibayangi oleh “ecologically unequal exchange” — aliran sumber daya dan tenaga dari Selatan ke Utara yang memungkinkan konsumsi tinggi Utara tetap berjalan. JSTOR+1 Dalam konteks Indonesia, bagian ini mengingatkan bahwa meskipun transisi energi atau ekonomi hijau dikampanyekan, jika tetap menggunakan model ekspor bahan mentah atau dependensi teknologi asing, maka keadilan ekologis dan kedaulatan lokal akan sulit tercapai.
Nnimmo Bassey—aktivis lingkungan dari Nigeria—membuka bab ini dengan kalimat kuat: “The color of colonialism today is green.” Ia dengan judul artikel yang menohok, “Green Colonialism in Colonial Structures: A Pan-African Perspective,” menunjukkan bahwa Afrika kembali menjadi ladang eksperimen proyek global yang dijustifikasi dengan wacana penyelamatan iklim. Bassey menyoroti proyek REDD+, penanaman hutan karbon, dan investasi energi hijau yang seringkali mencabut hak masyarakat adat dan petani kecil. Ia menyebut fenomena ini sebagai “ecological subjugation,” lanjutan dari sejarah kolonial yang memandang Afrika sebagai lumbung sumber daya bagi dunia.
Bassey tidak hanya mengkritik, tetapi juga menekankan pentingnya “pan-African solidarity” untuk membangun agenda transisi ekologis yang berkeadilan dan berbasis komunitas. Ia menulis, “We cannot outsource our sovereignty to global carbon markets.” Dengan mengutip Ali Mazrui dan Thomas Sankara, ia menegaskan bahwa dekolonisasi lingkungan harus dimulai dengan mengembalikan kendali rakyat terhadap tanah, air, dan udara mereka sendiri.
Dari perspektif Indonesia, bab ini menggemakan perjuangan serupa: antara pembangunan nasional, kebutuhan energi, dan hak komunitas lokal atas sumber daya. Gerakan masyarakat adat di Kalimantan atau Papua menghadapi situasi mirip dengan apa yang Bassey deskripsikan—proyek “hijau” yang menyingkirkan masyarakat demi kepentingan global.
Pada Bagian II, Bab 11 buku The Geopolitics of Green Colonialism juga membahas konsep yang digadang-gadang oleh banyak pihak: NbS (Nature-Based Solutions), sebuah istilah yang memang sangat seksi di dunia yang demam serbaalam. Mary Ann Manahan dengan “‘Nature-Based Solutions’ for a Profit-Based Global Environmental Governance” tak pelak mengritik habis konsep ini. Mary Ann Manahan mengupas bagaimana konsep Nature-Based Solutions (NbS)—yang populer di forum PBB dan lembaga keuangan global—telah direduksi menjadi alat kapitalisasi baru atas alam. Ia menulis bahwa “nature is not being protected, it is being monetised.” Dalam kerangka NbS, hutan, lahan basah, dan lautan diperlakukan sebagai aset yang bisa dihitung, diperdagangkan, dan dijadikan kompensasi karbon oleh perusahaan multinasional. Manahan menyebut hal ini sebagai bentuk “green neoliberalism” yang memindahkan tanggung jawab perubahan iklim dari struktur industri ke pasar solusi alam.
Bab ini menyingkap bahwa program-program besar yang mengklaim restorasi alam sering kali menyingkirkan masyarakat adat atau memprivatisasi akses terhadap sumber daya bersama. Ia mengutip peringatan Vandana Shiva bahwa “when nature is reduced to a service, life itself becomes a commodity.” Manahan menyerukan agar kita mengembalikan dimensi etis, sosial, dan spiritual dalam memahami alam—sebagai relasi timbal balik, bukan sekadar kapital ekologis.
Di Indonesia konsep carbon offset dan carbon trading sedang naik daun. Bab ini memberikan peringatan tajam. Jika tidak hati-hati, proyek NbS bisa menjadi bentuk kolonialisme baru: perusahaan global membeli hak atas hutan Indonesia dengan kedok perlindungan iklim, sementara masyarakat lokal kehilangan ruang hidupnya.
Jalan Alternatif
Bagian III: alternative pathways for just eco-social transitions dari The Geopolitics of Green Colonialism mencoba menawarkan jalan baru sebagai alternatif. Dunia alternatif sangat memungkinkan jika ada kemauan tidak saja individual tetap kolektif untuk mewujudkannya dan melangkah bersama. Bagian ketiga bersifat konstruktif: setelah menguraikan kritik dalam bagian I dan II, buku ini menampilkan berbagai alternatif yang dikembangkan oleh komunitas, gerakan sosial, dan tokoh lokal di Selatan—termasuk pendekatan degrowth, eco-feminisme, kedaulatan energi, dan ekoterritorialisme. Pengulas menyebut bahwa buku ini “does not stop at critique — it offers tangible alternatives grounded in the lived experiences of those resisting ecological injustice.” Intl Spectator+1 Contoh yang diangkat seperti inisiatif komunitas di Bangladesh, Kolombia, dan Afrika yang menolak model “ekspor mineral untuk panel surya Utara” dan mengembangkan model produksi lokal yang adil dan ekologi‐sentris. Untuk dunia, bagian ini penting karena menunjukkan bahwa transisi yang adil bukan hanya menunggu kebijakan global, melainkan dibangun dari aspirasi lokal dan relasi antar wilayah. Untuk Indonesia, hal ini berarti kesempatan untuk mengembangkan model ekonomi hijau yang berbasis masyarakat adat, energi terbarukan lokal, dan diversifikasi ekonomi — bukan hanya menjadi pemasok bahan baku global.
Breno Bringel & Sabrina Fernandes) melalui artikelnya yang bertajuk “Towards a New Eco-Territorial Internationalism” (Bagian III, Bab 18) yang sekaligus sebagai bab penutup ini menulis pandangan yang bersifat reflektif sekaligus visioner. Bringel dan Fernandes berargumen bahwa menghadapi krisis planet tidak cukup dengan kebijakan nasional atau forum antarnegara. Mereka mengusulkan konsep “eco-territorial internationalism”: bentuk solidaritas lintas batas yang menghubungkan perjuangan masyarakat adat, gerakan petani, feminis, dan aktivis iklim dari berbagai wilayah dunia. “Our struggles must be as interconnected as the systems that oppress us,” tulis mereka. “Geopolitik transisi menyiratkan pengorbanan bukan hanya wilayah, tetapi juga cara-cara menghuni dunia ini yang benar-benar berkelanjutan.” – Degrowth+1
Konsep ini menekankan pentingnya territory sebagai pusat perlawanan—bukan sekadar ruang geografis, tetapi ruang hidup yang sarat nilai, relasi, dan makna budaya. Mereka mengutip pemikir dekolonial Arturo Escobar: “The future will be territorial or it will not be.” Bagi Bringel dan Fernandes, eco-territorial internationalism adalah langkah melampaui batas negara dan kapital—menuju dunia multipolar yang berakar pada keadilan ekologis dan sosial. Arturo Escobar: “We need a pluriversal ontology for socio-ecological transformations.”
Pandangan eco-territorial internationalism ini sangat relevan bagi Indonesia: konsep ini bisa mengilhami jaringan solidaritas antara masyarakat adat di Nusantara dengan gerakan serupa di Latin Amerika dan Afrika. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi namun terpecah dan terbelah, gagasan mereka mengingatkan bahwa penyelamatan bumi hanya mungkin jika dibangun dari bawah ke atas—berdasarkan solidaritas lintas wilayah, etika kebersamaan, dan penghormatan terhadap keberagaman ekologi. Dari tradisi spiritual Islam: “Manusia adalah khalifah di bumi; bukan pemilik yang tak terkalahkan.” — mengingat bahwa etika ekologis dan keadilan global harus menjadi bagian dari transisi hijau.
Kritik, apresiasi, dan kutipan penting
Buku ini dipuji sebagai “kontribusi penting dalam wacana keadilan iklim dan transisi ekologi” yang membuka suara Global Selatan. Intl Spectator+1 Namun kritik muncul: salah satu pengulas menyebut bahwa karena banyak kontributor dan topik yang sangat berbeda, beberapa esai terasa terlalu pendek dan struktur keseluruhan agak terfragmentasi. Intl Spectator+1 Meski demikian, inti buku – bahwa transisi hijau bisa jadi kelanjutan kolonialisme jika tidak berhati-hati – diterima luas. “Buku ini menyediakan platform bagi suara-suara yang telah conspicuously absent (sangat mencolok ketidakhadirannya) dalam debat-debat seputar energi dan iklim di Global Utara.” – ResearchGate
Pesan untuk Indonesia
Melalui lensa The Geopolitics of Green Colonialism, Indonesia dapat dilihat sebagai “negara strategi” dalam geopolitik hijau: kaya akan nikel, tembaga, litium potensial; memiliki wilayah laut luas; dan menghadapi tekanan global untuk “menjadi bagian transisi.” Namun, tanpa kerangka keadilan sosial, keberlanjutan dan kedaulatan, Indonesia riskan menjadi korban green colonialism: ekspor sumber daya untuk konsumsi orang lain, relokasi masyarakat pesisir untuk proyek energi asing, atau impor teknologi tanpa pengembangan kapasitas lokal. Buku ini menegaskan bahwa Indonesia harus mengedepankan kriteria keadilan—antara generasi, antara pusat dan daerah, antara manusia dan alam. Sebagaimana buku ini menyatakan: “Green growth and clean energy plans of the Global North require the large-scale extraction of strategic minerals from the Global South.” ifaaza.org+1 Dengan demikian, Indonesia perlu memilih jalur “just transition” yang tidak menjual kemerdekaan ekologisnya — melainkan memperkuat kedaulatan sumber daya, diversifikasi ekonomi, dan memperkuat masyarakat lokal serta hak adat.
Catatan Akhir
Buku The Geopolitics of Green Colonialism memberikan peta kritis yang sangat diperlukan dalam era transisi hijau global: ia menunjukkan bahwa walau bertujuan mulia—menghadapi perubahan iklim—tanpa keadilan struktural dan epistemik, transisi bisa memperkuat kolonialisme baru. Struktur trilogi buku (kritik hegemoni → analisis ketergantungan → alternatif lokal) memberi arah bagi siapa pun yang ingin memahami dan bertindak. Untuk Indonesia dan banyak negara Global Selatan, buku ini bukan hanya bacaan akademik, tetapi panggilan untuk memilih jalur transisi yang mendalam, adil, dan berdaulat.
Inti tuntutan dekolonial adalah soal relasi kekuasaan, bukan sekadar teknologi. Kelima bab The Geopolitics of Green Colonialism itu bersama-sama menegaskan sesuatu yang sederhana tapi radikal: masalah utama dalam “transisi hijau” bukanlah kurangnya teknologi, tetapi struktur kekuasaan yang mengatur siapa mendapat manfaat dan siapa dibebankan. Dari Hamouchene (energi Sahara yang diekspor ke Eropa) sampai Bassey (REDD+, green projects di Afrika), pola yang sama muncul: sumber daya dan wilayah Selatan dipetakan ulang untuk kebutuhan Utara.
Di sinilah pemikiran dekolonial menjadi penting: bukan sekadar redistribusi materi, tetapi pembongkaran narasi yang membuat Selatan terlihat sebagai “sumber” tanpa subjek politik.
Artikel-bab ini menuntut perubahan narasi: dari “pulau/lahan kosong yang siap dikuasai” menjadi “territori hidup dengan hak dan kewenangan”. Achille Mbembe — necropolitics, kedaulatan, dan teknologi pembiaran, mengingatkan bahwa kedaulatan modern seringkali dinyatakan dalam kemampuan menentukan “siapa hidup, siapa mati” (konsep necropolitics). Dalam konteks green colonialism, necropolitics mengambil wujud baru: kebijakan yang menukar keselamatan iklim untuk kehidupan lokal—mis. merelokasi komunitas pesisir demi proyek energi atau menanggung polusi tambang untuk kebutuhan listrik jauh. Politisasi iklim dapat menjadi alat legitimasi yang menormalisasi korban tertentu. Analisis Mbembe membantu memahami bagaimana “transisi” dapat mereproduksi logika biopolitik: bukan hanya pengelolaan populasi tetapi pengelolaan wilayah yang hidupnya dipersyaratkan untuk menjadi kurban. Implikasi etisnya bagi Indonesia: perlu mekanisme pencegahan yang menjamin kehidupan komunitas sebagai nilai fundamental, bukan variabel yang boleh ditukar demi target emisi.
Vandana Shiva — ekofeminisme, kedaulatan pangan, dan komodifikasi alam, telah lama menunjukkan bagaimana modernisasi dan praktek agribisnis merusak kedaulatan komunitas dan keanekaragaman hayati; ia juga mengaitkan patriarki, kapital, dan destruksi lingkungan. Kritik Mary Ann Manahan tentang Nature-Based Solutions sebagai kapitalisasi alam sangat resonan dengan Shiva: ketika hutan dan layanan ekosistem dijadikan komoditas (karbon sebagai aset), hak komunitas dan relasi hidup menjadi subordinat. Dari perspektif ini, NbS tanpa demarkasi hak dan tanpa partisipasi komunitas berubah menjadi “green enclosures” — penguasaan privat atas commons. Bagi Indonesia, inspirasi Shiva mengarah pada kebijakan yang mengutamakan kedaulatan pangan, pengakuan hukum terhadap hutan adat, dan penolakan terhadap mekanisme pasar yang meng privatisasi layanan ekosistem.
Etika dekolonial sebagai epistemic justice (koreksi pengetahuan). Buku ini juga menyerukan epistemic justice: pengakuan atas pengetahuan lokal sebagai sumber solusi. Pemikiran dekolonial (Escobar, Haraway, dkk.) menolak hegemoni epistemik ilmiah-industri yang memonopoli definisi “teknis” dari solusi. Hamouchene dan Bassey menegaskan bahwa perlu ada ruang bagi pengetahuan pelaut, petani, penjaga mangrove, dan ritual-lokal sebagai penentu proyek pengelolaan wilayah. Dalam praktik kebijakan di Indonesia, ini menuntut revisi prosedur AMDAL dan konsultasi publik agar berbasiskan pengakuan pengetahuan adat dan perjanjian hak.
Fazlur Rahman — tanggung jawab moral, ijtihad kontemporer, dan amanah. Walau Fazlur Rahman bukan pemikir ekologi dalam arti modern, gagasan utamanya tentang ijtihad (interpretasi kontekstual dari teks religius) dan penekanan pada moralitas berperan relevan di dunia Muslim—termasuk banyak komunitas di Indonesia. Prinsip amanah (kepercayaan) dan khalifah (penjaga bumi) bisa menjadi dasar etis yang menentang ekstraksi yang merusak: bumi merupakan amanah yang harus dijaga, bukan objek untuk dieksploitasi. Menggunakan kerangka Rahman — yakni reinterpretasi teks agama untuk tuntutan moral kontemporer — komunitas Muslim di Indonesia dapat menuntut kebijakan “transisi” yang sesuai moral agama: adil, memihak yang rentan, menghormati generasi mendatang.
Etika solidaritas: eco-territorial internationalism dan pembalikan logika donor-penerima. Bringel & Fernandes menawarkan eco-territorial internationalism sebagai etika solidaritas lintas batas. Filosofisnya, ini adalah pembalikan logika donor-penerima: bukan pusat memberikan blueprint kepada pinggiran, tetapi jaringan penghuni territory saling belajar dan berkongsi strategi. Etika ini menuntut tanggung jawab kolektif: utara tidak hanya mengurangi emisi, tetapi merestorasi relasi ekonomi yang adil, termasuk transfer teknologi yang bersyarat pada kedaulatan lokal. Untuk Indonesia, ini berarti merancang perjanjian internasional yang mengandung klausul proteksi hak adat dan pembagian nilai yang adil (value sharing) terhadap komoditas hijau.
Dari teori ke praktik: prinsip-prinsip etika dekolonial yang dapat dioperasionalkan. Menggabungkan gagasan di atas, beberapa prinsip etika praktis muncul: (a) non-sacrifice — tidak menjadikan komunitas tertentu sebagai zona pengorbanan; (b) prior informed consent kolektif dan pengakuan hak atas tanah/laut; (c) benefit-sharing yang nyata dan transparan; (d) epistemic inclusion—keputusan yang memasukkan pengetahuan lokal dalam rancangan teknis; (e) transformative reparations — kompensasi yang memperkuat kapasitas lokal, bukan sekadar pembayaran. Kebijakan di Indonesia harus menempatkan prinsip-prinsip ini dalam regulasi investasi, perizinan tambang, dan kontrak energi terbarukan.
Konflik etis: teknologi vs. keadilan; mitigasi vs. kedaulatan. Fakta pragmatis: negara-negara berhak mencari energi bersih; perusahaan berhak berinovasi. Tetapi etika dekolonial menuntut agar hak ini tidak mengesampingkan kedaulatan rakyat. Feffer & Lander memperingatkan bahwa “great polluters” yang memimpin transisi seringkali mempertahankan konsumsi tinggi dengan memindahkan beban ekstraksi. Etika menuntut: teknologi harus dipasangkan dengan mekanisme hak, transparansi, dan kontrol publik—bukan hanya perdagangan karbon yang menutupi terusnya ketidaksetaraan.
Seni narasi: merawat bahasa—dari “resources” menjadi “relational lives.” Filsafat bahasa etis mengatakan: cara kita berbicara membentuk tindakan. Jika hutan disebut “stock” atau “asset”, tindakan kita cenderung memperlakukan hutan seperti properti. Jika hutan disebut “rumah bersama” atau “territori hidup”, kita bertindak berbeda. Menurut Vandana Shiva dan para dekolonial, perjuangan juga berlangsung di ranah bahasa dan kategorisasi. Di Indonesia, mengganti istilah di regulasi—mis. dari “pemanfaatan area” menjadi “perlindungan wilayah hidup”—bukan sekadar retorika, melainkan langkah etis yang nyata.
Secara filosofis, analisis ini menunjukkan bahwa transisi hijau yang adil memerlukan lebih dari koreksi teknis: ia memerlukan paradigma etis baru yang mengedepankan kedaulatan, solidaritas, epistemic plurality, dan tanggung jawab antar generasi. Achille Mbembe memperingatkan tentang kekuatan necropolitics yang terselubung; Vandana Shiva mengingatkan kita bahwa alam dan perempuan sering menjadi korban kapitalisasi; sementara Fazlur Rahman mengingatkan pada kebutuhan reinterpretasi moral yang relevan secara kontekstual. Bagi Indonesia, tugasnya adalah menerjemahkan etika ini ke dalam hukum, perjanjian investasi, dan pendidikan publik—sehingga transisi hijau tidak lagi menjadi sambungan kolonialisme lama, tetapi pintu bagi kedaulatan ekologis dan sosial.
Hari-hari ini kita disibukkan oleh pertemuan penting perubahan iklim di Belem, Brasil, COP30. “Persetujuan Paris (Paris Agreement) bekerja untuk memberikan kemajuan nyata, tetapi kita harus berjuang dengan gigih untuk lebih banyak (untuk mencapai kemajuan nyata itu),” kata Simon Stiell pada hari pembukaan COP30 di Belém, Brazil, 10 November 2025.
“Konferensi Perubahan Iklim PBB #COP30 di Belém, Brazil, adalah tentang mempercepat aksi iklim. Kemajuan nyata sedang dibuat, tetapi kita perlu bergerak lebih cepat. COP30 akan mengirimkan sinyal yang jelas bahwa dunia sepenuhnya berkomitmen pada multilateralisme iklim—karena itu berhasil,” demikian catatan dari website COP30.
Mungkin, sekali lagi, apakah kita akan menyaksikan green colonialism sedang dirundingkan? —sebuah cara baru untuk melegalkannya.
Bogor, 11 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Lang, M., Manahan, M. A., & Bringel, B. (Eds.). (2024). The Geopolitics of Green Colonialism: Global Justice and Eco-social Transitions. Pluto Press.
Calienno, V. (2023). Book Review: How Is the Energy Transition Reproducing Global Injustices? The International Spectator. Retrieved from https://www.theinternationalspectator.com/post/book-review-how-is-the-energy-transition-reproducing-global-injustices Intl Spectator
Degrowth.info. (2024, July 17). The Geopolitics of Green Colonialism – review. Retrieved from https://www.degrowth.info/de/blog/the-geopolitics-of-green-colonialism-global-justice-and-ecosocial-transitionsDegrowth
Mbembe, A. (2003). Necropolitics. (course readings / essay; see Mbembe’s essays on sovereignty and necropolitics).
Shiva, V. (2000). Staying Alive: Women, Ecology and Development. Zed Books.
Rahman, F. (1982). Islam and Modernity: Transformation of Religious Thought in the Modern World (selected works on ijtihad and ethical reinterpretation).
Escobar, A. (2018). Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Duke University Press.