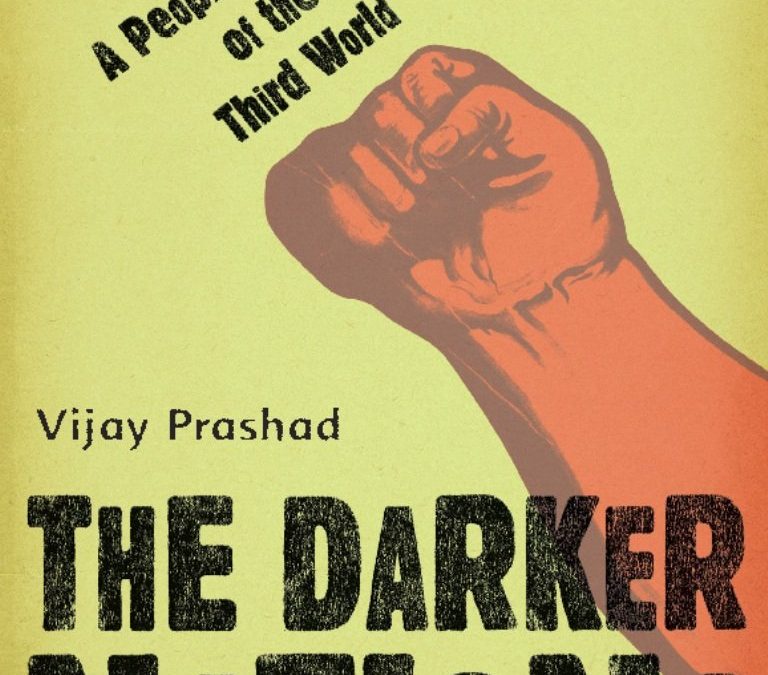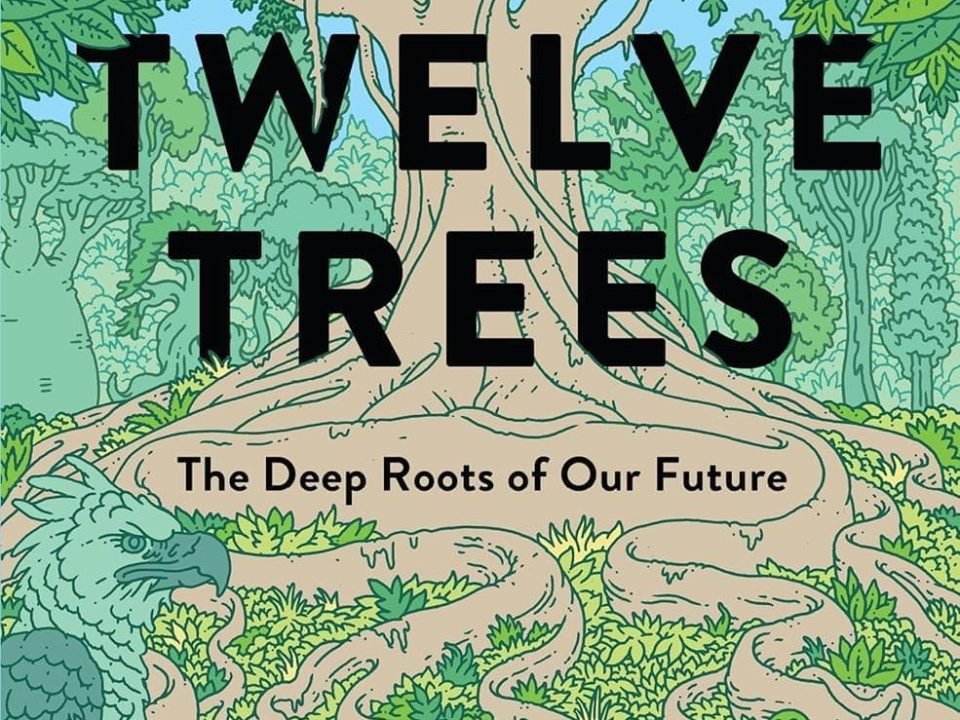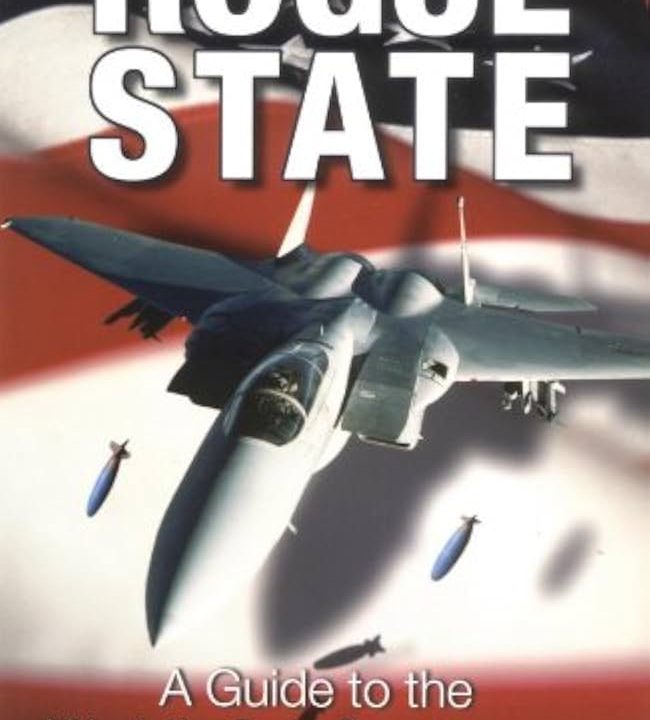Rubarubu #09
The Darker Nations: Kisah Bangsa-bangsa Terpinggirkan
Pada suatu pagi tahun 1955, di kota Bandung, sekretaris serikat tani Jawa tiba di sebuah aula yang ramai, membawa poster yang bertuliskan “Kedaulatan untuk Rakyat.” Ia datang jauh dari desa, lelah tetapi penuh harap: pertemuan pekan itu bukan sekadar konferensi diplomatik — ia adalah momen ketika suara-suara yang selama ini disisihkan berusaha menata kata “kedaulatan” kembali menjadi nyata. Kisah semacam ini — orang biasa, gerakan akar rumput, intelektual yang berkumpul bukan untuk menghangatkan kursi kekuasaan, melainkan untuk merencanakan masa depan lain — membentuk nadi The Darker Nations: A People’s History of the Third World (New Press; edisi 15th-anniversary preface 2022). Vijay Prashad, seorang yang lebih dari sekadar penulis—ia adalah seorang sejarawan, jurnalis, dan intelektual publik yang getar suaranya menjadi penuntun bagi gerakan-gerakan pembebasan di Global Selatan, menulis sejarah Third World bukan sebagai kronik negarawan semata, melainkan sebagai “people’s history”: bagaimana jutaan orang, melalui gerakan politik, budaya, dan solidaritas, mencoba memutus rantai kolonial dan membangun alternatif modernitas. Buku ini dirancang dengan kisah negara-negara yang mengukir sejarah harapan Dunia Ketiga. Judul Bagian-bagiannya menggunakan nama-nama kota ikonik untuk menggambarkan peran negara dimana kota-kota itu berada. Nama kota digunakan sebagai simbol, bukan semata tempat kejadian sebenarnya.
Prashad adalah intelektual organik dalam arti yang sesungguhnya. Gagasannya tidak me-ngendap di menara gading akademis, tetapi menjelma menjadi senjata analitis bagi aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang berjuang melawan ketidakadilan. Melalui ratusan artikel, wawancara, dan pidatonya yang blak-blakan, ia konsisten membongkar ilusi neoliberalisme dan mengecam wajah brutal kapitalisme global.
Dengan gaya bahasanya yang tajam namun puitis, Prashad meneruskan estafet tradisi pemikir kritis seperti Eduardo Galeano dan Eqbal Ahmad. Ia adalah pengamat zaman yang tak kenal lelah yang terus melukiskan peta perlawanan rakyat, dari pelosok Amerika Latin hingga jantung konflik di Asia Barat, mengingatkan kita bahwa sejarah belum berakhir, dan perjuangan untuk emansipasi manusia tetap hidup.
Prashad mengurai sejarah Third World secara tematik dan kronologis. Bagian awal buku menempatkan munculnya Third World dalam konteks runtuhnya kolonialisme formal pasca-Perang Dunia II dan gejolak Perang Dingin: negara-negara baru merdeka berhadapan dengan tekanan bipolar tetapi menolak diposisikan sebagai sekadar alat blok. Bandung (1955) dan konferensi-konferensi Non-Aligned Movement menjadi simbol lahirnya gagasan bahwa Selatan hadapi pilihan lain: solidaritas antar-negara terjajah, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan yang berorientasi rakyat. Prashad menekankan bahwa gerakan ini bukan monolitik—ia dipenuhi perdebatan antara nasionalis, sosialis, kaum kiri, dan gerakan rakyat—tetapi yang menyatukan adalah penolakan terhadap subordinasi geopolitik dan ekonomi.
Harapan dari Brussels hingga Mecca
Pada bagian Brussels – the 1928 League Against Imperialism: awal sebuah mimpi Global Selatan. Bab “Brussels” membuka kisah The Darker Nations dengan momentum simbolik kelahiran solidaritas anti-kolonial internasional. Pada tahun 1928, di kota yang menjadi jantung kekaisaran kolonial Belgia, ratusan aktivis, serikat buruh, dan perwakilan bangsa-bangsa terjajah berkumpul dalam League Against Imperialism (LAI). Mereka datang dari Asia, Afrika, Amerika Latin—sebuah pertemuan lintas ras dan bangsa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tokoh-tokoh seperti Jawaharlal Nehru (India), Messali Hadj (Aljazair), dan Tan Malaka (Indonesia) hadir sebagai representasi dari mimpi dunia yang ingin bebas dari penjajahan dan kapitalisme global.
Prashad melihat Brussels 1928 bukan sekadar kongres politik, melainkan “the embryo of the Third World” — cikal bakal kesadaran kolektif bahwa bangsa-bangsa tertindas berbagi nasib historis yang sama. LAI menolak dikotomi antara perjuangan nasional dan kelas; mereka menegaskan bahwa kemerdekaan politik tanpa pembebasan ekonomi hanyalah semu. Namun mimpi ini segera dibungkam oleh kekuatan geopolitik: pengawasan kolonial, represi, dan perpecahan ideologis di antara blok kiri dan nasionalis membuat LAI hancur sebelum mencapai masa dewasa.
Brussels menjadi metafora kelahiran yang gagal, tapi juga titik awal penting: benih gagasan yang kelak hidup kembali di Bandung (1955). Dalam konteks dunia kini, bab ini mengingatkan bahwa solidaritas lintas bangsa bukan hal baru — ia lahir dari luka kolonial yang sama. Hari ini, ketika negara-negara Global South menghadapi neokolonialisme ekonomi, gagasan “League Against Imperialism” menemukan gaung barunya dalam gerakan transnasional melawan utang, eksploitasi, dan perubahan iklim.
Secara filosofis, bab Brussels dapat dibaca sebagai momen ontologis kelahiran “Third World” bukan sebagai entitas geografis, melainkan sebagai being-in-struggle. Prashad menulis dunia ketiga sebagai a project, not a place — sebuah proyek eksistensial untuk mengembalikan martabat manusia setelah berabad-abad kolonialisme. Dalam pengertian Heideggerian, keberadaan Dunia Selatan bukan sekadar “ada”, melainkan “ada dalam perjuangan”, selalu terbuka terhadap kemungkinan baru.
Dalam konteks ini, pemikiran Aimé Césaire dan Frantz Fanon memberi resonansi kuat. Césaire menulis bahwa kolonialisme “dehumanizes even the colonizer himself”, sedangkan Fanon menegaskan bahwa dekolonisasi adalah “a program of complete disorder”—yakni momen ketika tatanan lama harus diguncang agar manusia dapat diciptakan kembali sebagai subjek bebas. League Against Imperialism di Brussels menjadi cermin dari praxis itu: usaha kolektif membayangkan tatanan dunia di mana keadilan, bukan dominasi, menjadi fondasi hubungan antarbangsa.
Dari sudut etika, Brussels mengandung pesan universal humanisme dekolonial — seperti ditegaskan oleh Paulo Freire: “The oppressed must be their own example in the struggle for liberation.” Kesadaran akan keterhubungan penderitaan global menuntun pada solidaritas lintas bangsa — sebuah prinsip yang sangat dibutuhkan di era krisis iklim, migrasi, dan perang sumber daya hari ini.
Di bagian tengah, Prashad menguraikan percobaan ekonomi dan politik, Third World: industrial policy, reforma agraria, nasionalisasi sumber daya, dan proyek kultural untuk membangun identitas pascakolonial. Ia memberi perhatian khusus pada pengalaman negara-negara seperti Indonesia, India, Mesir, Ghana. Dan Indonesia muncul berulang sebagai contoh: antusiasme pembangunan terpaut pada realitas eksterior—hutang, intervensi, dan tekanan pasar global—yang kerap menggagalkan transformasi sejati. Prashad menunjukkan pola: ambisi kedaulatan sering diserang lewat kudeta, embargo, atau sabotase ekonomi; internalnya, kelas borjuis nasional dan birokrasi yang lemah kadang mereproduksi ketidakadilan yang sama.
Termasuk tragedy yang memilukan di Indonesia yang dikemas dalam bagian Bali– Death of the Communists: Kekerasan dan Kematian Solidaritas. Bab “Bali” adalah bagian paling tragis dan personal dari buku Prashad. Ia menulis tentang pembantaian besar-besaran terhadap kaum komunis dan simpatisan kiri di Indonesia tahun 1965–66, yang memakan korban ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Bagi Prashad, peristiwa “di Bali” — simbol dari keindahan tropis dan harmoni, bukan sebagai tempat peristiwanya — menjadi kuburan dari mimpi Third World di Asia Tenggara.
Indonesia, di bawah Sukarno, sebelumnya menjadi pelopor utama Gerakan Non-Blok, menjembatani nasionalisme dan sosialisme, serta mendorong solidaritas antarbangsa terjajah. Namun kudeta militer 1965 dan naiknya Soeharto, dengan dukungan CIA dan sekutu Barat, menandai pergeseran tajam: kekuatan rakyat dihancurkan, partai kiri dihapus, dan kapitalisme internasional masuk dengan bebas.
Prashad menulis dengan nada elegi: pembunuhan di Bali bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan “the death of the dream that the Third World could chart its own course.” Kematian para komunis adalah kematian kelas pekerja, kaum tani, dan idealisme internasionalisme. Dunia yang lebih gelap menyusul: kapitalisme militeristik, represi budaya, dan kooptasi pembangunan.
Dalam refleksi masa kini, bab ini mengingatkan bahwa pembunuhan ideologi sering kali merupakan prasyarat bagi munculnya rezim neoliberal. Di Indonesia, jejak trauma 1965 masih terasa: anti-komunisme tetap jadi alat pembungkam kritik sosial, sementara neoliberalisme terus menguasai ruang ekonomi-politik. “Bali” menjadi peringatan abadi: tanpa keadilan sejarah, tidak ada pembebasan sejati.
Bab Bali – Death of the Communists menghadirkan bukan hanya peristiwa politik, tetapi tragedi ontologis manusia: pembunuhan terhadap daya imajinasi untuk berpikir dunia yang lain (a world otherwise). Dalam kerangka Fanon, pembantaian 1965 di Indonesia adalah necropolitics —politik kematian yang dikelola oleh kekuasaan kolonial baru (militer dan kapitalisme Barat) untuk memastikan dunia tetap dalam status quo.
Dalam filsafat Achille Mbembe, kekuasaan modern tidak hanya mengatur kehidupan, tetapi juga hak untuk memutuskan siapa yang boleh hidup dan siapa yang boleh mati. Maka, pembunuhan komunis bukan hanya eliminasi politik, tapi juga bentuk pemusnahan epistemik: membungkam cara lain berpikir tentang kemerdekaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Etika dekolonial menuntut kita untuk mengingat — karena pelupaan adalah bentuk kekerasan kedua. Seperti kata Primo Levi, “those who forget their past are condemned to live it again.” Dalam konteks Indonesia, rekonsiliasi historis terhadap 1965 adalah keharusan moral agar bangsa ini tidak terus terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan terhadap ideologi, padahal ideologi itu dulu memperjuangkan keadilan sosial.
Kematian harapan Dunia Ketiga berlanjut hingga New Delhi– The Obituary of the Third World: Kematian Sebuah Proyek Politik. Bab “New Delhi” berfungsi sebagai obituari ideologis dari proyek Third World. Di sini, Prashad melacak kemunduran Gerakan Non-Blok (NAM) yang lahir dengan janji besar: kemerdekaan, solidaritas, dan pembangunan berdaulat. Namun menjelang akhir 1970-an hingga 1980-an, New Delhi — simbol diplomasi dan kepemimpinan politik Selatan — justru menjadi saksi keterpecahan internal dan kooptasi neoliberal.
Prashad menunjukkan bahwa setelah kegagalan New International Economic Order (NIEO) di PBB pada 1970-an, banyak negara Selatan kehilangan arah. Hutang luar negeri menjerat, bantuan Barat membawa syarat politik, dan elite nasional mulai lebih loyal pada IMF dan Bank Dunia ketimbang solidaritas Selatan. Dalam gaya ironis, Prashad menulis bahwa “the Third World died not in the battlefield but in the conference room.”
Namun “obituary” ini bukan sekadar kisah kematian, melainkan otopsi politik: mengapa idealisme itu gagal? Bagi Prashad, kegagalan terletak pada absennya basis rakyat yang kuat, lemahnya industrialisasi mandiri, dan dominasi elite nasional yang menggantikan imperialisme lama dengan oligarki domestik. Ia juga menyoroti India sebagai contoh negara yang “berbelok ke kanan” secara ekonomi setelah era Nehruvian sosialisme.
Relevansinya kini jelas: globalisasi pasca-1990 melanjutkan logika yang sama — integrasi tanpa kedaulatan. “New Delhi” menantang pembaca untuk berpikir ulang tentang proyek politik global yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar pertumbuhan.
Bab New Delhi – The Obituary of the Third World membuka diskusi filosofis tentang kegagalan etis-politik elite pascakolonial. Prashad menegaskan bahwa matinya proyek Dunia Ketiga bukan karena kekuatan eksternal semata, melainkan karena elite nasional yang mengkhianati idealisme solidaritas dan menggantinya dengan oligarki.
Dari perspektif Hannah Arendt, kegagalan ini dapat dibaca sebagai hilangnya “public realm of action and speech” — ruang publik di mana politik dimaknai sebagai tindakan bersama untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, politik berubah menjadi administrasi teknokratik. Dunia Ketiga mati bukan di medan revolusi, tapi di meja birokrasi dan lembaga keuangan internasional.
Etika dekolonial di sini berarti menghidupkan kembali politik sebagai praksis emansipatoris, bukan sekadar manajemen pembangunan. Ini sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman, yang menekankan bahwa Islam sebagai etika sosial harus menolak “struktur ketidakadilan yang terinstitusionalisasi” — baik dalam bentuk kapitalisme global maupun korupsi nasional. Maka, perjuangan politik Dunia Selatan adalah juga perjuangan moral untuk ihsan sosial: keadilan sebagai ibadah.
Aspek lain yang juga penting sebagai faktor yang membunuh harapan Dunia Ketiga adalah Kingston – IMF-led Globalization: Ekonomi Hutang dan Pembunuhan Masa Depan. “Kingston” membawa kita ke Jamaika, simbol dunia pascakolonial yang dijerat oleh IMF dan program penyesuaian struktural (structural adjustment) pada 1980-an. Prashad menggambarkan dengan getir bagaimana negeri yang dulu menyanyikan lagu Bob Marley tentang kebebasan kini menjadi laboratorium kebijakan neoliberal: privatisasi, deregulasi, dan penghapusan subsidi yang menghancurkan petani dan kelas pekerja.
Ia menunjukkan bahwa globalisasi versi IMF adalah bentuk baru imperialisme: tidak dengan senjata, tetapi dengan bunga pinjaman dan “reformasi ekonomi”. Dalam satu kalimat penting, Prashad menyebutnya “a counterrevolution of the banks.” Ketimpangan sosial meningkat tajam, pendidikan dan layanan publik runtuh, dan seluruh generasi kehilangan masa depan.
“Kingston” bukan hanya kisah Jamaika, melainkan mikrokosmos dunia Selatan: dari Amerika Latin hingga Asia, kebijakan IMF menciptakan ketergantungan baru. Prashad menulis dengan empati pada rakyat miskin yang harus membayar harga dari keputusan elit dan pasar global.
Bagi Indonesia, bab ini mencerminkan pengalaman krisis 1997–1998: intervensi IMF, deregulasi, dan liberalisasi pasar yang memperlemah kedaulatan ekonomi. “Kingston” mengajarkan bahwa utang adalah alat kolonialisme modern — dan bahwa pembangunan sejati tidak mungkin terjadi tanpa kedaulatan ekonomi.
Bab Kingston – IMF-led Globalization adalah kritik mendalam terhadap imperialisme ekonomi dan fetisisme pasar. Prashad menggambarkan globalisasi neoliberal sebagai bentuk kolonialisme baru di mana utang menggantikan senjata sebagai alat dominasi.
Dalam perspektif Karl Marx, ini adalah reproduksi surplus extraction dalam skala global: “capital comes dripping from head to foot, from every pore, with blood and dirt.” Tapi Prashad melangkah lebih jauh: ia menyoroti penderitaan moral yang dihasilkan oleh utang — kehilangan martabat, kedaulatan, dan masa depan.
Filsuf India Vandana Shiva menyebut fenomena ini sebagai “eco-imperialism”: eksploitasi ekonomi yang menghancurkan tatanan ekologis dan sosial masyarakat. Dalam konteks etika Islam, konsep riba dan gharar menjadi relevan: utang berbunga dan ketidakpastian ekonomi menciptakan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan Ilahiah.
Untuk Indonesia, refleksi ini penting: krisis utang, privatisasi air, dan deregulasi lingkungan mencerminkan apa yang Prashad sebut sebagai “IMF colonialism.” Etika dekolonial berarti merebut kembali kedaulatan ekonomi dan ekologis sebagai hak moral bangsa.
Sisi kultural buku ini kuat: Prashad menggambarkan bagaimana sastra, musik, film, dan festival politik membentuk solidaritas Third World. Ia memberi tempat kepada seniman dan intelektual—dari penyair Afrika sampai sutradara Asia—yang merumuskan narasi alternatif. Kultur politik ini menjadi “modal sosial”: partai-partai kiri, gerakan perempuan, serikat tani, dan jaringan antarnegara yang menukik jauh dari ruang diplomasi elit. Pentingnya diskursus budaya inilah yang membuat Third World menjadi gagasan hidup—bukan sekadar kategori geopolitik.
Bagian Mecca membahas tentang aspek budaya – When Culture Can Be Cruel: Antara Spiritualitas dan Otoritarianisme. Bab terakhir, “Mecca,” adalah refleksi kultural dan moral yang tajam. Prashad menyoroti transformasi dunia Islam pascakolonial, khususnya peran Arab Saudi dan ekspor wahabisme yang mengubah lanskap spiritual dan politik di Dunia Selatan. “Mecca,” bagi Prashad, melambangkan paradoks: tempat suci yang seharusnya memancarkan solidaritas umat justru menjadi sumber penyebaran ideologi konservatif yang sering menindas perempuan, membungkam pemikiran progresif, dan melayani kepentingan geopolitik Barat.
Ia menulis dengan nada getir bahwa “culture, too, can be cruel when it forgets justice.” Dalam pandangan Prashad, proyek budaya Third World seharusnya menggabungkan spiritualitas dengan keadilan sosial, bukan menggantikan solidaritas internasional dengan moralitas eksklusif.
“Mecca” sekaligus menutup buku ini dengan refleksi universal: setiap gerakan pembebasan yang kehilangan jiwa kemanusiaannya akan melahirkan bentuk baru penindasan. Dalam konteks dunia kini, bab ini terasa relevan — mengingat kebangkitan fundamentalisme, politik identitas, dan kooptasi agama oleh kekuasaan kapitalistik.
Untuk Indonesia, pelajaran dari “Mecca” sangat penting: kebangkitan konservatisme agama sering berjalan seiring dengan neoliberalisme, keduanya sama-sama menekan wacana emansipasi sosial dan keadilan kelas. Prashad mengingatkan agar perjuangan moral tidak tercerabut dari basis material dan kemanusiaan universal.
Bab Mecca – When Culture Can Be Cruel membuka dimensi spiritual dari krisis pascakolonial. Prashad menunjukkan bagaimana agama — yang seharusnya menjadi sumber pembebasan — bisa berubah menjadi alat kekuasaan dan represi. Dalam bahasa Ali Shariati, agama dapat menjadi “religion of protest” atau “religion of power”; tergantung siapa yang memegang tafsirnya.
Prashad tidak menyerang iman, tetapi mengkritik institusionalisasi agama yang kehilangan etika keadilan. Ini sejalan dengan Fazlur Rahman yang menulis bahwa inti Islam adalah moral vision of justice and compassion—bukan dogma beku. “Mecca” adalah peringatan bahwa ketika budaya dan agama berhenti berinteraksi dengan realitas sosial, ia menjadi kejam, eksklusif, dan kehilangan ruh pembebasannya.
Dalam konteks global, ini relevan terhadap fenomena populisme religius dan politik identitas yang menutupi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, bab ini berbicara langsung pada risiko Islam politik yang kehilangan kesadaran sosialnya: ketika moralitas dipisahkan dari solidaritas kelas, agama bisa berubah menjadi ideologi penghakiman, bukan pembebasan.
Prashad, Dekolonialitas dan Dunia Hari Ini
Dalam preface edisi 15-tahun (2022) Prashad merefleksikan jatuh-bangunnya warisan Third World: neoliberalisme, krisis hutang 1980-an, dan globalisasi meruntuhkan banyak proyek pembangunan mandiri, tetapi gagasan solidaritas Selatan-Selatan, kedaulatan, dan gerakan rakyat tidak lenyap. Justru munculnya dunia multipolar (kebangkitan China, jaringan baru kerjasama Selatan) dan gerakan iklim/antiglobalisasi menunjukkan bahwa banyak gagasan Third World kini mendapat bentuk baru. Prashad menegaskan: sejarah Third World bukan nostalgia, melainkan repertori strategi untuk masa depan—pembatalan hutang, pembangunan berdaulat, kontrol sumber daya, dan koalisi rakyat lintas batas.
Relevansi global hari ini: buku Prashad membantu memahami fenomena yang tampak baru—ketimpangan global, “green colonialism”, dan tekanan pasar global—sebagai kelanjutan struktur historis kolonial-kapitalis. Misalnya, tuntutan “transisi hijau” yang tidak memperhitung-kan kedaulatan lokal mengulang pola ekstraksi: Selatan jadi pemasok bahan baku (litium, nikel, tanah jarang) untuk industri Utara. Prashad memberi amunisi analitis untuk melihat bahwa tanpa reparasi struktural dan klausul keadilan, transisi iklim dapat memperkuat ketergantungan lama.
The Darker Nations bersuara langsung kepada pengalaman Indonesia—dari proses kemerdeka-an, percobaan pembangunan Sukarno (nasionalisasi, proyek industria l), hingga era Orde Baru (kapitalisme oligarkis dan integrasi ke pasar global). Pelajaran utama Prashad untuk Indonesia termasuk: pentingnya menegakkan kedaulatan atas sumber daya (tidak hanya kontrol nominal), membangun kapasitas teknologi dalam negeri (hindarkan jebakan komoditas), memperkuat demokrasi sosial (mengatasi “borjuis nasional” yang mereplikasi ketidakadilan), dan memupuk solidaritas internasional berbasis gerakan rakyat (bukan hanya diplomasi negara). Di era “green economy”, Indonesia harus menolak peran sekadar pemasok bahan baku dan menegosiasikan pembagian nilai yang adil serta perlindungan hak masyarakat adat.
Banyak pengamat memuji gaya people’s history Prashad—mengembalikan protagonisme ke rakyat dan gerakan sosial, serta menyajikan sejarah Third World sebagai ruang kreativitas politik. Penghargaan datang dari kalangan kiri, aktivis, dan sebagian akademisi yang melihat buku ini sebagai counter-narrative penting terhadap sejarah yang didominasi perspektif Barat. Kritik yang muncul mencatat dua hal utama: (1) Prashad kadang terlihat idealis terhadap solidaritas Third World—terlalu menonjolkan kontinuitas antarnegara tanpa menimbang perbedaan nasional yang mendalam; (2) sebagian pengulas akademik menilai ia kurang memberi ruang pada varian pembangunan yang berhasil (contoh: beberapa kebijakan industrial negara Asia Timur) sehingga generalisasi menjadi berisiko. Meski demikian, mayoritas menilai buku ini esensial untuk memahami politik global abad ke-20 dan warisannya.
Menurut Prashad Third World berupaya “to make history where none was written for them” (parafrasa semangat bukunya). Kalau kita bandingkan dengan Aimé Césaire—“colonization is not a machine capable of thinking, a body endowed with reason; it is naked violence and only gives birth to violence”—bunyi ini memperkuat analisis Fanon dan Prashad soal kekerasan historis kolonial. Apa yang terjadi di Palestina kini adalah contoh yang tak terbantahkan. Dari tradisi pemikir Islam modern, Fazlur Rahman menekankan pentingnya ijtihad kontekstual—berguna bagi negara Muslim Third World yang menafsirkan pembangunan sesuai tradisi lokal. Dari penyair/aktivis seperti Pablo Neruda dan Pramoedya Ananta Toer, kita bisa membayang-kan bahwa seni memperkuat keberanian kolektif—Prashad menempatkan budaya di pusat strategi politis.
Sebagai Direktur thetricontinental.org dan Chief Editor di LeftWord Books, tulisan Prashad telah menjadi kompas yang menuntun kita memahami gejolak politik, ketimpangan sosial, dan perlawanan rakyat di dunia yang tak setara. Filosofi Prashad sejalan dengan dekolonialitas yang diperjuangkan oleh Walter Mignolo dan Aníbal Quijano: membongkar kolonialisme bukan hanya dari politik dan ekonomi, tapi juga dari epistemologi — cara kita berpikir dan memahami dunia. The Darker Nations adalah proyek dekolonial karena menghidupkan kembali ingatan yang dihapus oleh narasi Eropa dan neoliberalisme.
Etika dekolonial, menurut Prashad, bukan sekadar menolak Barat, tetapi menuntut dunia yang lebih adil dan saling bergantung secara etis. Ini adalah bentuk planetary ethics — seperti diungkapkan oleh Vandana Shiva: “We are all part of the Earth family. The future depends on reclaiming this belonging.”
Dalam tradisi Islam, gagasan ini sejalan dengan khalifah fil-ardh: tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi dan sesama manusia. Maka, dekolonisasi bukan hanya pembebasan dari kekuasaan luar, tetapi juga pembebasan batin dari keserakahan, egoisme, dan ketakutan yang diwariskan oleh sistem kolonial.
Karya Prashad yang legendaris, “The Darker Nations: A People’s History of the Third World” ini, bukan hanya sekadar buku sejarah. Itu adalah sebuah manifesto yang menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 dan proyek “Dunia Ketiga” yang progresif—sebuah visi tentang solidaritas Global Selatan yang mandiri, bebas dari cengkeraman imperialisme lama maupun baru. Buku ini telah menjelma menjadi semacam “kitab suci” sekunder bagi siapa saja yang ingin menggali akar ketimpangan global dan impian akan tatanan dunia yang lebih adil.
Penutup Reflektif
The Darker Nations adalah buku yang menyatukan sejarah, politik, dan kultur dalam satu narasi rakyat—bukan hanya katalog kegagalan atau kemenangan negara-negara pascakolonial, tetapi manual politis bagi yang ingin membangun kedaulatan sejati. Bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan akademisi di Indonesia, ia merupakan panggilan: belajarlah dari sejarah Third World—pelajari kapan solidaritas berhasil, kapan ia dipatahkan oleh tekanan eksternal dan pengkhianatan internal, dan bagaimana hari ini gagasan-gagasan itu dapat diadaptasi dalam menghadapi tantangan ekologi, teknologi, dan geopolitik baru.
Bab-bab yang disusun dengan kronologis ini membentuk miniatur perjalanan lahir, hidup, dan kematian proyek Third World — dari Brussels (kelahiran solidaritas), Bali (pembunuhan ideologi), New Delhi (kematian politik), Kingston (pengkhianatan ekonomi), hingga Mecca (kemerosotan moral dan kultural). Namun seperti ditulis Prashad dalam edisi 2022: “The darker nations have not vanished; they live on in movements that fight for the planet, for justice, and for dignity.”
Dalam dunia hari ini — ditandai oleh krisis iklim, perang sumber daya, dan ketimpangan global — The Darker Nations berbicara dengan kekuatan profetis. Ia menegaskan bahwa imperialisme belum berakhir; ia hanya berganti wajah menjadi globalisasi, teknologi, dan utang. Indonesia, dengan sejarah panjang kolonialisme dan transisi neoliberal, berada tepat di pusat kontradiksi ini.
Maka, tugas kita bukan sekadar nostalgia terhadap “Third World,” tetapi membayangkan kembali solidaritas global berbasis keadilan ekologis dan sosial. Gerakan petani, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan di Nusantara hari ini — dari Kendeng hingga Wadas — sesungguhnya melanjutkan roh Brussels dan Bandung: menolak kolonialisme baru dan menegakkan martabat manusia.
Vijay Prashad mengajak kita untuk memahami “Darker Nations” bukan sebagai yang terbelakang, tapi sebagai sumber cahaya moral dunia. Dunia yang berpijar. Dalam kata penutupnya: “The Third World is not a place but a project. Its dream is unfinished, its people are unbowed.”
Analisis filosofis dari lima bab tadi menunjukkan bahwa The Darker Nations bukan sekadar sejarah politik, tetapi manifesto etika global — tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan tanpa dominasi. Ia menantang kita untuk menyalakan kembali api solidaritas, agar dunia yang gelap ini menemukan kembali cahayanya.
Karena itu kita perlu “membaca ulang dunia ketiga di cermin nusantara.” Di tengah hiruk-pikuk kota dan layar digital yang tak pernah tidur, kita sering lupa bahwa dunia yang kita pijak pernah dibangun di atas luka. Luka kolonialisme, luka ketimpangan, luka alam yang dikeruk demi kemajuan yang tidak pernah sampai pada semua orang. Membaca The Darker Nations karya Vijay Prashad hari ini, terasa seperti bercermin: wajah Dunia Ketiga ternyata masih menatap kita dari balik bayangan—lapar, terpinggirkan, dan mencari makna keadilan yang sejati.
Bangsa-bangsa Selatan dahulu bersatu di Bandung tahun 1955, menolak tunduk pada dua kutub kekuasaan dunia. Mereka percaya akan lahir dunia yang lebih adil, di mana kemerdekaan bukan sekadar simbol bendera, tetapi kemampuan menentukan arah hidup sendiri. Namun Prashad mengingatkan kita bahwa “obituari Dunia Ketiga” ditulis bukan karena cita-citanya gagal, tetapi karena semangat solidaritas itu dilupakan. Hari ini, imperialisme hadir kembali dalam rupa baru: proyek hijau yang menyingkirkan petani, investasi yang menukar tanah dengan utang, dan kebijakan ekonomi yang mengabaikan kemanusiaan. Tetapi juga hari ini, lebih 100 tahun, kehadirannya lebih telanjang dan brutal yang bisa kita saksikan dengan langsung di Palestina.
Bagi Indonesia, refleksi ini lebih dari sejarah. Ia adalah peringatan. Di balik pembangunan yang megah, hutan dibakar, tambang dikeruk, dan laut dikuasai korporasi global. Prashad seolah berbisik kepada kita: “Kedaulatan bukanlah slogan, tetapi keberanian menolak menjadi kaki tangan perbudakan global.” Di sinilah peran generasi muda—bukan sekadar untuk melawan, tetapi untuk menulis ulang makna kemajuan: yang berpihak pada bumi, pada manusia, dan pada masa depan yang berkeadilan.
Seperti yang pernah ditulis Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah.”
Maka tugas kita hari ini adalah menulis ulang sejarah Dunia Ketiga dari tanah air sendiri: melalui tindakan, solidaritas, dan ingatan. Sebab seperti yang dikatakan Vijay Prashad, “The Third World was not a place—it was a project.” Dan proyek itu belum selesai. Ia menunggu untuk kita hidupkan kembali, di bumi Indonesia yang masih mencari keadilan dan cahaya.
Seperti yang disimpulkan dalam bagian Conclusion, Vijay Prashad menutup kisah Dunia Ketiga dengan nada elegi—sebuah ratapan atas cita-cita besar solidaritas global yang lahir pasca kolonialisme, tetapi juga sebuah panggilan agar mimpi itu dihidupkan kembali. Ia menulis bahwa “the Third World was not a place, but a project”—yakni proyek politik, moral, dan spiritual untuk menciptakan dunia yang adil bagi bangsa-bangsa Selatan yang lama dieksploitasi.
Namun proyek ini, kata Prashad, runtuh di tengah neoliberalisme global yang menggantikan kolonialisme lama. Kekuatan ekonomi dunia memecah solidaritas Selatan melalui utang, intervensi IMF dan Bank Dunia, serta kooptasi elit lokal. “Bandung Spirit,” simbol perlawanan dan kerja sama nonblok, berubah menjadi kenangan diplomatik tanpa tenaga. Dunia Ketiga tidak mati karena kekalahan ide, melainkan karena pengkhianatan terhadap janji emansipasi itu sendiri.
Prashad tidak berhenti pada nostalgia. Ia menegaskan bahwa cita-cita Dunia Ketiga harus dibaca ulang dalam konteks kini—bukan sekadar romantisme anti-Barat, tetapi gerakan untuk menantang struktur ekonomi global yang masih menindas. Ia menyerukan lahirnya kembali solidaritas global, bukan di bawah bendera ideologi lama, tetapi di bawah panji global justice movements, perjuangan feminis, ekologi dekolonial, dan ekonomi solidaritas lintas bangsa.
Dengan nada reflektif, Prashad menulis bahwa “The Third World may be dead, but its ghosts continue to haunt the conscience of the planet.” Hantu itu adalah seruan bagi dunia untuk mengakui sejarah kekerasan kapitalisme global dan tanggung jawab moral untuk menciptakan tatanan dunia yang setara. Dalam penutupnya, Prashad mengajak pembacanya untuk melihat Selatan bukan sebagai korban, tetapi sebagai sumber inspirasi politik baru—tempat lahirnya bentuk-bentuk perlawanan dan kehidupan yang lebih manusiawi di tengah reruntuhan globalisasi.
Prashad menutup bukunya dengan paragraf ini: “Keterbatasan globalisasi yang digerakkan oleh IMF dan tradisionalisme balasan (revanchist traditionalism) telah memicu gerakan-gerakan massa di seluruh dunia. Pertempuran demi hak atas tanah dan hak atas air, demi martabat budaya dan kesetaraan ekonomi, demi hak-hak perempuan dan hak-hak masyarakat adat, demi pembangunan institusi demokratis dan negara yang responsif—semuanya bermunculan di setiap negara, di setiap benua. Dari sekian banyak inisiatif kreatif inilah, sebuah agenda sejati bagi masa depan akan muncul. Ketika saat itu tiba, Dunia Ketiga akan menemukan penerusnya.”
Bogor, 13 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Prashad, V. (2007). The Darker Nations: A People’s History of the Third World. New York: The New Press.
Prashad, V. (2022). Preface to the Fifteenth Anniversary Edition. In The Darker Nations: A People’s History of the Third World. The New Press.
Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth. Grove Press.
Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11–40.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum.
Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace. South End Press.
Rahman, F. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. University of Chicago Press.
Césaire, A. (1950). Discourse on Colonialism. Présence Africaine.