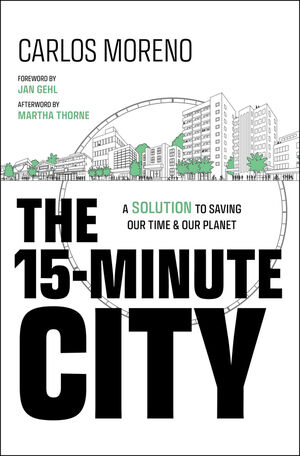Sustainability 17A #63
Memancing: dan Waktupun Diam
Dwi R. Muhtaman,
Sustainability Partner
“Aku ingin menjadi ikan
yang tak tergoda umpan…”
— Puisi “Aku Ingin,”
Sutardji Calzoum Bachri
“Kalau kamu tak sabar
menunggu ikan datang,
bagaimana kamu akan sabar
menunggu hidup memberimu makna?”
Emha Ainun Nadjib (Cak Nun),
Sastrawan dan budayawan Indonesia
Daftar Isi
Ia duduk. Tangannya memegang gagang sebuah benda seperti tongkat penyodok bola bilyar. Ada tali senar menjulur dan lepas ke sungai. Lemparan yang tak terlalu jauh dari tempat ia duduk. Itulah alat pancing. Dan lelaki di tepi Sungai Kayan itu duduk saja. Berkali-kali ditariknya pancing dan memasang ulang umpan. Lalu diulurkan kembali ke tengah sungai. Ia memandanga ke cakrawala. Mungkin termenung. Mungkin membayangkan ikan-ikan yang damai. Tak hirau atas umpan yang melayang-layang di dekatnya. Karena ia tahu itu hanya tipuan. Tak satupun ikan memangsa umpannya pagi itu. Tak sekalipun ia kesal. Karena dengan tenang dan sabar ia selalu memasang umpan kembali.
Sebab memancing bukan hanya soal mendapatkan ikan. Bagi banyak orang, bisa jadi ia adalah metafora hidup—tentang kesabaran, ketekunan, harapan, dan kedekatan dengan alam. Pemancing di pagi yang cerah itu nampak begitu menikmati segala kejadian. Ia nikmati memasang umpan. Dipilihnya bentuk umpan yang sesuai. Dilekatkan dengan penuh kekhusyukan ke mata kail. Seperti tengah berdoa. Lalu dengan gerak perlahan ia lemparkan menjauh. Melemparkan harapan yang jauh, dengan sabar dan berdebar.
Aktivitas yang tampak hening ini diam-diam mengajarkan banyak hal: menanti dengan sabar, menghadapi ketidakpastian, dan menerima hasil dengan lapang dada. Pagi itu ia tidak mendapatkan apapun dari umpan. Ikan-ikan mungkin hanya memandang dan pergi. Harapan yang makin menjauh. Nampaknya hasil bukan jadi persoalan betul. Karena ia tetap bisa memandang jauh ke seberang. Bisa menikmati lalu lalang perahu. Bisa menghirup udara pagi dengan sukacita. Dan sesekali bertegursapa dengan orang-orang yang lalu lalang. Sekedar ditanya: “Sudah dapat berapa?” “Belum,” jawabnya singkat.
Bagi para penggemar, memancing adalah ritual pelepasan stres, pelarian dari hiruk pikuk kehidupan urban. Juga riuhrendah pedesaan. Karena memancingpun juga digemari warga desa. “Memancing bukan hanya soal apa yang kau tangkap, tapi soal apa yang kau tinggalkan di daratan,” ungkap salah satu komunitas pemancing di New England.
Sastrawan dan filsuf memandangnya lebih jauh. Izaak Walton, penulis klasik The Compleat Angler (1653), menyebut memancing sebagai “the contemplative man’s recreation”—kegiatan rekreatif bagi mereka yang suka merenung. Adakah sesuatu di kedalaman? Apakah kehidupan lain memerlukan umpan? Kau memancing dengan memberi umpan bukankah sebuah tipuan? Memberi sesuatu yang menjebak kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan itu, meski tak selalu, mungkin diam-diam timbul di hati. Dalam kata lain, memancing adalah meditasi aktif, tempat jiwa bisa duduk, diam dan mendengarkan alam. Ada cerita dalam keheningan. Ada keramaian dalam ruang yang sepi. Dan menjebak untuk menangkap sesuatu. Bukankah hidup ini juga selalu membutuhkan umpan agar mendapatkan yang diharapkan?!
“Angling may be said to be so like the mathematics, that it can never be fully learnt,” kata Izaak Walton, The Compleat Angler.
“Memancing bisa dikatakan mirip seperti matematika: ia tak akan pernah bisa sepenuhnya dikuasai.”
Memancing bukan sekadar teknik sederhana—melainkan seni dan ilmu yang terus berkembang, tak ada habisnya untuk dipelajari. Sama seperti matematika yang selalu memiliki kerumitan dan kedalaman, memancing pun menuntut kesabaran, kepekaan, dan pengalaman yang terus-menerus diasah. Kapan menarik, kapan pula mengulur. Merasakan getaran dengan tepat senar dan tongkat pancing untuk mendapatkan momentum menarik kail. Kemampuan membedakan gigitan ikan dengan arus dalam. Semua memerlukan perasaan dan ketelitian mengamati pergerakan dan tanda-tanda.
Izaak Walton ingin menyampaikan bahwa: Memancing itu bukan hanya soal melempar kail dan menunggu. Ia menuntut pemahaman tentang alam, waktu, cuaca, air, ikan, bahkan batin manusia sendiri. Sama seperti matematika, tak ada titik akhir dalam belajar memancing. Selalu ada sesuatu yang bisa diperbaiki, dipelajari, dan ditemukan kembali. Selalu ada hal-hal baru setiap kali mata pancing berbaur dengan kedalaman air dan melayang-layang, menari mengikuti arus dan menggoda ikan-ikan menyergapnya.
Memancing adalah seni belajar seumur hidup. Seorang pemancing sejati tak pernah merasa “sudah ahli”—karena seperti matematika, kesempurnaan dalam memancing hanyalah cita-cita yang terus dikejar.
Bagi Henry David Thoreau, sang filsuf Transendentalis Amerika, memancing adalah bagian dari relasi spiritual dengan alam. Dalam jurnalnya, ia menulis:
“Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.”
— Henry David Thoreau
Thoreau ingin mengatakan: memancing adalah pencarian batin, bukan sekedar hasil. Kita tidak sedang mengejar ikan, tapi mengejar ketenangan, pengendapan waktu, dan keheningan jiwa.
Bagi sebagian sastrawan Asia, seperti penyair Tiongkok Li Bai, memancing melambangkan kebebasan dan pengunduran diri dari dunia yang gaduh. Dalam salah satu puisinya ia menggambarkan seorang nelayan tua yang hidup tenang di sungai, tak peduli urusan istana:
“A boat, a line, a bamboo rod—his joy beneath the sky.
He casts the world behind him, watching clouds drift by.”
Puisi pendek ini menyimpan makna yang dalam dan kontemplatif, meski disusun dari kata-kata yang sederhana.
“A boat, a line, a bamboo rod—his joy beneath the sky.” Tiga benda sederhana: sebuah perahu, seutas tali pancing, dan sebatang tongkat bambu. Tidak ada kemewahan, tidak ada hiruk pikuk—yang ada hanyalah kebahagiaan yang tenang, hadir dalam kesederhanaan. “His joy beneath the sky” menggambarkan kebebasan, keterhubungan langsung dengan alam raya, dan kebahagiaan yang tidak dibeli oleh uang, melainkan oleh kehadiran utuh di saat ini.
“He casts the world behind him, watching clouds drift by.” Dia melemparkan dunia ke belakang. Ini bukan cuma melempar kail ke air, tapi juga: Melepaskan beban kehidupan, menjauh dari kesibukan, kekacauan, dan ambisi manusiawi, memasuki dan menyambut ruang keheningan batin. Bergelut dengan suara hati. Berkecamuk pikiran dalam diam. “Watching clouds drift by”—memandangi awan berlalu, adalah simbol dari kesadaran murni, mengamati kehidupan tanpa melekat, tanpa terburu-buru. Ini seperti praktik meditasi: melihat sesuatu tanpa mengubahnya. Mengamati semua gerak alam dengan penuh hikmat. Dan menyalurkan dalam tubuh dan jiwa dengan nikmat.
Puisi ini adalah meditasi dalam bentuk aktivitas memancing. Ia berbicara tentang: Melarikan diri dari dunia tanpa benar-benar kabur—melainkan menghadirkan diri secara utuh di tempat lain. Menemukan kedamaian dalam alam dan kesunyian. Menggambarkan memancing sebagai perjalanan spiritual, bukan sekadar hobi.
Puisi ini sejalan dengan: Thoreau dalam Walden yang menyendiri di alam untuk mencari makna hidup. Zen Buddhism, yang mengajarkan keheningan, pelepasan, dan kesadaran saat ini. Hemingway dalam The Old Man and The Sea, yang menggambarkan nelayan tua melawan laut bukan demi ikan, tapi demi harga diri, keberadaan, dan kesendirian yang bermakna.
Memancing adalah membaca perlahan lembar demi lembar suasana alam sekitar, fokus pada satu hal pada suatu waktu, merasakan suasana yang dibangun: hening, damai, terbuka. Ketika memancing kerap kita berbicara dengan diri sendiri dan bertanya: Apa yang sedang kutinggalkan? Apa “dunia” yang ingin kulepaskan sejenak? Apa yang aku inginkan? Dan membayangkan apapun yang bisa dibayangkan. Imajinasi bisa berlari lepas begitu saja.
Begitulah kalau memancing menjadi bagian penting penyair. Seperti pada puisi itu. Puisi ini tak hanya bicara tentang memancing—tapi tentang mewujudkan ketenangan batin dalam dunia yang penuh kebisingan. Dan kadang, semua yang kita butuhkan hanyalah sebuah perahu, seutas tali, dan waktu untuk menatap awan.
Di tengah dunia yang serba cepat dan bising, memancing adalah seni memperlambat. Ia melatih kesabaran, pengendalian diri, bahkan kerendahan hati—karena tak ada jaminan bahwa kail kita akan disambut ikan.
Memancing bukan sekadar hobi. Ia adalah cermin dari cara kita menghadapi hidup: apakah kita bisa menunggu dengan sabar? Menerima hasil dengan syukur? Menikmati perjalanan tanpa terlalu terikat pada hasil?
Sebagaimana kata pemancing sekaligus penulis John Gierach:
“The solution to any problem — work, love, money, whatever — is to go fishing, and the worse the problem, the longer the trip should be.”
Memancing, pada akhirnya, adalah pelajaran tentang hidup itu sendiri. Meskipun Gierach terkesan menjadikan mancing sebagai pelarian, tetapi ia juga bis aberfunsi sebagai penyaluran, katarsis. Makin banyak masalah makin lamalah kau memancing. Membuang segala kekusutan. Meninggalkan dunia yang galau dan berjelaga. Berharap, pikiran kembali jernih dan terang usai memancing.
Di tepi danau yang sunyi, di ujung perahu kecil, atau di pinggir sungai yang deras namun sabar, seseorang melempar kail. Bukan dengan tergesa, melainkan dengan ritme alam. Ia menunggu. Di situlah esensi memancing—bukan pada tarikan ikan, tetapi pada jeda antara harapan dan hasil.
Memancing mungkin tampak seperti kegiatan sederhana, bahkan membosankan bagi sebagian orang. Tapi bagi para pemancing sejati—baik yang memancing dengan joran maupun dengan pikiran—aktivitas ini adalah laku batin, sejenis meditasi yang berlangsung di antara arus air dan arus waktu.
Memancing dan Filsafat Waktu
Di dunia modern yang bergerak cepat, memancing adalah tindakan perlawanan terhadap desakan waktu. Seseorang tidak bisa memaksa ikan datang. Ia hanya bisa menanti. Di sinilah pelajaran tentang kesabaran muncul. Bersabarlah hingga waktu yang tepat, waktu yang paling tepat. Bersabar menunggu momentum datang dalam hitungan sekian per detik. Ketika ujung kail bergoyangan karena ikan-ikan yang menutul umpan, momentum akan datang pada detik tertentu diantara getaran itu. Terlalu cepat menarik kau akan gagal. Terlalu lambat kau juga akan gagal. Hanya hitungan momentum yang paling sempurna yang akan berhasil. Dan itu berarti diperlukan kehalusan rasa dan keyakinan diri untuk bisa memutuskan. Diperlukan latihan yang lama untuk meletakkan kesabaran yang tepat dan ketepatan memahami momentum.
Filsuf José Ortega y Gasset, dalam bukunya Meditations on Hunting, menulis bahwa berburu (dan memancing sebagai bentuknya yang lebih kontemplatif) adalah pengalaman waktu yang lambat:
“Hunting, or fishing, returns man to the rhythm of nature. He is no longer time’s slave, but its companion.”
Bersama alam, pemancing belajar bahwa tidak semua hal bisa dicapai dengan kecepatan dan kekuasaan. Kadang kita hanya perlu diam, membuka diri, dan percaya.
Memancing Sebagai Refleksi Diri
Bagi Henry David Thoreau, yang hidup selama dua tahun di hutan Walden, memancing bukan hanya soal menangkap ikan. Ia adalah perjumpaan dengan diri sendiri:
“I went to the woods because I wished to live deliberately… I caught a fish, yes, but what I really sought was clarity.”
Aktivitas memancing memaksa kita untuk duduk berlama-lama hanya dengan diri kita sendiri. Di sinilah muncul ruang untuk introspeksi. Setiap getaran di ujung kail bisa menjadi simbol dari kepekaan batin terhadap kehidupan.
Dalam Pandangan Sastra: Imajinasi, Keheningan, dan Alam
Dalam puisi-puisi klasik Tiongkok dan Jepang, memancing sering digambarkan sebagai tindakan penyatuan dengan semesta. Penyair Dinasti Tang, Meng Haoran, menulis:
“I love the fisherman’s idle boat drifting among lotus leaves.”
Sementara dalam sastra Indonesia, aktivitas memancing kerap tampil dalam karya Sitor Situmorang dan Sapardi Djoko Damono sebagai lambang kontemplasi. Dalam puisinya “Pada Suatu Hari Nanti”, Sapardi menulis tentang waktu yang perlahan hilang, seperti seseorang yang menunggu ikan yang tak kunjung datang:
“…tak ada lagi yang akan dikenang dengan diam,
seperti hujan yang jatuh di danau itu,
seperti kail yang tak kunjung mendapat sambutan.”
Kail yang tak ditarik ikan menjadi simbol dari harapan manusia, sering kali sunyi, namun tidak pernah sia-sia. Pada saat seseorang mencurahkan enerjinya untuk memancing ia paham bahwa waktu yang dikerahkan untuk itu tak akan pernah sia-sia. Sebab bukanlah mendapatkan ikan atau tidak itu yang penting. Kesunyian selama menunggu, keheningan antara ketika kail dilemparkan dan saat kail diangkat itulah sebetulnya hakikat memancing menemukan kenikmatan: momentum ketika percakapan dengan sunyi terjadi. Saat ketika pikiran mengembara pada dunia yang tak bertepi.
Ernest Hemingway, melalui novella klasiknya The Old Man and the Sea (1952), mungkin adalah sastrawan yang paling kuat menempatkan memancing sebagai alegori hidup. Tokohnya, Santiago, seorang nelayan tua Kuba, digambarkan berjuang menangkap ikan marlin raksasa seorang diri, selama berhari-hari di tengah laut.
Memancing dalam kisah ini bukan semata soal hasil, melainkan perjuangan manusia melawan batas-batas kekuatan, kesepian, dan martabat.
“But man is not made for defeat,” he said. “A man can be destroyed but not defeated.”
— Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea
Hemingway memanfaatkan laut sebagai ruang eksistensial—tempat manusia diuji, dibentuk, dan pada akhirnya menemukan dirinya sendiri dalam hubungan dengan alam yang agung dan tak terduga.
Berbeda dengan Hemingway dalam novella A River Runs Through It (1976), Norman Maclean menulis tentang keluarganya dan kebiasaan mereka fly fishing di Montana. Di sini, memancing menjadi bahasa cinta, memori, dan spiritualitas yang menghubungkan ayah-anak, manusia-alam, dan trauma hidup dengan keindahan alam.
“Eventually, all things merge into one, and a river runs through it.”
— Norman Maclean
Fly fishing menjadi metafora pengampunan dan pencarian makna—sangat puitis dan tenang, tetapi menyimpan luka dan cinta yang dalam.
Sementara dalam cerpen “Nobody Said Anything” (1976), Raymond Carver, memancing muncul dalam konteks urban dan personal. Seorang anak yang frustrasi dengan keluarganya mencoba memancing di kolam kota. Cerita ini menggambarkan memancing sebagai pelarian, mimpi, dan keinginan untuk menjadi “dewasa”. Carver menampilkan memancing sebagai cara anak muda memahami dunia—penuh harapan tapi juga kekecewaan.
Meski tidak secara langsung tentang memancing, Yukio Mishima – The Sound of Waves (1954) menggambarkan kehidupan nelayan muda Jepang di sebuah pulau kecil, serta hubungannya dengan laut, cinta, dan nilai-nilai tradisional Jepang.
Laut dalam karya ini adalah latar bagi pertumbuhan batin, dan kehidupan nelayan menjadi simbol kejujuran dan kedekatan dengan ritme alam.
Dalam novel epik ini, Herman Melville – Moby Dick (1851), laut dan penangkapan paus menjadi obsesi eksistensial. Kapten Ahab tak lagi sekadar memancing atau berburu paus, tapi mengejar makna dan pembalasan, bahkan terhadap nasib dan takdir itu sendiri.
“There is, one knows not what sweet mystery about this sea, whose gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul beneath.”
— Herman Melville, Moby Dick
Moby Dick adalah gambaran ekstrem dari memancing yang berubah menjadi kegilaan filosofis dan spiritual—pencarian yang menghancurkan, namun juga memuliakan.
Dalam puisi W.S. Rendra, laut, ikan, dan nelayan kerap hadir sebagai metafora pemberontakan, keteguhan, dan keterhubungan manusia dengan kekuatan besar yang tak bisa dikendalikan. Ia menulis:
“Karena laut bukan hanya ombak,
tapi ia menyimpan dendam dan harapan.”
(Rendra, “Nyanyian Angsa”)
Rendra memandang laut sebagai sumber kehidupan sekaligus kekuatan yang harus dihormati, bukan dikuasai. Dalam banyak puisinya, ia menggambarkan alam bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang hidup—sebuah ciri khas dari ekopuitika (ecopoetry).
“Laut itu seperti rahim.
Ia memberi makan,
menyusui kehidupan,
dan sesekali menenggelamkan.”
— Puisi “Nyanyian Angsa”
“Aku ingin menjadi ikan
yang tak tergoda umpan…”
— Puisi “Aku Ingin”
Puisi Sutardji Calzoum Bachri ini secara metaforis mencerminkan kesadaran akan kebebasan alamiah—ikan yang menolak godaan manusia. Bisa dibaca sebagai kritik terhadap ekspansi manusia ke wilayah alam yang tidak seharusnya dieksploitasi.
“Di laut, manusia menjadi kecil. Tapi justru karena itu ia belajar rendah hati. Ia tidak punya pilihan selain mendengar suara angin, ombak, dan langit.”
— Catatan dalam esai “Laut Bercerita” (pengantar novel Leila S. Chudori)
Seno Gumira Ajidarma tidak hanya menempatkan laut sebagai latar cerita, tetapi juga sebagai tokoh naratif yang mengajarkan nilai etis dan eksistensial: kerendahan hati, keheningan, dan mendengar alam.
Dalam Kearifan Lokal: Memancing sebagai Bagian dari Etika Hidup
Dalam budaya Indonesia, memancing bukan hanya kegiatan individu. Di banyak daerah, ia menjadi bagian dari ritual komunitas dan ajaran moral. Misalnya, dalam masyarakat pesisir Bugis dan Buton, memancing adalah cara belajar tentang resopa temmangingi—kerja keras tanpa menyerah, sambil tetap berserah pada rezeki laut.
Sastrawan dan budayawan Indonesia Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) pernah berkata: “Kalau kamu tak sabar menunggu ikan datang, bagaimana kamu akan sabar menunggu hidup memberimu makna?”
Memancing mengajarkan bahwa hasil bukanlah ukuran utama, melainkan cara kita menghadapi ketidaktahuan dan ketidakpastianlah yang mendidik jiwa.
Dalam pengantar karya sastra Sunda tradisional yang banyak menyebut kehidupan nelayan, Ajip Rosidi menyebut: “Orang kampung tahu kapan waktu laut bisa diambil, dan kapan ia harus dibiarkan sendiri. Mereka tidak diajari oleh undang-undang, tapi oleh rasa.”
— Ajip Rosidi, dalam “Sastra dan Lingkungan” (1975)
Ini menunjukkan adanya etika ekologis lokal yang hidup di tengah masyarakat, yang kerap diabaikan oleh pendekatan modern yang eksploitatis.
Meski novel ini lebih politis, Leila S. Chudori – Laut Bercerita (2017), laut dalam novel Leila memiliki dimensi simbolis yang sangat kuat: “Laut bisa menjadi rumah dan kuburan. Tapi ia selalu setia membawa cerita.”
Laut menjadi ruang transisi antara hidup dan mati, antara suara yang dihilangkan dan suara yang bangkit kembali. Ini adalah bentuk ekologi naratif, di mana alam menjadi saksi penderitaan manusia.
Antara Hobi, Spiritualitas, dan Etika Ekologis
Bagi para hobiis, memancing adalah pelepas penat. Tapi bagi mereka yang memancing dengan hati, kegiatan ini juga menjadi pengingat hubungan harmonis antara manusia dan alam. Pemancing yang baik tahu bahwa ia tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan ia mengembalikan ikan-ikan kecil ke air sebagai tanda hormat terhadap siklus kehidupan. Melatih diri menghormati keberlangusungan hidup. Belajar memahami arti cukup yang sebenarnya. Menghindari menjadi tamak karena paham alam rusak karena ketamakan. Kekayaan alam yang melimpah tidak akan pernah cukup memenuhi sekeping orang yang tamak.
Aktivitas ini dengan sendirinya menjadi bentuk spiritualitas ekologis: menyatu dengan alam, tidak menguasainya. Kesadaran ekologis (ecoconsciousness) dalam sastra mengacu pada upaya sastra untuk: Menempatkan alam sebagai subjek, bukan hanya latar. Menyoroti relasi etis antara manusia dan alam. Merekam, mengkritik, dan mengajak pembaca mewaspadai kerusakan lingkungan, termasuk laut, hutan, sungai, dan habitat lainnya. Mengangkat nilai-nilai kearifan lokal ekologis, seperti pantang merusak ekosistem, mengambil secukupnya, dan menghormati musim alam.
Memancing dalam sastra—baik dalam karya Hemingway, Maclean, maupun para penyair Indonesia—bukan hanya soal menangkap ikan. Ia mencerminkan: Kesabaran dan kesadaran ekologis: Menunggu waktu yang tepat, tidak serakah. Pengendalian diri terhadap alam: Tidak menjarah, tapi memahami. Refleksi diri sebagai bagian dari alam, bukan penguasa atasnya.
Sastrawan memperlihatkan bahwa interaksi manusia dengan laut dan sungai harus disertai rasa hormat dan batin yang peka, bukan sekadar aktivitas ekonomi atau rekreasi.
Memancing dalam sastra bukan hanya praktik fisik, melainkan simbol spiritual dan ekologis. Ia mengajarkan manusia untuk: hidup tidak tergesa, mendengar suara air dan angin, serta menjadi bagian dari lanskap, bukan penguasa atasnya.
Kesadaran ekologis ini menjadi semakin penting di era krisis lingkungan hari ini. Sastra, dengan segala kepekaan estetikanya, dapat menjadi alat rekonstruksi hubungan manusia dengan alam—hubungan yang lebih adil, puitis, dan berkelanjutan.
Kail, Air, dan Diri
Memancing mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan dalam hidup: bahwa tidak semua hal bisa didapat secara instan. Diperlukan seperangkat upaya untuik bisa menghasilkan sesuatu. Dan upaya itu tidak semuanya materi. Ada nilai dalam menunggu. Ada harga untuk sebuah kesabaran. Ada makna dalam keheningan. Dan ada kedalaman dalam kesederhanaan. Ada nilai penting dalam setiap upaya dan ada kehormatan setiap hasil dari upaya. Dan tidak semua ‘hasil’ adalah hasil. Tidak semua ‘tanpa hasil’ adalah kegagalan. Bahkan tidak ada kegagalan dalam setiap upaya yang dilakukan. Karena setiap kegagalanpun adalah sebuah hasil yang mempunyai makna.
Sebagaimana kata Ted Hughes, penyair Inggris: “Fishing is not an escape from life, but often a deeper immersion into it.”
Di ujung kail, mungkin ada ikan. Tapi lebih dari itu, di ujung kesabaran, ada kebijaksanaan.
Tanjung Selor-Tarakan-Balikpapan-Bogor, 9 Agustus 2025
Referensi Kutipan dan Rujukan
1 Hughes, T. (1999). Collected poems. Faber & Faber.
2 Nadjib, E. A. (2005). Kiai Bejo dan Dukun Beranak. Yogyakarta: Pustaka Cakrawala.
3 Ortega y Gasset, J. (1942). Meditations on hunting (H. W. Weaver, Trans.). Charles Scribner’s Sons.
4 Sapardi Djoko Damono. (2000). Hujan Bulan Juni. Jakarta: Grasindo.
5 Thoreau, H. D. (1854). Walden; or, life in the woods. Ticknor and Fields.
6 Walton, I. (1653). The compleat angler. London.