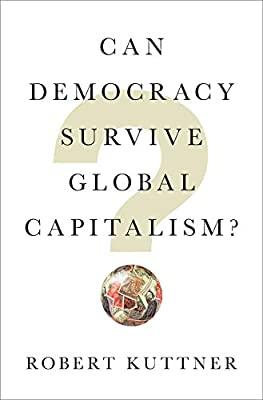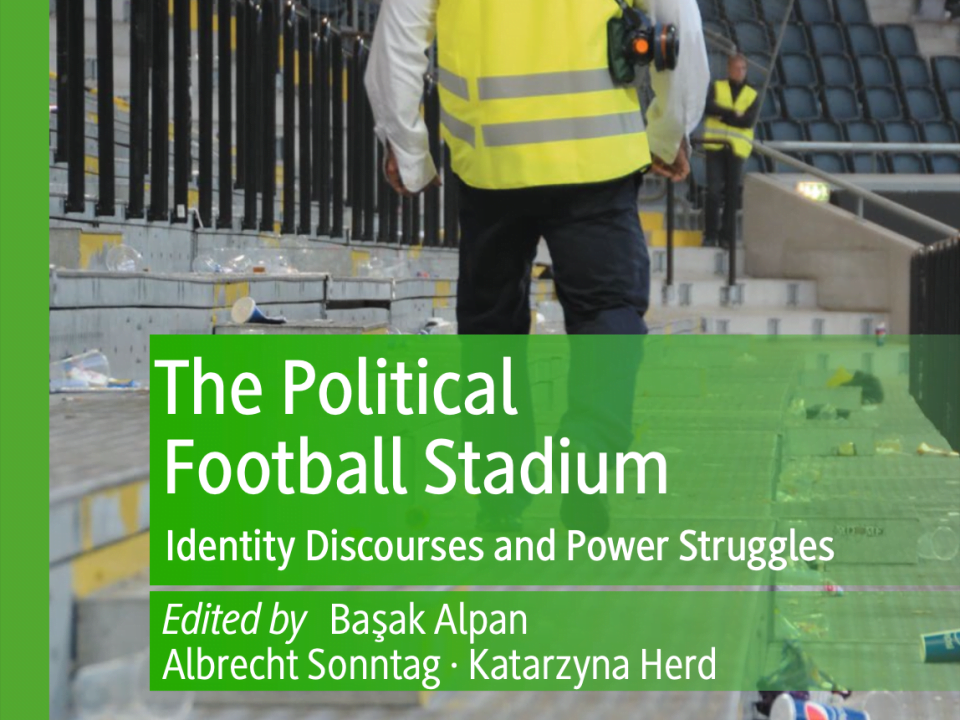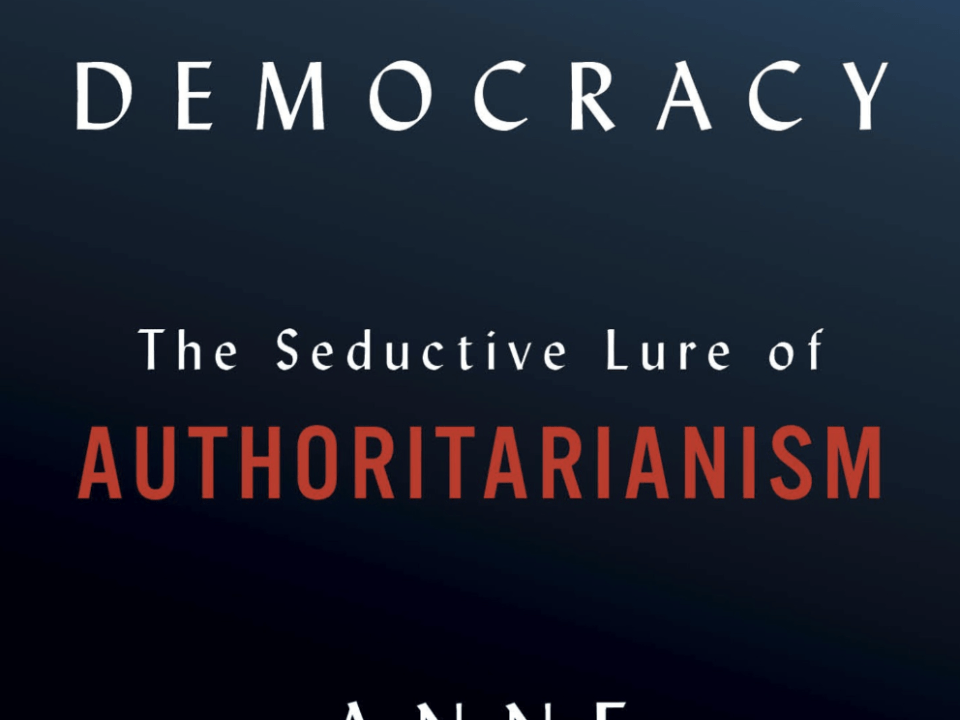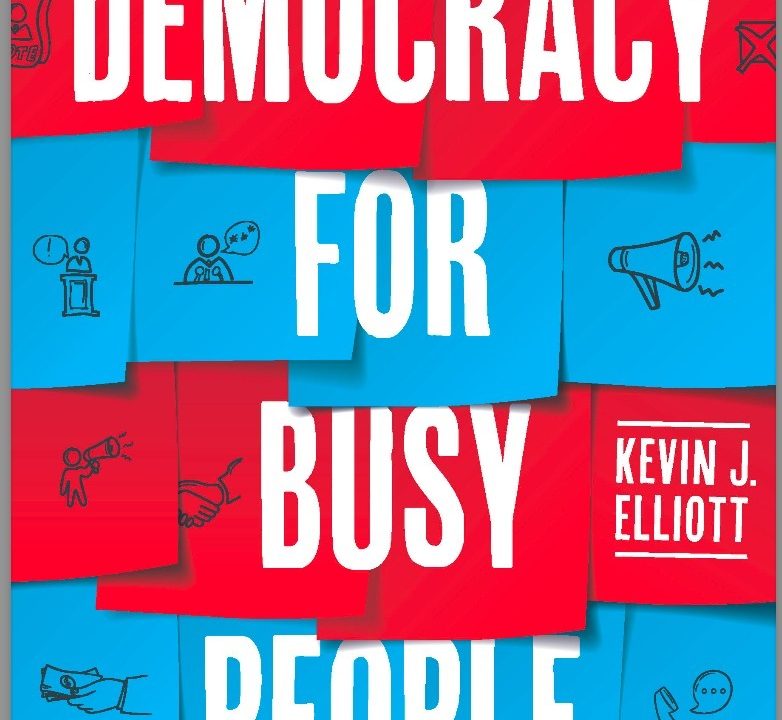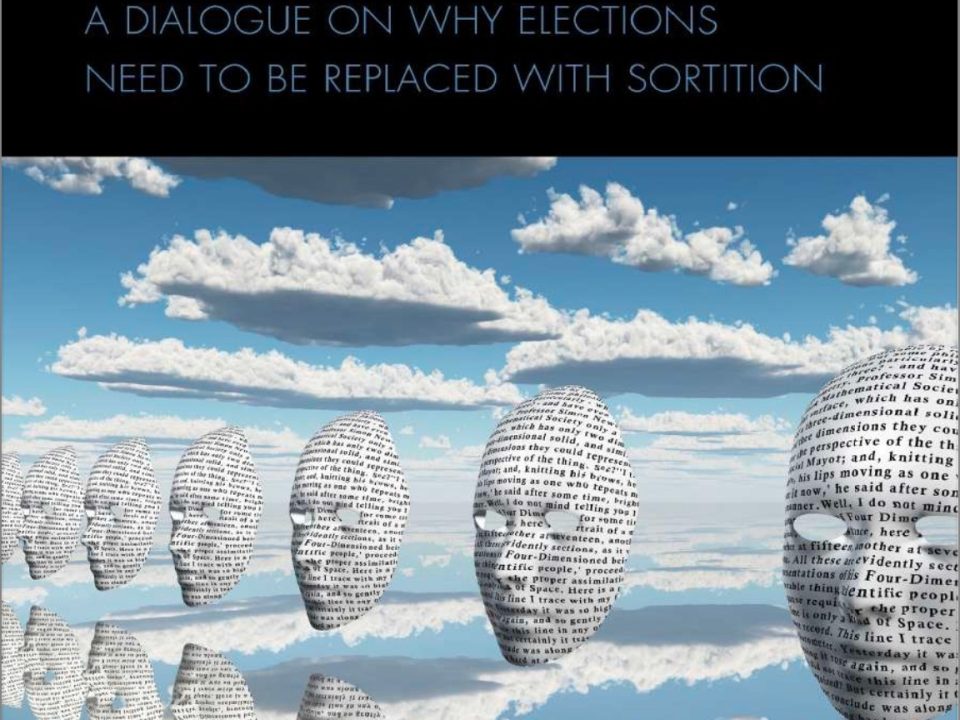Akankah Kapitalisme Menelan Demokrasi?
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor-Cirebon, 05.08.2020
#BincangBuku #46
“Democracy, national sovereignty and global economic integration are mutually incompatible.”
— DANI RODRIK
“Globalization is a new word which describes an old process: the integration of the global economy that began in earnest with the launch of the European colonial era five centuries ago. But the process has accelerated over the past 30 years with the explosion of computer technology, the dismantling of barriers to the movement of goods and capital, and the expanding political and economic power of transnational corporations.”
—Wayne Ellwood
“History doesn’t repeat, but sometimes it rhymes. The current rhyme is a discordant one, with echoes that should be treated as ominous warnings.”
—Mark Twain dikutip Robert Kuttner. “Can Democracy Survive Global Capitalism?.”
Globalisasi bukan hal yang baru seperti ditulis Wayne Ellwood dalam buku The No-Nonsense Guide to Globalization (2010). Kosakata baru yang menggambarkan proses kuno. Lebih dari lima abad yang lalu, di dunia tanpa listrik, ponsel, pendingin, DVD, internet, mobil, pesawat terbang atau senjata nuklir, ada satu orang yang memiliki mimpi bodoh. Begitulah tampaknya pada waktu itu, 1492. Cristóbal Colón, seorang pelaut muda Genoa yang ambisius dan petualang. Terobsesi dengan Asia – suatu wilayah yang dia tidak tahu apa-apa, selain hanya berdasar rumor tentang kekayaan kolosalnya. Kekuatan obsesinya (ada yang bilang keserakahannya) itu pada akhirnya mampu meyakinkan Raja dan Ratu Spanyol untuk membiayai perjalanan ke wilayah yang penuh ‘kegelapan’, hamparan air yang tampaknya tak terbatas yang kemudian dikenal sebagai Laut Samudera. Tujuannya: untuk menemukan Grand Khan di Cina dan emas yang dilaporkan sangat melimpah.
Berabad-abad kemudian, Colón menjadi akrab bagi jutaan anak sekolah di Barat sebagai Christopher Columbus, ‘penemu’ terkenal Amerika. Bahkan, ‘penemuan’ itu lebih dari sekedar kebetulan. Columbus Si Pemberani itu tidak pernah mencapai Asia, bahkan tidak sedikitpun dekat. Sebaliknya, setelah lima minggu di laut, dia menemukan dirinya berlayar di bawah matahari tropis ke dalam perairan pirus di Karibia, membuat pendaratannya pada suatu tempat di Bahama, yang kemudian diberi nama San Salvador (Juruselamat). Tempatnya jelas menyenangkan kru Columbus yang lelah. Mereka memuat air segar dan bahan makanan yang tidak biasa. Dan mereka berteman dengan penduduk asli pulau itu, Taino.
‘Mereka adalah orang-orang terbaik di dunia dan sangat ramah, lembut,’ Columbus menulis dalam jurnalnya. ‘Mereka
dengan sangat rela menunjukkan orang-orang saya di mana ada air, dan mereka sendiri membawa barel-barel penuh air ke kapal. Sangat menyenangkan kami. Mereka menjadi teman kami adalah sebuah keajaiban. Dua puluh tahun dan beberapa perjalanan kemudian, sebagian besar Taino sudah mati dan masyarakat adat lainnya di Karibia diperbudak atau diserang. Globalisasi, bahkan saat itu, telah bergerak dengan cepat dari proses pertukaran lintas budaya yang ramah ke perebutan jahat untuk kekayaan dan kekuasaan. Ketika penduduk lokal mati karena penyakit pendatang Eropa atau karena benar-benar bekerja sampai mati oleh penculiknya, majikannya, ribuan penjajah Eropa diikuti. Pencarian yang mati-matian para penjajah itu adalah untuk emas dan perak. Namun konversi dari jiwa-jiwa kafir pada iman Kristen memberi tambahan perangsang untuk perampasan mereka. Akhirnya pemukim Eropa menjajah sebagian besar tanah baru di utara dan selatan Karibia.
Petualangan Columbus di Amerika menjadi terkenal untuk banyak hal, paling tidak fokusnya adalah mengekstraksi kekayaan sebanyak mungkin dari tanah dan orang-orang setempat. Tapi, yang lebih penting, pelayarannya membuka pintu hingga 450 tahun kolonialisme Eropa. Dan inilah era kekaisaran selama berabad-abad yang meletakkan dasar
untuk ekonomi global saat ini (Ellwood, 2010).
Kini setelah berabad-abad kita bergandengan tangan, globalisasi telah makin menghisap tangan dan sekujur tubuh kita. Globalisasi menjelma menjadi monster yang menakutkan. Dalam kalimat Kuttner: “A quarter century ago in the glow of postcommunist triumphalism, many were predicting that globalization would link democracy with capitalism in a splendid convergence. Instead, we are witnessing a primitive backlash against both the global market and liberal democracy.”
Dan menyangsikan kemampuan demokrasi untuk bisa bertahan dalam global kapitalisme. “Corrupt capitalism seems to be gaining, while the number of democracies is shrinking. Some twenty-five democracies have failed just since 2000,” kata Kuttner.
Kuttner yang merupakan pendiri the Economic Policy Institute dan duduk sebagai komite eksekutifnya, mencatat bahwa
saat ini, elit perusahaan dan keuangan telah secara substansial menaklukkan alat-alat negara dan menetralisir partai kiri tengah sebagai sumber reformasi sistemik. Gagasan Galbraith tentang pemerintahan yang demokratis, serikat pekerja, dan organisasi warga sebagai kekuatan yang “menyeimbangkan” melawan kekuatan perusahaan swasta (sebuah teori yang dikemukakan pada tahun 1952 selama gelombang boom pascaperang) tidak berfungsi ketika kekuatan korporasi mendominasi negara juga. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah dan politik sebagai instrumen perbaikan publik yang luas telah kehilangan kredibilitas. Populisme nasionalis sayap kanan dan neofasisme telah secara substansial mengisi kekosongan ini. Lembaga-lembaga globalis selanjutnya telah menghalangi alternatif-alternatif demokratis-kiri. Bagaimana kita bisa mengubah lingkaran setan ini kembali menjadi yang berbudi luhur? Itulah pertanyaan yang jawabannya didiskusikan dalam buku Kuttner ini.
Dalam #BincangBuku #46 kali ini kita akan mengupas buku yang ditulis oleh Robert Kuttner: “Can Democracy Survive Global Capitalism?.” (2018). Perkembangan politik di berbagai negara dalam sepuluh tahun terakhir ini menyiratkan ancaman nyata terhadap demokrasi. Demokrasi dalam kepungan segala penjuru. Pergolakan ini terjadi tidak hanya di negara-negara dengan akar demokrasi yang lemah seperti Turki, Hongaria, Mesir, dan Filipina, tetapi juga di jantung demokrasi – Eropa Barat dan Amerika Serikat. Autokrat menggunakan bentuk demokrasi untuk menghancurkan substansi. Sebagai model lain, semi-kapitalisme yang dipimpin negara Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi demokrasi liberal. Cina juga tidak merangkul pasar bebas. Reaksi ultranasionalis ini diperparah dengan kebencian terhadap para imigran dan pengungsi, serta rasisme yang bangkit kembali. Tetapi pendorong mendasar dari tren ini adalah kebangkitan kapitalisme yang lalai dan global yang melayani segelintir orang, merusak banyak orang, dan melahirkan politik antisistem. Meskipun belokannya tiba-tiba dan ekstrem, frustrasi massal telah muncul selama beberapa dekade, di bawah pengawasan dan pemantauan para elit (hal. 8).
Beragam penelitian dan buku ditulis para ilmuwan dan pengamat politik tentang kecemasan nasib demokrasi dalam jaman yang penuh guncangan ini. Misalnya, “Democracy may not exist, but we’ll miss it when it’s gone” (Astra Taylor, 2019); “Can Democracy Work?” (James Miller, 2018); Edge of Chaos: Why Democracy Is Failing to Deliver Economic Growth—and How to Fix It (Dambisa Moyo, 2018); “Our Damaged Democracy.” (Joseph A. Califano Jr., 2018) untuk menyebut beberapa. Sebagian besar memberi peringatan tentang tanda-tanda runtuhnya demokrasi bersama dengan kapitalisme.
Buku “Can Democracy Survive Global Capitalism?” yang ditulis oleh co-founder and co-editor of The American Prospect magazine, dan Ketua the Ida and Meyer Kirstein pada the Heller School for Social Policy and Management di Brandeis University ini diakui merupakan upaya untuk menghubungkan titik-titik antara bangkitnya populisme sayap kanan dan runtuhnya kontrak sosial yang pernah menjadi panduan kewargaan dalam demokrasi Barat. Setelah serangan 11 September 2001 banyak yang menganggap telah terjadi “clash of civilizations,” sebagaimana pernah dipopulerkan oleh Samuel P. Huntington— demokrasi Barat melawan bentuk barbar dari Islam radikal. Namun perlu diingat bahwa sebelum 9/11, seperti dikutip Kuttner, buku ilmuwan politik Benjamin Barber yang berjudul “Jihad versus McWorld” menyimpulkan: komersialisasi—dan seringkail vulgar— norma-norma globalisasi Barat justru mempromosikan reaksi primitif ketimbang penyebaran demokrasi liberal.
Dan perkembangan terkini memberi sinyal yang lebih buruk. “The threat to democracy is increasingly within the West.”
Kuttner telah menerbitkan sebelas buku, termasuk buku Obama’s Challenge yang masuk the 2008 New York Times best seller. Tulisan-tulisannya muncul di The Atlantic, The New Yorker, Harper’s Magazine, New York Review of Books, New Republic, Foreign Affairs, Dissent, New Statesman, Harvard Business Review, Columbia Journalism Review, Political Science Quarterly, dan the New York Times Magazine dan New York Times Book Review. Dia adalah kolumnis mingguan HuffPost. “Can Democracy Survive Global Capitalism?” merupakan kisah yang mendalam tentang hubungan antara kapitalisme yang berwajah sosial dan demokrasi yang kuat. Ketika sistem ini seimbang, demokrasi yang kuat akan menekan kekuatan pasar untuk kebaikan umum, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi demokrasi. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem yang mengatur warga pada aras nasional karena pemerintahannya nasional. Sebagai warga negara suatu negara, kita dapat memilih para pemimpin masing-masing. Pemerintah, khususnya Amerika Serikat, memiliki aturan dan prosedur tertentu yang relatif transparan dan dapat diganggu gugat.
Tetapi, demikian menurut Kuttner, tidak ada pemerintahan global dan tidak ada kewarganegaraan global. Pada tingkat tertentu demokrasi perlu mengatur pasar. Globalisasi melemahkan upaya itu. Globalisasi saat ini melemahkan otoritas regulasi nasional. Tidak ada pemberi pinjaman global dari upaya terakhir, tidak ada pengawas keuangan global, tidak ada otoritas antimonopoli global, tidak ada pengumpul pajak global, tidak ada dewan hubungan kerja global, tidak ada entitas global untuk menegakkan hak-hak demokratis atau memperantarai kontrak sosial. Organisasi global semu-pemerintah, seperti Dana Moneter Internasional dan Organisasi Perdagangan Dunia, jauh kurang transparan dan kurang akuntabel daripada lembaga-lembaga publik domestik, dan lebih mudah bagi elit korporasi untuk menguasai dan mendominasi. Globalisasi cenderung mengubah distribusi politik kekuasaan di dalam negeri, dan untuk meningkatkan pengaruh para elit yang lebih menyukai laissez-faire dan lebih banyak globalisasi, sehingga prosesnya berkembang dengan sendirinya yang menguntungkan korporasi (hal. 13). Laissez-faire alias pasar bebas ini semakin marak dengan skema pembangunan ekonomi yang diadopsi oleh banyak negara sebagai bagian dari virus bantuan pembangunan cara Amerika.
Kuttner mengkritik tajam soal kapitalisme global yang makin membabibuta. Kapitalisme global, yang semakin dideregulasi dan tidak ditambatkan dari pengekangan nasional, merongrong ekonomi yang seimbang dalam berbagai cara yang kompleks, dan kumulatif. Dengan pasar global dan tidak ada standar global, pekerja domestik dilemparkan ke dalam persaingan langsung dengan pekerja asing yang lebih mati-matian berebutan. Perjuangan demokratis selama seabad untuk mengatur standar perburuhan disingkirkan. Di ujung lain dari spektrum kekayaan, pembebasan keuangan di seluruh dunia menciptakan pendapatan yang melangit bagi para elit. Dunia berkembang mendapatkan akses ke pasar dunia tetapi, sebagian besar, menjadi kasus yang lebih ekstrim dari kekayaan dan kemiskinan. Uang menjadi lebih kuat daripada kewarganegaraan, merusak pemerintahan dan ekonomi. Globalisasi juga mempercepat pergerakan orang lintas batas. Para pemimpin perusahaan dan sekutu politik mereka mengambil manfaat itu. Mempromosikan aliran tenaga kerja murah internasional.
“Beberapa orang berpendapat bahwa kapitalisme mempromosikan demokrasi, karena norma umum transparansi, supremasi hukum, dan persaingan bebas — untuk pasar, untuk gagasan, untuk suara (vote). Dalam dunia ideal, kapitalisme dapat meningkatkan demokrasi, tetapi dalam sejarah Barat, demokrasi telah berkembang dengan membatasi kekuatan kapitalis. Ketika proyek itu gagal, kekuatan gelap sering dilepaskan. Pada abad kedua puluh, kapitalisme hidup berdampingan dengan baik dengan kediktatoran, yang dengan mudah menciptakan iklim bisnis yang ramah dan menekan organisasi pekerja independen. Kapitalis Barat telah memperkaya dan menopang para penguasa dunia ketiga yang menghancurkan demokrasi lokal. Hitler memiliki pemahaman yang baik dengan perusahaan dan bankir Jerman, yang berkembang pesat sampai kesalahan perhitungan pada Perang Dunia II yang tidak menguntungkan. Komunis Tiongkok bekerja sama erat dengan mitra bisnis kapitalisnya untuk menghancurkan serikat perdagangan bebas dan untuk melestarikan monopoli politik Partai. Vladimir Putin memimpin sebuah merek kapitalisme yang dicurangi dan memerintah secara harmonis dengan kleptokrat. Ketika dorongan datang untuk menekan, kisah bahwa kapitalisme dan demokrasi adalah pelengkap alami adalah mitos. Perusahaan dengan senang hati membuat perdamaian terpisah dengan para diktator — dan singkatnya, mempersempit wilayah keleluasaan kewarganegaraan bahkan di negara-negara demokrasi.” (hal. 17).
Bagi Kuttner jika demokrasi dihidupkan kembali, gerakan pengendalian pasar dan kapitalisme itu akan datang dari warga negara yang diberdayakan, bukan dari perusahaan.
Kuttner yang tamatan Oberlin College, The London School of Economics, dan the University of California at Berkeley, dan juga mengajar di the University of Massachusetts, the University of Oregon, Boston University, and Harvard’s Institute of Politics ini memaparkan dengan panjang lebar timbul tenggelamnya democratic globalism yang dimulai dari masa-masa berakhirnya Perang Dunia II, 1945-1946. Kemudian lahirnya arsitektur keuangan, Bretton Woods, Marshall Plan, IMF—lembaga-lembaga broker yang menjadi andalan pemulihan ekonomi dunia pasca perang. Perdebatan awal panjang yang menentukan tentang tatakelola arsitektur keuangan global itu telah mendorong kembalinya benih awal laissez-faire orthodoxy, sebuah keperkasaan pasar yang bebas tanpa intervensi pemerintah sebagai regulator (hal 96). Benih awal ini kemudian berkembang.
“Penataan sistem perdagangan dunia di era setelah Perang Dunia II adalah jantung dari kisah tentang bagaimana aturan-aturan globalisasi digunakan, pertama-tama untuk mempromosikan bentuk kapitalisme yang layak yang dikendalikan secara demokratis pada 1940-an dan kemudian, dimulai pada 1970-an, untuk menghancurkannya. Dalam kebijakan perdagangan seperti dalam sistem moneter global, kekuatan keuangan yang bangkit kembali adalah persoalan utama dari pembelokan kendali itu (hal 304).
“Terlepas dari klaim teori perdagangan bebas, secara harfiah tidak ada negara yang melakukan industrialisasi dengan mengandalkan pasar bebas.” Keterlibatan negara dalam pengembangan ekonomi telah menyebar luas – tidak hanya untuk raksasa manufaktur yang baru muncul seperti Jepang, Korea, dan Cina, tetapi juga pada masa-masa awal untuk Jerman, Prancis, dan Italia, serta kekuatan industri Amerika Latin seperti Brasil, Meksiko, dan Argentina. Pembangunan yang dipimpin oleh negara bahkan menggambarkan situasi Inggris awal, yang kemudian menemukan ‘kesucian’ perdagangan bebas. Dan itu juga mencerminkan Amerika Serikat.”
Dalam sejarahnya, Inggris pada akhir abad 16 atau Amerika pada abad 18 merupakan negara adidaya yang membatasi kebebasan pasar, kebebasan perdagangan. Tarif yang besar dikenakan untuk produk-produk impor tertentu. Bahkan Jerman juga bergabung sebagai negara yang gencar proteksi pasar domestiknya. Tetapi dengan makin merasuknya globalisasi, lembaga-lembaga internasional didesain untuk menghapus batas-batas negara dalam pergadangan dan membuka jalan korporasi untuk mengambil peran dominan dalam lalulintas barang dan jasa. WTO diciptakan dengan mandat menjadi regulator yang sangat berkuasa. “..the WTO has real power and mandatory rules,” tulis Kuttner yang pada akhir 1970-an setelah tidak lagi aktif dalam jurnalisme merancang the Foreign Corrupt Practices Act untuk bossnya waktu itu, Senator William Proxmire. Undang-undang itu melarang bisnis-bisnis Amerika menyuap pejabat-pejabat asing—sebuah contoh luar biasa dimana sebuah negara meletakkan dasar aturan progresif untuk globalisme.
Kehadiran WTO ini mewakili kedaulatan yang hilang — secara nominal bagi sebuah lembaga transnasional, tetapi secara efektif bagi pasar—dipersonifikasikan oleh tangan-tangan tak kasat mata dari bank-bank besar dan perusahaan multinasional. Dalam hal ini, rejim WTO tidak hanya secara sengaja merusak ekonomi campuran tetapi juga antidemokratis, karena seluruh bidang kebijakan sosial dan ekonomi telah dihapus dari musyawarah demokratis nasional, sementara prosedur WTO jauh tidak transparan atau lebih memprihatinkan daripada prosedur demokrasi nasional.
Justin Fox, seorang kolumnis pada Bloomberg Opinion dan pengarang buku “The Myth of the Rational Market” menulis tinjauan buku Kuttner ini. Tulisannya muncul di the Sunday Book Review (May 20, 2018): Laissez Not Fair, dan menyatakan bahwa lebih dari empat dekade, global capitalism telah membuat aturan-aturan untuk negara-bangsa. Itu dilakukan lebih banyak melalui mekanisme pasar bebas dan pasar keuangan bebas yang sagnat berkuasa, tetapi juga melalui badan-badan multilateral seperti the International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization dan European Union.
Ada banyak organisasi internasional, tulis Kuttner, tetapi satu-satunya yang tampaknya mampu memaksa negara untuk melakukan apa pun adalah yang menetapkan aturan ekonomi. I.M.F. dan Bank Dunia diciptakan pada masa Perang Dunia II dan mengalami adaptasi sesudahnya dengan gagasan bahwa mereka akan memberikan ruang bagi negara-negara untuk mengejar tujuan ekonomi domestik tanpa harus khawatir tentang krisis mata uang dan semacamnya. Mereka berevolusi pada 1970-an menjadi apa yang disebut Kuttner sebagai “instrumen untuk penegakan laissez-faire klasik sebagai prinsip pemerintahan universal. Hasilnya, menurut Kuttner, seperti ditulis Fox, termasuk peningkatan ketimpangan, pendapatan kelas menengah yang stagnan dan, dalam beberapa tahun terakhir, reaksi populis sayap kanan diwujudkan di Amerika Serikat melalui pemilihan Donald Trump.
Keberadaan lembaga-lembaga internasional yang cenderung mengangkangi kedaulatan nasional menegaskan kehadiran global governance yang antidemokrasi (hal 388). Bahkan menurut Kuttner suara-suara lantang dari mulut korporasi tentang Social Corporate Responsibility pada galibnya adalah tak lebih dari public relations (hal. 394). Skema sertifikasi produk, termasuk Forest Stewardship Council (FSC) yang disinggung Kuttner (hal 398) meskipun proses FSC telah meningkatkan kesadaran konsumen dan telah memperlambat deforestasi tetapi tidak membalikkan proses deforestasi global, yang kini telah menghancurkan lebih dari setengah hutan dunia. Praktek berkelanjutan masih hanya mencakup sebagian kecil dari pemanenan pohon. Apa yang tidak kita miliki adalah perjanjian global tentang standar hutan yang dapat ditegakkan (enforceable global treaty on forest standards). Meskipun kampanye branding telah membantu, menurut Kuttner, sebagian besar kredit digunakan untuk perubahan kebijakan yang disengaja oleh dua pemerintah nasional, Brasil dan Indonesia, yang membalikkan kebijakan sebelumnya yang mempromosikan laju deforestasi yang cepat. Sayangnya Kuttner tidak mengelaborasi lebih lanjut soal deforetasi di Indonesia yang hingga kini masih berada pada kisaran nyaris 500.000 ha/tahun, Laju deforestasi tercepat kedua di dunia setelah Bazil.
Gerakan masyarakat sipil global adalah harapan penting bagi Kuttner. Pada Januari 2001, ketika elit politik dan ekonomi global berkumpul di pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, sebuah countermeeting diadakan di Porto Alegre, Brasil, disebut World Social Forum. Pertemuan ini telah menjadi acara tahunan, dan biasanya diadakan di lingkungan dunia ketiga, menyatukan ribuan aktivis dan intelektual yang mewakili partai oposisi global yang beragam. Karena pasar dan perusahaan telah melampaui hambatan pemerintah nasional, barangkali WSF itu bisa memberi harapan bahwa masyarakat sipil global sebagai penyeimbang adalah bagian utama dari solusi.
Pada eventnya Juni dan Oktober 2020 WSF mengangkat tema besar Transformative Economies. Tema ini dimaksudkan untuk melangkah besar “connecting and involving movements and transformative practices that are changing the economic system in their communities all over the planet. More than Another World is possible, we affirm that “another world already exists”, and is being made by different practical visions of alter-globalization movements and by the renewal of long historical traditions such as co-operativism and community economies.”
Apa yang harus dilakukan, jika kita ingin menyelamatkan demokrasi? Atau bersiap-siaplah dengan sistem baru sebagai bagian dari penyelamatan ummat manusia dan bumi.
Kuttner dalam buku setebal 628 (dalam versi digital jumlah dan nomor halaman bisa problematik karena tergantung besar font yang digunakan pada saat membacanya) ini menguraikan gagasannya dengan memaparkan kesimpulan situasi kapitalisme global yang dibacanya.
Kapitalisme demokratik saat ini, tulis Kuttner, adalah kontradiksi dalam istilah yang dikandungannya. Globalisasi di bawah naungan keuangan swasta terus merongrong kendala demokrasi pada kapitalisme. Dalam spiral ke bawah, pembangkangan populer terhadap kapitalisme ganas telah memperkuat ultranasionalisme populis dan semakin melemahkan demokrasi liberal. Jika demokrasi ingin bertahan hidup, siklus itu perlu dibalik. Ini akan membutuhkan institusi demokrasi yang jauh lebih kuat dan transformasi kapitalisme yang radikal menjadi ekonomi sosial yang jauh lebih baik. Ini akan memerlukan aturan global yang berbeda, untuk memberikan lebih banyak ruang bagi kebijakan nasional. Sebaliknya, jika merek kapitalisme saat ini bertahan, ia cenderung menjadi lebih korup, terkonsentrasi, dan tidak demokratis. Jadi sistem yang muncul akan menjadi lebih otokratis dan lebih dikendalikan oleh modal — atau lebih demokratis dan kurang kapitalis.
Pandangan Kuttner itu sejalan dengan gagasan yang ditulis Dani Rodrik, ekonom Turki dan Profesor pada Ford Foundation of International Political Economy pada the John F. Kennedy School of Government di Harvard University, dalam bukunya: The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy (2011). Bagi Rodrik pasar global, negara dan demokrasi tidak bisa hidup berdampaingan. Mereka akan selalu kontradiksi satu sama lainnya. Sama sekali tidak kompatibel. Kapitalisme bisa jadi akan melumat demokrasi. Faktanya seperti dijelaskan Kuttner, lembaga-lembaga global sama sekali tidak demokratis.
Fasisme, layak untuk diingat, memiliki dua aspek. Salah satunya adalah kediktatoran, dengan massa yang menyembah atau terintimidasi marah pada elit biasa dan mencari keselamatan pada orang yang kuat. Wajah fasisme lainnya adalah korporat. Terlepas dari kontradiksi yang tampak, para diktator dan korporasi tetap akrab. Mereka berdua memahami kekuatan. Donald Trump melambangkan aliansi perusahaan, di mana kepentingan politik dan pemimpin bisnis berbaur. Separuh anggota kabinetnya memiliki konflik serupa. Bagi para penggemarnya, kapitalisme adalah demokrasi dalam dua hal utama. Norma kapitalis dan norma demokrasi konvergen melalui transparansi dan supremasi hukum. Tetapi ada perbedaan mendasar antara prinsip demokrasi inti dari satu orang/satu suara dan norma pasar dasar satu dolar/satu suara. Demokrasi tumbuh subur sejauh kekuatan uang dibatasi.
Kapitalisme juga dikatakan demokratis karena setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang saham atau wirausahawan.
“Dalam beberapa hal, ekonomi campuran (mixed economy yang menurut Fox: dimaksudkan untuk menggambarkan sistem di mana pasar dan bisnis untuk meraup keuntungan memainkan peran penting, tetapi berbagi kekuasaan dengan lembaga-lembaga seperti serikat pekerja dan asosiasi serupa dan pada akhirnya tunduk kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis) seperti menggabungkan minyak dan air. Bagian kapitalis terus berusaha mengubah semuanya kembali menjadi komoditas pasar. Karena uang dapat membeli yang lain, orang kaya terus berusaha membeli pengaruh politik. Namun sejarah menunjukkan bahwa ekonomi campuran bekerja lebih baik daripada ekonomi komando atau pasar yang tidak diatur. Tantangannya adalah agar lembaga publik menjadi tangguh seperti yang komersial, dan untuk memobilisasi kekuatan laten dari demokrasi populer untuk menjaga keuangan dalam perannya yang layak sebagai pelayan seluruh ekonomi. Ini sulit, tetapi bukan tidak mungkin.” (hal. 510).
Sebagai kesimpulan dari pemaparan yang panjang dalam 12 Bab itu Kuttner menegaskan kapitalisme saat ini tidak demokratis dan bahkan malah antidemokratis. Demokrasi pasca-kapitalis diperlukan sebagai solusi, dengan bentuk-bentuk baru ekonomi sosial. Demokrasi jenis itulah yang dapat bertahan dan bahkan berkembang untuk menyelamatkan cara manusia mengelola kehidupan dan sumberdaya yang tersedia.
Jika di negara-negara yang diklaim mempunyai kisah panjang demokrasi dan kapitalisme saja mempertanyakan keberlangsungan sistem itu, maka sudah sepantasnya negara Republik Indonesia melakukan inovasi demokrasi yang sungguh-sungguh. Inovasi demokrasi sangat mendesak agar kita tidak ikut terjerambab pada jurang bahaya yang sudah diketahui di depan mata. Inovasi demokrasi akan memungkinkan kita menelusuri jalan baru yang lebih baik, lebih sesuai dengan modal kekayaan sejarah, sosial budaya dan ekonomi kita.
Today’s capitalism is both undemocratic and antidemocratic. Post-capitalist democracy, with new forms of a social economy, could survive and even thrive. It is admittedly a long shot, but our only shot.”
Ini memang upaya panjang, tapi itulah satu-satunya upaya kita.