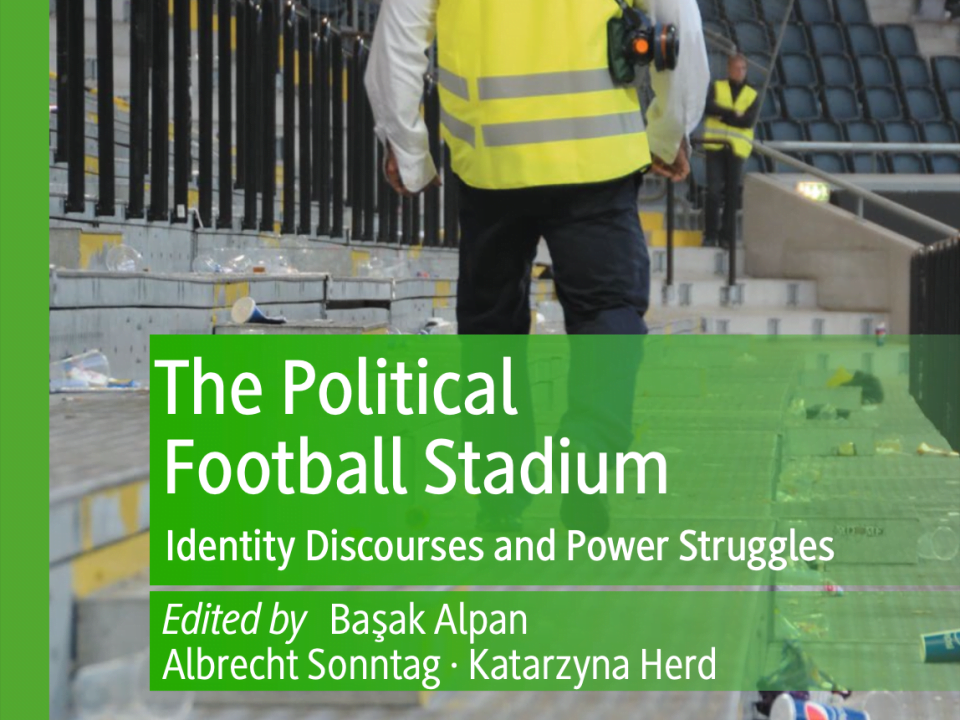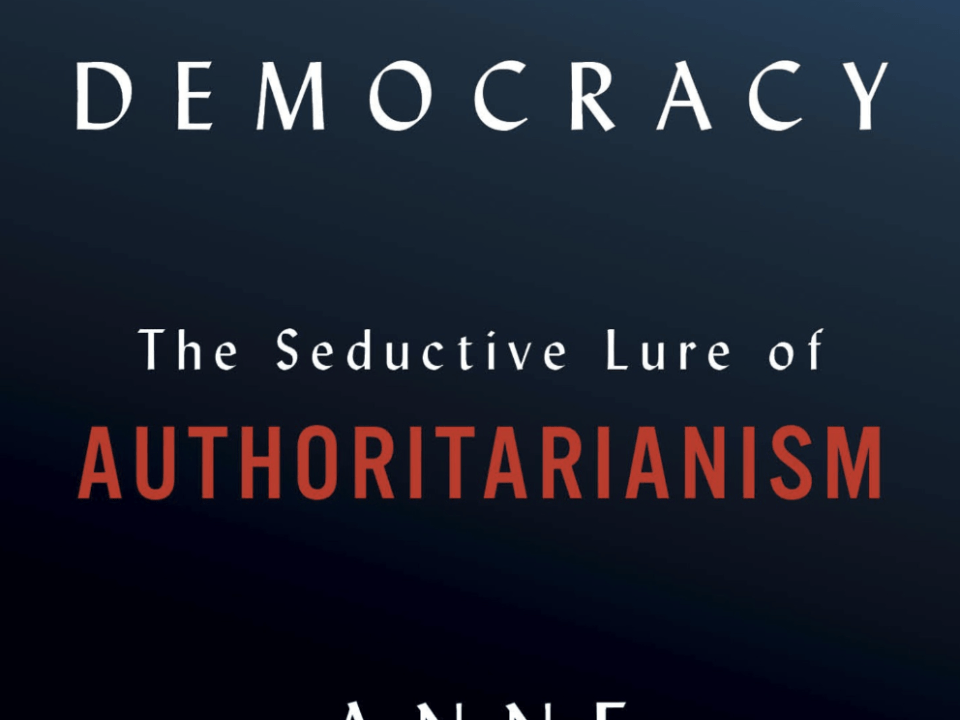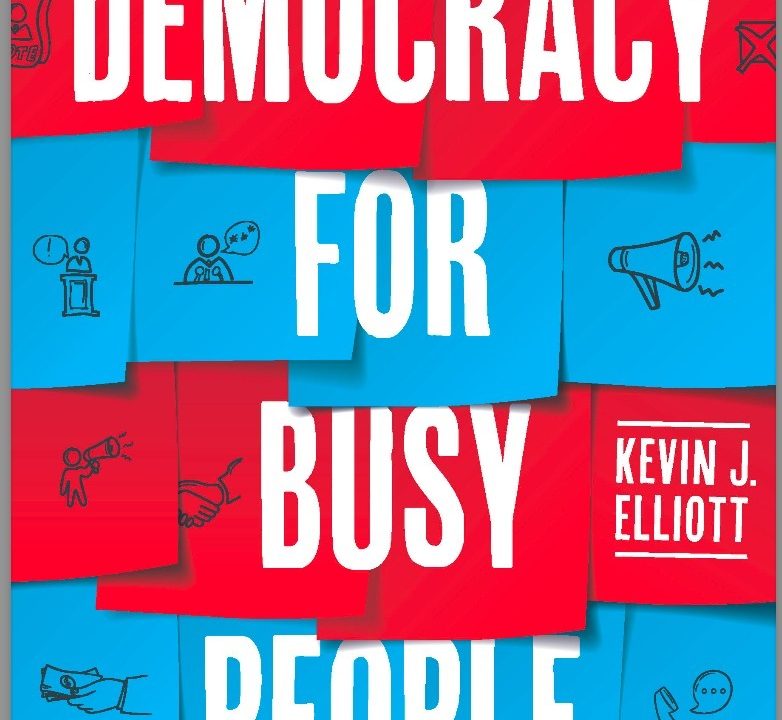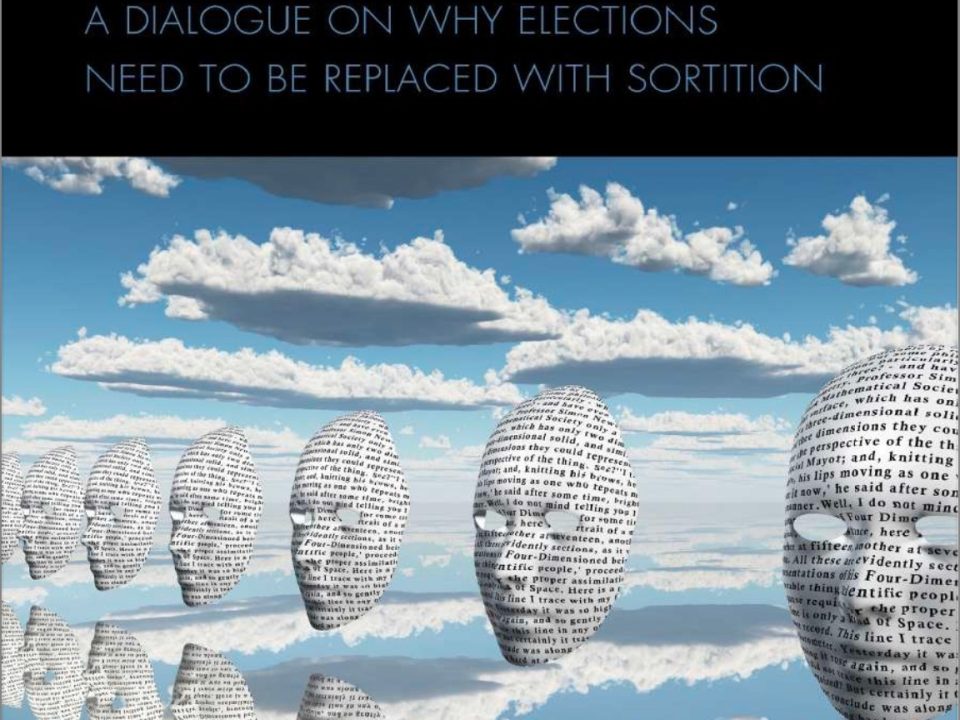Mari Kita Bicara: Merebut Kembali Perbincangan
—Dwi R. Muhtaman—
Lumajang-Surabaya, 12062019
#BincangBuku #29
Sengaja saya menulis pengantar ini. Tidak seperti biasanya, tanpa pengantar. Saya sadar tidak banyak orang yang suka atau berminat membaca tulisan-tulisan panjang, khususnya di ponsel cerdasnya. Kita semua sibuk. Kita ingin membaca sekilas saja. Tulisan yg ringkas.
Meski begitu, saya berharap kawan-kawan bisa menyisihkan waktu sedikit untuk membaca tulisan bincang buku #29 ini. Diperlukan 9 menit untuk membacanya.
Menurut saya ini buku penting sebagai renungan dan refleksi kita bersama, tentu utamanya untuk saya sendiri. Membaca bukunya langsung jauh lebih menarik ketimbang membaca tulisan saya.
Dengan semangat Mari Kita Bicara, bacalah pada waktu yang tepat. Saya tidak ingin ikut membuat Anda malah menghindari berbincang dengan kawan, keluarga atau kolega di sebelah, di depan Anda.
Selamat membaca. Mari Kita Berbincang-bincang.
“We had talk enough, but no conversation”.
—SAMUEL JOHNSON, THE RAMBLER (1752)”
(Sherry Turkle. “Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age.” (2015).
“Everything that deceives may be said to enchant.
—Segala sesuatu yang menipu bisa dikatakan memikat.”
—Plato, “The Republic”
Seberapa sering Anda melihat meja-meja di restoran, kafe, halte, ruang tunggu klinik, dan bandara dan sejumlah fasilitas umum lainnya yang nampak ramai tetapi sepi dari perbincangan? Seberapa sering Anda melihat sepasang muda mudi, orang dewasa, paruh baya, keluarga tua muda, mungkin juga anak-anak yang duduk manis dengan hidangan di meja tetapi masing-masing sibuk dengan piranti cerdas masing-masing, sibuk dengan dawai masing-masing? Seberapa sering Anda hadir dalam sebuah pertemuan, konferensi, diskusi tetapi perhatian melayang ke seberang yang jauh?
Seberapa sering Anda sendiri melakukannya? Anda tidak sendiri. Kita adalah bagian dari lebih 100 juta pengguna smart phone, keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Kita adalah bagian dari lebih lima milyar pengguna ponsel global. Adakah yang perlu kita risaukan? Sherry Turkle membincangkannya untuk kita simak. Dan saya berharap kita bisa mengambil hikmat dari apa yang dipaparkan dengan cermat.
Sebelum menulis buku Reclaiming Conversation ini (2015), Sherry Turkle, juga menuliskan buku yang serupa dari aspek yang berbeda, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (2011). Profesor yang dikenal keahliannya pada Social Studies of Science and Technology pada the Abby Rockefeller Mauzéini di Massachusetts Institute of Technology (MIT) ini mencurahkan sebagian hidupnya untuk mengamati perkembangan teknologi cerdas (robot, smartphone, internet) dan dampaknya terhadap relasi sosial manusia. Sherry Turkle yang lahir pada 18 June 1948 memperoleh sarjana mudanya bidang Social Studies. Kemudian mendapatkan Ph.D. pada bidang Sociology and Personality Psychology di Harvard University. Tidak kurang dari sepuluh buku telah ditulisnya dengan subyek sosial dan teknologi.
Sebagai bagian dari warga pengguna teknologi dan, seperti antropolog mana pun, kita merasa ada sesuatu yang asing di negeri asing ini. Ketika beberapa waktu lalu Turkle tinggal di Paris ia mempelajari bagaimana ide-ide psiko-analitik telah menyebar ke dalam kehidupan sehari-hari di Prancis — bagaimana orang-orang mengambil dan mencoba bahasa baru ini untuk memikirkan eksistensi diri sendiri. Lalu Turkle datang ke MIT karena merasakan sesuatu yang serupa terjadi dengan bahasa komputer. Metafora komputasi, seperti “debugging” dan “pemrograman,” mulai digunakan untuk berpikir tentang politik, pendidikan, kehidupan sosial, dan — yang paling sentral dalam analogi dengan psiko-analisis — tentang diri. Demikian dalam catatannya di Alone Together (2011, h.17).
Turkle menyimak bahwa komputer memprovokasi percakapan menjadi pengetahuan baru. Mungkin, orang bertanya-tanya, pikiran manusia hanyalah mesin yang diprogram, mirip komputer. Mungkin jika pikiran adalah sebuah program, free will adalah ilusi. Bagi Turkle, yang juga pernah menulis buku soal kehidupan dibalik layar komputer (Life on the Screen, 1995) yang paling mengejutkan, percakapan melalui komputer ini terjadi tidak hanya di ruang seminar. Mereka terjadi di sekitar meja dapur dan ruang bermain. Komputer membawa filosofi ke dalam kehidupan sehari-hari; khususnya, mereka telah mengubah anak-anak menjadi filsuf. Di hadapan permainan elektronik mereka yang sederhana — misalnya permainan yang memainkan tic-tac-toe atau menantang mereka dalam mengeja — anak-anak bertanya apakah komputer itu hidup, apakah mereka memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang-orang, dan apa, di zaman mesin pintar ini, yang spesial tentang komputer yang menjadi seseorang. Sebuah fenomena yang kini tak lagi sebuah ilusi. Mesin-mesin serupa manusia diciptakan. Mesin-mesin yang bahkan mampu mengungguli apapun yang dimiliki manusia. Kecuali satu hal: mereka tak memilik jiwa, soul.
Pada masa yang risau, George Orwell melihat dekade mendatang, 1984 dengan terang. Novel 1984 itu, Nineteen Eighty-Four, menggambarkan masyarakat yang membuat orang terus-menerus diawasi oleh pemerintah, mengendalikan pikiran publik, dan kehilangan hak-hak individu. Turkle, sebagaimana sebagian orang lain, mungkin merasa ironis bahwa bukunya sendiri yang pernah ditulis pada 1984, tentang teknologi yang dalam banyak novel fiksi ilmiah memungkinkan dunia dystopian seperti itu, penuh kontras dengan harapan dan optimisme atas maraknya teknologi. Teknologi berkembang dan mempengaruhi segenap kehidupan yang tidak diharapkan. Kita memperlakukan mesin seperti manusia, dan memperlakukan manusia seperti mesin (h. 609). Tetapi mungkin kita tidak bisa mengelak. Turkle memiliki kekhawatiran tentang “memegang kekuatan” dari atau kemampuan berkuasa atas— teknologi baru: beberapa orang menganggap komputer begitu menarik sehingga tidak ingin berpisah sejengkalpun. Yang menjadi renungan bersama kita adalah apakah kehilangan diri sendiri di dunia dalam mesin akan mengalihkan kita dari menghadapi masalah kita yang sebenarnya — baik pribadi maupun secara politik.
Buku Alone Together ini merekam kisah budaya digital selama lima belas tahun terakhir (mulai sekitar tahun 1995-an), dengan fokus pada kaum muda, mereka yang berusia lima hingga awal dua puluhan—”penduduk asli digital” atau “digital natives” yang tumbuh dengan ponsel dan mainan yang meminta cinta dari penggunanya. Dan kita pada hari-hari ini, merasa tidak aman dan nyaman dalam hubungan sosial—kerabat, sahabat, tetangga, teman sekantor dan seterusnya— dan cemas tentang keintiman, dan pada saat yang sama kita mencari teknologi untuk menjaga hubungan sosial dan melindungi diri kita. Kita membungkuk, menunduk ke benda mati dengan perhatian baru, perhatian yang sepenuh hati (h. 23). Tekun ‘berbincang’ dengan “makhluk” digital, termasuk Tamagotchi, Furbies, AIBO, My Real Babies, Kismet, Cog, dan Paros, bayi robot terakhir yang dirancang khusus untuk memberikan penemanan bagi orang tua ini. Belum lagi media sosial yang betul-betul merenggut perhatian, pikiran dan waktu dari para penggunanya jika tidak waspada.
Kita dikendalikan teknologi atau kita mengendalikan teknologi.
Buku Sherry Turkle yang terbaru ini, “Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age,” (2015), merupakan pernyataan keprihatinan yang makin mengental dari perjalanan panjangnya mengamati dampak sosial psiokolgis dari kehadiran teknologi di hadapan kita. Kehadiran yang begitu dekat. Kedekatan yang merasuk. Merasuk yang berpotensi ‘merusak.’
“Mengapa tentang perbincangan?” katanya membuka bukunya.
Berbincang adalah bagian peradaban manusia sejak purba. Nenek moyang kita berbagi cerita dalam lingkungan keluarga kecil, komunitas yang lebih besar hingga dalam lingkungan batas-batas yang lebih luas lagi. Berbincang dengan bercerita merupakan cara manusia untuk membangun kesepakatan-kesepakatan kolektif, aturan-aturan individual dan komunal, serta cara merekam pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bertahun-tahun, berabad-abad. Peradaban dibuat dan dirawat dari riuh rendah perbincangan. Teknologi cerdas ini telah melahirkan silent spring baru.
Kita berbicara sepanjang waktu. Tetapi kini, sejak teknologi ajaib itu hadir kita gemar mengirim pesan teks, menayangkannya dan chatting. Kita bahkan mungkin mulai merasa lebih betah di dunia layar kita. Diantara keluarga dan teman, di antara kolega dan kekasih, kita beralih ke telepon kita alih-alih berbincang satu sama lain. Kini kita lebih suka mengirim pesan atau surat elektronik daripada melakukan pertemuan tatap muka atau bahkan menelpon langsung dan mendengarkan suaranya. Sibuk adalah alasan yang paling sering kita dengar. Kebiasaan baru ini telah membuat kita merasa nyaman dan menjadi new normal. Idiom yang sering kita dengar, telepon cerdas itu telah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
“Kehidupan baru melalui perantara teknologi ini telah membawa kita ke dalam masalah,” demikian keprihatinan Turkle—seolah mewakili banyak orang. Perbincangan tatap muka adalah hal yang paling manusiawi – dan yang memanusiakan – yang kita lakukan. Dari sepenuhnya hadir satu sama lain, kita belajar mendengarkan. Di sinilah kita, manusia yang rumit ini, mengembangkan kapasitas untuk berempati. Di situlah kita mengalami kegembiraan karena didengarkan, dipahami. Dan sebuah percakapan, perbincangan, memajukan refleksi diri. Percakapan dengan diri sendiri juga merupakan landasan perkembangan awal peradaban dan terus berlanjut sepanjang hidup kita.
Namun, betapa sayangnya, hari-hari ini kita menemukan jalan menghindari perbincangan. Dalam buku ini, Turkle—sebagaimana juga yang saya rasakan, mungkin juga Anda— dalam pengamatannya bertahun-tahun, kita bersembunyi dari satu sama lain meskipun tetap terus terhubung satu sama lain. Karena di layar itu, kita tergoda untuk menampilkan diri kita seperti yang kita inginkan. Menciptakan realitas semu. Tentu saja, kinerja dalam profesi kita adalah bagian penting dari pertemuan apa pun, di mana saja. Tetapi keterhubungan online dan pada waktu luang yang tersedia, kita begitu mudah dan sigap untuk menulis, mengedit, dan merevisi sesuatu yang mendestraksi perhatian utama kita.
Dalam pengamatannya yang tajam dan jeli Turkle, menguraikan bahwa seringkali ada momentum sebuah pengalaman saat kita dengan cepat beralih ke telepon ketika bosan. Dan kita sering merasa bosan karena kita menjadi terbiasa dengan segala sesuatu dalam keterhubungan dawai kita, informasi, status, kontak dalam puluhan group, dan hiburan—yang konstan mengalir deras ke dalam dawai. Kita selamanya di tempat lain. Di kelas atau di pertemuan peribadatan atau bisnis, kita memperhatikan apa yang menarik minat kita dan kemudian ketika bosan dan merasa tidak tertarik, kemudian dengan sertamerta melihat pada perangkat genggam atau laptop untuk menemukan sesuatu yang menarik—meski tidak bermanfaat.
Ada yang pernah dengar kata baru dalam kamus yang disebut “phubbing?” Ini adalah sebuah keadaan dimana seseorang melakukan kontak mata dan pada saat yang bersamaan, mengirim pesan dengan gawainya. Banyak orang melakukannya sepanjang waktu dengan mudah.
Itu semua menguapkan kemampuan kita untuk berbincang. Padahal perbincangan yang terbuka dan spontan merangsang kita bermain dengan ide-ide. Membiarkan diri kita hadir sepenuhnya dan rentan—karena gagasan, pendapat atau konten perbincangan kita mungkin akan disanggah, ditantang. Namun ini adalah percakapan di mana empati dan keintiman berkembang dan aksi sosial mendapatkan kekuatan. Perbincangan akan memantik kolaborasi kreatif orang-orang.
Turkle mengingatkan. Kita dibungkam oleh teknologi — tak perlu berbicara. Keheningan bersama ini (istilah yang menjadi judul bukunya: Alone Together) — sering juga terjadi di hadapan anak-anak kita — telah menyebabkan krisis empati yang telah melemahkan kita di rumah, di tempat kerja, dan di depan pergaulan publik. Obatnya hanya satu, paling sederhana, adalah bicaralah, mari kita berbincang-bincang. Demikian nasihat Turkle.
Pada awal 1980-an, Prof Turkle mewawancarai salah satu siswa muda dari Marvin Minsky yang mengatakan kepadanya bahwa, sebagaimana dia melihatnya, pahlawannya, Minsky, salah satu pendiri kecerdasan buatan, artificial intelligent (AI), sedang mencoba membuat komputer yang cukup indah dan saking indahnya sehingga jiwa pun ingin hidup di dalamnya. Gambaran pernyataan itu telah melekat pada Turkle selama lebih dari tiga puluh tahun (h. 597).
Kini anak-anak tumbuh dan begitu akrab dengan hewan peliharaan robot dan boneka digital. Mereka pikir itu adalah hal yang wajar untuk mengobrol dengan ponsel mereka. Inilah yang disebut Prof Turkle sebagai “robotic moment,” bukan karena kebaikan mesin yang dibuat tetapi karena keinginan untuk berteman, berbincang dengan ‘seseorang.’ Ketika kita merasa dalam kesendirian dalam keramaian, ketika kita merasa sendiri secara bersama-sama, kita menginginkan kehadiran teman, dan mainan-mainan robot dihadirkan untuk anak-anak kita. Karena kita sendiri kehilangan kemampuan menjadi teman, menjadi pendamping bagi anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang.
Banyak hal yang kita semua perjuangkan dalam cinta dan pekerjaan dibantu oleh perbincangan. Tanpa perbincangan, penelitian menunjukkan bahwa kita kurang empatik, kurang akrab, kreatif dan puas. Kita tak berarti, lemah. Tetapi untuk generasi yang tumbuh menggunakan ponsel mereka untuk mengirim teks dan pesan, hasil penelitian itu tidak mereka rasakan. Mereka tidak tumbuh dengan banyak pembicaraan tatap muka (h. 28).
Apa yang harus dilakukan?
“Tidaklah cukup untuk meminta anak-anak Anda menyimpan telepon mereka,” kata peneliti yang sering membuka konsultasi dengan sekolah-sekolah yang banyak murid-muridnya menggunakan ponsel ini. “Anda harus memberi teladan dengan menyimpan telepon Anda. Jika anak-anak tidak belajar cara mendengarkan, membela diri sendiri dan bernegosiasi dengan orang lain di kelas atau saat makan malam keluarga, kapan mereka akan belajar memberi dan menerima yang diperlukan untuk sebuah hubungan yang baik atau, dalam hal itu, untuk sebuah partisipasi debat dalam demokrasi?”
Merebut kembali perbincangan dimulai dengan pengakuan bahwa berbicara dan mendengarkan dengan penuh perhatian adalah sebuah keterampilan. Kemampuan berbincang bisa diajarkan. Berlatihlah mulai sekarang. Di rumah Anda, di ruang kelas, di tempat kerja Anda. Merebut kembali perbincangan. Gunakan ponsel dan segala jenis dawai Anda secukupnya dan sepantasnya. Dalam hidup ini ada yang jauh lebih penting daripada menggunakan dawai sepanjang waktu.
Buku ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab membahas fenomena dari kehadiran teknologi komunikasi dan dampak sosial psikologisnya. Membahas soal hilangnya empati, soal kesendirian, hubungan sosial individual, keluarga dan publik, lingkungan kerja dan pendidikan. Dikemas dalam 784 halaman, buku ini berisi fisolofi kehidupan masa kini dan tantangannya dalam belantara kemajuan teknologi. Gelombang kecemasan yang menerpa, berbarengan dengan badai perkembangan teknologi yang nampak tak mudah dielakkan. Semuanya harus dihadapi. Kemampuan manusia menghadapi dan mengadaptasi kehadiran ombak teknologi ini akan menentukan relasi dan kelangsungan hidup spesies Homo sapien ini.
Jika Anda, para pembaca yang budiman, setuju dengan yang kita perbincangkan ini, bergabunglah dengan saya dalam Komunitas Mari Kita Berbincang-bincang. Sebuah upaya untuk merebut kembali kemampuan manusia untuk merawat sebuah peradaban: berbincang.
Dari ruang yang jauh terngiang Charlie Puth melantunkan tembangnya…“We don’t talk anymore, we don’t talk anymore We don’t talk anymore, like we used to do …..” Terasa sebuah ironi. Cinta yang pupus bisa memutus perbincangan. Namun cinta yang tuluspun mampu menghapus perbincangan.