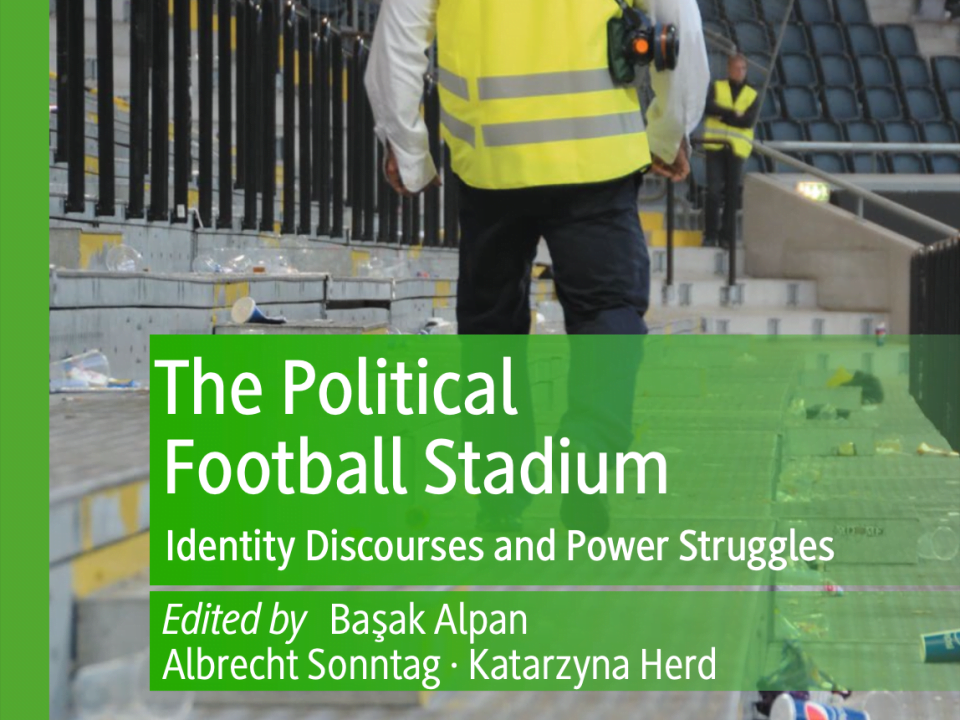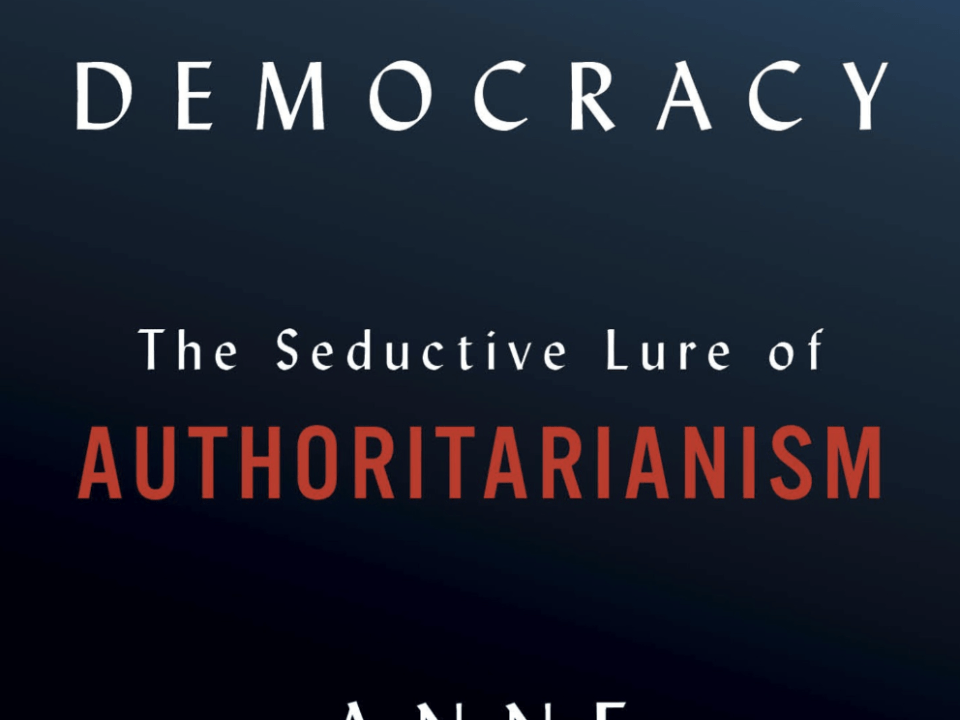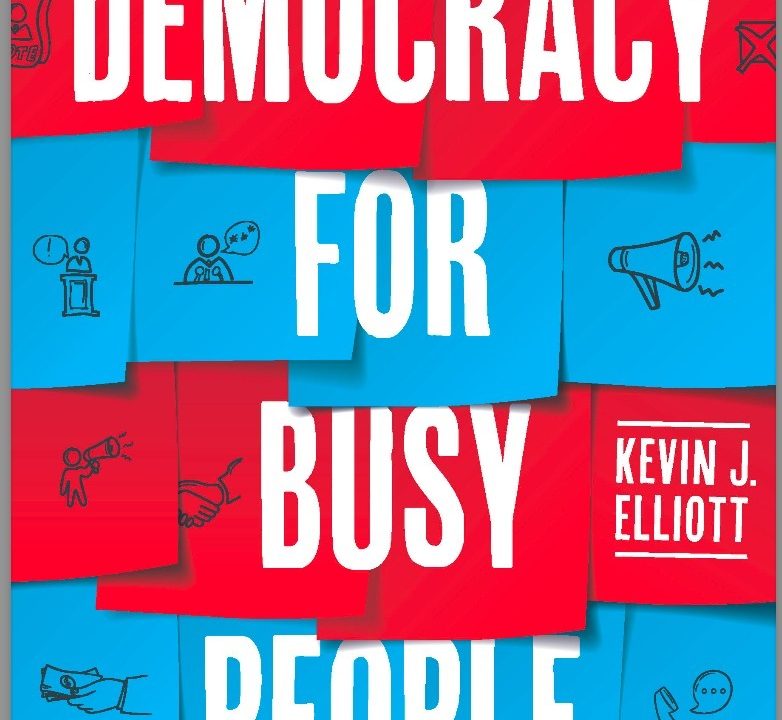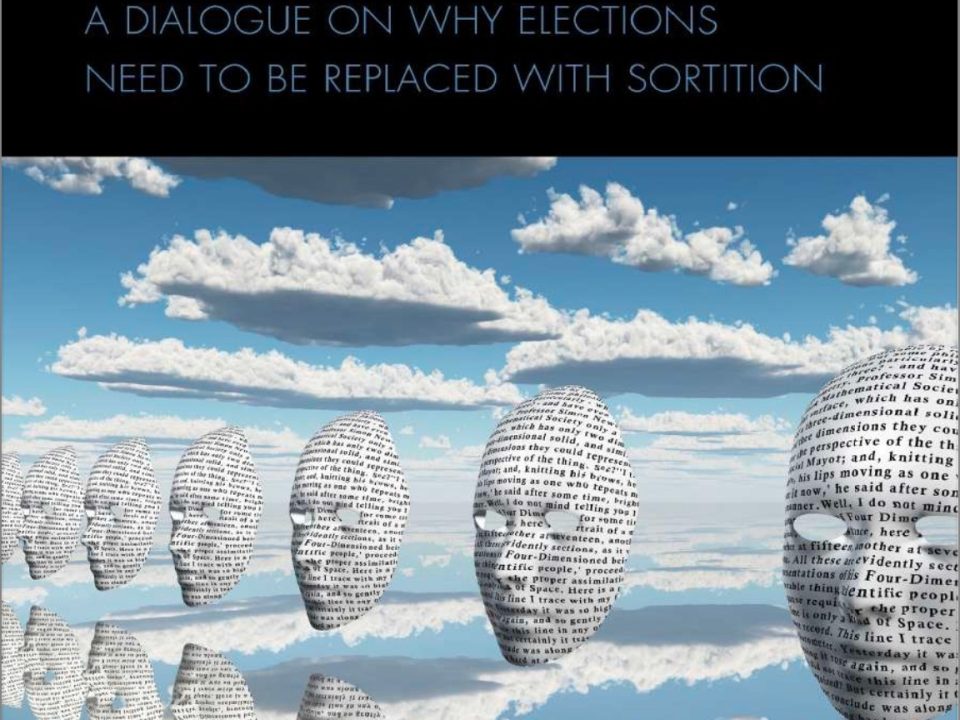Keberpihakan: Pelajaran dari Kaum Pemberontak
—Dwi R. Muhtaman—
Kuningan, 04062019
#BincangBuku #27
“We must take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.”
-ELIE WIESEL-
“Being objective and neutral—simply “professional”—isn’t enough. Good journalism always antagonizes power.”
—Jorge Ramos. “Take a Stand,” (2016)
“The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis”
—Dante Alighieri
Dante sadar bahwa sebagai manusia, apalagi penyair, netralitas adalah celaka. Penyair besar Itali abad Pertengahan Akhir itu tidak ingin hanya menyaksikan sejumlah krisis moralitas di tengah masyarakat tempat dia hidup. Dia menolak tidak melakukan apa-apa untuk menjaga ‘netralitas’ nya sebagai seniman. Tidak. Dante dengan karya sajak panjangnya “the Divine Commedy” yang dianggap mahakarya sastra dunia itu, memilih untuk berpihak. Mereka yang bersikap netral di tengah krisis moral hanya menempatkan pada neraka yang paling kelam.
#BincangBuku #27 kali ini mengupas sebuah buku yang ditulis oleh wartawan kawakan: Jorge Ramos. ““Take a Stand: Lessons from Rebels.” Buku ini diterbitkan oleh Penguin Random House (2016). Buku yang terdiri dari 21 Bagian, Pendahuluan, dan Lampiran yang merupakan naskah pidatonya pada “the Committee to Protect Journalists, New York, November 24, 2014” ini memuat kisah Ramos wawancara dengan tokoh dunia dan para pemberontak atas rezim pemerintah atau kebijakan publik yang buruk. Sikapnya sebagai wartawan yang memegang teguh prinsip keberpihakan sangat jelas dalam kisah-kisah itu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bertubi-tubi, pertanyaan yang mengiris tajam. Pertanyaan yang membuat orang yang diwawancarainya berpikir keras, kadang jengkel. Prinsip jurnalistik yang “obyektif” mendapatkan perspektif baru. Sebab “Being objective and neutral—simply “professional”—isn’t enough. Good journalism always antagonizes power,” tulis Ramos—yang menunjukkan sikap jurnalistiknya. Seperti halnya kaum pemberontak, mereka harus memilih antara diam atau melawan. Dan para pemberontak itu memilih melawan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
“ALL REBELS HAVE something in common: they challenge and they confront. They put aside silence and fear. Their principles are very clear: I won’t shut up. I won’t sit down. I won’t go away. All rebels take a stand. They decide and they act. Neutrality is not an option.”
Dan itu seperti sikap jurnalistik Ramos yang dipilih.
“Saya tidak ingin netral. Perubahan tidak akan terjadi jika pada posisi netral. Kebahagiaan, cinta, dan kesuksesan tidak ditemukan dalam netralitas. Sebaliknya, mereka—yang berpihak itu—adalah bentuk pemberontakan itu sendiri. Menjadi netral tidak cukup, baik dalam jurnalisme atau dalam kehidupan. Kita semua membutuhkan sedikit pemberontakan,” ungkap Ramos dalam bukunya (h. 10). Ramos pertama kali belajar tentang pemberontak dan pemberontakan melalui jurnalisme. “Jurnalisme terbaik adalah memberontak melawan kekuasaan dan penyalahgunaannya.”
Bagi Ramos—yang pernah mewawancarai Desmond Tutu, 2010— bahwa pencapaian yang terbaik dalam jurnalisme — dan dalam kehidupan — ketika para jurnalis itu terlibat, ketika mempertanyakan mereka yang berkuasa, ketika menghadapi politisi yang menyalahgunakan wewenangnya, ketika mereka berbicara dan mengecam ketidakadilan. Apa yang terbaik dari diri para wartawan terungkap ketika mereka berpihak pada para korban — yang paling rentan, mereka yang haknya telah diabaikan atau dilecehkan. Dan jurnalisme terbaik hadir, tentu saja, ketika kita berhenti berpura-pura netral dan mengakui kewajiban moral kita untuk menyuarakan kebenaran kepada mereka yang berkuasa.
Hidup memang tidak selalu seperti air yang murni. Praktik jurnalisme perlu dihadirkan dengan perspektif. Ini berarti bersikap transparan dan mengakui kepada audien — kepada para pembaca — bahwa wartawan pun memiliki pendapat, serta kode etik. Mereka tidak hidup dalam ruang hampa. Mereka membuat keputusan moral sepanjang waktu, apakah itu sebelum wawancara, sebelum penyelidikan, atau sebelum meliput berita. Sangat dapat diterima untuk mengambil sikap, untuk berpihak, menolak bersikap netral. Bahkan hal ini sebenarnya adalah keharusan. Salah satu pewawancara terbaik dalam sejarah berpikir demikian. “Journalists are human beings, after all. They care about their work and they do have opinions. Claiming that they are completely objective suggests that they have no values,” kata Deborah Potter (Handbook of Independent Journalism, 2009).
Ketika Ramos mewawancarai rezim otoriter, demokrasi, pebisnis atau pemberontak; dari Fidel, Chavez, Daniel Ortega hingga Bush, Desmond Tutu, Bill Gates, Richard Branson, Jorge Perez, dan orang-orang yang tak dikenal di luar batas negara mereka tetapi menjadi pemberontak atas rezim tiran, maka sebetulnya Ramos tengah melakukan perlawanan. Dari soal perlawanan politik atau bisnis dan segala kekuasaan yang menindas. Dan mengambil pelajaran dari semua itu. “Kita harus bersikap ketika berhadapan dengan mereka yang berkuasa. Ya, kita harus membuat keputusan etis untuk memihak mereka yang tidak memegang tampuk kekuasaan. “Jika kita harus memutuskan antara menjadi teman atau musuh presiden, gubernur, atau diktator, keputusannya harus mudah: Saya seorang reporter, dan saya di sini bukan untuk menjadi teman Anda,” tulis Ramos dalam nada yang tegas dan berani.
Dan sebagian orang-orang yang ditemui dan ditulis dalam buku ini—politisi, penguasa, aktifis, pengusaha adalah orang-orang yang memilih untuk tidak netral. Mereka mengambil sikap keberpihakan. Dan mereka melanjutkan berdiri dan berjuang untuk apa yang mereka yakini. Yang perlu dicatat pula adalah bahwa keberpihakan tidak berarti menjadi partisan, yang menggunakan profesi wartawan untuk membantu pihak lain berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya.
Ramos menguraikan dalam Take a Stand itu bahwa ada enam arena di mana kita harus selalu memihak: rasisme, diskriminasi, korupsi, kebohongan publik, hak asasi manusia, dan kediktatoran atau rezim otoriter lainnya. Anda tidak dapat tetap netral ketika seseorang menyerang minoritas, ketika seseorang didiskriminasi karena jenis kelamin atau orientasi seksual, ketika politisi atau pemilik bisnis menggunakan posisi mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri, ketika seorang tokoh publik berbohong, ketika hak asasi manusia dilanggar, ketika suatu penguasa melakukan penipuan atau memaksakan kehendaknya pada mayoritas.
Kebebasan pers juga merupakan hak azasi manusia (lihat uraian detil mengenai ini pada Wiebke Lamer: Press Freedom as an International Human Right, 2018). Karena keteguhan dan keberpihakan jurnalis pada dasarnya mempunyai landasan hukum dan landasan etika moral. Ini tak terbantahkan. Jurnalis mempunyai hak untuk memberontak. Karena pemberontakan itu juga bagian dari upaya memajukan peradaban manusia dan kemanusiaan.
“A rebellion is not something that needs to be prevented or suppressed. In fact, rebellions are essential to the advancement of humanism in this world. Rebels are good. Rebels make us better.”
Pada Mei 2008 seorang senator dari Ilinois, Chicago sedang berpikir keras untuk bisa menjadi kandidat dari Kubu Demokrat dalam pertarungan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Satu hal yang bisa membuatnya lolos: merebut suara dari kalangan Latino, kelompok masyarakat Amerika Latin di Amerika yang jumlahnya mencapai 45 juta penduduk atau 15% dari total penduduk Amerika Serikat. Sepuluh juta suara saja akan menentukan Barack Obama, Sang Senator itu, maju mewakili Demokrat. Maka ia mencari cara untuk bisa meraup simpati dan suara Latino. Satu yang dia dilakukan: berjanji. “IT ALL STARTED with a promise,” demikian kata Jorge Ramos, jusnalis veteran yang pada ujung karirnya menjadi the host untuk program televisi “Noticiero Univisión and Al Punto,” dan program berjudul America on the Fusion network. Program itu menarget Latino sebagai pemirsa utama. Obama mendapatkan dukungan Latino. Dan kita tahu Obama kemudian menduduki tampuk Gedung Putih. Maka Ramos secara gigih dan konsisten menagih janji Obama tentang jaminan keadilan pada para imigran Latino. Dimanapun dan pada kesempatan apapun yang tersedia. Dalam setiap wawancara dengan Presiden Obama, Ramos dengan tajam, tanpa basa basi, mencerca dan mengejar Obama dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menagih janjinya: keadilan bagi imigran. Dia tidak segan memotong wawancara jika lawan bicaranya tidak menjawab dengan tegas dan relevan dengan apa yang ditanyakan. Ramos akan berhenti bertanya sampai ada jawaban yang relevan dan tegas.
“It’s true,” kata Ramos yang telah mewawancarai beberapa pemimpin dunia, “I’m not afraid to interrupt someone I’m interviewing. But I only do it when it’s necessary to emphasize a point, to highlight a contradiction, or when an answer doesn’t quite make sense.” Ramos melakukan hal itu pada pada beberapa kesempatan. Pada saat kampanye Mei 2008, April 2009 di Gedung Putih ketika Obama telah menjadi Presiden, pada September 2009 dan Maret 2011. Tema sentral Ramos: menagih janji Obama soal imigran Latino. Pada akhirnya the truth is coming. Ramos mendapatkan jawaban jelas: Presiden gagal memenuhi janjinya. Tetapi Ramos, sebagai jurnalis yang mempunyai sikap keberpihakan terus mengikuti perkembangan janji Presiden Obama. Pada 20 November 2014, setelah masa periode kepresidenan kedua, Obama telah membuat keputusan penting dengan lahirnya Immigration Policy. Kebijakan ini melindungi lima juta imigran Amerika Latin yang tanpa dokumen imigrasi. Kebijakan yang positif itu tidak membuat Ramos puas dan selesai. Ia masih terus mencermati dengan kritis dan menguliti apa yang terjadi setelah itu. Isu imigrasi di Amerika Serikat adalah isu sensitif dan selalu menjadi bahan kampanye, siapapun yang bertarung merebut kursi Gedung Putih. Dan Ramos masih saja bertanya soal itu khususnya deportasi Latino yang masih berlangsung.
Ramos yang ngeyel membuat Obama marah. Dia sangat kesal dengan cara Ramos mengemukakan pertanyaan. Dia merasa telah melakukan sesuatu yang sangat positif bagi komunitas Latino — melindungi jutaan orang dari deportasi — sementara Ramos berfokus pada “masalah yang lebih negatif, seperti posisinya yang berubah dan 2 juta orang yang telah dideportasi.
Sebuah wawancara tidak seharusnya menjadi sekedar corong pameran orang yang diwawancarai. Anda selalu harus mengajukan pertanyaan yang sulit dan tidak nyaman. “You always have to ask the tough, uncomfortable questions,” kata Ramos.
Bagi Jorge Ramos, pelajaran yang bisa dipetik dari prose panjang mengikuti dan wawancara Obama adalah: “No matter who you are, don’t make promises you can’t keep,” begitulah nasihat Ramos. “A promise is a promise,” katanya kepada President Obama pada sebuah forum di Miami September 2012, “and with all due respect, you didn’t keep that promise.” Tanpa basa-basi Ramos menyatakan posisinya, keberpihakannya.
Demikianlah seorang wartawan sejati, Jorge Ramos yang selalu mempunyai sikap jelas dan tegas dalam setiap isu yang menjadi perhatian dan kepentingan publik.
Hal yang sama dilakukan ketika mewawancarai Two Bushes President: yang pertama, George H. W. Bush yang memulai Perang Teluk. Kedua, George W. Bush yang menjadi promotor Perang Afghanistan dan Iraq. Kedua Presiden itu, dalam pandangan Ramos, telah menjadi pemecut kebangkrutan peradaban kemanusian dan defisit keuangan.
Dari interaksinya dengan dua Bush itu pelajaran pertama adalah bahwa wartawan seharusnya bertanya lebih banyak dari kedua Bush itu. Dan terus bertanya lebih banyak lagi. Wartawan seharusnya mempertanyakan segalanya. Wartawan seharusnya tidak membiarkan dia melakukan apa pun dan semua dengan kedok keamanan nasional. Bahkan hari ini, rakyat Amerika menderita konsekuensi dari kebijakan semacam itu. Kehidupan pribadi menjadi area penyelidikan lain untuk keamanan nasional yang kompleks. Tetapi Ramos mengakui banyak jurnalis yang membebek, tunduk dan patuh pada apa yang dilakukan pemerintah. Meninggalkan misi jurnalis untuk mencari kebenaran, apa pun risikonya. Meski ada beberapa jurnalis yang benar-benar menyatakan menentang perang dan melakukannya dengan cara yang sangat jelas dan tidak ambigu. Mereka, tentu saja, adalah minoritas kecil tapi berani.
Setelah Ramos kembali dari perang di Irak, ia melaporkan apa yang telah dilihat. Tidak ada cara untuk membenarkan invasi militer. Dan kritik tajam yang dilontarkan Ramos membuat pemerintah marah. Ramos tidak lagi bisa mewawancarai Presiden Bush. Permintaan wawancara berkali-kali ditolak. Bahkan ia tidak lagi menerima undangan ke acara-acara sosial di Gedung Putih. Ramos memang seorang jurnalis yang langka. Sikap keberpihakannya tidak saja ditunjukkan pada cara dia berpikir, cara mengajukan dan substansi pertanyaan hingga sikap bahasa tubuh ketika melakukan wawancara.
Pada saat wawancara (Juli 1991) dengan Fidel Castro, seorang pemimpin dari Revolusi Kuba yang telah berkuasa beberapa dekade, Ramos menolak dengan menghindari upaya Fidel memeluk dia seperti seorang sahabat. “You can’t accept anything from a dictator. Not even a hug,” tulis Ramos dalam bukunya “Take Stand” (2016, h. 123). Demikian juga ketika dia mewawancarai Hugo Chavez, Presiden Vanezuela (5 Desember 1998). Ia menjaga jarak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang terlihat sikap keberpihakan dan values yang dianutnya. Wawancara ini berakhir hanya beberapa menit saja. Pertanyaan-pertanyaan yang tajam menjengkelkan dia.
“Sometimes, people haven’t fully matured by the time they first come to power,” kata Marisabel Rodríguez, istri kedua Chavez. “And in order to sustain that power, they become totalitarian. Some of the people around him filled his head with the idea of perpetuating his power.”
And that is how totalitarian Chavismo was born.
Ramos wawancara Chávez tahun 1998 dimana dia berjanji untuk lengser masa kepresidenan berakhir. Tetapi dia bohong. Karena menjelang masa kepemimpinan pertamanya usai, ia telah menyiapkan untuk kemenangan pemilu berikutnya. Begitulah seorang diktator melakukannya. “When Venezuelans tried to correct their mistake, it was too late. Chávez was already controlling everything.”
Inti buku Ramos ini sebetulnya ada pada Bagian Pendahuluan. Karena pada bagian itulah Ramos mencurahkan seluruh gagasan idealismenya sebagai wartawan. Menuliskan suka duka kecintaannya pada profesi wartawan dan bersikap jelas dan tegas dalam keberpihakan. Sambil mengutip penulis legendaris Kolumbia dan Nobel laureate, Gabriel García Márquez, ia mengatakan jurnalis adalah pekerjaan terbaik di dunia. Dan harus menggunakan media sebagai senjata untuk kepentingan yang lebih tinggi: social justice, keadilan sosial. Dan sepanjang karir kewartawannanya Ramos telah mempraktekkan keberpihakan untuk keadilan sosial itu. Sebab: “I cannot ignore injustice when I see it—I’m just a reporter asking questions. But if we don’t question authority, how are we ever going to change anything?” Sikapnya tergambar dalam setiap karya jurnalistik yang dilahirkan dan dituangkan dalam buku Take a Stand ini. Dari wawancaranya dengan Barack Obama, Hugo Chavez, Leopoldo Lopez dan Lilian Tintori (pemberontak rezim Chavez), Daniel Ortega, Desmond Tutu, Bill Gates, Subcomandante Marcos (Sang Gerilyawan Bertopeng dari Meksiko), sejumlah para pemberontak yang hidup dalam pengasingan hingga Benjamin Netanyahu dan Hanan Ashrawi.
Bagi Ramos misinya jelas: “Life is too short to bask in the warmth of ambiguity. Dare to explore. Refuse to be neutral.”
Sikap keberpihakan seperti ini adalah impian dan harapan publik yang mempunyai hak atas informasi yang benar dan untuk itu kita semua mengandalkan wartawan sebagai pihak yang dipercaya untuk menyampaikan pesan keadilan dan kebenaran. Wartawan yang berani mengambil posisi yang bebas dan berpihak.
Bagaimana kita di Indonesia? Adakah kita mempunyai seorang Ramos? Dua atau tiga Ramos? Ataukah jurnalisme kita hanya jurnalisme corong dan stempel yang memberi legitimasi apapun yang dikatakan penguasa? Padahal, seperti kata Desmond Tutu, “….. Injustice can’t continue forever.” Masalahnya, jurnalis yang hanya diam dan netral melihat ketidakadilan, bisa jadi pada dasarnya ikut dalam barisan melanggengkan ketidakadilan itu. Mungkin hanya kesabaran yang mampu menghentikan ketidakadilan.
“Patience is a virtue of the warrior,” kata Subcomandante Marcos.