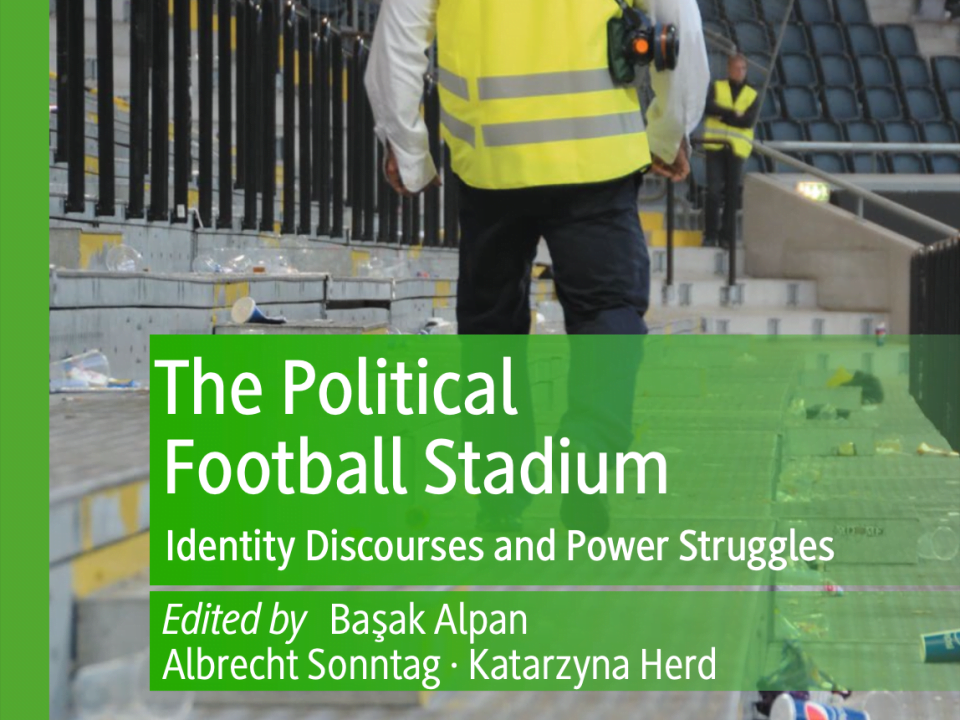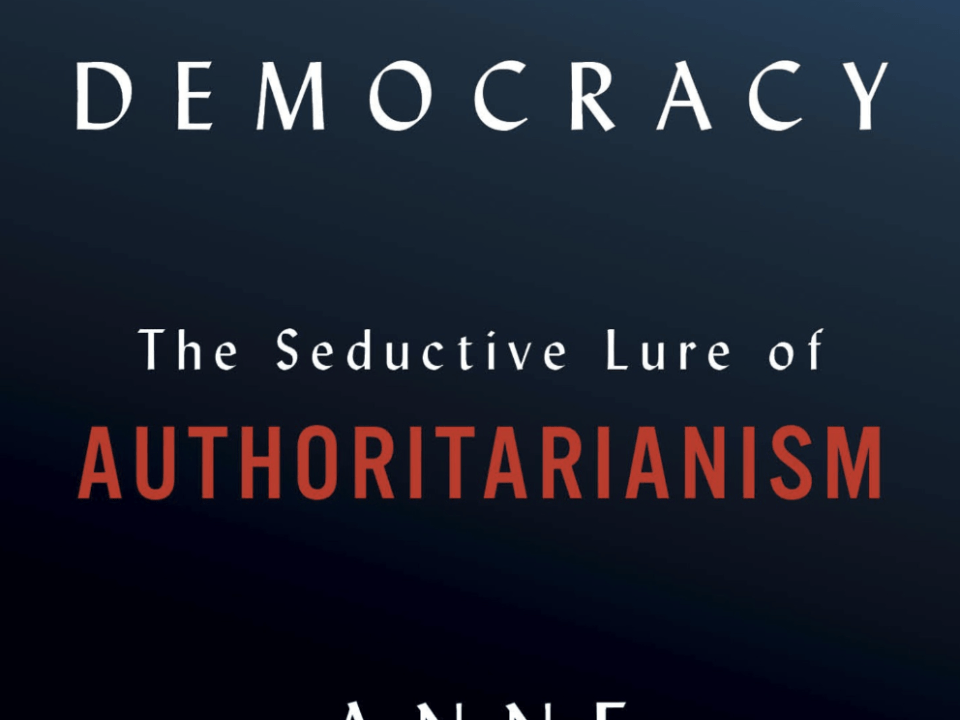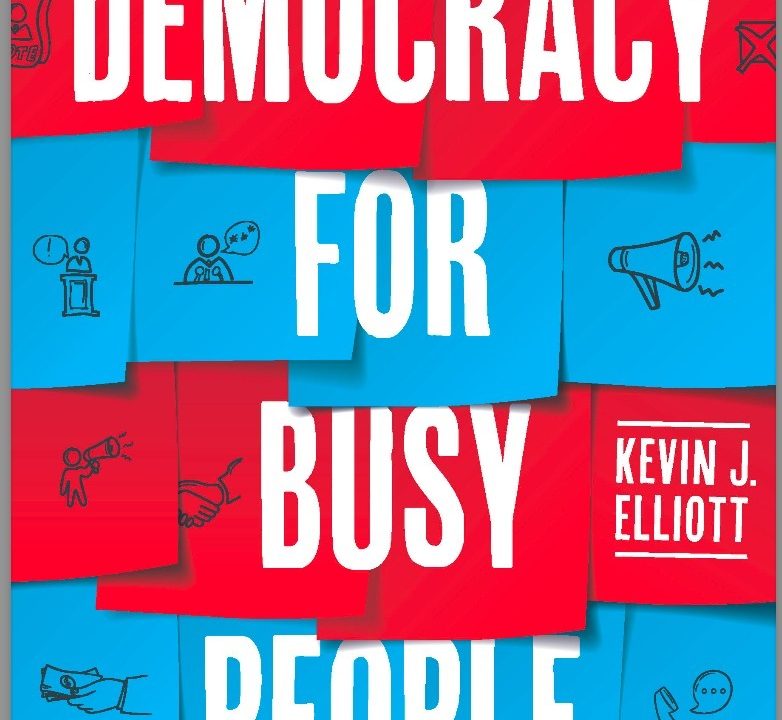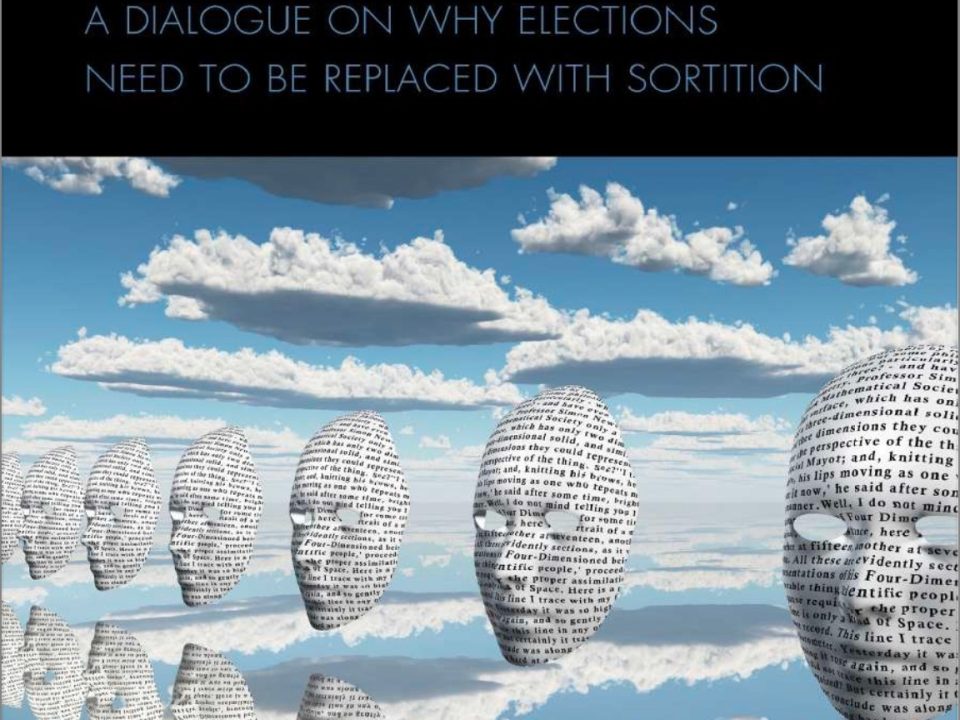Inilah Cara Curangi Pemilu dan Tetap ‘Demokratis’
—Dwi R. Muhtaman—
Cirebon, 31052019
#BincangBuku #25
“…..it is striking that Shakespeare does not envisage the tyrant’s climactic accession to the throne as the direct result of violence. Instead, it is the consequence of an election. To solicit a popular mandate, Richard conducts a political campaign, complete with a fraudulent display of religious piety, the slandering of opponents, and a grossly exaggerated threat to national security.”
(Stephen Greenblatt. “Tyrant: SHAKESPEARE ON POLITICS,” 2018), p. 116.
“The greatest political paradox of our time is this: there are more elections than ever before, and yet the world is becoming less democratic.”
(Nic Cheeseman and Brian Klaas. “How to Rig an Election,” 2018), p. 7.
rig | rɪɡ |
verb (rigs, rigging, rigged) [with object]
manage or conduct (something) fraudulently so as to gain an advantage: the results of the elections had been rigged | (as noun, in combination -rigging): charges of vote-rigging.
noun archaic
a trick or swindle.
Penyelenggaraan pemilihan umum adalah satu pilar penting untuk pengejawantahan sistem demokrasi. Pemilu yang diselenggarakan dengan profesional, jujur, dan adil akan memberi kepercayaan publik pada penetapan dan pilihan sejarah perjalanan bangsa ke depan. Rakyat akan bangga, tegak berdiri melangkah dengan pemimpin pilihan. Sebaliknya pemilu yang buruk akan membuat perjalanan bangsa tersendat. Mungkin bisa tersesat. Karena itu electoral process merupakan salah satu indikator yang dipilih dalam menentukan skor kedewasaan demokrasi suatu negara.
Sejak 2006 The Economist Intelligence Unit (EIU) dari majalah The Economist menerbitkan Democracy Index. Hingga 2018 Democracy Index yang diterbitkan telah masuk pada edisi ke-11. Indeks Demokrasi ini merekam perkembangan demokrasi global pada 167 negara di dunia. Democracy Index dibuat dengan menilai lima kategori yang dianggap sebagai indikator kemajuan demokrasi: electoral process and pluralism; civil liberties; the functioning of government; political participation; and political culture. Berdasarkan skor demokrasi itu kemudian dibuat empat tipe demokrasi atau rezim masing-masing negara: “full democracy”, “flawed democracy”, “hybrid regime” dan “authoritarian regime”.
Dari The Democracy Index 2018 menunjukkan perkembangan global yang beragam. Memang selama tiga tahun berturut-turut skor global demokrasi nampak stabil. Kosta Rika bergerak maju dari demokrasi yang cacat (flawed democracy) ke demokrasi penuh (full democracy); di sisi yang kontras Nikaragua justru terjerumus dari rezim demokrasi cacat ke rezim otoriter. Terdapat 42 negara mengalami penurunan skor total mereka dibandingkan dengan 2017; 48 negara mengalami peningkatan skor total. Tetapi jika dihitung dari persentase populasi dunia, makin sedikit orang yang hidup dalam rezim demokrasi (47,7%, dibandingkan dengan 49,3% pada 2017. Dan sangat sedikit dari persentase itu (4,5%) yang diklasifikasikan sebagai hidup dalam rezim demokrasi penuh. Lebih dari sepertiga populasi dunia hidup di bawah pemerintahan otoriter, dengan porsi besar diwakili oleh Cina.
Dimana Indonesia? Indeks Demokrasi 2010, posisi Indonesia pada peringkat 60 dengan skor total 6,53. Electoral Process and Pluralism mendapatkan skor 6,92 dan Civil Liberty pada angka 7,06. Bandingkan, misalkan dengan Timor-Leste yang menduduki peringkat 42 dengan skor total 7,22; Electoral Process and Pluralism mendapatkan skor 8,67 dan Civil Liberty pada angka 8,24.
Pada Indeks Demokrasi 2014 perubahan signifikan terjadi dalam kehidupan demokrasi. Peringkat Indonesia pun melesat pada posisi 49 dengan skor total 6,95. Electoral Process and Pluralism mendapatkan skor 7,33 dan Civil Liberty pada angka 7,35. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama. Indeks Demokrasi Indonesia kembali terjun bebas pada 2018 dengan menduduki peringkat 65 dengan skor 6,39. Posisi yang lebih buruk dari tahun 2010. Electoral Process and Pluralism mendapatkan skor 6,92 dan Civil Liberty pada angka 5,59. Demokrasi Indonesia menempati peringkat 11 di kawasan regional (Asia dan Australia). Tetangga Indonesia masih lebih baik seperti Timor-Leste (42), Malaysia (52), Filipina (53), Jepang (22), Taiwan (32).
Itulah demokrasi Indonesia.
Kita tidak membahas lebih jauh soal itu. #BincangBuku #25 kali ini justru mengupas sebuah buku cara mencurangi pemilu. Buku ini berjudul: How to Rig An Election ditulis oleh Nicholas Cheeseman and Brian Klaas (2018).
Inilah faktanya. Sebuah paradoks. Saat ini makin banyak diselenggarakan pemilu. Hampir setiap negara di bumi melakukannya. Namun dunia justru menjadi kurang demokratis. Sebagian besar pemerintah melakukan gerakan kampanye pemilihan. Secara retoris berkomitmen mendorong warga negara untuk memberikan suara untuk memilih pemimpin yang akan memerintah mereka. One vote makes a different. Kampanye: satu suara Anda, sangat menentukan nasib bangsa. Slogan ini dilakukan dimana-mana. Namun, di banyak tempat, demikian tulis Nicholas Cheeseman and Brian Klaas, pilihan itu tidak lebih dari sebuah ilusi: kontes ini dicurangi dari awal.
Pada tahun 2013 pemerintah Azerbaijan mengadakan pemilu. Pemerintahan Presiden Ilham Aliyev yang sangat represif berusaha meningkatkan kredibilitas demokrasinya dengan adopsi gaya milenial: meluncurkan aplikasi iPhone yang memungkinkan warga untuk mengikuti kecepatan penghitungan suara ketika penghitungan suara dilakukan. Keren banget. Sang Presiden berkomitmen terhadap transparansi. Dikatakan bahwa teknologi baru akan memungkinkan siapa saja untuk menonton hasilnya secara real time. Apa yang terjadi kemudian? Rakyat Azerbaijan dapat melihat hasilnya di aplikasi bahkan sehari sebelum pemungutan suara dilakukan. Keren.
Dengan kata lain, siapa pun yang memiliki aplikasi itu dapat melihat siapa yang menang, siapa yang kalah, dan seberapa banyak perolehan suara, bahkan sebelum surat suara dicoblos. Ketika para jurnalis bertanya, pemerintah sibuk mencari pembenaran dengan mengklaim bahwa itu adalah hasil dari pemilihan sebelumnya. Faktanya, para kandidat yang terdaftar adalah mereka yang ikut dalam pemungutan suara saat ini. Rezim telah menyorotkan cahaya digital atas penipuan yang dilakukan dalam bayang-bayang kegelapan.
Mungkin Azerbaijan adalah sebuah pengecualian. Namun penelitian mendalam yang dilakukan Nicholas Cheeseman, Professor pada Democracy and International Development, the University of Birmingham, dan rekannya Brian Klaas seorang ilmuwan Politik Amerika dan kolumnis pada the Washington Post dan juga Assistant Professor in Global Politics pada University College London, menunjukkan bahwa di negara-negara otoriter lain di mana para pemimpin mengadakan pemilihan umum meskipun tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kecurangan adalah norma dan bukan pengecualian. Manipulasi pemilu menjadi tradisi dan strategi untuk mempertahankan kekuasaan. Bukan untuk melakukan perubahan.
Pemilu dan proses pencoblosan suara yang berkualitas rendah ini fenomena yang mencengangkan di seluruh dunia. Temuan yang dipaparkan dalam buku ini: pada skala 1 hingga 10, di mana 10 mencerminkan pemilu sempurna dan 1 mencerminkan kemungkinan terburuk, rata-rata pemilu di seluruh dunia hanya mendapat skor 6. Di Asia, Afrika, Eropa pasca-komunis, dan Timur Tengah angkanya lebih dekat ke 5. Selain itu, pada para pemimpin otoriter seluruh jagat raya dari semua pemilihan secara global, hanya sekitar 30 persen pemilihan menghasilkan transfer kekuasaan. Dengan kata lain, petahana menang tujuh kali dari sepuluh kali pemilu—dan angka ini tidak banyak berubah sejak awal 1990-an (p. 9).
Dalam dekade terakhir ini mutu demokrasi global memang sangat memprihatinkan. Sejumlah 71 negara mengalami penurunan hak-hak politik dan kebebasan sipil. “…the worst annual democratic recession in quite some time, but the pattern is consistent: in each of the last twelve years more countries have experienced democratic backsliding rather than democratic consolidation,” (h. 10).
Salah satu faktor penting yang memperburuk mutu demokrasi adalah pemilu yang curang. Para penguasa yang diktator, lalim, dan demokrat palsu telah menemukan cara aman untuk mencurangi pemilu, lolos begitu saja dan mungkin masih dianggap demokratis pada negara-negara yang masuk kategori demokrasi (palsu). Bagi para penulis buku yang telah menulis buku-buku soal demokrasi ini tergambar jelas bahwa pada banyak negara di dunia “…the art of retaining power has become the art of electoral manipulation.” Dalam buku ini penulis menggunakan istilah rig, rigging—curang, mencurangi.
Ringging dibedakan dari misalnya penggunaan janji-janji pemilu untuk menghasilkan dukungan. Sementara janji kampanye dapat memberi keuntungan pada petahana, yang biasanya memiliki akses jauh lebih besar ke sumber daya daripada partai-partai oposisi, mereka juga merupakan fitur umum dan sah dari politik demokrasi. Penulis juga membedakan kecurangan dari keunggulan yang biasa dimiliki petahana lainnya, seperti kemampuan partai yang berkuasa untuk mengatur waktu program-program pemerintah tertentu sehingga program itu bisa diluncurkan selama masa kampanye pemilu, termasuk juga fakta bahwa petahana cenderung menerima lebih banyak liputan media daripada pemimpin oposisi. Intinya adalah ini: kecurangan merupakan cara praktek politik yang tidak sah dan tidak demokratis karena menguntungkan satu partai atau kandidat dengan mengorbankan yang lain. Menurut Cheeseman and Klaas, keputusan untuk curang atau tidak, paling baik dipahami sebagai perhitungan cost–benefit daripada hanya produk sampingan kepemimpinan preman yang tak terelakkan.
Cheeseman and Klaas mengidentifikasi enam jenis manipulasi pemilu. Yang pertama apa yang disebut gerrymandering (Bab 1) yaitu upaya mendistorsi ukuran batas-batas wilayah pemilu (atau kalau di Indonesia wilayah-wilayah Tempat Pemungutan Suara) sehingga partai-partai petahana mendapatkan kesempatan awal yang lebih baik dalam pemilu. Dengan cara ini, menurut penulis, partai-partai oposisi dapat berakhir dengan lebih sedikit kursi meskipun mereka menerima lebih banyak suara. Yang kedua adalah pembelian suara (vote buying, Bab 2), yang melibatkan pembelian langsung dukungan warga melalui hadiah tunai atau, seperti yang sering disebut di Afrika, ‘something small’. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mengamankan suara yang tidak dapat diperoleh. Tetapi ini tentu strategi yang mahal dan – dan belum tentu mencoblos pemberi uang.
Kaum Otokrat juga dapat menggunakan jenis kecurangan ketiga, yakni cara-cara represif untuk mencegah kandidat lain berkampanye (Bab 3). Menolak akses mereka ke media. Membatasi akses ke lokasi kampanye, dan mengintimidasi pendukung saingan agar tidak pergi ke tempat pencoblosan. Jika strategi ini tidak berhasil, demokrat palsu (counterfeit democrats) memiliki dua opsi utama yang terbuka bagi mereka: meretas pemilu secara digital (Bab 4) untuk mengubah persepsi dan, dalam beberapa kasus, untuk menulis ulang hasilnya; dan mengisi kotak suara (Bab 5) – menambahkan suara palsu atau memfasilitasi pemilihan ganda untuk meningkatkan kinerja kandidat. Untuk melepaskan diri dari taktik semacam itu, mereka mungkin juga perlu bermain dengan komunitas internasional (Bab 6), menipu para donor agar melegitimasi pemilu yang berkualitas buruk. Karena tiga opsi terakhir dapat dengan mudah menjadi bumerang, otokrat yang paling efektif tidak membiarkan kecurangan dalam pemilihan hingga menit terakhir. Inilah enam cara pemerintahan otoriter dan juga demokrasi palsu mencurangi pemilu untuk mempertahankan kekuasaannya. Kecurangan bisa dilakukan bahkan jauh hari sebelum pemilu digelar. Dan satu lagi, seperti kata Shakespeare yang saya kutip di atas: hembuskan isu keamanan nasional (national security), kaum oposisi mengancam keamanan nasional….
Dalam buku setebal 508 halaman ini Cheeseman and Klaas memang membatasi analisisnya pada sistem pemerintahan yang disebutnya demokrasi palsu (counterfeit democracy, sebagai istilah umum untuk competitive authoritarian). Penulis buku yang telah menulis beberapa buku tentang demokrasi ini juga mendeskripsikan empat tipe dasar sistem politik, yang ada di sepanjang spektrum demokrasi. Yang pertama adalah rezim otoriter murni (pure authoritarian) di mana tidak ada pemilu sama sekali, seperti di Cina, Eritrea dan Arab Saudi. Yang kedua adalah negara-negara otoriter dominan (dominant authoritarian) di mana pemilu diadakan dalam konteks hak-hak politik dan kebebasan sipil yang sangat terbatas, sedemikian rupa sehingga oposisi hampir tidak mampu bersaing, misalnya Rusia, Rwanda dan Uzbekistan. Kategori ketiga adalah negara-negara otoriter yang kompetitif (competitive authoritarian), di mana pemilu dilangsungkan dengan cukup pedas tetapi oposisi tetap bersaing dengan satu tangan terikat di belakangnya. Ini adalah jenis sistem politik yang berlaku di negara-negara seperti Kenya dan Ukraina. Akhirnya, ada negara-negara demokratis elektoral, di mana pemilu cenderung cukup bebas dan adil, meskipun mungkin ada beberapa perbedaan, seperti di Amerika Serikat dan Inggris Raya.
Lantas bagaimana mencegah kecurangan terjadi? Cheeseman and Klaas menyarankan tiga hal: Reforming election monitoring, Digitizing elections, Empowering the opposition and civil society.
“We know how to rig an election; we also know how to make it more difficult. If we care about democracy, we must act now. There is no time to waste,” pungkas Cheeseman and Klaas menutup bukunya yang penuh harapan untuk memberi kontribusi pada kehidupan politik demokrasi yang lebih baik.
Bagaimana dengan pemilu di Indonesia?