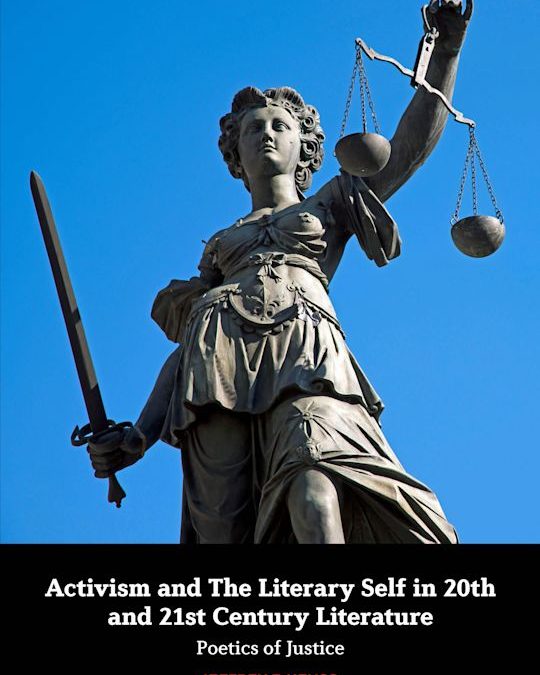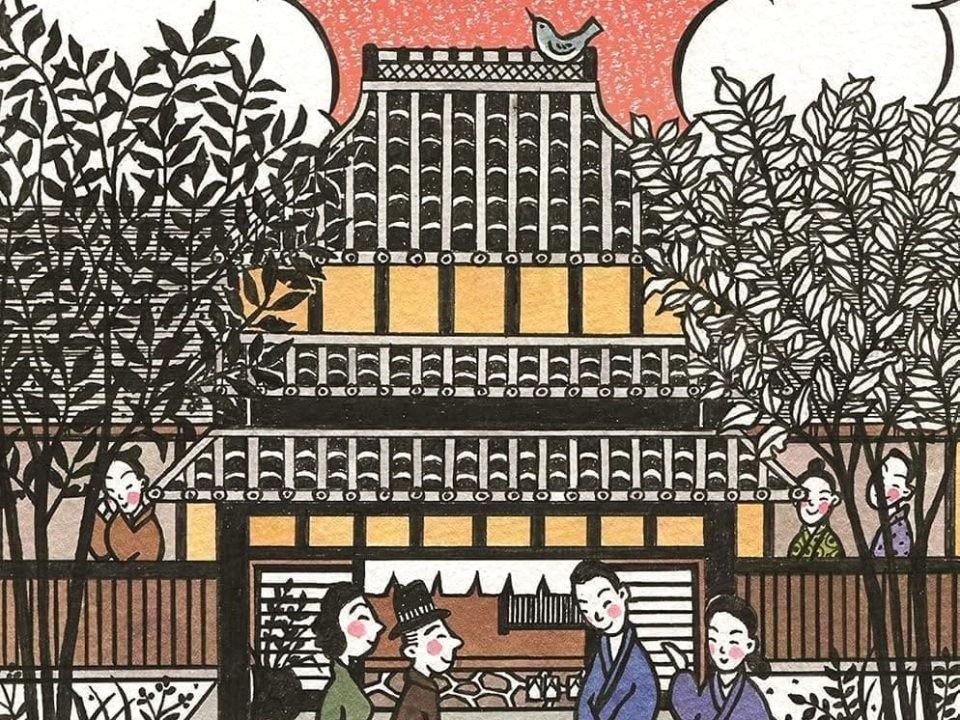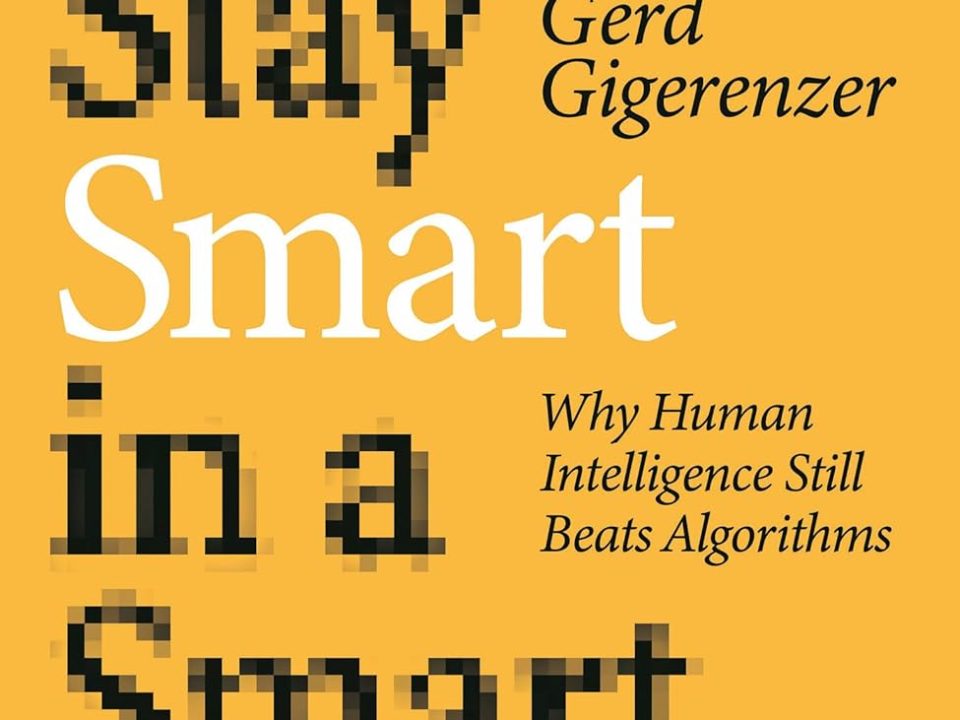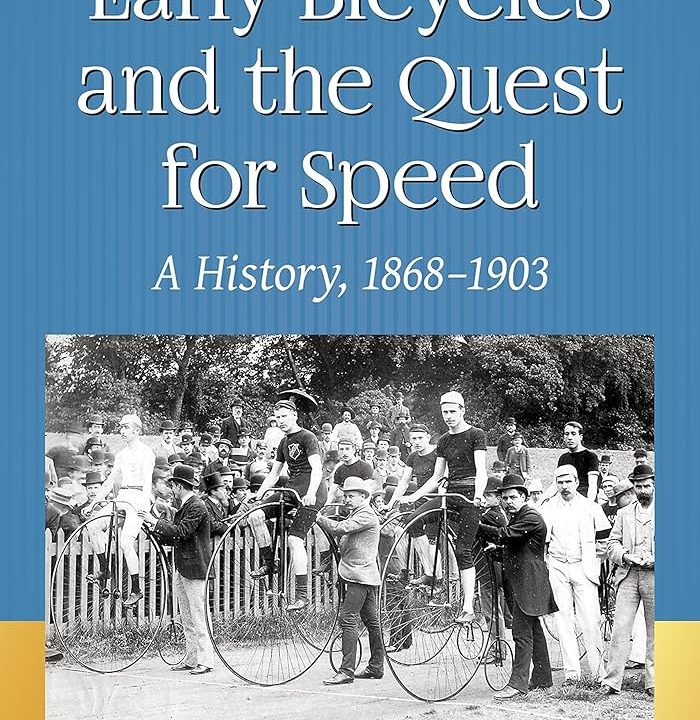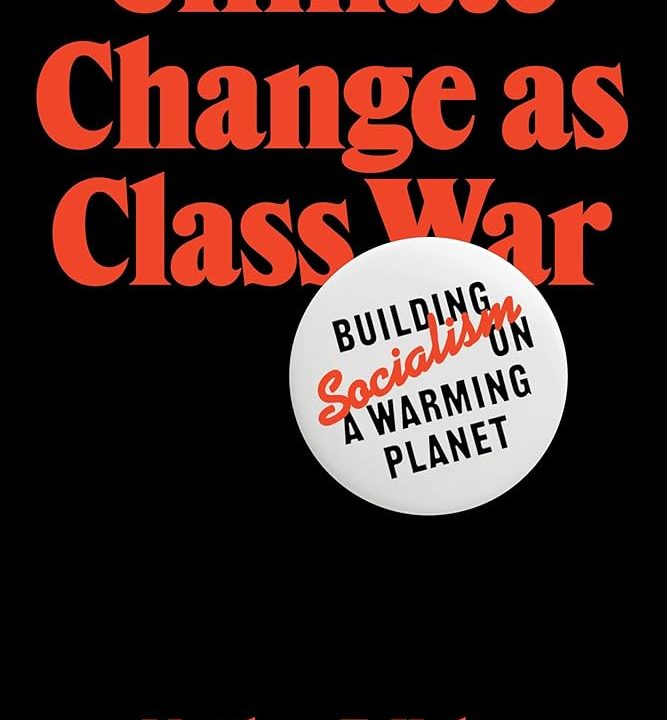# 05 Rubarubu i
Aktifisme dan Sastra, Senjata yang Ditakuti
Banyak cara untuk melakukan perlawanan. Sejuta cara untuk menyampaikan pesan. Bagi yang tidak mampu memanggul senjata, kata-kata adalah alat yang juga ditakuti oleh tirani atau penjajah. “Kata adalah Senjata,” seru Subcomandante Marcos pada pidatonya, 12 Oktober 1965. Ia menekankan pentingnya bahasa dan narasi dalam perjuangan. Menurutnya, kata-kata dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam perlawanan dan perubahan sosial, sama efektifnya dengan senjata fisik. Marcos sering mengaitkan kekuatan kata-kata dengan kemampuan untuk membangkitkan kesadaran, membentuk opini publik, dan menginspirasi tindakan kolektif. Pidato Marcos ini mencerminkan filosofi Zapatista yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga pada penyebaran ide dan pengaruh budaya sebagai strategi untuk mencapai tujuan mereka.
Subcomandante Marcos adalah seorang tokoh kunci dalam gerakan Zapatista di Meksiko, sebuah gerakan sosial yang menuntut hak-hak dan keadilan bagi masyarakat adat dan petani di negara bagian Chiapas. Ia dikenal sebagai juru bicara Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sebuah organisasi pemberontak yang menarik perhatian internasional setelah melakukan pemberontakan bersenjata pada 1 Januari 1994, bertepatan dengan berlakunya Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). Subcomandante Marcos memiliki latar belakang intelektual yang kuat dan sering menggunakan pidato, tulisan, dan komunikasi dengan media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan gerakan Zapatista. Gaya komunikasinya yang penuh dengan metafora, simbolisme, dan kritik sosial membuatnya menjadi figur ikonik yang melampaui batas-batas geografi dan politik.
Secara lebih luas, ungkapan ini menunjukkan keyakinan bahwa perjuangan untuk keadilan tidak hanya dilakukan di medan perang, tetapi juga di ranah intelektual dan moral, di mana ide-ide dan kata-kata dapat menantang status quo dan menginspirasi perubahan (Our Word Is Our Weapon: Selected Writings of Subcomandante Marcos).
Buku “Activism and The Literary Self in 20th and 21st Century Literature: Poetics of Justice” karya Jeffrey F. Keuss membahas hubungan simbiosis antara praktik aktivisme dan pembentukan diri dalam sastra modern. Keuss berargumen bahwa sastra bukan sekadar cermin realitas, melainkan ruang dinamis tempat “diri” yang terlibat politik dibentuk dan diartikulasikan. Melalui konsep “poetics of justice”, buku ini menunjukkan bagaimana bahasa dan narasi menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. “The literary self is not born in isolation but is forged in the fires of social engagement,” tulis Keuss. Pemikir Muslim Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya menyatakan, “Keadilan adalah fondasi peradaban,” dan Keuss menegaskan bahwa sastra merupakan pilar penting tempat fondasi keadilan itu dibangun dan diuji dalam kesadaran kolektif. Keuss dalam karya ini mempertemukan transformatif antara sastra dan aktivisme.
Keuss membongkar strategi sastra yang digunakan penulis abad ke-20 dan ke-21 untuk melakukan intervensi politik. Keuss menunjukkan bagaimana aktivisme sastra tidak selalu tampak eksplisit, tetapi sering tersembunyi dalam struktur naratif, metafora, dan permainan bahasa yang menantang konvensi. Bentuk sastra yang eksperimental justru menjadi senjata efektif untuk mengganggu struktur kekuasaan yang mapan. “To write a poem after a genocide is not an act of escapism, but a radical commitment to remembering,” tegas Keuss. Penyair Audre Lorde pernah menyatakan, “For the master’s tools will never dismantle the master’s house,” dan Keuss mengembangkan ini dengan menunjukkan bagaimana sastra menciptakan ‘perkakas’ bahasanya sendiri untuk membongkar ketidakadilan dari dalam. Ia melakukan dekonstruksi kekuasaan melalui bentuk sastra. Sastra yang menjadi senjata yang ditakuti.
Dalam konteks dunia yang dibanjiri informasi dangkal, misinformasi dan kelelahan informasi, Keuss menegaskan relevansi kritikus sastra kini lebih dari sebelumnya. Ia berpendapat bahwa kedalaman, nuansa, dan kapasitas empati yang ditawarkan sastra merupakan penangkal vital terhadap penyederha-naan isu-isu kompleks. Membaca dan menulis menjadi tindakan politik yang memulihkan dimensi kemanusiaan dalam debat publik. “In an age of the soundbite, the novel, the poem, the play, are acts of deep resistance,” paparnya. Filsuf Søren Kierkegaard mengamati, “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards,” dan Keuss melihat sastra sebagai medium yang memungkinkan pemahaman reflektif ini sekaligus memberikan peta moral untuk masa depan. Menggunakan sastra sebagai penangkal simplifikasi di era digital.
Activism and The Literary Self memproyeksikan bahwa masa depan aktivisme akan semakin terkait dengan pertarungan narasi dan konstruksi diri. Perjuangan untuk keadilan adalah perjuangan untuk hak bercerita—siapa yang ceritanya didengar dan dianggap sahih. Buku ini mengeksplorasi bagaimana sastra membuka ruang bagi suara-suara terpinggirkan untuk menuliskan diri mereka ke dalam sejarah. “The future of activism is not merely in the streets, but in the stories we tell,” tegas Keuss. Dalam tradisi Islam, perintah pertama “Iqra!” (Bacalah!) bukan hanya tentang literasi, tetapi engagement kritis dengan tanda-tanda di alam. Aktivisme sastra, dalam pembacaan Keuss, adalah pemenuhan perintah ini—pembacaan kritis terhadap dunia yang disusun ulang menjadi narasi penuntut keadilan. Inilah masa depan aktivisme dalam ekologi naratif.
Buku ini mendalami bagaimana sastra menjadi medan pertarungan representasi di mana identitas dan memori kolektif diperebutkan. Keuss menganalisis karya-karya yang menantang narasi dominan dan membuka kemungkinan bagi pembentukan subjektivitas yang otonom. Proses membaca dan menulis menjadi lokus di mana individu dapat merekonstruksi diri mereka melawan determinisme sosial. “Every act of reading is potentially an act of resistance against the tyranny of a single story,” tulis Keuss. Pemikir Muslim kontemporer Khaled Abou El Fadl menegaskan, “Ketika keadilan menjadi kata yang tak bermakna, maka tugas sastrawanlah yang mengisinya kembali dengan makna,” menekankan peran vital sastrawan dalam merebut definisi keadilan dari kekuasaan yang korup. Sastra sebagai ruang kontestasi dan pembentukan diri.
Keuss mengembangkan konsep estetika yang tidak terpisah dari etika, melainkan justru menjadi landasannya. Buku ini menunjukkan bagaimana keindahan sastra tidak bertentangan dengan komitmen politik, tetapi justru dapat memperkuatnya melalui daya persuasif yang khas. Estetika menjadi medium transformasi sosial yang menghubungkan yang personal dengan yang politis. “Beauty in literature is not an escape from injustice, but a different way of engaging with it,” jelas Keuss. Penyair Indonesia Sapardi Djoko Damono dalam puisinya menulis, “kita adalah derai kata-kata yang tak sempat mengucapkan diri,” dan Keuss menegaskan bahwa sastra justru memberi ruang bagi “pengucapan diri” yang tertunda itu, terutama bagi mereka yang dibungkam. Estetika sebagai etika yang memberdayakan.
Catatan Akhir
Buku ini menawarkan visi pendidikan sastra yang membekali pembaca dengan kemampuan membaca kritis terhadap teks dan konteks sosialnya. Keuss berargumen bahwa literasi sastra yang baik merupakan prasyarat untuk partisipasi demokratis yang bermakna. Melalui analisis teks-teks sastra, pembaca dilatih untuk mengenali mekanisme kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat. “Teaching literature is teaching justice,” simpul Keuss. Filosof Prancis Jacques Rancière menyatakan, “Emansipasi dimulai ketika kita mempertanyakan pembagian antara yang bisa dan yang tidak bisa berbicara,” dan Keuss menunjukkan bagaimana sastra secara radikal mempertanyakan pembagian ini. Pendidikan sastra untuk keadilan sosial.
Sastra adalah media dan juga alat untuk merawat warisan berkelanjutan sekaligus panggilan untuk bertindak. Pada akhirnya, “Activism and The Literary Self” adalah panggilan mendesak untuk menyadari kekuatan transformatif praktik sastra. Keuss menyimpulkan bahwa membentuk dunia yang lebih adil memerlukan komitmen untuk membentuk kembali cerita-cerita yang kita hidupi bersama. Setiap keterlibatan dengan karya sastra yang menantang ketidakadilan adalah partisipasi dalam “poetics of justice”. “Words are the seeds of change, and literature is the soil where they grow,”tutup Keuss. Seperti kata penyair Persia Jalaluddin Rumi, “Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder,” menegaskan bahwa kata-kata yang dirangkai dalam puisi dan prosa adalah hujan yang menyuburkan benih keadilan—sebuah aktivisme berkelanjutan yang membangun masa depan dari dalam diri manusia.
Bogor, 31 Oktober 2025.
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi:
Keuss, J. F. (2025). Activism and the literary self in 20th and 21st century literature: Poetics of justice. Bloomsbury Academic.
i Ruang Baca Ruang Buku (Rubarubu) adalah sebuah prakarsa yang mempunyai misi untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan lewat bacaan dan buku. Merangsang para pembaca Rubarubu untuk membaca lebih dalam pada buku asal yang diringkas, mendorong percakapan untuk membincangkan buku-buku yang telah diringkas dan juga meningkatkan gairah untuk menulis pengalaman baca dan berbagi dengan khalayak. Prakarsa Rubarubu adalah bagian dari prakarsa ReADD (Remark Asia Dialogue and Documentation), sebuah program untuk menjembatani praktik dan gagasan — agar pengalaman lapangan dapat berubah menjadi narasi yang inspiratif, dokumentasi yang bermakna, dan percakapan yang menggerakkan.
ReADD mendukung penulisan, penerbitan, dan dialog pengetahuan agar Remark Asia memperluas perannya bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai rumah gagasan tentang masa depan berkelanjutan.
ReADD (Remark Asia Dialogue and Documentation) lahir dari kesadaran bahwa keberlanjutan tidak hanya dibangun melalui proyek dan kebijakan, tetapi juga melalui gagasan, refleksi, dan narasi yang menumbuhkan kesadaran kolektif. Buku, diskusi, dan dokumentasi menjadi medium untuk menyemai dan menyerbuk silang pengetahuan, membangun imajinasi masa depan, serta memperkuat hubungan antara manusia, budaya, dan bumi.
Dengan kemajuan teknologi kita juga bisa memanfaatkan kecanggihannya untuk meringkas buku-buku yang ingin kita baca singkat. Rubarubu memanfaatkan teknologi intelegensia buatan untuk meringkas dan mengupas buku-buku dan dijadikan bacaan ringkas. Penyuntingan tetap dilakukan dengan intelegensia asli untuk memastikan akurasinya dan kenyamanan membaca. Karena itu tetap ada disclaimer bahwa setiap artikel Rubarubu tidak menjamin 100% akurat berasal dari seluruhnya buku yang dikupas. Penulisan artikel dilakukan dengan sejumlah improvisasi, olahan dari sumber lain dan pandangan/interpretasi pribadi penulis. Pembaca disarankan tetap membaca sumber aslinya untuk mendapatkan pengalaman dan jaminan akurasi langsung.