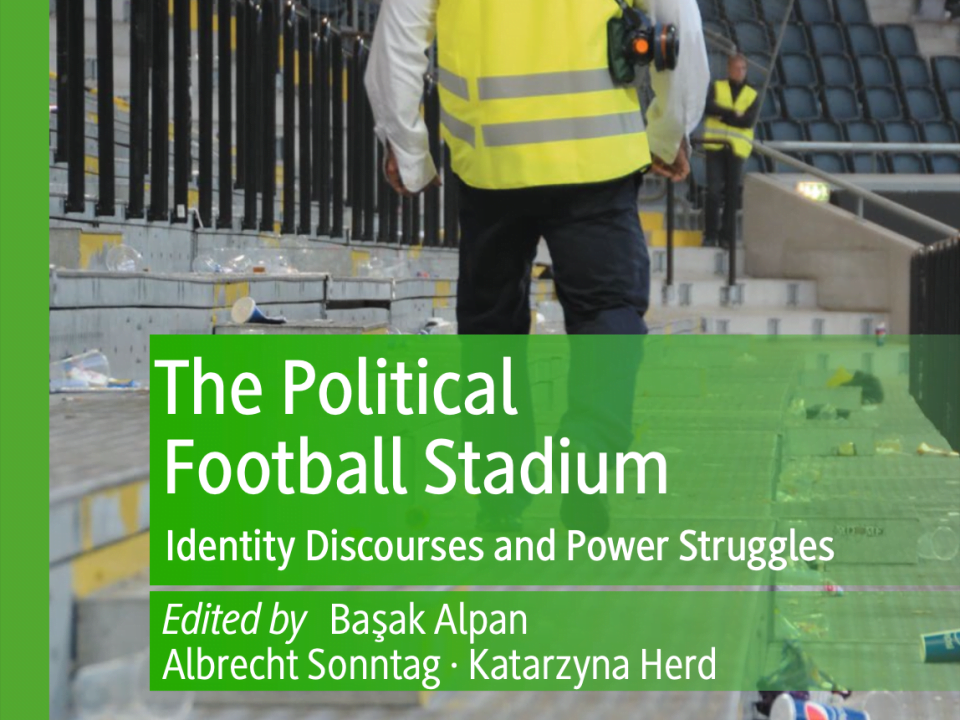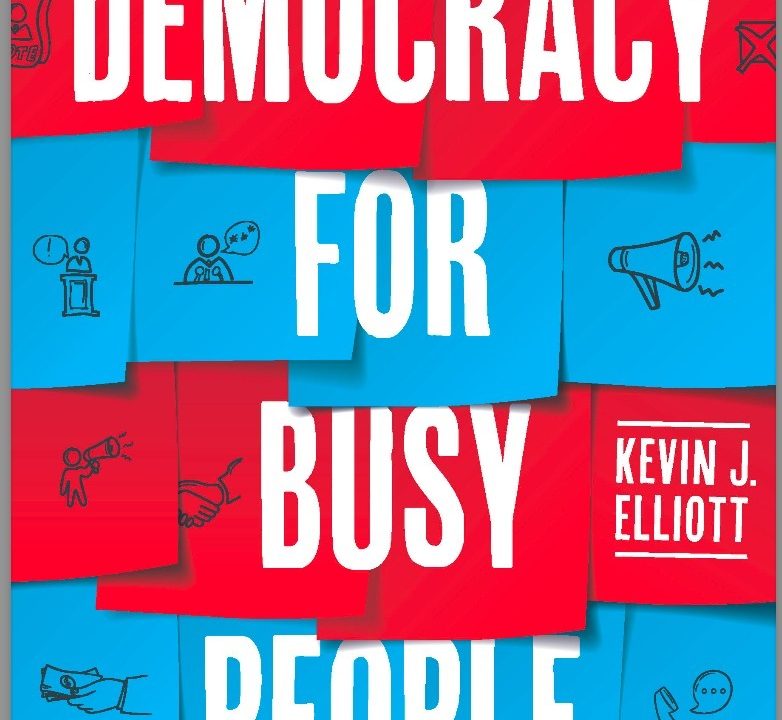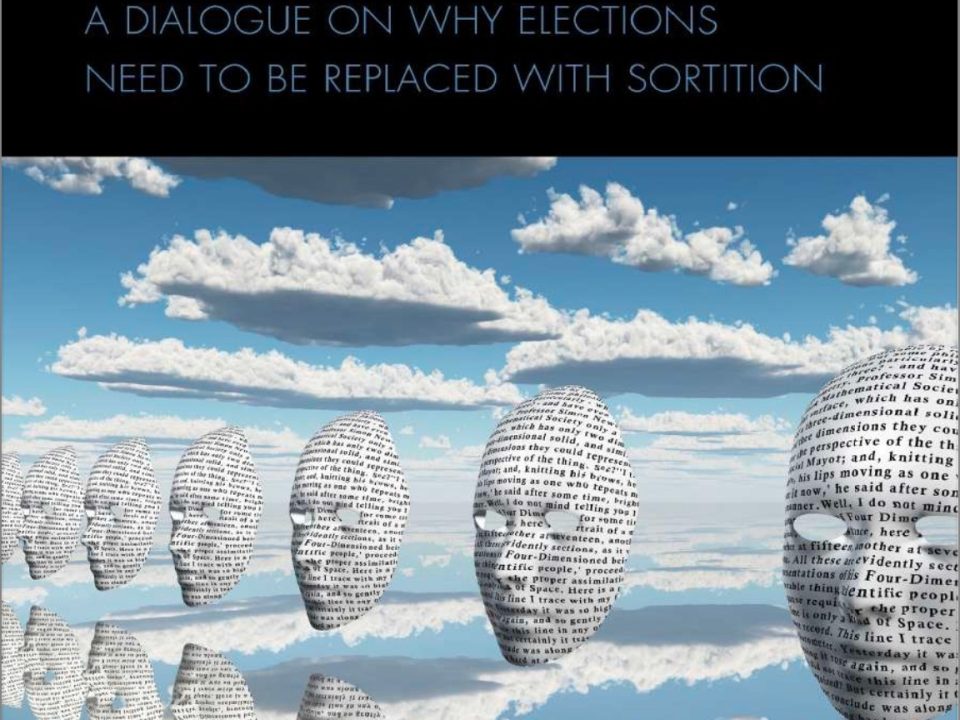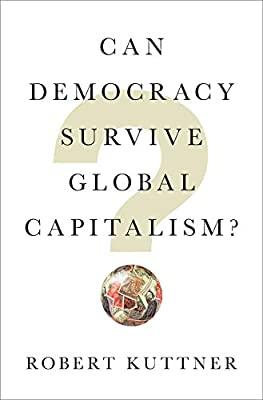Mengapa Intelektual Mendukung Diktator?
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor-Balikpapan-Cirebon, 26.06.2023
#BincangBuku #50
“This form of soft dictatorship does not
require mass violence to stay in power.
Instead, it relies upon a cadre of elites
to run the bureaucracy, the state media,
the courts, and, in some places,
state companies.”
Twilight of Democracy
Anne Applebaum, 2020.
“Our age is indeed the age of the intellectual organization
of political hatreds.
It will be one of its chief claims to notice
in the moral history of humanity.
—Julien Benda, La trahison des clercs, 1927”
dikutip dari Twilight of Democracy,
Anne Applebaum
“Political regimes come and go,” he wrote,
but “bad habits remain”—and the worst habit is nihilism,
“a disease of the spirit which can be diagnosed only
by those who are immune from it or have been cured of it, ….’ ”
Twilight of Democracy
Anne Applebaum
Demokrasi nampaknya tak ubahnya seperti sebuah memoar politik–catatan kisah perjalanan politik yang sulit ditebak dan seringkali mengejutkan. Dalam kehidupan sistem demokrasi setiap warga negara harus bersiap untuk menerima kejutan-kejutan dalam perjalanan bernegara. Kejutan yang mengecewakan ataupun yang menggembirakan. Itu semua harus diterima sebagai sebuah proses memandang masa depan dengan tetap optimis. Meski dengan rasa getir. Kawan dekat, tetangga, tokoh publik sebagai budayawan, wartawan, cendekiawan, atau kawan yang dulu pernah satu jalur perjuangan menumbangkan rezim lama, yang kita kenal cerdas, kritis tiba-tiba berubah haluan: mendukung rezim yang nampak dari luar demokratis tetapi isinya justru sebaliknya. Itulah yang dialami oleh Anne Applebaum, salah satu jurnalis pertama yang memperingatkan tentang campur tangan Rusia dalam pemilu AS dan tren antidemokrasi di Eropa.
Pada 31 Desember 1999, ia mengadakan pesta. Pesta mengakhiri satu milenium dan awal dari yang baru. Banyak orang merayakan moment itu di seluruh dunia. Termasuk Anne Applebaum yang mengadakannya di Chobielin, sebuah rumah bangsawan kecil di Polandia barat laut yang dibeli oleh suami dan orang tuanya satu dekade sebelumnya—rumah yang tak dapat dihuni, tidak direnovasi sejak penghuni sebelumnya melarikan diri dari Tentara Merah pada tahun 1945.
Para tamu yang diundang bermacam-macam: teman jurnalis dari London dan Moskow, beberapa diplomat junior yang berbasis di Warsawa, dua teman yang terbang dari New York. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang Polandia, teman mereka dan kolega suaminya, Radek Sikorski, yang saat itu menjabat sebagai wakil menteri luar negeri di pemerintahan aliran kanan-tengah Polandia. Ada teman-teman lokal, beberapa teman sekolah Radek, dan sekelompok besar sepupu. Sejumlah jurnalis muda Polandia juga datang—tidak ada yang terkenal pada waktu itu—bersama dengan beberapa pegawai negeri dan satu atau dua anggota pemerintahan yang masih sangat muda. Anne Applebaum menulis artikel pada Majalah Atlantik tahun 2018 “A Warning from Europe” yang mengilhami buku Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism (2020) yang kita bincangkan ini. Artikel itu menjadi finalis National Magazine Award. Setelah tujuh belas tahun sebagai kolumnis di The Washington Post, dia menjadi staf penulis di The Atlantic pada Januari 2020. Pesta ini sangat menyenangkan. Polandia pada masa itu dan juga Eropa Timur pada umumnya memasuki era baru: demokrasi.
“Pada saat itu, ketika Polandia hampir bergabung dengan barat, rasanya kami semua berada di tim yang sama. Kami sepakat tentang demokrasi, tentang jalan menuju kemakmuran, tentang bagaimana segala sesuatunya berjalan,” tulis penulis tiga sejarah Uni Soviet yang memenangkan penghargaan: Kelaparan Merah, Tirai Besi, dan Gulag, pemenang Hadiah Pulitzer.
Pesta merayakan demokrasi ada dimana-mana, juga di rumah lama yang baru direnovasinya.
Tetapi momen itu telah berlalu. Hampir dua dekade kemudian, saat ini ia harus menyeberang jalan untuk menghindari berpapasan dengan beberapa orang yang menghadiri pesta Malam Tahun Baru itu. Merekapun tidak hanya menolak untuk memasuki rumah tua di Chobielin itu, mereka juga akan malu untuk mengakui bahwa mereka pernah ke sana, tulis Applebaum dalam bukunya. Bahkan, sekitar separuh orang yang berada di pesta itu tidak lagi berbicara dengan separuh lainnya. Kerenggangan bersifat politis, bukan pribadi. Menurut catatan Applebaum, Polandia sekarang adalah salah satu masyarakat yang paling terpolarisasi di Eropa. Ia telah dianggap berada di sisi berlawanan dari perpecahan yang mendalam, yang tidak hanya melewati apa yang dulunya adalah Polandia kanan tetapi juga dialami oleh Hungaria lama kanan, Spanyol kanan, Prancis kanan, Italia kanan, dan, dengan beberapa perbedaan, Inggris kanan dan juga Amerika kanan. “..Ketika politik membuat persahabatan berakhir,” tulis John Kampfner di the Guardian memberi komentar pada buku Applebaum.
Demokrasi ternyata tidak seperti yang dibayangkan saat menyingkirkan rezim otoriter. Kawan-kawan Applebaum yang dikenalnya dulu kini setelah berkuasa atau masuk dalam lingkaran kekuasaan menjadi sangat berbeda. Beberapa, katanya, menjajakan teori konspirasi antisemit online. Orang-orang ini tidak kehilangan pekerjaan atau kehilangan tempat tinggal karena para migran. Mereka tidak jauh jatuh ke dalam kategori “tertinggal.” Mereka berpendidikan tinggi dan sering bepergian. Bukan termasuk kalangan orang biasa. Tetapi sangat mengherankan mengapa mereka merangkul dan menyebarkan kebohongan dan setengah kebenaran yang diusung oleh partai berkuasa di Polandia, Law and Justice? “Mengapa kaum intelektual mendukung diktator? tulis Bill Keller di the New York Times. Bagi Applebaum, pelajaran sejarah nomor satu: otoriter membutuhkan dukungan massa, tetapi, seperti fasis tahun 1930-an, mereka juga membutuhkan kolaborasi orang-orang di tempat tinggi. Memerlukan kaum terpelajar, intelektual, jurnalis, LSM, agamawan, budayawan dan akademisi.
Mereka membutuhkan “para penulis . . . pamfleter, blogger, spin doctor, produser program televisi, dan pembuat meme,” tulisnya, sangat penting bagi demagog untuk berhasil karena mereka “menjual citra mereka kepada publik”. Otoriter “membutuhkan orang-orang yang dapat menggunakan bahasa hukum yang canggih, orang-orang yang dapat berargumen bahwa melanggar konstitusi atau memutarbalikkan hukum adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mereka membutuhkan orang-orang yang akan menyuarakan keluhan, memanipulasi ketidakpuasan, menyalurkan kemarahan dan ketakutan, dan membayangkan masa depan yang berbeda.”
“Dengan kondisi yang tepat, masyarakat mana pun dapat berbalik melawan demokrasi,” catat penulis. “Given the right conditions, any society can turn against democracy.” “Memang, jika sejarah adalah segalanya, semua masyarakat kita pada akhirnya akan melakukannya,” tambahnya.
Ini adalah buku politik; dan sangat pribadi. Sebuah memoar perjalanan mengikuti senjakala demokrasi, twilight of democracy.
Menjadi diktator pada era demokrasi yang terus menghadapi berbagai tantangan saat ini tidak perlu mengerahkan senjata. ini dikatakan juga oleh Steven Levitsky dan rekannya Daniel Ziblatt dalam buku “How Democracies Die” (2018). “Bentuk kediktatoran lunak ini tidak membutuhkan kekerasan massal untuk tetap berkuasa,” tulis Applebaum. “Sebaliknya, ia mengandalkan kader elit untuk menjalankan birokrasi, media negara, pengadilan, dan, di beberapa tempat, perusahaan negara. Para intelektual (atau dengan mengutip Benda, disebut clercs) zaman modern ini memahami peran mereka, yaitu membela para pemimpin, betapapun tidak jujurnya pernyataan mereka, betapapun besarnya korupsi mereka, dan betapapun buruknya dampak mereka terhadap rakyat dan lembaga-lembaga biasa dan negara. Sebagai gantinya, mereka tahu bahwa mereka akan dihargai dan maju. Rekan dekat pemimpin partai bisa menjadi sangat kaya, menerima kontrak atau kursi yang menguntungkan di dewan perusahaan negara tanpa harus bersaing untuk mendapatkannya. Orang lain dapat mengandalkan gaji pemerintah serta perlindungan dari tuduhan korupsi atau ketidakmampuan. Betapapun buruknya kinerja mereka, mereka tidak akan kehilangan pekerjaan.”
Memang tidak semua intelektual atau intelektual individu dalam satu negara atau kelompok memiliki sikap yang sama terhadap pemerintahan otoriter, atau bahkan terhadap demokrasi, demokrasi yang cacat. Namun, beberapa faktor dan dinamika mungkin mempengaruhi dukungan intelektual terhadap pemerintahan otoriter. Dalam buku “Twilight of Democracy”, Anne Applebaum mengamati beberapa faktor yang dapat berperan dalam dukungan tersebut. Keuntungan Pribadi: Beberapa intelektual mungkin mendukung pemerintahan otoriter karena mereka memperoleh manfaat pribadi atau kekuasaan dalam hubungan dengan pemerintah tersebut. Termasuk akses ke sumber daya, posisi dan jabatan, atau kebebasan untuk melanjutkan penelitian atau karya mereka. Nasionalisme dan Identitas: Dalam beberapa kasus, dukungan terhadap pemerintahan otoriter dapat muncul dari nasionalisme yang kuat atau identitas etnis tertentu. Intelektual yang terlibat dalam gerakan nasionalis atau kelompok identitas mungkin memandang pemerintahan otoriter sebagai pelindung kepentingan kelompok mereka, meskipun hal itu melibatkan pembatasan kebebasan atau pelanggaran hak asasi manusia. Kepercayaan terhadap Kekuatan Pemerintah: Beberapa intelektual mungkin berpendapat bahwa pemerintahan otoriter dapat memberikan stabilitas, keamanan, atau kemajuan ekonomi yang dianggap penting dalam situasi sosial dan politik yang rumit. Dalam beberapa kasus, kegagalan pemerintahan demokratis atau ketidakstabilan politik dapat mendorong dukungan terhadap otoritarianisme. Ketidakpuasan Terhadap Demokrasi: Beberapa intelektual mungkin merasa kecewa dengan demokrasi dan institusi-institusi demokratis yang mereka anggap tidak efektif atau korup. Mereka mungkin percaya bahwa pemerintahan otoriter dapat memberikan solusi yang lebih baik atau mengatasi kelemahan yang mereka lihat dalam demokrasi. Manipulasi dan Propaganda: Pemerintahan otoriter sering menggunakan strategi manipulasi dan propaganda untuk mempengaruhi opini publik, termasuk para intelektual. Mereka dapat menyebarkan narasi yang menggambarkan diri mereka sebagai pelindung atau penjaga nilai-nilai nasional, sementara mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia atau pembatasan kebebasan.
Meski begitu tidak sedikit pula intelektual yang terus mempertahankan integritas dan nilai-nilai universal dalam mengevaluasi pemerintahan dengan segala risiko. Sementara yang lain mungkin termotivasi oleh faktor-faktor yang lebih pragmatis atau berideologi.
Dimanapun peran sejati cendekiawan atau intelektual selalu diimpikan. Masyarakat luas menaruh harapan pada cendekiawan sebagai pencerah jalan dalam menghadapi isu-isu pelik. Masyarakat berharap kaum cendekiawanlah yang mampu memberi petunjuk jalan yang jernih dan benar kemana melangkah. Sebab, “..suatu masyarakat yang menyingkirkan kaum intelektualnya, pada hakikatnya, sedang menyingkirkan dirinya sendiri. Karena kekuatan masyarakat itu untuk melanjutkan hidupnya akan bergantung juga kepada para anggotanya yang merasakan, menghayati, dan mencintai kebenaran (Soekito, 1983).”
Buku The Twilight of Democracy adalah memoar penulis yang mengambil situasi di Polandia, negara yang cukup punya ikatan emosional dengan penulis. Namun, gaungnya seperti bisa kita dengar nyata berkisah pula tentang sebuah negeri ijo royo-royo, yang jadi rebutan negeri seberang selama berabad-abad lampau. Lembaga-lembaga demokrasi diperalat untuk mempertahankan kekuasaan dari segala gangguan. Suara-suara kritik tidak jarang menghadapi ancaman serius. Hukum dijadikan alat transaksi untuk patuh pada kekuasaan. Kampus, lembaga penelitian, perusahaan-perusahaan negara menjadi ajang bagi kader elit menjalankan birokrasi yang diinginkan. Oposisi adalah musuh yang harus dibasmi. Kalau bisa semua partai hanya tunduk pada satu komando. Para pembangkang akan terjungkang.
“Mungkin saja kita sudah melewati masa senja demokrasi,” tulis Applebaum dalam buku setebal 207 halaman ini. “Bahwa peradaban kita mungkin sudah menuju anarki atau tirani, seperti yang pernah ditakuti oleh para filsuf kuno dan pendiri Amerika; bahwa generasi baru para intelektual, pendukung ide-ide yang iliberal atau otoriter, akan berkuasa di abad ke-21, seperti yang mereka lakukan di abad ke-20; bahwa visi mereka tentang dunia, yang lahir dari kebencian, kemarahan, atau mimpi mesianik yang dalam, dapat menang. Mungkin teknologi informasi baru akan terus merusak konsensus, memecah belah orang lebih jauh, dan meningkatkan polarisasi hingga hanya kekerasan yang dapat menentukan siapa yang berkuasa. Mungkin ketakutan akan penyakit akan menciptakan ketakutan akan kebebasan.”
Dan berharap bahwa virus corona akan menginspirasi rasa solidaritas global yang baru. Mungkin kita akan memperbaharui dan memodernisasi institusi kita. Mungkin kerja sama internasional akan berkembang setelah seluruh dunia memiliki pengalaman yang sama pada saat yang sama: lockdown, karantina, ketakutan akan infeksi, ketakutan akan kematian. Mungkin ilmuwan di seluruh dunia akan menemukan cara baru untuk berkolaborasi, di atas dan di luar politik. Mungkin kenyataan penyakit dan kematian akan mengajarkan orang untuk curiga terhadap pedagang asongan, pembohong, dan penyebar informasi yang salah. Meski pada kenyataannya, setelah pandemi kita lewati semua dengan perih, business as usual nampak yang terjadi. Bahkan politik kita makin mencemaskan.
Applebaum berharap, meski dengan jengkel, kita harus menerima bahwa masa depan yang menakutkan atau menjanjikan, mungkin saja terjadi. Tidak ada kemenangan politik yang permanen, tidak ada definisi “bangsa” yang dijamin bertahan, dan tidak ada elit dalam bentuk apa pun, baik yang disebut “populis” atau yang disebut “liberal” atau yang disebut “aristokrat,” yang berkuasa selamanya. Menurutnya, sejarah Mesir kuno terlihat, dari jarak waktu yang sangat jauh, seperti kisah monoton tentang firaun yang dapat dipertukarkan. Namun jika diamati lebih dekat, itu termasuk periode ringan budaya dan era kesuraman yang lalim. Sejarah kita suatu hari nanti akan terlihat seperti itu juga.
Diakui bahwa demokrasi, seperti halnya bentuk pemerintahan lainnya, tidak selamanya akan ada. Ia tidak bisa seperti mesin yang bekerja dengan sendirinya; ia adalah mesin yang, sebaliknya, hanya berjalan selama para pengguna merawatnya. Dan apakah kolom alat kemudi berada di kanan atau kiri, menurut Applebaum, kita telah mencapai momen di mana terlalu banyak penggunanya yang mengendarainya justru lurus ke arah tembok.
Applebaum, sebagaimana beberapa penulis yang mengupas tentang intelektual, selalu merujuk pada seorang Prancis yang menulis pada tahun 1920-an, mengantisipasi gejolak yang akan datang: Julian Benda. Kutipan dari Benda menjadi pembuka pada epigraf yang digoreskan pada bukunya.
Julien Benda adalah seorang intelektual dan penulis Prancis yang dikenal karena karyanya yang berpengaruh, “La Trahison des Clercs” (The Treason of the Intellectuals). Karya fenomenal ini diterbitkan pada tahun 1927. Benda lahir pada tanggal 26 Desember 1867 dan meninggal pada tanggal 7 Juni 1956. “La Trahison des Clercs” merupakan kritik tajam terhadap intelektual dan elit intelektual pada masanya. Benda mengungkapkan keprihatinannya atas pengaruh politik dan ideologi yang korup terhadap intelektual dan mengecam mereka yang mengorbankan nilai-nilai universal dan kejujuran intelektual demi kepentingan politik atau ideologi sempit.
Benda mengkritik intelektual yang terlibat dalam pandangan politik sempit, fanatisme nasionalis, dan mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Ia menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan intelektual dan kejujuran dalam mengejar kebenaran dan keadilan. Karya Benda lainnya termasuk “Le Bergsonisme” (1932), yang merupakan analisis kritis tentang filsafat Henri Bergson, dan “Discours à la nation européenne” (1945), di mana ia membangkitkan ide tentang pentingnya persatuan Eropa dan penolakan terhadap nasionalisme sempit. Julien Benda dianggap sebagai salah satu pemikir yang berpengaruh dalam mempertahankan peran intelektual independen dan pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam dunia intelektual. Karyanya “La Trahison des Clercs” terus menjadi sumber inspirasi dan perdebatan dalam kajian intelektual dan politik hingga saat ini.
Buku ini diakhiri dengan mengutip novelis Ignazio Silone, seorang Italia yang menulis pada tahun 1950-an. Disepanjang hidupnya mengalami turbulensi politik. Menulis dan menerbitkan “The Choice of Comrades,” sebuah esai di mana dia mencoba menjelaskan, antara lain, mengapa dia masih terlibat dalam politik, meskipun begitu banyak kekecewaan dan kekalahan.
Silone telah bergabung dan meninggalkan Partai Komunis; dia mungkin, beberapa percaya, pertama kali berkolaborasi dengan fasisme sebelum menolaknya juga. Dia telah hidup melalui perang dan revolusi, berada di bawah ilusi dan kemudian kecewa, telah menulis sebagai seorang anti-Komunis dan antifasis. Dia telah melihat ekses dari dua jenis politik ekstremis yang berbeda. Tetap saja, dia pikir perjuangan itu layak untuk dilanjutkan. Bukan karena ada nirwana yang harus diperoleh, dan bukan karena ada masyarakat sempurna yang harus dibangun. Tetapi karena sikap apatis begitu mematikan, begitu mematikan pikiran, begitu menghancurkan jiwa.
Dia juga hidup di era ketika orang-orang hidup, seperti yang mereka lakukan hari ini, dengan sayap kanan dan sayap kiri, dengan berbagai jenis ekstremis, semua jenis ekstremis yang berbeda. Semuanya berteriak pada saat yang bersamaan. Banyak rekan senegaranya bereaksi dengan menyatakan bahwa “semua politisi adalah penjahat” atau “semua jurnalis berbohong” atau “Anda tidak dapat mempercayai apa pun”. Di Italia pascaperang, bentuk skeptisisme, anti-politik, dan apa pun-isme ini bahkan mendapat nama, qualunquismo, istilah bahasa Italia yang merujuk pada sikap apatis, sinis, dan tidak peduli terhadap politik dan masalah sosial. Silone telah melihat dampaknya. “Rezim politik datang dan pergi,” tulisnya, tetapi “kebiasaan buruk tetap ada”—dan kebiasaan terburuk adalah nihilisme, “penyakit jiwa yang hanya dapat didiagnosis oleh mereka yang kebal terhadapnya atau telah disembuhkan darinya, tetapi yang kebanyakan orang tidak menyadarinya, karena mereka pikir itu sesuai dengan cara keberadaan yang sangat alami: ‘Begitulah selalu; akan selalu seperti itu.’ ”
Silone tidak menawarkan obat mujarab atau penawar ajaib karena memang tidak ada. Tidak ada solusi akhir, tidak ada teori yang akan menjelaskan semuanya. Tidak ada peta jalan menuju masyarakat yang lebih baik, tidak ada ideologi didaktik, tidak ada buku peraturan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih sekutu dan teman kita—rekan-rekan kita, seperti yang dia katakan—dengan sangat hati-hati, karena hanya dengan mereka, bersama-sama, kita dapat menghindari godaan dari berbagai bentuk otoritarianisme yang ditawarkan sekali lagi. Karena semua otoritarianisme memecah belah, mempolarisasikan, dan memisahkan orang ke dalam kubu-kubu yang bertikai, perang melawan mereka membutuhkan koalisi baru. Bersama-sama kita bisa membuat kata-kata lama dan disalahpahami seperti liberalisme berarti sesuatu lagi; bersama-sama kita bisa melawan kebohongan dan pembohong; bersama-sama kita dapat memikirkan kembali seperti apa seharusnya demokrasi di era digital.
Seperti para pengungsi yang berjuang untuk mencapai tujuan yang jauh di jalan yang gelap, kita dipaksa, tulis Silone, untuk memilih jalan kita sepanjang malam tanpa tahu apakah kita akan tiba: “Langit Mediterania kuno yang cerah, dulu dipenuhi dengan konstelasi yang bersinar, mendung; tetapi lingkaran kecil cahaya yang tersisa bagi kita ini memungkinkan kita setidaknya untuk melihat di mana harus meletakkan kaki kita untuk langkah selanjutnya.”
“Saya merasa beruntung telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan orang-orang yang peduli dengan apa yang terjadi setelah kita mengambil langkah selanjutnya,” kata Applebaum dengan penuh kegembiraan dan optimisme.
Bagi sebagian orang, kegentingan saat ini tampak menakutkan, namun ketidakpastian ini selalu ada. Liberalisme John Stuart Mill, Thomas Jefferson, atau Václav Havel tidak pernah menjanjikan sesuatu yang permanen. Checks and balances dalam demokrasi konstitusional Barat tidak pernah menjamin stabilitas. Demokrasi liberal selalu menuntut hal-hal dari warga negara: partisipasi, argumen, usaha, perjuangan. Mereka selalu membutuhkan toleransi terhadap hiruk-pikuk dan kekacauan, serta kemauan untuk melawan orang-orang yang menciptakan hiruk-pikuk dan kekacauan.
Mereka selalu mengakui kemungkinan gagal—kegagalan yang akan mengubah rencana, mengubah kehidupan, menghancurkan keluarga. Kita selalu tahu, atau seharusnya tahu, bahwa sejarah dapat sekali lagi menjangkau kehidupan pribadi kita dan mengaturnya kembali. Kita selalu tahu, atau seharusnya tahu, bahwa visi alternatif bangsa akan mencoba menarik perhatian kita. Tapi mungkin, dengan memilih jalan melalui kegelapan, kita akan menemukan bahwa bersama-sama kita dapat melawan mereka.
Maka kalau kita percaya dan berjanji bahwa demokrasi adalah pilihan kita sementara ini maka jangan biarkan pihak-pihak lain ada kesempatan untuk menghalangi, apalagi menghancurkan-nya. Tugas kita adalah merawat demokrasi dan memperkuat peran-peran intelektual sebagai warga negara ke jalan yang lurus. Bukan jalan mendukung kediktatoran dan otoriterianisme. Berpartisipasi, berargumen, berusaha, berjuang dalam proses-proses politik yang demokratis. Melawan setiap upaya yang merusak rajutan-rajutan kebangsaan.
“Twilight of Democracy” menawarkan banyak pelajaran tentang perjuangan panjang antara demokrasi dan kediktatoran. Tapi mungkin yang paling penting adalah betapa rapuhnya demokrasi: kelangsungan hidupnya bergantung pada pilihan yang dibuat setiap hari oleh para elit dan rakyat biasa. “Tidak ada peta jalan menuju masyarakat yang lebih baik,” tulis Applebaum, “tidak ada ideologi didaktik, tidak ada buku peraturan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih sekutu dan teman kita. . . dengan sangat hati-hati, karena hanya dengan mereka, bersama-sama, kita dapat menghindari godaan dari berbagai bentuk otoritarianisme.”
Buku ini bisa menjadi pengingat, penyemangat dan pelajaran bagi kita untuk bergerak ke depan dengan lebih meyakinkan.