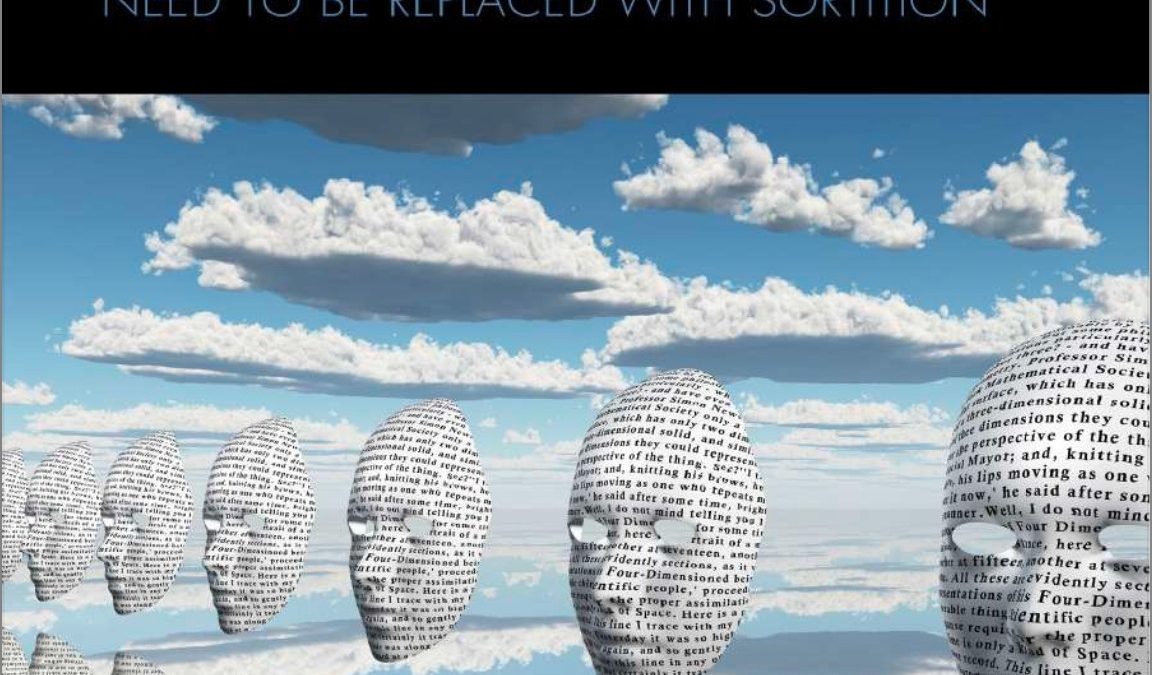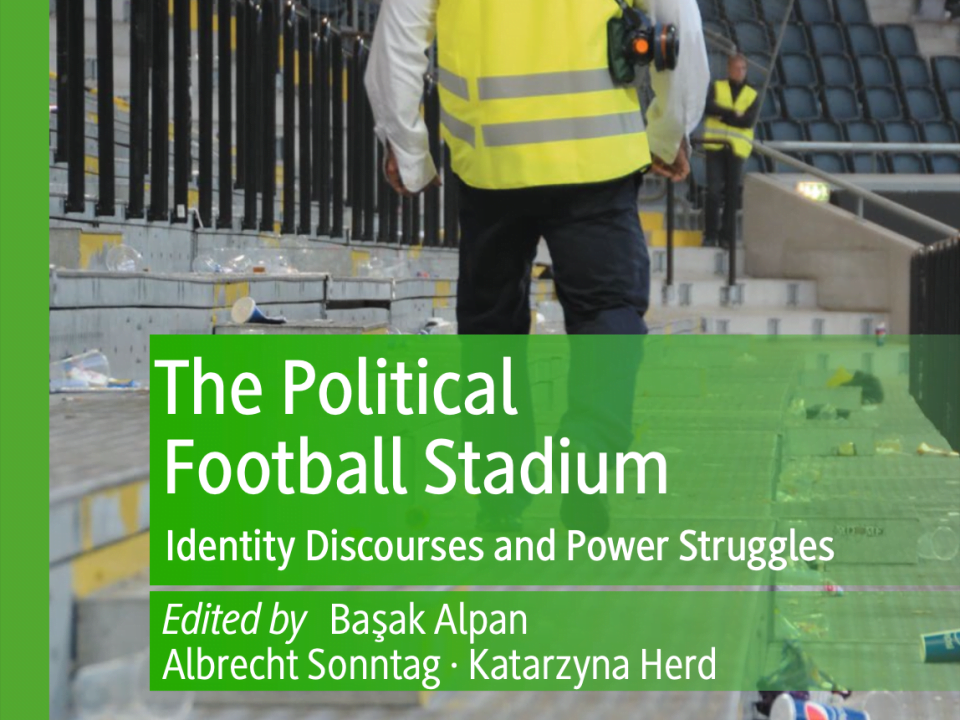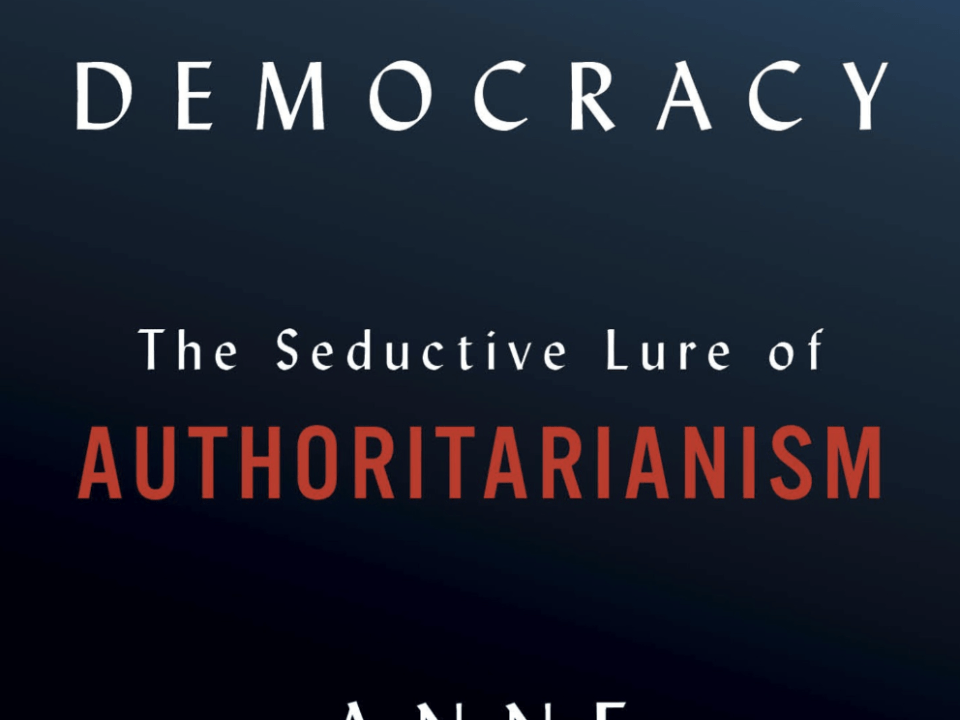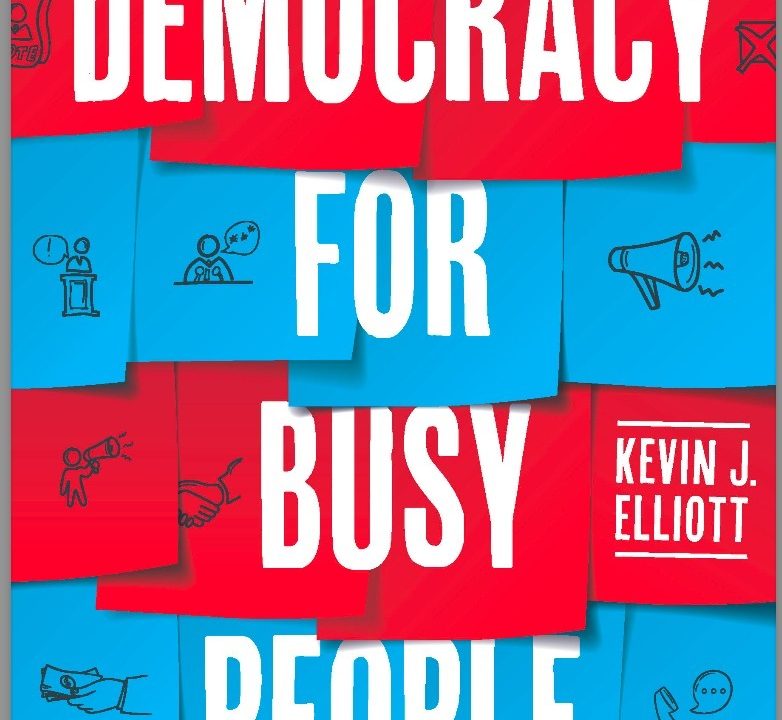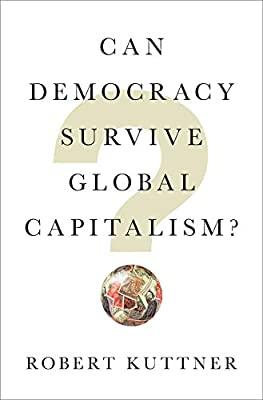Manifesto Demokrasi: Demokrasi Tanpa Partai, Demokrasi Tanpa Pemilu, Politik Tanpa Politisi
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor-Cirebon, 30.05.2023
#BincangBuku #48
“Democracy, aristocracy, oligarchy, dictatorship, despotism, totalitarianism,
absolutism and anarchy: every political system has to achieve
a balance between two fundamental criteria, efficiency and legitimacy.”
David van Reybrouck. Against Elections:
The Case for Democracy. New York: Seven Stories Press, 2018.
Demokrasi Cacat, Demokrasi Semu
Dalam setiap perbincangan isu publik apapun dan kebijakan-kebijakan yang menyertainya kehadiran partai politik tak terelakkan. Mereka tampil dengan peran beragam. Baik sebagai sosok kepartaian, pemerintah dan kadang juga sebagai legislator. Keterlibatannya dalam isu-isu publik juga beragam kepentingan. Sekali waktu membawa kepentingan partai. Kesempatan lainnya sebagai suara pemerintah atau memanggul suara parlemen. Satu hal yang selalu diingat publik: mereka seringkali membosankan, dan menjengkelkan. “Partai politik Indonesia adalah lembaga politik yang paling tidak dipercaya di negara ini. Perpaduan politik elit dan kehadiran bisnis yang mengakar dan kepentingan pribadi lainnya di tingkat pemerintahan tertinggi membuat partai politik sulit untuk bertindak sebagai penjaga demokrasi Indonesia,” demikian kata para peneliti. Dikutip dari survey Indikator, tahun 2022, Indonesia masih berada dalam kelompok negara flawed democracy atau demokrasi cacat menurut Indeks Demokrasi 2021 yang dirilis oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Ini berarti Indonesia masih menghadapi persoalan dalam praktik demokrasi. Misalnya dalam kebebasan pers, budaya politik, partisipasi politik, dan fungsi pemerintahan. Indeks Demokrasi 2023 bahkan juga tak beranjak dari peringkat tahun 2022 dan 2021 itu: demokrasi cacat.
Pada aras global kepercayaan publik pada partai politik juga sangat menyedihkan. Edelman Trust Barometer Global Report (2023) mencatat bahwa para pemimpin negara adalah sosok yang paling tidak bisa dipercaya. Tingkat kepercayaan publik terhadap para pemimpin itu hanya 41%, tingkat kepercayaan paling rendah diantara sosok lainnya (Jurnalis, 47%; warga negara di negara masing-masing, 59; tetangga saya, 63; rekan kerja saya, 73; dan paling tinggi adalalah ilmuwan, 76). Pemimpin pemerintahan tentu adalah representasi partai politik dan pilihan rakyat melalui partai politik. Ini adalah cermin dari partai politik.
Bagi de Leon (2014) partai politik berbeda dari entitas lain seperti masyarakat sipil, swasta atau negara karena kontrol mereka atas sistem nominasi, pemilihan, dan penunjukan untuk jabatan politik (misalnya, presiden, menteri pertahanan, anggota dewan kota). Dengan kata lain, mereka memimpin mesin kelembagaan formal yang banyak dari kita diasosiasikan dengan proses demokrasi. Partai politik yang menang dalam pemungutan suara memegang tampuk kekuasaan negara. Fenomena “pemerintahan partai” ini berarti para politisi mengarahkan kebijakan luar negeri dan dalam negeri komunitasnya masing-masing. Oleh karena itu, partai politik telah menjadi pemain kunci dalam transformasi sosial yang paling signifikan dan menyakitkan di zaman kita. Kebangkitan dan kejatuhan pemerintahan Bush dan pemerintahan Blair, misalnya, seperti ditulis dalam buku de Leon “Party and Society: Reconstructing a Sociology of Democratic Party Politics,” penting untuk memahami tidak hanya politik Amerika dan Inggris, tetapi juga kebijakan Perang Melawan Teror dan resesi, yang efek lanjutannya terus berdampak pada kehidupan hingga kini di seluruh dunia. Bagi kita di Indonesia aneka kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah juga tak lepas dari campurtangan dan kepentingan partai politik. Istilah yang melekat pada Presiden sebagai “Petugas Partai” menjadi bukti telanjang betapa kuat partai mengikat kader yang menjadi pemimpin pemerintahan meskipun mandatnya sebagai kepala negara menjadi pemimpin bagi semua.
Itulah salah satu hal yang menjengkelkan dari partai politik. Terlepas dari sentralitas partai politik dalam kehidupan demokrasi dan pengaruh mereka pada urusan publik saat ini, masih diperlukan memahami kompleksitas dan dinamisme peran partai ini. Dalam praktiknya, menurut de Leon dan kita saksikan juga dalam panggung keriuhan tahun politik ini, partai-partai berdiri dalam kontinum yang cair antara negara dan masyarakat sipil, sehingga terkadang sulit membedakan di mana salah satu dari ketiga entitas ini bermula dan yang lainnya berakhir.
Lalu dalam situasi kompleks dan menjengkelkan soal tingkah laku partai dan politisi itu timbul pertanyaan: Mungkinkah demokrasi tanpa partai?
BincangBuku kali ini mengintip sebuah buku yang sedikit bisa menjawab pertanyaan itu: “The Democracy Manifesto: A Dialogue on Why Elections Need to be Replaced with Sortation (Waxman and McCulloch, 2022). Buku ini berbicara tentang bagaimana menghidupkan kembali demokrasi sejati. Demokrasi melalui pemilu, tentang pemilu—bagaimana memperbaikinya dan membuatnya lebih adil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan. Dan tentu saja tidak menjengkelkan publik dengan tingkah laku para politisinya yang memuakkan. Meski dengan mencoba melambungkan harapan, faktanya, demokrasi yang kita saksikan kini makin memburuk. Bahkan untuk menegaskan itu, Penerbit LP3ES menghimpun pandangan ilmuwan sosial politik yang dituangkan dalam buku Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia (2021). Pada bagian akhir buku ini Jeffrey A Winters (Demokrasi Parsial di Indonesia) menyebut demokrasi Indonesia sebagai demokrasi parsial bahkan semu. Demokrasi yang ada tidak punya alat yang efektif untuk membatasi atau menetralkan kuasa kekayaan yang sangat besar dan pengaruh para oligarki dan elite.
Buku “The Democracy Manifesto” menarik karena mengupas tentang cara menghidupkan kembali demokrasi dengan menyingkirkan pemilu sama sekali dan menggantinya dengan tatanan politik jenis baru yang menarik para pemimpinnya secara acak dari populasi pada umumnya. Warga biasa siapapun mereka.
Seperti dipaparkan oleh para penulis, politik yang digambarkan mengingatkan pada beberapa sistem yang berkembang di Yunani kuno, tempat kelahiran demokrasi. Demokrasi Yunani memberikan kekuasaan pada orang biasa—pengrajin, buruh, pemilik toko, petani, pelaut, dan lain-lain seperti mereka. Sialnya waktu itu, wanita tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Begitu pula penduduk non-warga negara dan orang-orang yang ditahan sebagai budak. Tetapi karena hal yang sama berlaku untuk semua negara-kota Yunani terlepas dari sistem politik mereka (oligarki, tirani, dll.), kekurangan ini berkaitan dengan adat istiadat budaya dan sosial ekonomi yang berlaku waktu itu, bukan demokrasi.
Dianggap murni secara politis, demokrasi Yunani berdiri terpisah sebagai sistem pemerintahan pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang mengambil kekuasaan dari elit dan me-nempatkannya di tangan mayoritas non-elit. Ini termasuk kendali atas pengeluaran negara, kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkan kebijakan, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, otoritas peradilan, kekuasaan darurat untuk bertindak dalam krisis, dan kendali atas urusan luar negeri dan perang. Menurut Waxman and McCulloch sistem ini bukan untuk mengatakan bahwa elit tidak terus memainkan peran besar: lebih terdidik, diuntungkan secara materi, dan terbiasa mengambil alih, mereka cenderung lebih terampil dalam seni pemerintahan dan persuasi. Namun demikian, elit tidak dapat mencapai apa pun di bawah pemerintahan demokratis jika mereka tidak dapat meyakinkan massa besar bahwa langkah-langkah yang mereka anjurkan memajukan kepentingan semua orang. Karena dalam demokrasi, rakyat berkuasa. Bukan oligarchy, the rule of the powerful few over the powerless many.
Demokrasi Yunani berakhir ketika seluruh Yunani jatuh di bawah kekuasaan, pertama Makedonia dan kemudian Roma—kedua negara dikendalikan oleh elit yang dengan tegas menentang membiarkan orang lain menjalankan kekuasaan politik. Hal yang sama berlaku sejak saat itu, hingga dan termasuk apa yang disebut demokrasi elektoral saat ini. Karena tidak dapat disangkal bahwa di negara bagian yang pemimpinnya dipilih dan semua jabatan tinggi lainnya diisi oleh orang yang ditunjuknya, otoritas tertinggi untuk mengenakan pajak, membelanjakan, membuat undang-undang, menetapkan kebijakan, mengadili, mengelola, dan mengendalikan polisi jatuh ke tangan orang-orang yang bukan orang biasa. Penguasa kita direkrut dari elit politik, bisnis, keuangan, birokrasi sipil dan militer, dan profesi. Mereka juga tidak dapat mencapai posisi tinggi mereka di pemerintahan tanpa dukungan yang luas dan berkantong tebal dari elit lainnya. Bahkan mereka yang memulai sebagai anggota mayoritas non-elit mencapai keunggulan politik hanya dengan pertama-tama masuk ke lembaga pendidikan elit, mendapatkan kredensial profesional, memegang posisi tinggi di sektor swasta, atau membedakan diri mereka sebagai orang luar biasa.
Jelas, sifat sistem pemilu adalah menyingkirkan orang biasa dari kekuasaan dan menempatkan-nya sepenuhnya di tangan para elit. Sulit diterima bahwa sistem yang melakukan hal itu dapat disebut “demokratis” secara bermakna.
Mereka adalah pilihan masyarakat, dan merekalah yang memenangkan pemilihan dan datang untuk menjalankan kekuasaan atas kita semua. “Oleh karena itu, pertanyaannya tidak dapat dihindari: bagaimana sebuah sistem yang selalu memastikan bahwa tidak ada orang yang benar-benar biasa yang dapat mendekati tuas kekuasaan yang sebenarnya layak disebut demokrasi? Orang Yunani kuno pasti akan menertawakan kepura-puraan demokrasi kita kini,” tulis Waxman and McCulloch.
Sortitive Representative Democracy
Adakah jalan keluarnya? Maka dikenalkanlah apa yang disebut penulis sebagai “Sortitive Representative Democracy” (SRD). Ini bukan gagasan yang baru. Oliver Dowlen menerbitkan buku “The Political Potential of Sortition: A Study of the Random Selection of Citizens for Public Office” (2008). Buku Dowlen ini merupakan studi tentang satu aspek tertentu dari pemerintahan: pemilihan acak pejabat politik melalui sortasi atau undian. Cara penyortiran ini banyak digunakan di Athena Kuno dan di republik kota Italia pada akhir abad pertengahan dan periode renaisans. Oleh karena itu, terdapat investasi yang cukup besar dalam bentuk seleksi ini selama periode yang sangat penting dalam pengembangan gagasan dan praktik politik kita. Namun, menurut Dowlen, dengan pengecualian pemilihan juri, sebagian besar absen dari politik elektoral saat ini. Meskipun sejak 1970-1980an mulai ada kebangkitan minat dalam pemilahan baik dari penulis akademis maupun dari mereka yang terlibat dalam politik praktis. Sebagian besar ini merupakan tanggapan terhadap masalah yang dirasakan dengan demokrasi liberal seperti jurang yang semakin lebar antara warga negara dan politisi profesional dan pengucilan kelompok minoritas yang signifikan dari proses politik.
Gagasan utama SRD adalah mengembalikan 100% kekuasaan pada orang biasa. Bukan elit. (Padahal bisa jadi sebagian elit yg bercokol sekarang itu juga tadinya adalah orang biasa. Tetap saja terpilihnya dalam gerbong kekuaaan memlalui proses-proses elitis, yang ditentukan oleh elit-elit partai). Konsep SRD berupaya menghidupkan kembali demokrasi sejati dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat kompleks amat besar, canggih secara teknologi, dan saling terhubung secara global. Ini tentu tidak akan mudah. Selain rintangan praktis, bagi banyak orang ada pertanyaan nyata apakah demokrasi masih sesuai atau bahkan masihkah diinginkan. Seberapa nyamankah kita dengan gagasan memberikan hoi polloi—tukang ledeng, penata rambut, pekerja toko, buruh tani, bahkan orang jalanan—bukan hanya suara dalam pemerintahan tetapi, berdasarkan jumlah yang banyak, sebagai pembuat keputusan akhir?
Tampaknya ada preferensi yang hampir naluriah untuk menyerahkan politik kepada para profesional, orang-orang yang memiliki keterampilan dan kepemimpinan yang terbukti di saat-saat baik dan buruk. Tetapi apakah itu berarti tidak ada kondisi di mana demokrasi layak untuk dikejar? Atau bahwa kondisi yang berlaku saat ini—kerusakan lingkungan yang parah, meningkatnya ancaman perang nuklir, ketidaksetaraan dan kerentanan yang akut dan meningkat, mengikis kebebasan sipil, dan menipisnya sistem dukungan sosial—membuat demokrasi tidak hanya diinginkan tetapi juga diperlukan?
Menurut para penulis keberatan yang paling memaksa terhadap demokrasi murni—pemerintahan yang 100% dikendalikan oleh mayoritas non-elit—dapat diatasi dengan sistem yang mereka sebut demokrasi perwakilan sortitif, atau SRD itu, di mana perwakilan politik dipilih secara acak dan tunduk pada protokol prosedural yang ketat, tidak berbeda dengan juri pengadilan kalau di Amerika. Menurut penulis SRD akan lebih baik bagi orang biasa dalam segala hal daripada pemilu, dan, mengingat keadaan dunia saat ini yang berbahaya, jauh lebih kecil risikonya daripada bertahan dengan pihak yang tidak demokratis, status quo.
Apa yang membedakan SRD dari sistem demokrasi sortitif yang diusulkan sebelumnya adalah soal kelengkapannya, comprehensiveness. Pada gagasan sortitif sebelumnya sebagian besar ruang lingkupnya terbatas, melengkapi atau mereformasi bagian dari tatanan politik yang ada. Sebaliknya, sistem yang SRD yang diusulkan ini tidak dimaksudkan sebagai tambalan atau perbaikan tetapi sebagai pengganti lengkap dari sistem yang ada, berlaku di seluruh planet ini.
Dalam sistem SRD setiap cabang, departemen, dan tingkat pemerintahan, badan pemerintahan
sebagian besar terdiri dari orang-orang biasa, termasuk mereka yang bertugas mengawasi, mengatur, dan mengoreksi SRD itu sendiri. Mereka dipilih secara acak. Sebagai sebuah sistem komprehensif yang mengatur dirinya sendiri secara demokratis dan mengoreksi dirinya sendiri secara demokratis, tidak ada proposal lain untuk pemerintahan sortitif yang diketahui dapat mendekati SRD secara luas dan mendalam, atau sesuai dengan janjinya untuk menyerahkan pemerintah nasional, regional, dan perkotaan dengan cara yang sama dikontrol secara demokratis 100%.
Para penulis mengemas buku The Democracy Manifesto: A Dialogue on Why Elections Need to be Replaced with Sortation dalam format tanya jawab antara para panelis dengan pengaturan dialog oleh moderator. Pengemasan penulisan gagasan SRD dalam format dialog dilatar-belakangi keinginan penulis untuk menyajikan sesuatu yang berbeda dengan cara perbincangan para tokoh-tokoh warga biasa. Kebaruan SRD membutuhkan kebaruan dalam presentasinya.
Tapi menurut penulis itu bukan satu-satunya alasan memilih format dialog. Proses yang mirip dengan SRD telah dilakukan di beberapa tempat, meskipun dalam kapasitas murni sebagai penasehat dan tidak pernah dengan pemikiran untuk mengembangkan dan memperluasnya ke dalam sistem yang sesuai untuk menjalankan tugas yang saat ini dilakukan oleh pejabat terpilih. Kita mungkin sulit membayangkan bagaimana implementasi SRD ini. Belum ada yang melakukannya dimana pemerintahan dijalankan dari dan oleh orang biasa. Akibatnya, siapa pun yang menulis dan menawarkan gagasan SRD ke khalayak akan menghadapi perjuangan berat agar bisa meyakinkan dan memberi pemahaman pada orang. Mungkin tidak sepenuhnya benar bahwa tidak ada pemerintahan yang menjalankan SRD. Sebab pada tingkat Sub pemerintahan desa, RT (Rukun Tetangga) rasanya telah menjalankan SRD. Setidaknya di lingkungan RT saya. Dimana semua warga RT memilih calon Ketua RT dengan suara langsung. Suara terbanyak langsung bisa dilantik sebagai Ketua RT. Pada tingkat pemerintahan di atas memang masih belum terbayangkan.
Pendekatan dialog ini menampilkan imajinasi orang-orang biasa yang membincangkan tentang SRD. Dialog berlatar di amfiteater (fiksi) universitas di mana seorang penulis (fiksi), moderator, empat panelis, dan audiens berkumpul untuk menanyai penulis tentang buku terbarunya, Apakah Musuh Demokrasi Pemilu No.1? Midge, begitu dia dipanggil, adalah seorang profesor filsafat yang melakukan begitu banyak pemaparan nonakademik sehingga dia akhirnya menjadi intelektual publik penuh waktu, aktif di sejumlah organisasi dan tujuan. Secara politik, dia adalah seorang sosialis yang meninggalkan politik kiri untuk menjadi advokat penuh waktu untuk demokrasi non-partisan.
Moderator dalam dialog ini, tidak pernah disebutkan namanya, menyuarakan pandangan yang lebih sentris dan mapan, sebagaimana layaknya seseorang yang penting di universitas dan komunitas di luar. Keempat panelis dengan nama samaran yang dianonimkan secara teknologi—tentu saja dipilih dengan acak, undian!—mewakili berbagai jalinan opini politik yang umum di komunitas universitas. Mereka menyebut diri mereka Cato (konservatif), Uhuru (liberal), Rangi (komunis), dan Atlas (libertarian). Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, para penanya audiens, baik di aula maupun yang berpartisipasi dari jarak jauh, menyuarakan pendapat yang umum di masyarakat pada umumnya. Perlu dicatat semua aktor dalam dialog ini adalah fiksi.
Tokoh-tokoh dalam dialog ini mewujudkan ideologi partisan hanya dalam arti luas dan umum: Cato konservatif dalam mendukung pemerintah yang mengutamakan tradisi, Uhuru liberal karena menginginkan pemerintah mengambil peran utama dalam mengganti cara dan nilai tradisional dengan yang lebih modern. Libertarian Atlas yang lebih suka melihat pemerintah diminimalkan semaksimal mungkin, dan Rangi sayap kiri dalam mendukung pemerintah yang menjadikan pekerja dan orang miskin sebagai prioritas dalam segala hal. Dialog dibangun di atas tesis bahwa tidak ada komitmen partisan atau prinsip ideologis yang mencegah mereka untuk setidaknya terbuka terhadap gagasan SRD.
Dari uraian sepanjang 12 Bab dalam 189 halaman, buku The Democracy Manifesto: A Dialogue on Why Elections Need to be Replaced with Sortation ingin menegaskan bahwa jika ingin melihat demokrasi berjalan dengan warga sebagai penguasa utama maka SRD ini adalah jalannya. Dengan SRD maka kita akan mempunyai demokrasi tanpa perlu lagi partai,
demokrasi tanpa adanya pemilu, dan demokrasi dengan politik tanpa diperlukan satu politisipun.
Di bawah SRD, tidak perlu memilih pemimpin karena orang-orang anonim yang dipilih secara acak yang menjabat untuk jangka waktu singkat sekali seumur hidup dan memegang semua posisi kepemimpinan. Jadi, tidak perlu berorganisasi untuk mendaftarkan pemilih, melakukan kampanye, atau melakukan penggalangan jumlah pemilih pada hari pemilihan—tidak ada kampanye untuk diliput media, tidak ada kontestasi politik untuk diramalkan, tidak diperlukan lembaga survei, tidak ada kualitas kepemimpinan untuk dijadikan patokan, tidak ada reputasi untuk diumumkan, tidak ada puja puji dan segala permainan kotor. Partai politik juga akan kehilangan keberadaannya karena tidak perlu atur-atur daftar pemilihan, memberikan dukungan keuangan, manajer dan konsultan kampanye, menawar untuk dukungan individu dan kelembagaan, bekerja media, dan melakukan semua hal lain yang dilakukan partai dalam Pemilu modern. Pada sistem Pemilu modern saat ini, Pemilu nampak memberikan rasa keterlibatan langsung masyarakat dalam kehidupan politik bangsa, daerah, atau kotanya. Politisi memberikan isu dan menyebabkan wajah dan suara publik, yang dipublikasikan media massa dengan melakukan yang terbaik untuk mengubah kampanye pemilu dan pertarungan politik menjadi penuh drama. Hasilnya adalah publik yang terlibat. Tapi semua itu akan hilang di bawah SRD. Hanya akan ada avatar yang sewenang-wenang dan selalu berubah-ubah yang melindungi identitas pembuat keputusan yang fana, dan mungkin terlalu membosankan. Tidak ada yang perlu dipersonalisasi atau didramatisasi, tidak ada orang yang terlibat atau berhimpun dalam lapangan luas dengan orasi bertubi-tubi.
Bagi Waxman and McCulloch politik yang kita kenal telah mati dengan adanya pemilu. Sama seperti politik yang diketahui orang Romawi kuno mati dengan kekaisaran mereka, politik budak mati dengan feodalisme, dan politik Soviet mati dengan bubarnya Uni Soviet. Karena SRD belum diterapkan di mana pun, kita tidak dapat mengetahui perubahan politik seperti apa yang akan terjadi.
Bagaimanapun sebagai sebuah gagasan yang terus berkembang dan makin mendapatkan perhatian sebagai sebuah inovasi demokrasi kedatangan SRD pasti akan terjadi, merangsang dan memperkaya, bukan melemahkan keterlibatan politik. Setidaknya demikian optimisme yang ditebarkan pada buku yang luar biasa ini. SRD yang bakal menghilangkan Pemilu maka akan menciptakan efisiensi (tidak ada lagi biaya besar, tidak ada korupsi, tidak ada politik uang), dan legitimasi–dua kriteria fundamental dalam sistem politik seperti ditulis David van Reybrouck: Against Elections: The Case for Democracy yang saya kutip pada epigraph di atas..
Ekperimen demokrasi dan politik Perlu kita lakukan di Indonesia. Menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan pengelolaan negara lebih baik dalam waktu kini dan mendatang. Berdemokrasi dan berpolitik juga memerlukan inovasi. Tanpa inovasi maka akan mati.