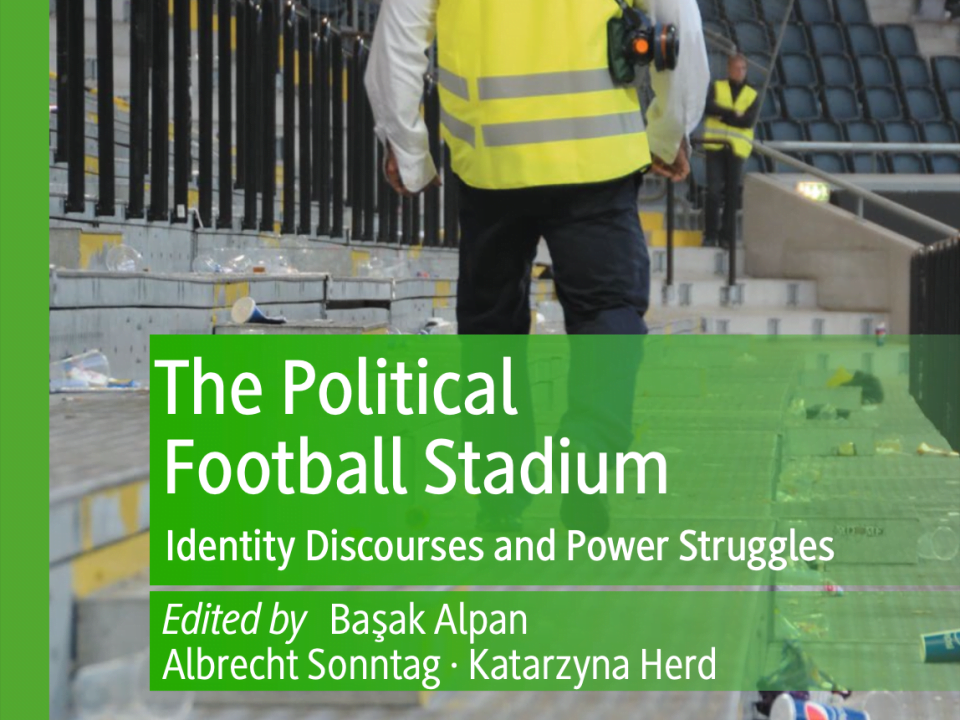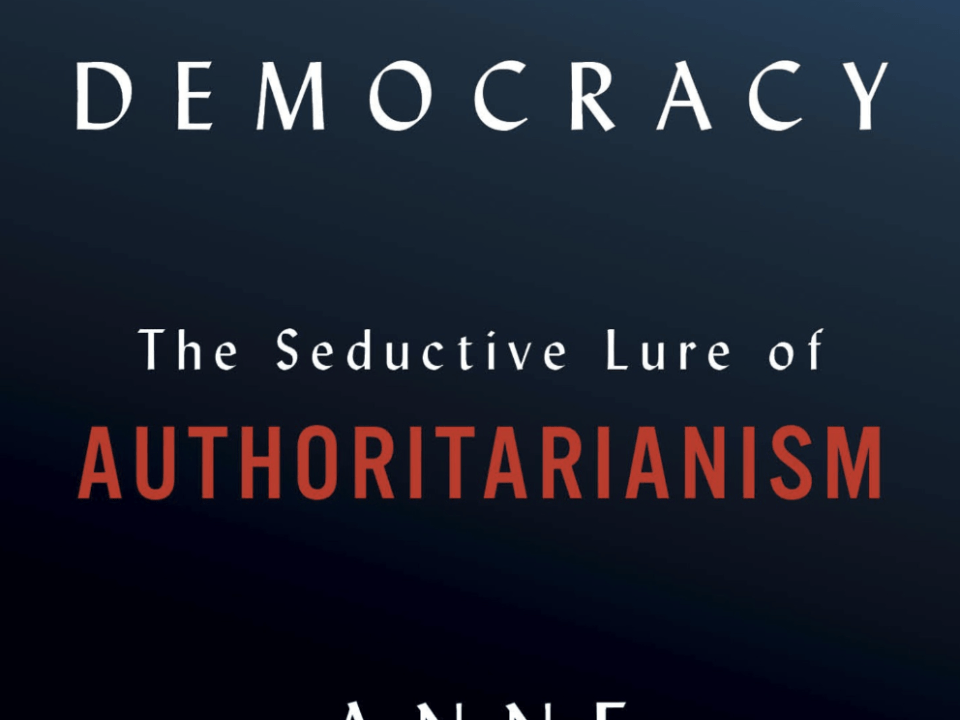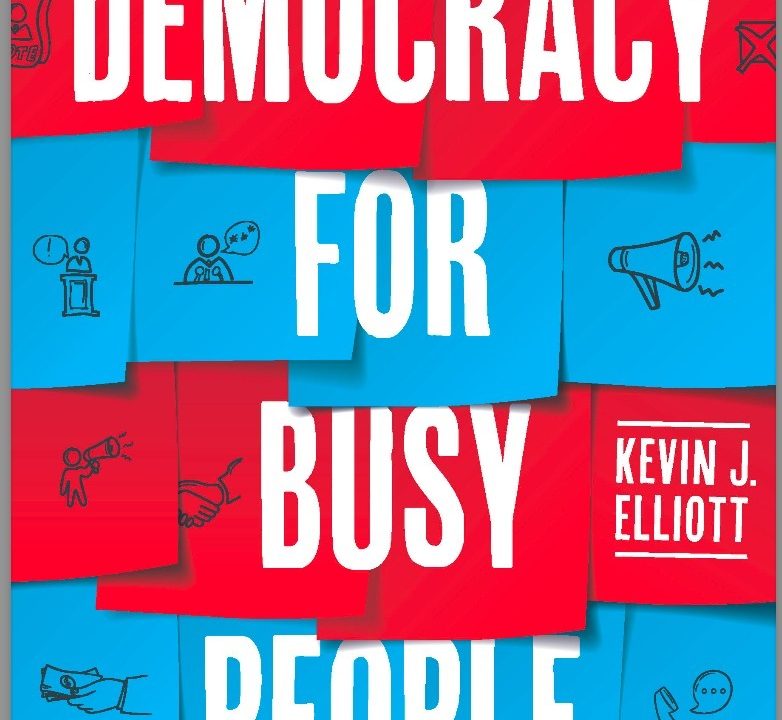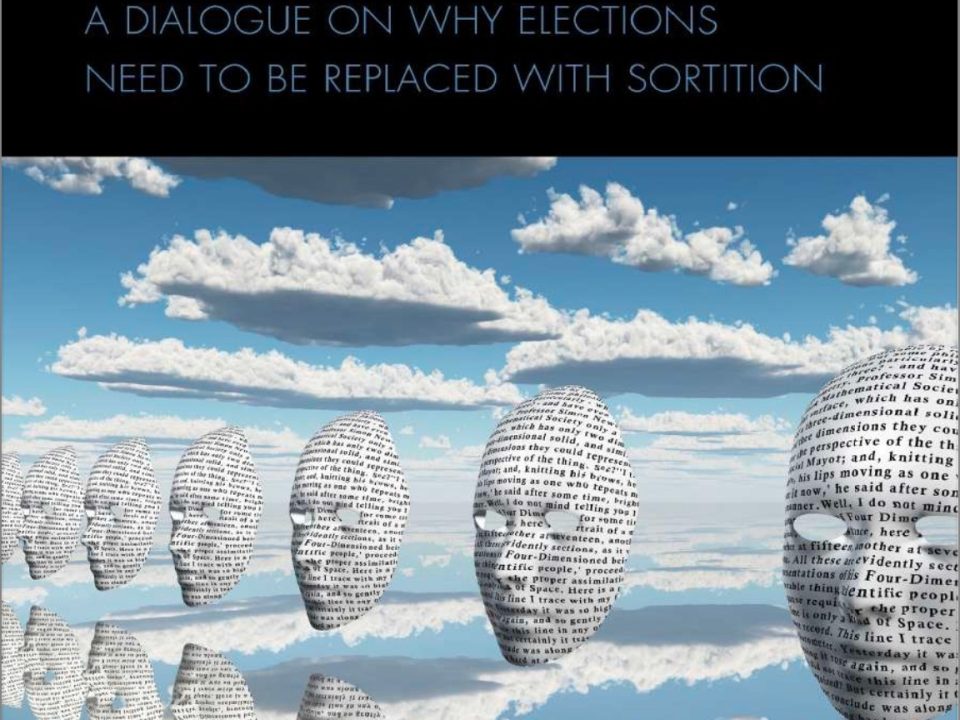Tidak Ada Demokrasi, Hanya Imajinasi
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor, 30.05.2020
#BincangBuku #43
“Democracy, as we’ve seen, is a deceptively simple concept that requires a robust set of supports to enact.”
“Plato’s warning about democracy devolving into tyranny rings chillingly prophetic. The promise of self-rule risks becoming not a promise but a curse, a self-destructive motor pushing toward destinations more volatile, divided, despotic, and mean.”
—Astra Taylor. “Democracy May Not Exist, but We’ll Miss It When It’s Gone.” 2020.
“The symbols of today enable the reality of tomorrow. Notice the swastikas and the other signs of hate. Do not look away, and do not get used to them. Remove them yourself and set an example for others to do so.”
—Timothy Snyder. “On Tyranny.” 2017
“In politics, being deceived is no excuse.”
“Dalam politik, ditipu bukan alasan.”
—LESZEK KOŁAKOWSKI
Apa itu demokrasi ketika seorang Ravio Patra mengritik pemerintah, lalu diretas ponselnya, sejumlah percakapannya dimanipulasi, dia dibawa ke kantor polisi? Apa arti demokrasi ketika seorang anak merdeka Said Didu dilaporkan ke polisi karena kritiknya pada pejabat publik? Apa arti demokrasi ketika seorang Farid Gaban mengritik pejabat publik karena preferensinya pada pihak swasta dianggap tidak pada tempatnya? Apa arti demokrasi ketika kalangan akademik dilarang berpikir bebas termasuk berdiskusi dalam konteks ketatanegaraan tentang pemecatan presiden di tengah pandemi? Apa arti demokrasi ketika Ruslan Buton ‘diamankan’ polisi karena dia meminta presiden mundur? Apa arti demokrasi ketika seorang kulit hitam, George Floyd, megap-megap dicekik lehernya dengan dengkul dan membawanya meregang nyawa, dan memicu kerusuhan? Apa arti demokrasi ketika demonstrasi dibayar dengan enam nyawa warga sipil? “A riot,” kata Martin Luther King, Jr. “is the language of the unheard.” Kerusuhan itu bisa bersumber dari kebuntuan saluran berpendapat warga negara. Bagaimana kekuasaan bisa mendengar suara warga negaranya jika berbicara saja dibungkam, bahkan berpikir saja dilarang?
Apa itu demokrasi?
Jika kita bertanya “What is democracy?” pada Google maka akan muncul 207,000,000 jawaban hanya dalam waktu 0.52 detik (diakses pada 30 Mei pada jam 20.48). Tetapi kalau kita tanya pada Astra Taylor maka jawabannya ada pada sejumlah 618 halaman buku yang ditulisnya, berjudul: “Democracy May Not Exist, but We’ll Miss It When It’s Gone” (2019). Kita akan membincangkan buku ini.
Kita seringkali tidak lagi mempertanyakan apa itu demokrasi karena merasa sudah ada dalam sebuah pemerintahan yang menganut demokrasi. Kita menerimanya sebagai apa adanya. Kita tidak lagi bertanya apapun tentang demokrasi. Ketika demokrasi telah menjadi jargon, menjadi kata-kata yang biasa digunakan maka itulah demokrasi. Apapun yang dialami dalam alam demokrasi mungkin, pikir kita, itulah demokrasi. Demokrasi tak bisa dilepaskan dari kosakata keadilan, kesetaraan, kebebasan, solidaritas, sosialisme, dan revolusi bergaung lebih dalam. Demokrasi juga menjadi bagian penting percakapan para anarkis dan pemimpin otoriter yang idealis sama-sama cenderung mengklaim “demokrasi” sebagai milik mereka sendiri, demokrasi yang berbeda.
Berkali-kali diskriminasi warga kulit hitam dalam penegakan hukum di Amerika Serikat mereka masih menyebutnya sebagai negara demokrasi. Venezuela dipuja-puji karena menuju negara demokratis kemudian dengan demokrasi pula mengantarkannya pada otoritarian. Kita tahu rezim otoriter Korea Utara nama resminya adalah “Democratic People’s Republic of North Korea.” Amerika Serikat melakukan intervensi militer dan memorakporandakan Irak atas nama membawa demokrasi pada negara itu. William Blum, seorang analis politik luar negeri non-mainstream, seorang jurnalis freelance, menuliskan dalam bukunya: “America’s Deadliest Export: Democracy – the Truth about US Foreign Policy and Everything Else” (2013). Demokrasi adalah komoditi paling mematikan yang diekspor Amerika Serikat.
Berabad-abad lalu Plato telah mengingatkan kemungkinan demokrasi terjerambab pada lingkaran tirani. Janji self-rule berisiko menjadi bukan janji, tetapi kutukan, motor penghancur diri yang mendorong tujuan lebih mudah diubah, terbelah, lalim, dan kejam.
Biasanya, demokrasi dikenal terdiri dari elemen ini: one person, one vote; dilaksanakan dalam pemilihan berkala; hak konstitusional; dan ekonomi pasar. Paling tidak di atas kertas, tidak ada kekurangan negara yang mengikuti konsepsi ini meskipun agak terbatas — oleh beberapa perkiraan, dengan mengutip Freedom House, Taylor mencatat delapan puluh satu negara beralih dari otoritarianisme ke demokrasi antara 1980 dan 2002. Namun penelitian terbaru mengungkapkan bahwa demokrasi, yang ditentukan oleh atribut-atribut sebelumnya, telah melemah di seluruh dunia selama dekade terakhir ini. Tujuh puluh satu negara mengalami penurunan dalam hak politik dan kebebasan sipil pada tahun 2017, yang membuat penurunan kebebasan global secara keseluruhan. Pada awal 2018, Indeks Demokrasi yang dikeluarkan the Economist, secara resmi menurunkan peringkat Amerika Serikat dari “demokrasi penuh” (full democracy) menjadi “cacat” (flawed democracy). Namun demokrasi tidak mundur dengan sendirinya atau dengan proses organik dan permanen. Demokrasi bisa terkikis, dirusak, diserang, atau dibiarkan layu. Jatuh ke dalam kehancuran dan keburukan berkat tindakan atau juga pengabaian manusia sehingga tidak peduli, lari dari tanggungjawab—sesuatu yang diperlukan dalam sistem self-government (p. 21).
Kita merasa mengerti soal demokrasi.
Seperti juga dirasakan oleh Taylor (p. 13), kata demokrasi ada di sekitar kita. Digunakan dalam hampir setiap konteks yang dapat dipikirkan: pemerintah, bisnis, teknologi, pendidikan, dan media. Namun pada saat yang sama, maknanya, dianggap jarang dipikirkan dengan serius. Banyak analis politik, penulis buku hingga tajuk berita meneriakkan dengan lantang dan cemas bahwa demokrasi sedang dalam “krisis.” Demokrasi dalam bahaya; Bagaimana demokrasi mati; Akankah demokrasi bisa bertahan? “Democracy in Crisis,” tulis Freedom House dalam laman utamanya pada 2018. Pada 2020 ini Frredom House memberi tajuk lamannya: Dropping the Democratic Facade, wajah demokrasi yang suram. Laporan Indeks Demokrasi 2019 dari The Economist Intelligence Unit diberi judul: Democracy Index 2019, A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest.
Cita-cita demokrasi, serta substansi praktisnya, bagi Taylor, sulit dipahami.
Pada tahun 2019 Astra Taylor membuat film dokumenter berjudul What Is Democracy? Film ini bisa didapatkan di berbagai channel online. Selama pembuatan film itu penulis yang juga aktifis ini makin memahami tentang demokrasi. Baginya demokrasi mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Konsepnya seperti sebuah jalan tersaput embun. Ketidakjelasan dan karakter konsep demokrasi, dan juga membingungkan, bagi Taylor, justru merupakan sumber kekuatan; “I have come to accept, and even appreciate, that there is no single definition I can stand behind that feels unconditionally conclusive,” tulisnya (p. 14).
Seperti kita pahami meski praktik demokrasi memiliki akar global yang luas, kata demokrasi datang dari Yunani kuno, dengan gagasan yang tampaknya sederhana: orang-orang (demo) memerintah atau memegang kekuasaan (kratos). Demokrasi adalah janji kekuasaan ada di tangan rakyat—sebuah janji yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dipenuhi karena implikasi dan ruang lingkupnya terus berubah. Selama berabad-abad konsepsi demokrasi kita telah berkembang dan berkembang, dengan demokrasi menjadi lebih inklusif dan kuat dalam banyak hal, namun yang dianggap sebagai rakyat, bagaimana mereka memerintah, dan di mana mereka melakukannya tetap abadi untuk diperdebatkan. Demokrasi merusak kestabilan legitimasi dan tujuannya sendiri dengan desain, menjadikan komponen intinya untuk diuji dan diawasi secara terus menerus.
Namun seperti diuraikan singkat sebelumnya, banyak penguasa menggunakan demokrasi sebagai tabir untuk mengelabui apa yang sebenarnya dilakukan: berkuasa atas nama rakyat, menindas atas nama rakyat dan korupsi atas nama rakyat.
Sebagai sebuah sistem kepemerintahan yang diklaim terbaik, demokrasi sama sekali tidak sempurna. Menurut Taylor, demokrasi yang sempurna mungkin sebenarnya tidak ada dan tidak akan pernah ada, tetapi itu tidak berarti kita tidak dapat membuat kemajuan ke arah itu, atau bahwa apa yang ada di dalamnya tidak dapat menghilang. Maka pertanyaan tentang apa itu demokrasi — dan, yang lebih penting, seperti apa itu — adalah pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan. Kita sebagai rakyat dan juga mereka sebagai penguasa harus bertanya, apa itu demokrasi. Semua pihak senantiasa bertanya itu agar peringatan Plato tidak menjadi kenyataan: demokrasi terperosok menjadi tirani. Dan itu, sialnya, telah terjadi di beberapa negara.
Harus diakui saat ini, banyak yang mempertanyakan demokrasi yang dipraktekkan. Kekecewaan, ketakutan, dan kemarahan pada sistem demokrasi yang menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, kemacetan politik, korupsi, perwakilan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan kurangnya alternatif yang berarti; kemarahan mereka yang membara pada dehumanisasi birokrasi, kemunafikan yang terang-terangan, dan pembungkaman suara berpendapat. Para pemimpin tidak bertanggungjawab dan para pemilih merasa bahwa pilihan mereka terbatas, sementara orang kaya terus bertambah kaya dan orang-orang biasa berebut untuk bertahan hidup. Di negara-negara demokrasi maju di seluruh dunia, semakin banyak orang yang bahkan tidak mau repot-repot memilih — hak yang banyak orang perjuangkan dan mati di bagian dunia yang lain.
Dalam catatan Taylor, kebanyakan orang Amerika akan mengatakan bahwa mereka hidup dalam demokrasi, tetapi hanya sedikit yang akan mengatakan bahwa mereka mempercayai pemerintah, sementara negara pada umumnya mengilhami reaksi negatif, mulai dari frustrasi hingga penghinaan dan kecurigaan. Ini seperti pengamatan Jean-Jacques Rousseau pada karyanya The Social Contract: “In a well-ordered city every man flies to the assemblies; under a bad government no one cares to stir a step to get to them.… As soon as any man says of the State What does it matter to me? the State may be given up for lost” (p. 16). Ya, di kota yang tertata rapi, setiap orang bisa berhimpun dengan senang. Di bawah pemerintahan yang buruk tidak ada yang peduli pada negara.
Dalam buku terbaru ini, Astra Taylor, yang sebelumnya telah menulis tiga buku “Examined Life: Excursions with Contemporary Thinkers (2009), Occupy! Scenes from Occupied America (co-editor, 2011) dan “The People’s Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age” (2014), memaparkan semacam perenungan seorang aktifis demokrasi. Buku “Democracy May Not Exist” sebagai pengingat bahwa kita adalah bagian dari kronik yang panjang, kompleks, dan terus berlangsung, apa pun tajuk utama perihal demokrasi pada hari itu atau siapa pun yang berkuasa.
Mengambil pendekatan yang lebih teoretis terhadap jalan demokrasi yang berkelok-kelok, berduri, dan sifatnya yang paradoksal juga dapat memberikan kenyamanan dan kepastian. Memerintah diri sendiri tidak pernah mudah dan tidak akan pernah terjadi. Selalu menjengkelkan dan tidak dapat diprediksi, demokrasi adalah proses yang melibatkan penilaian ulang, reflektif dan pembaruan tanpa akhir, bukan sebuah titik akhir yang kita capai sebelum semua selesai. Karena itu, buku ini adalah seruan Taylor yang tidak lazim, unik, dan demokratis untuk mendemokratisasi masyarakat dari bawah ke atas. Ini juga merupakan ekspresi dari keyakinannya bahwa kita tidak dapat memikirkan kembali demokrasi jika kita belum benar-benar memikirkannya. “We cannot rethink democracy if we haven’t really thought about it in the first place,” tulisnya dengan penuh renungan yang mendalam. Dari buku-buku tentang demokrasi, buku Taylor ini memang termasuk berbeda. Taylor menyadari kesulitan yang dihadapi oleh provokator demokrasi yang melihat demokrasi justru makin jauh dari yang dicita-citakan. Sepanjang jalan selalu terjadi pembajakan, manipulasi dan korupsi atas sistem itu dan atas nama sistem demokrasi. Apalagi ketika pada membahas demokrasi dalam konteks freedom/kebebasan dan equality/keadilan, kesetaraan (p.30).
Sebab dengan mengutip Danielle Allen: “Freedom requires political equality; political equality requires social equality and economic egalitarianism. You line the concepts up that way, and freedom and equality fit together like hand in glove.” Kebebasan membutuhkan kesetaraan politik; kesetaraan politik membutuhkan kesetaraan sosial dan egaliterisme ekonomi. Anda meletakkan konsep-konsep seperti itu, dan kebebasan dan kesetaraan cocok bersama seperti tangan dengan sarung tangannya.
Meskipun secara definisi atau interpretasi sangat sulit disatukan tetapi seruan demokrasi sesungguhnya menggema di seluruh dunia dalam konteks yang sangat berbeda. Menyatukan aktivis di Mesir dan Bahrain melawan otoritarianisme. Merekatkan optimisme mahasiswa berkumpul di Hong Kong di bawah “Gerakan Payung” (the Umbrella Movement) dan warga negara Eropa dan Amerika Serikat yang memiliki hak istimewa yang konon mewakili demokrasi liberal paling maju di dunia. Sementara pemberontak di Alun-alun Tahrir Mesir atau Taman Taksim Gezi di Turki mungkin menyerukan hak asasi manusia dan pemilihan umum yang adil, konstituensi inti kaum anarkis di Occupy Wall Street memahami demokrasi yang sesungguhnya berarti menjalankan segalanya dengan konsensus.
Orang akan membuat keputusan untuk diri mereka sendiri, tanpa mendelegasikan tugas kepada perwakilan, dan semua orang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak peduli seberapa melelahkan. Kebulatan suara adalah tujuannya. Sebuah primer yang dibagikan di situs Majelis Umum Kota New York menjelaskan, “Konsensus adalah proses berpikir kreatif: Ketika kita memilih, kita memutuskan di antara dua alternatif. Dengan konsensus, kita mengambil sebuah isu, mendengar berbagai antusiasme, gagasan, dan kekhawatiran tentangnya, dan mensintesis proposal yang paling sesuai dengan visi semua orang.”
Di jantung demokrasi ada abstraksi berbentuk “rakyat,” suatu entitas yang diberdayakan untuk memerintah tetapi tidak ada secara nyata. Hanya hadir melalui representasi-representasi dan kemudian ketika representasi itu mewujud dalam trias politika maka rakyat hanya menjadi alasan untuk apapun—yang seringkali buruk— untuk memenuhi kepentingan sendiri dan kelompoknya. Padahal tentu saja untuk memiliki demokrasi maka harus ada kita, rakyat.
Konstitusi Amerika Serikat, demikian paparan Taylor (p. 147), mencerminkan inkoherensi mendasar soal rakyat ini ketika mengidentifikasi tiga populasi berbeda yang menghuni benua yang sama: “Orang” atau mereka yang berhak atas hak dan kebebasan; “Orang lain,” atau yang diperbudak; dan orang Indian, yang memiliki kedaulatan suku dan dikecualikan dari badan politik. Terlepas dari, atau karena, ambiguitas konseptual mendasar ini, setiap komunitas demokratis, tidak peduli seberapa besar atau kecil, harus berjuang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan batas-batasnya. Pemerintahan sendiri adalah negosiasi abadi tentang siapa yang dimasukkan dan siapa yang dikecualikan, siapa kita dan siapa mereka. Batas-batas ‘demos’ meluas dan berkontraksi, dan “rakyat” dapat dipanggil untuk melayani tujuan yang berbeda dan sering bertentangan.
Pada 1513 Machiavelli puyeng memikirkan soal skala dalam republik (p. 416). Pikiran-pikirannya dalam diskursus sangat memperhatikan peran republik-republik kecil dalam kekaisaran kolosal, khususnya kekaisaran Roma. Sebuah komunitas yang cukup kecil untuk memerintah dirinya sendiri sebagai sebuah republik, menurutnya, kemungkinan akan terlalu kecil untuk mengatur pertahanannya sendiri. Tetapi, jika cukup besar untuk secara efektif melindungi dirinya sendiri, republik semacam itu akan terganggu oleh “kebingungan” internal dan “keributan” dan pada akhirnya akan jatuh ke despotisme, totaliter. Pertumbuhan dan kesuksesan, dalam perhitungan Machiavelli yang hebat itu, mengarah langsung ke Ceasarisme. Dia menghianati pikirannya sendiri dan meninggalkan republik yang kecil untuk merangkul “kebesaran Romawi.”
Analogi “negara-negara kecil pasti hancur, mengapa tidak pergi dan bergabung dengan kekaisaran” bisa menjadi telada dan refleksi gerakan-gerakan kecil pro-demokrasi di manapun, termasuk di Indonesia. “Republik” pro-demokrasi selalu tergoda dengan pikiran meninggalkan republik yang kecil dan bergabung dengan imperium. Para aktifis yang mudah tergoda akan masuk ke imperium dan melupakan sama sekali perjuangan republiknya.
Buku ini terdiri dari delapan bagian yang menguraikan berbagai konteks. Pada Bagian Pertama misalnya diuraikan mengenai Freedom/Equality; Bagian Dua membahas demokrasi dalam konteks (Confllict/Concensus) hingga Bagian Tujuh (Local/Global) dan ditutup dengan Bagian Delapan yang membahas demokrasi saat ini dan ke depan (Present/Future).
Sebagai penutup, buku ini memang memaksa kita untuk mengajukan beragam pertanyaan. Apakah demokrasi merupakan sarana atau tujuan, suatu proses atau serangkaian hasil yang diinginkan? Bagaimana jika hasil-hasil itu, apa pun itu – perdamaian, kemakmuran, kesetaraan, kebebasan, warga negara yang terlibat – dapat dicapai dengan cara-cara non-demokratis? Dalam bidang kehidupan apa seharusnya prinsip-prinsip demokrasi berlaku? Jika demokrasi berarti diperintah oleh rakyat, apa artinya memerintah dan siapa yang dianggap sebagai rakyat?
Paradoks inheren demokrasi seringkali tidak disebutkan namanya dan tidak dikenali. Menjelajahi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Democracy May Not Exist menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mungkin, apa yang kita inginkan, mengapa demokrasi begitu sulit untuk diwujudkan, dan mengapa itu layak diperjuangkan.
Demokrasi mungkin memang tidak akan terwujud nyata. Tetapi kita akan bisa merasakan ada tidaknya keadilan, kita akan mampu mencerna ada tidaknya kebebasan, kita akan rasakan ada tidaknya getaran solidaritas pada momentum tertentu. Dari situlah kita bisa merasakan kehadiran demokrasi. Jika kita tak lagi merasakan semua itu. Tidak ada demokrasi, hanya imajinasi. Mungkin demokrasi telah pergi. Dan kita akan merasa kehilangan.