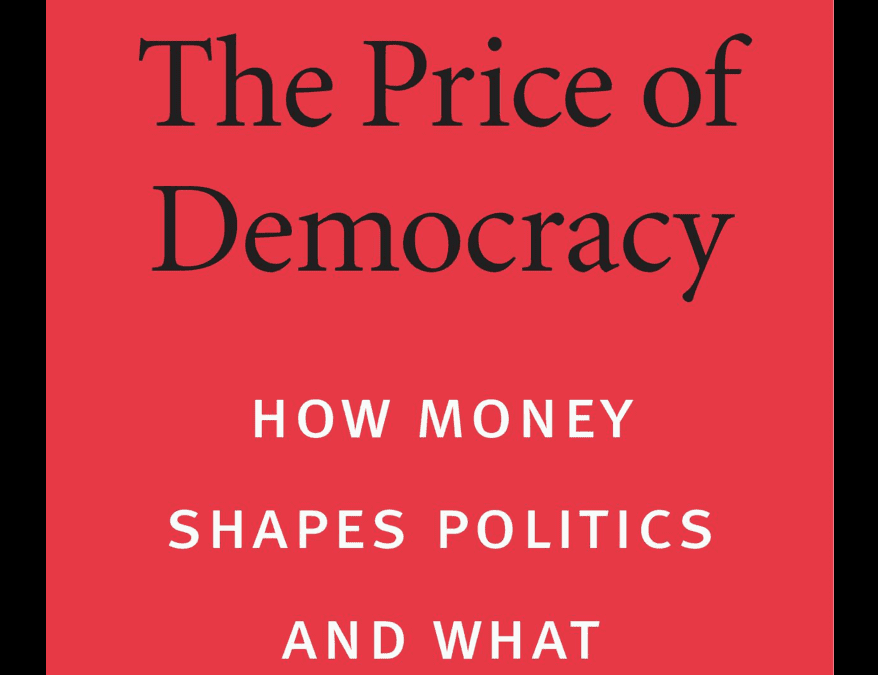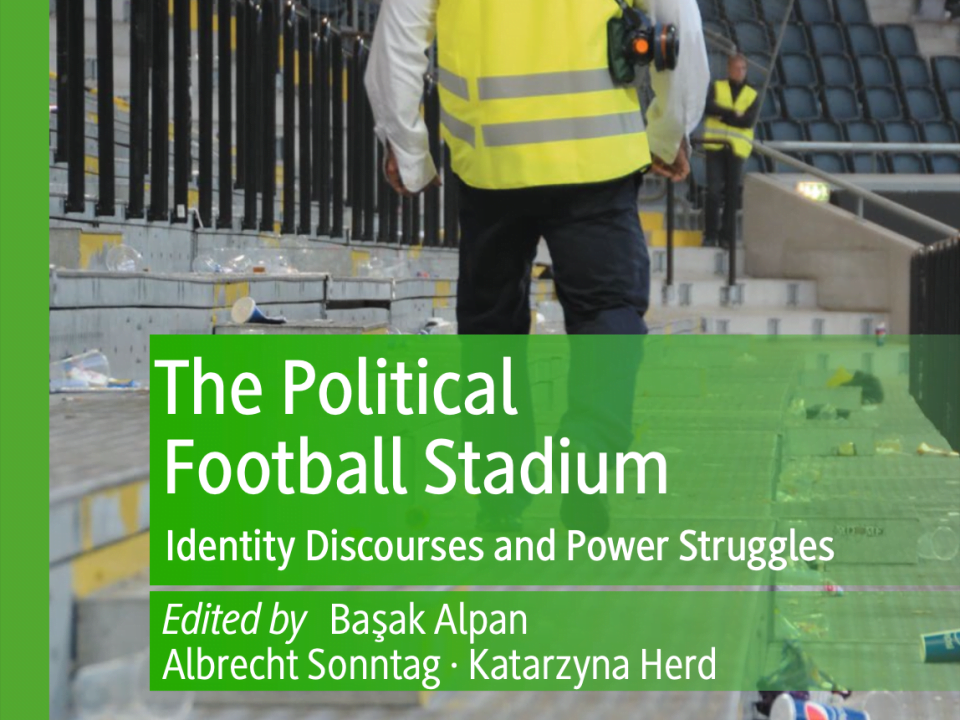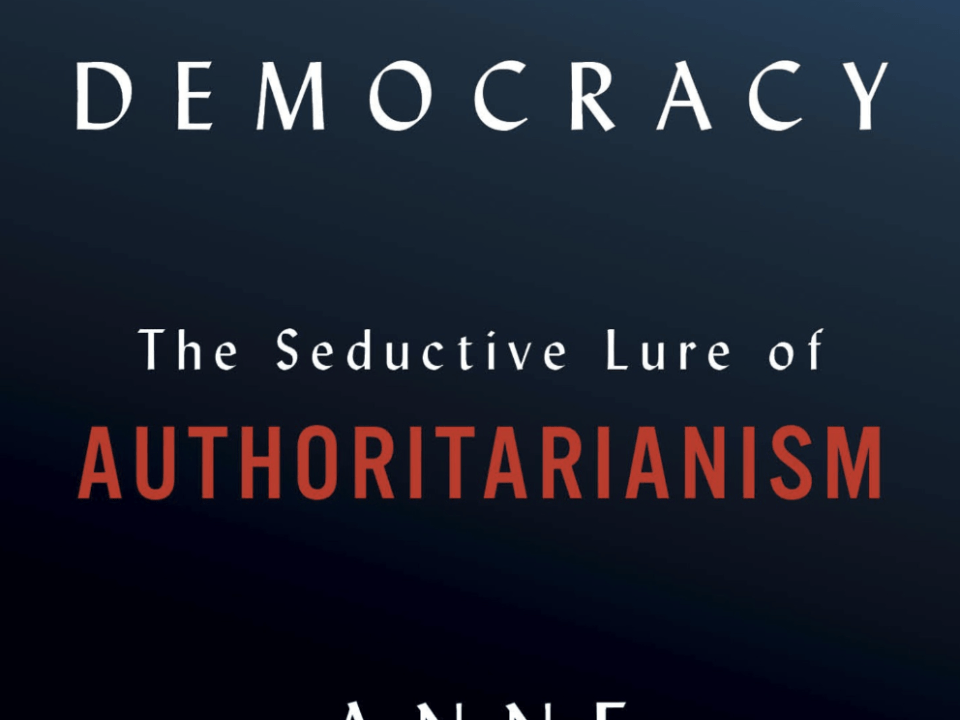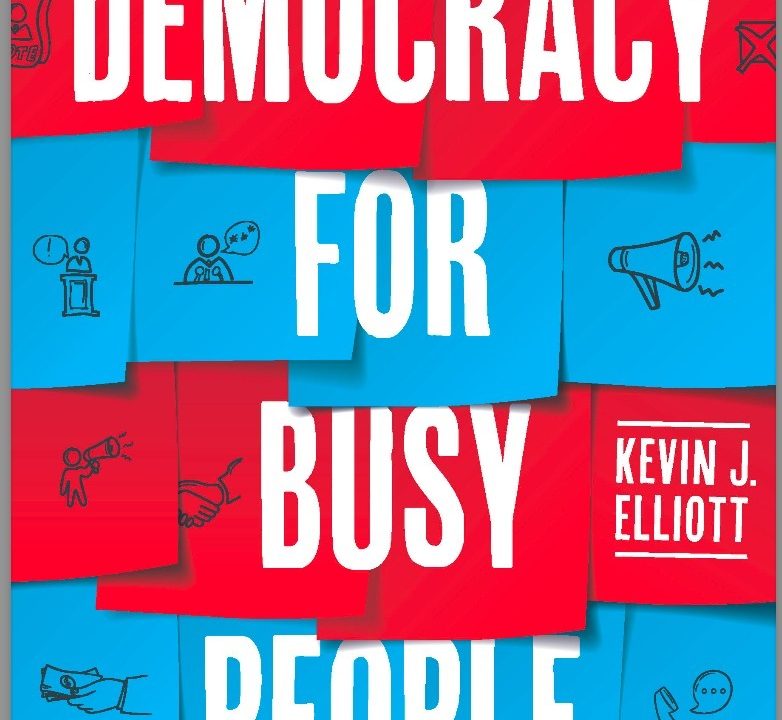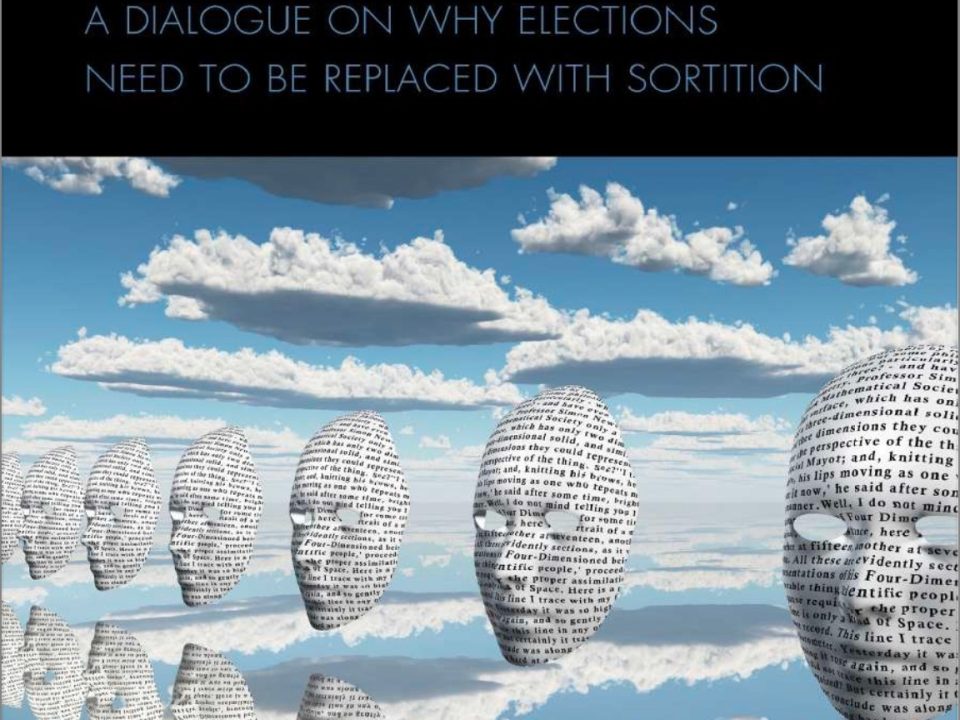“Democratic Voucher,” Melawan Korupsi Demokrasi
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor, 27.05.2020
#BincangBuku #42
“Democracy is a messy concept.”
“Democracy as a system in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote” (Joseph Schumpeter).
—RICHARD S. KATZ AND PETER MAIR: Democracy and the Cartelization of Political Parties (2018).
“They have achieved this through the power of their wallets—whether by donating to political parties and election campaigns, by financing think tanks and other foundations, or by acquiring an equity stake in influential news media.”
—Julia Cagé and Patrick Camiller. “The Price of Democracy: How Money Shapes Politics and What to Do about It.” 2020.
“…truth under the conditions of modern democracy has always been fragile.”
—Sophia Rosenfeld. “Democracy and Truth.” 2019.
“As long as there have been elections, there has been (often justified) fear of electoral fraud driven by corruption. Buying votes, buying politicians, manipulating the media,” begitulah pernyataan Julia Cagé yang seolah mewakili banyak warga dunia yang frustrasi terhadap praktek koruptif demokrasi (The Price of Democracy, 2020). Selama ada pemilihan umum, korupsi berkembang subur. Itulah yang menjadi keprihatinan Cage dalam buku yang menyajikan banyak data soal angka-angka harga demokrasi. Mulai dari kontribusi dana privat dan publik untuk partai, di Perancis, Inggris, Jerman dan Amerika Serikat hingga persentase kontribusi gaji yang disetorkan anggota parlemen pada partai masing-masing. Money politics ada dimanapun. Apalagi di Indonesia. Dan semakin tumbuh subur kalau itu tidak diatur dengan regulasi yang ketat dan inovatif.
Sejak berdiri pada Desember 2002, lembaga antirasuah KPK mencatat telah memproses 119 Kepala Daerah yang tersandung kasus korupsi (Data per 7 Oktober 2019). Dari 119 orang Kepala Daerah yang diproses KPK, 47 diantaranya dari kegiatan tangkap tangan atau 39,4 persen. Pejabat-pejabat publik yang tertangkap ini adalah contoh nyata dari harga sebuah demokrasi.
Dana besar yang dibutuhkan para kontestan pemilu bisa mencapai lebih dari sepuluh digit. Tidak tanggung-tanggung praktek politik uang seperti itu terjadi mulai dari pemilihan Kepala Desa, Cawolkot, Cabup, Cagub, Capres dan Cawapres. Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam bukunya Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia memaparkan dengan gamblang praktek bobrok demokrasi di Indonesia. Selalu ada persekongkolan antara pengusaha dan politisi. Semua orang mafhum, dan semua orang tidak mau membicarakannya di arena publik.
Dan Aspinall dan Berenschot mampu membongkar sistem daftar klientel ini dengan melakukan penelitian langsung yang luas, mendalam. Data dihimpun dari wawancara dengan para pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten, kota, dan provinsi, serta survei terhadap 509 pakar (jurnalis, cendekiawan, tim kampanye, dan pemimpin masyarakat sipil) di 38 kabupaten di 16 provinsi. Hasilnya cukup mengejutkan betapa banyak responden bersedia mengatakan yang dialami, misalnya memberikan harga suara tertentu dan mengungkapkan kemarahan ketika ‘kesepakatan’ itu dilanggar. Seorang kandidat menjelaskan bahwa ia mendekati berbagai partai politik untuk mendukung pencalonannya; setelah mengutarakan visinya, “….mereka hanya bertanya kepada saya berapa banyak uang yang bersedia saya bayarkan” (p. 80). Transparansi politik uang di Indonesia menjadi bacaan yang bagus: “..dia memberi begitu banyak sapi, dan mereka tidak memilihnya” (p. 144)!
Aspinall dan Berenschot mengambil contoh yang terjadi di Kalimantan Tengah (p. 209). Pengusaha (seringkali juga anggota keluarga) menyumbangkan uang dengan harapan bahwa kandidat yang berhasil akan membalas budi dengan membantu mereka mendapatkan izin untuk konversi hutan dan perusahaan lain. Investigasi terbaru yang dikutip dari laporan Gecko Project (2017) di Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah) menunjukkan, politisi sering lebih suka memberikan hak ekonomi seperti itu pada anggota keluarga untuk memastikan bahwa mereka akan memperoleh sebagian besar keuntungan. Kolusi antara politisi dan wirausahawan di tempat-tempat seperti Kalimantan Tengah merusak efektivitas perencanaan tata ruang dan peraturan lingkungan. Pemerintah daerah dengan senang hati dan kreatif menafsirkan rezim tataguna tanah di Indonesia yang sudah kabur dan bertentangan sehingga bisa menguntungkan perusahaan besar (McCarthy 2004 dalam Aspinall dan Berenschot, 2019). Banyak uang dihasilkan dengan menutup mata ketika perkebunan kelapa sawit kekurangan dokumen yang diperlukan.
Lebih jauh Aspinall dan Berenschot mengungkapkan di tempat seperti Kalimantan Tengah, bahkan sebelum kampanye pemilihan umum dimulai, para calon bupati harus mengeluarkan dana hingga US $ 500.000 untuk membeli nominasi partai politik. Untuk kontestasi gubernur, nilainya bisa mencapai hingga $ 2 juta. Lalu ada biaya operasional normal untuk menjalankan kampanye pemilihan, serta biaya membangun tim sukses dan memenangkan komunitas dengan menyediakan barang-barang atau uang dan membeli suara. Aspinall dan Berenschot memperkirakan bahwa, rata-rata, bupati yang menang di kabupaten mereka menghabiskan 28 miliar rupiah (sekitar $ 2,5 juta) untuk kampanye pemilihannya. Perkiraan berkisar dari 10 miliar rupiah di daerah berpenghasilan rendah seperti Nusa Tenggara Timur hingga 40 miliar rupiah di Kalimantan Timur yang kaya sumberdaya alam (yaitu, antara $ 880.000 dan $ 3,5 juta). Perkiraan rata-rata menurut pakar dalam timnya tentang biaya kampanye gubernur terpilih adalah 166 miliar rupiah (sekitar $ 15 juta).
Hal serupa terjadi di India. Christophe Jaffrelot, seorang ilmuwan politik Perancis dengan spesialisasi Asia Selatan khususnya India dan Pakistan, menjelaskan, seperti dikutip Cage, korupsi sistematis dari kelas politik di India karena mahalnya pemilihan umum. Menurut perkiraannya, seorang calon harus datang dengan 130 hingga 140 juta rupee (sekitar 1,7 juta euro atau setara dengan 27.5 M) untuk dipilih di majelis rendah Parlemen. Bagaimana dana sejumlah itu bisa diperoleh? Dengan memasuki bisnis (dan terjebloslah mereka di dalamnya): “Kita menghadapi situasi yang rumit hari ini. Anda tidak akan pernah tahu apakah seorang deputi itu seorang pengusaha atau politisi ”(wawancara di La Vie des idées, Februari 2018).”
Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kasus demi kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan para politisi menujukkan dengan terang tentang hal itu. Belum lagi kalau dilihat dari ‘kebijakan-kebijakan publik’ yang nongol dari gedung parlemen atau dari Istana. Makin sulit membedakan apakah itu kebijakan publik atau kebijakan privat?
Tetapi biaya demokrasi juga menjadi persoalan di negara-negara yang mempunyai index demokrasi yang jauh lebih baik daripada Indonesia. Misalnya Amerika dan Eropa. Demokrasi pasti membutuhkan biaya. Julia Cagé dan Patrick Camiller dalam buku barunya, “The Price of Democracy: How Money Shapes Politics and What to Do about It” (2020) membahas soal harga sebuah demokrasi dan solusi yang ditawarkan agar demokrasi menjadi sistem kepemerintahan yang adil dan jujur.
DEMOKRASI bertumpu pada janji tentang kesetaraan, yang terlalu sering berantakan jika berhadapan dengan dinding uang. Kita cenderung lupa bahwa menyediakan demokrasi harus dibayar mahal. Bukan selalu berarti harga sangat tinggi dalam istilah absolut – yang menunjukkan bahwa solusi kolektif yang rasional memungkinkan ditemukan. Tetapi jika biaya itu didistribusikan sangat tidak merata, dan jika bobot uang swasta dalam total dana sangat tidak dibatasi, maka seluruh sistem dalam bahaya, demikian menurut Cagé (p. 87).
Sebagai seorang ekonom Perancis dengan spesialisasi ekonomi pembangunan, ekonomi politik dan sejarah ekonomi, Cagé mengulas bukunya dengan sudut pandang ekonomi dan politik, menjadikan buku ini menarik untuk memahami peran kepentingan ekonomi dalam politik. Ia mengupas dengan lengkap. Evolusi pembiayaan pemilu dalam beberapa dekade terakhir marak di sejumlah negara, dimulai dengan Perancis, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus, pembiayaan ini terutama dibebankan kepada para kandidat itu sendiri, yang kemudian diganti oleh negara secara penuh atau sebagian; ini terjadi terutama di negara-negara yang menggunakan sistem first-past-the-post, dengan satu anggota parlemen per daerah pemilihan. Di negara-negara dengan sistem perwakilan proporsional, partai-partai mendukung sebagian besar pembiayaan kampanye dan berfungsi sebagai badan perantara antara kas publik dan kandidat. “Pendanaan kampanye dan pendanaan partai: kepala dan ekor dari koin demokrasi, yang, seperti dalam kisah peri Perrault tentang keledai dengan kotoran emas, terus berlipat ganda.
Namun, bagi Cagé, yang benar-benar diperhitungkan adalah siapa yang menghasilkan koin. Pendanaan publik atau sumbangan pribadi: tergantung pada tempatnya, tingkat pembiayaan kampanye yang sama dapat mencerminkan kenyataan yang berlawanan secara diametral. Karena dalam politik, kotoran keledai jarang diam ketika terbuat dari emas. Dan berat sumbangan pribadi terbukti sangat berat untuk ditanggung. Selalu akan ada balas budi di kemudian hari.
Demokrasi adalah soal pemilihan. Apa susahnya sih memasukkan kertas suara ke dalam kotak? Pergi ke tempat pemungutan suara suatu hari adalah hal yang lumrah dan kadng juga menyenangkan. Tidak terpikirkan adalah adanya transaksi logika pasar dalam proses itu. Di Indonesia TPS semarak dengan berbagai atribut unik dan beragam daya atarik kreatif. Panitia adalah warga negara biasa, sama seperti Anda atau saya, yang telah memilih untuk memberikan sedikit waktu untuk demokrasi. Satu-satunya syarat adalah nama kita harus ada dalam daftar pemilih. Tidak ada keuntungan langsung apapun yang kita dapatkan — kecuali kepuasan mengambil bagian dalam pesta demokrasi.
Lalu, berapa biaya pemilu di mancanegara? Pada tahun 2016, seorang kandidat yang menang untuk Senat AS menghabiskan rata-rata lebih dari $ 10 juta. Di Perancis, kandidat parlemen rata-rata menyediakan jauh lebih sedikit: sedikit lebih dari 18.000 euro pada tahun 2012, walaupun angka itu naik menjadi 41.000 euro untuk pemenang yang beruntung. Di Inggris — di mana, seperti halnya di Prancis, ada batas tertinggi untuk pengeluaran kampanye — rata-rata untuk pemilihan umum 2015 adalah 4.000 euro, naik menjadi 10.000 euro bagi mereka yang berada di puncak. Di Indonesia sudah disebutkan sebelumnya.
Perbedaan antara Jerman dan Inggris Raya dan Prancis — di mana pembelanjaan dibatasi oleh undang-undang, terutama dalam periode pemilihan umum — sangat mencolok di sisi kiri dan kanan, khususnya dalam hal total pengeluaran tahunan. Rata-rata, SPD menghabiskan 2,6 kali lebih banyak per tahun daripada Partai Sosialis Prancis (PS) selama periode 2012-2016, dan perbedaannya sama antara CDU dan the French Républicains. Menurut Cagé pola ini juga tidak aneh karena pihak “besar”, karena Partai Hijau Jerman menghabiskan rata-rata tahunan 35,5 juta euro selama periode ini, atau empat kali lebih banyak daripada Partai Hijau Prancis (8,8 juta euro). Tentu saja, Jerman memiliki populasi yang lebih besar daripada Prancis, tetapi ini tidak berarti cukup untuk menjelaskan perbedaan dalam pengeluaran. Per kepala populasi orang dewasa, pengeluaran rata-rata tahunan SPD selama tahun-tahun ini (2,40 euro) dua kali lebih tinggi dari rekan Prancisnya (p. 111).
Pemilihan umum selalu memerlukan biaya banyak. Atau lebih tepatnya, sejumlah negara demokrasi Barat telah memilih untuk mengalokasikan jumlah uang yang besar, terkadang sangat besar. Perbedaan di antara negara-negara mencerminkan peraturan mereka yang mengatur jumlah yang diizinkan untuk dibelanjakan oleh kandidat. Tetapi mereka juga mencerminkan berbagai peraturan yang mengatur apa yang diizinkan untuk disumbangkan oleh individu dan/atau perusahaan (p. 114). Pemilu di Indonesia tahun 2019 yang dilakukan serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) memakan dana sejumlah Rp25,59 triliun. Hasilnya?
Di Indonesia, misalnya, sumbangan dana kampanye diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terdapat dua sumber kategori sumbangan, yaitu berasal dari Badan Hukum Usaha dan Perseorangan. Sumbangan yang berasal dari Badan Hukum Usaha atau corporate maksimal Rp 25 miliar sekali nyumbang. Perseorangan boleh nyumbang maksimal Rp 2,5 miliar.
Sedangkan, untuk calon anggota DPD RI sumbangan perseorangan jumlahnya Rp 750 juta. Kemudian, kalau Badan Hukum Usaha atau corporate Rp 1,5 miliar.
Semua pihak asing dilarang memberi sumbangan. Sumbangan kampanye juga dilarang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, Anggaran Desa dan Badan Usaha Milik Desa.
Begitulah biaya sebenarnya dari pemilihan: pengeluaran kampanye oleh para kandidat ditambah pengeluaran oleh partai-partai dan kelompok-kelompok kepentingan. Uang yang masing-masing diletakkan di atas meja untuk meyakinkan para pemilih tentang bagaimana mereka harus memilih dihabiskan dengan berbagai metode seperti pertemuan publik, selebaran, kampanye dari rumah ke rumah, kampanye publisitas, dan – pada tingkat yang lebih tinggi – pembelian langsung tempat dan visibilitas di media dan jejaring sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, pengeluaran semacam itu terus tumbuh di sejumlah negara demokrasi. Kesenjangan antara pengeluaran untuk pemilu di Amerika Serikat dan di Inggris atau Prancis jelas bukan karena perbedaan budaya (p. 114). Atau karena perbedaan selera yang lebih besar untuk kontes pemilihan di sisi lain Atlantik. Jika jumlah yang dihabiskan bisa disamakan dengan tingkat minat populer dalam pemilihan, maka pengeluaran tertinggi harus sejalan dengan tingkat komitmen tertinggi. Tetapi dari semua negara Barat, Amerika Serikat memiliki jumlah pemilih terendah. Perbedaan dalam biaya kampanye bukanlah perbedaan budaya; itu adalah hasil langsung dari undang-undang pemilu yang memiliki, dan sering diabaikan, efek pada struktur proses demokrasi.
Seberapa besar dana calon anggota parlemen untuk bisa menang? Tanya Cagé. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita perlu bertanya yang lain: Berapa jumlah kandidat yang diizinkan untuk ikut kontes? Jumlahnya tidak hanya bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi juga berfluktuasi tajam dari periode ke periode.
Fakta pertama, jika tidak ada batasan yang ditetapkan, para kandidat cenderung tidak membatasi diri dan mereka seperti pengemis yang mampu menghabiskan sejumlah uang yang diyakini. Sejarah telah membuktikan hal itu pada abad kesembilan belas (p. 91). Di Inggris, salah satu negara pertama yang membatasi pengeluaran pemilu dengan Undang-Undang Praktik (Pencegahan) Korupsi tahun 1883, total pengeluaran kandidat parlemen (dinyatakan dalam euro hari ini, disesuaikan dengan inflasi) secara teratur melebihi 200 juta euro: 191 juta pada tahun 1868, 184 juta pada tahun 1874, dan 228 juta pada tahun 1880. “Ini lebih dari sepuluh kali jumlah yang dihabiskan hari ini — meskipun jumlah pemilih lebih sedikit, dan pendapatan nasional riil per orang dewasa hampir lima kali lebih rendah. Sebelum plafon pengeluaran pemilu ditetapkan pada tahun 1883, batas maksimal itu kadang-kadang bisa naik di atas seratus euro per pemilih. Hari ini, sebagai perbandingan, jumlah total yang dihabiskan per pemilih yang terdaftar untuk pemilihan parlemen Inggris bervariasi antara 0,40 dan 0,50 euro per pemilihan.
Angka pengeluaran pemilu ini bahkan lebih jelas jika dinyatakan sebagai proporsi pendapatan nasional per orang dewasa: pada tahun 1868, setiap kandidat menghabiskan rata-rata sedikit lebih dari 185.000 euro, atau tiga puluh kali pendapatan nasional tahunan per kepala orang dewasa dari populasi! Ini menunjukkan bahwa — lebih dari dan di atas pembatasan hak pilih — hanya warga terkaya yang dapat menggapai kursi di Parlemen. Namun hari ini, pengeluaran rata-rata seorang kandidat dalam pemilihan parlemen mewakili hampir tidak lebih dari 10 persen dari pendapatan nasional per kapita. Dengan kata lain, dinyatakan dalam hal pendapatan nasional per kepala penduduk dewasa, rata-rata pengeluaran kandidat telah dibagi dengan 262 selama 150 tahun terakhir.
Mengapa dan bagaimana sistem pembiayaan dan representasi politik di Eropa dan Amerika Utara memberi yang kaya pengaruh besar pada—dan melemahkan— demokrasi, dan apa yang dapat kita lakukan untuk itu.
Satu orang, satu suara. Secara teori, setiap orang dalam demokrasi memiliki kekuatan yang sama untuk memutuskan pemilihan. Tapi pada kenyataannya, hasil politik sangat ditentukan oleh logika satu dolar, satu suara. Kita pasrah begitu saja pada kekuatan politik uang. Tetapi apakah harus terus menerus seperti ini? Dalam The Price of Democracy, Julia Cagé, ekonom muda kelahiran 1984 lulusan Harvard University, yang juga istri ekonom kondang Thomas Piketty ini, menggabungkan analisis ekonomi dan sejarah dengan teori politik untuk menunjukkan betapa dalamnya sistem demokrasi di Amerika Utara dan Eropa, mulai dari lembaga think tank dan media hingga kampanye pemilihan umum, dibentuk oleh uang. Dia mengusulkan reformasi mendasar untuk membawa demokrasi kembali sejalan dengan janji egaliternya.
Dalam buku setebal 769 halaman itu Cagé menunjukkan bagaimana berbagai negara telah mencoba mengembangkan undang-undang untuk mengekang kekuatan uang pribadi/swasta dan mengembangkan sistem publik untuk mendanai kampanye dan partai. Namun upaya ini tidak koheren dan tidak sistematis. Dia menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk belajar dari eksperimen ini di Amerika Serikat, Eropa, dan di tempat lain untuk merancang sistem yang lebih baik yang akan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan politik. Menetapkan batasan ketat pada sumbangan pribadi dan menciptakan sistem kupon publik (public voucher system) untuk memberi setiap pemilih jumlah yang sama untuk dibelanjakan dalam mendukung partai politik. Lebih radikal lagi, Cagé berpendapat bahwa sebagian kecil kursi di majelis parlemen harus disisihkan untuk perwakilan dari kelompok sosial ekonomi yang kurang beruntung.
Pada saat kekecewaan politik yang meluas, seperti halnya di Indonesia, The Price of Democracy adalah pengingat kuat akan masalah yang kita hadapi dan panduan inspirasional untuk potensi reformasi, kalau kita mau. Dengan ongkos demokrasi yang mahal itu dan membuka peluang korupsi pada proses-proses demokrasi maka apa yang harus dilakukan?
Demokrasi dalam beberapa tahun terakhir ini memang limbung. Para ilmuwan politik mengamati dengan seksama ancaman menurunkan kualitas demokrasi secara global. Beberapa pengamat dan ilmuwan politik melontarkan gagasan-gagasan DEMOKRASI PARTISIPATIF, demokrasi kooperatif, demokrasi deliberatif, demokrasi permanen, demokrasi semi-langsung atau civic-tech-democracy, demokrasi 2.0 atau 3.0, demokrasi seleksi acak — pasti ada banyak proposal tentang cara membangun kembali sistem politik kita. Cagé mencatat banyak peneliti, politisi, dan warga biasa yang berpartisipasi dalam debat publik telah memikirkan masalah demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan. “Satu orang, satu suara”: ungkapan itu tampaknya sudah ketinggalan zaman, dan jumlah partisipasi pemilih yang rendah pada tiap pemilihan umum adalah isyarat betapa dalam ketidakpercayaan rakyat kini.
Apakah sudah terlalu terlambat? Cagé yang pada tahun 2015 menerbitkan buku, Saving the Media: Capitalism, Crowdfunding, and Democracy itu dengan tegas mengatakan “Tidak” (p. 503). Masih banyak yang bisa dikatakan dan dilakukan — karena alasan sederhana bahwa sejarah demokrasi baru saja dimulai. Pembelajaran apakah yang kita peroleh dalam demokrasi elektoral beberapa dekade masa lalu, dan terutama untuk masa depan, berabad-abad dalam sejarah manusia? Tidak semuanya telah selesai, dan penting untuk memulai dengan mengeksolorasi beragam gagasan yang ada untuk demokrasi partisipatif, percobaan sebelumnya yang sukses dan banyak juga tidak berhasil. “Ini akan membantu kita membangun model yang benar-benar inovatif untuk demokrasi abad ke-21, yang mengambil pelajaran dari masa lalu sehingga kita bisa lebih siap untuk masa depan.”
The Price of Democracy menegaskan selama masalah dana kampanye belum terpecahkan, inisiatif warga akan menjadi inisiatif yang dikangkangi. Kebutaan total terhadap masalah pendanaan ini, dalam pandangan Cagé, adalah kesalahan besar yang dibuat oleh banyak ahli teori demokrasi langsung (atau demokrasi “permanen” atau “berkelanjutan”, seperti yang kadang-kadang disebut).
Diantara beragam proposal baru untuk mereformasi demokrasi itu Cage mendukung gagasan Democratic Voucher. Democratic Voucher ini bukanlah hal yang baru. Pertama kali diperkenalkan oleh
Lawrence Lessig. Namun perlu dicatat bahwa Lessig bukan satu-satunya yang memperjuangkan gagasan “voucher demokrasi” ini. Dalam Plutocrats United (Yale University Press, 2016), Richard Hasen keduanya mengusulkan agar setiap warga negara AS harus diberi voucher untuk mendanai kampanye pemilihan — atau, lebih tepatnya, voucher $ 100 setiap dua tahun, bertepatan dengan siklus pemilihan — dan berpendapat untuk pembatasan maksimal dikenakan pada pembiayaan pemilu dan kontribusi. Batas yang disarankan Hasen agak tinggi, meskipun: tidak ada individu yang dapat berkontribusi atau menghabiskan total lebih dari $ 25.000 untuk pemilihan federal yang diberikan, atau lebih dari $ 500.000 untuk semua pemilihan federal selama siklus pemilihan dua tahun. Pada bulan Desember 2018, Perwakilan Ro Khanna memperkenalkan undang-undang pembiayaan publik, “Undang-Undang Dolar Demokrasi,” yang tujuannya adalah untuk “memberdayakan rata-rata orang Amerika dengan memberikan $ 50 ‘Demokrasi Dolar’ kepada setiap pemilih yang terdaftar untuk dibelanjakan dalam pemilihan federal: $ 25 untuk pemilihan presiden, $ 15 untuk Senat, dan $ 10 untuk kampanye House” (Notes 43, p. 716).
Democratic Voucher inilah, menurut Cagé, adalah solusi atas kekacauan demokrasi dan melahirkan demokrasi koruptif. Bagaimana warga negara bisa setara dalam kaitannya dengan pendanaan demokrasi politik? Salah satu solusinya dengan memberi setiap orang cek atau voucher demokrasi pada waktu pemilihan, dengan nilai nominal, katakanlah, sepuluh, lima puluh, atau seratus euro, yang dapat mereka gunakan untuk mendanai kampanye kandidat yang mereka pilih. Orang di balik proposal asli ini di Amerika Serikat adalah Lawrence Lessig, seorang spesialis hukum dalam hak kekayaan intelektual, yang dalam “beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu pendukung utama perang melawan lobi dan korupsi dalam kehidupan politik Amerika. Dia juga menempatkan dirinya maju pada tahun 2015 sebagai kandidat dalam pemilihan pendahuluan presiden dari Partai Demokrat, tetapi sayangnya harus mundur karena ia tidak memiliki pemilih yang memadai (dan karenanya prospek pendanaan yang cukup). Strategi memenangkan kekuasaan ini adalah bagian dari kampanyenya untuk mengakhiri korupsi politik: yaitu, memilih seorang presiden, atau lebih umumnya politisi, yang satu-satunya tujuan adalah mengembalikan fungsi demokrasi perwakilan yang tepat di Amerika Serikat.
Ide Lessig adalah untuk memberikan setiap warga negara voucher demokrasi senilai $ 50 yang dapat ia gunakan untuk mendanai kandidat atau kandidat (Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat) pilihannya. Selama sembilan bulan sebelum pemilihan, para kandidat akan dapat mengumpulkan voucher-voucher ini – dari warga negara yang dukungannya telah mereka menangkan – untuk membiayai kampanye mereka. Apakah semua kandidat dapat mengambil manfaat dari mereka? Dalam model Lessig, pertama-tama mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki dukungan publik yang cukup, misalnya dengan mengumpulkan sejumlah $ 5 kontribusi. Lebih penting, mereka harus melakukan untuk tidak menerima sumbangan pribadi lebih tinggi dari $ 100.
Apakah Democracy Vouchers bisa dilakukan? Rupanya voucher demokrasi semacam itu telah diperkenalkan di Amerika Serikat. Sejak 2017, setiap warga negara di Seattle yang berada dalam daftar pemilih secara otomatis menerima melalui pos empat voucher demokrasi $ 25 (atau total $ 100), yang kemudian dapat ia berikan kepada para kandidat pilihannya dalam pemilihan kota (untuk jabatan walikota, kota) anggota dewan, dan jaksa agung). Untuk berpartisipasi dalam sistem pendanaan publik ini, para calon harus terlebih dahulu memperoleh setidaknya 150 kontribusi (masing-masing dengan nilai minimum $ 10 dan maksimum $ 250) untuk jabatan Jaksa Agung, 400 kontribusi untuk Anggota Dewan Kota, dan 150 kontribusi untuk Distrik Dewan Kota. Maksudnya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi proliferasi kandidat “tidak kredibel.”
Calon yang ingin mendapat manfaat dari voucher demokrasi ini harus setuju untuk menghormati batasan pengeluaran yang ketat dan tidak menerima kontribusi di atas $ 250 (tidak termasuk nilai voucher) .49 “Yang menarik, kandidat yang memilih untuk tidak mengambil bagian dalam program voucher demokrasi adalah juga tunduk pada batasan ketat ($ 500) pada sumbangan yang mereka terima dari individu tertentu. Namun, Seattle ada di Amerika Serikat!
Jika Anda bertanya-tanya, Seattle membiayai voucher demokrasi ini melalui pajak properti yang seharusnya menghasilkan $ 3 juta per tahun. Sedikit persamaan ekonomi di atas persamaan politik! Rata-rata, biaya program pemilik properti $ 11,50 per tahun. “
Berita baik lainnya adalah bahwa voucher demokrasi ini berfungsi. Enam kandidat telah mendapat manfaat dari mereka sejak diperkenalkan pada tahun 2017, dan hampir 46.000 voucher telah digunakan dengan nilai total $ 1,1 juta dalam pendanaan publik.50 Selain itu, kandidat yang memilih pendanaan publik tampaknya tidak pernah menderita pada polling — pada sebaliknya. Calon pengacara kota Peter Holmes, misalnya, yang memilih voucher demokrasi (dan menerima 5.885, dengan nilai total $ 147.000), terpilih kembali dengan mayoritas besar (73 persen suara) terhadap saingannya Scott “Lindsay, yang tetap tinggal keluar dari program.51 Dan Teresa Mosqueda, yang mencalonkan diri untuk dewan kota dan mendaftar untuk voucher demokrasi, juga muncul sebagai pemenang; saingannya di kandang, Jon Grant, juga memilih pendanaan seperti itu, tidak seperti kebanyakan kandidat lain di pemilihan pendahuluan.”
Democratic Vouchers bukan hanya untuk mengadvokasi pendanaan publik untuk demokrasi — subsidi langsung kepada partai-partai sesuai dengan aturan yang tepat, yang saat ini biasanya menghubungkan mereka dengan hasil pemilu sebelumnya, tetapi yang dalam model yang diusulkan Cage mengikuti pilihan tahunan oleh semua warga negara — dan untuk membandingkan ini dengan pendanaan pribadi. Lebih mendasar lagi, debat tersebut menentang gagasan “demokrasi publik” sebagai upaya untuk memprivatisasi kekuatan-kekuatan utama demokrasi, khususnya alokasi public good.”
Namun pendanaan publik, dalam pandangan Cage, satu-satunya jalan yang akan mengarah pada pemulihan demokrasi. Ini adalah jalan yang penuh dengan jebakan, di mana akan perlu untuk bertarung melawan lobi-lobi swasta yang ingin mempertahankan hak-hak istimewa pemilihan finansial mereka dan melawan pihak manapun yang telah meninggalkan semua harapan dalam demokrasi pemilu. Tapi itu adalah jalan menuju kesetaraan demokratis: untuk satu orang, satu suara. Akhirnya — dan, mari kita berharap, untuk waktu yang lama untuk datang. “.. it is a path leading toward democratic equality: to one person, one vote. At last—and, let us hope, for a long time to come.”
Apakah lahirnya UU Pertambangan, dan RUU Sapujagad Omnibus yang sangat getol digodok parlemen adalah hasil dari demokrasi koruptif? Apakah di dalam kedua UU yang mengandung begitu banyak persembahan istimewa untuk pihak swasta adalah harga yang harus dibayar oleh sistem demokrasi yang kita anut dengan sistem pembiayaan pemilu seperti sekarang? Apakah itu semua karena ketidakmampuan (atau ketidakmauan?) publik, khususnya para politikus, berinisiatif untuk membangun pembiayaan demokrasi yang lebih baik, yang adil dan jujur?
“Excessive campaign spending also entails a major danger of corruption. A politician is all the more prone to accept kickbacks and other secret money if she has to spend several millions to have any chance of being elected.” Pada akhirnya pembiayaan kampanye yang berlebihan akan membawa bahaya besar mewabahnya korupsi. Seorang politisi semakin rentan menerima suap dan uang siluman lainnya jika ia harus menghabiskan harta karun untuk memiliki peluang terpilih.”