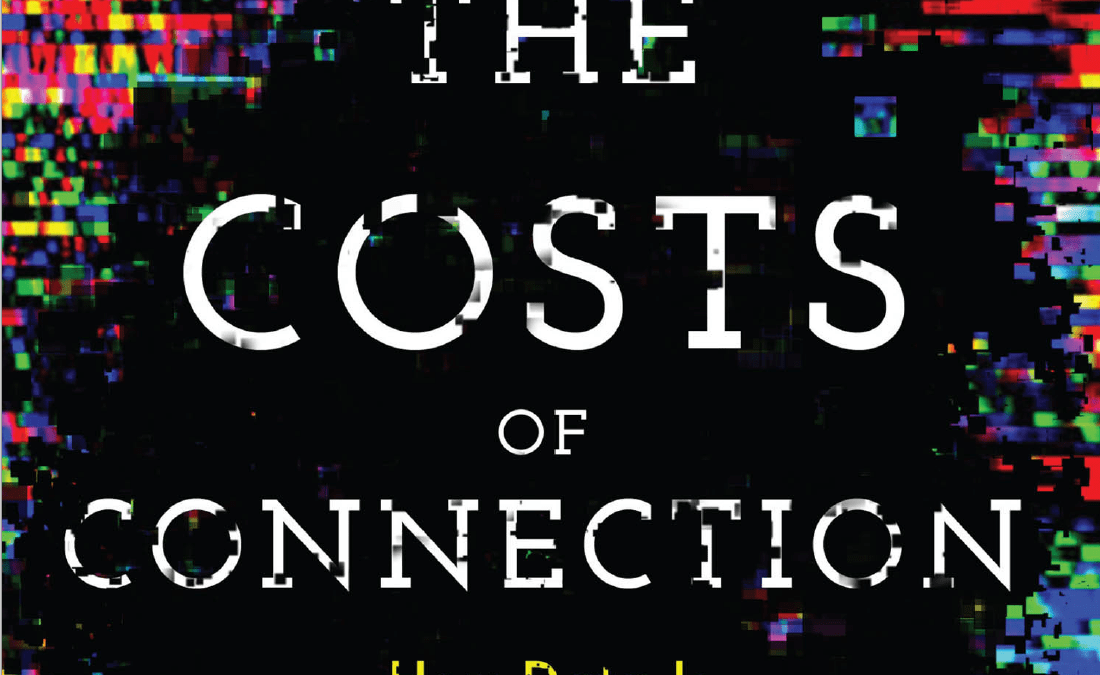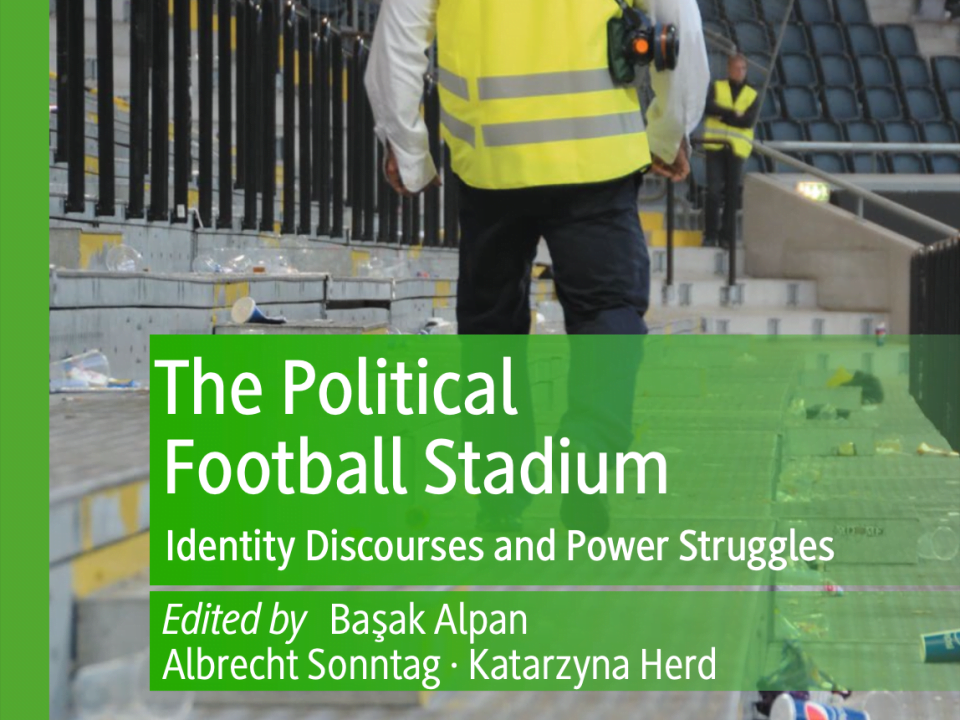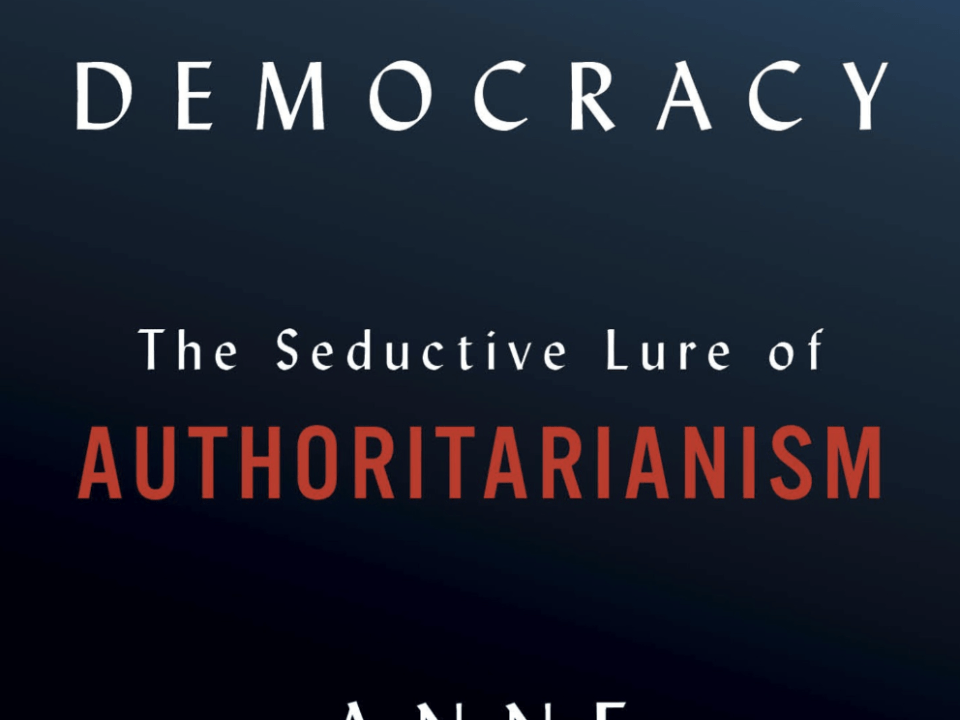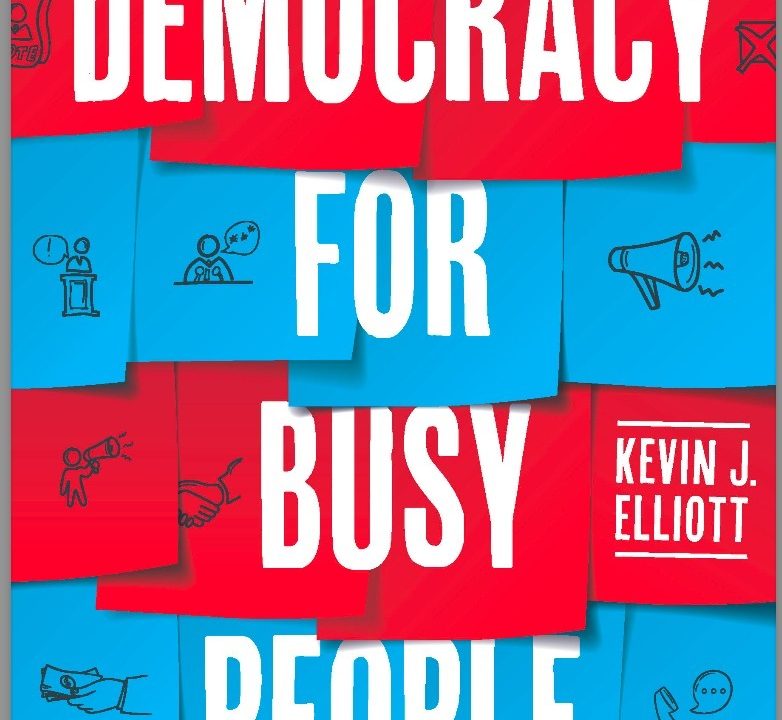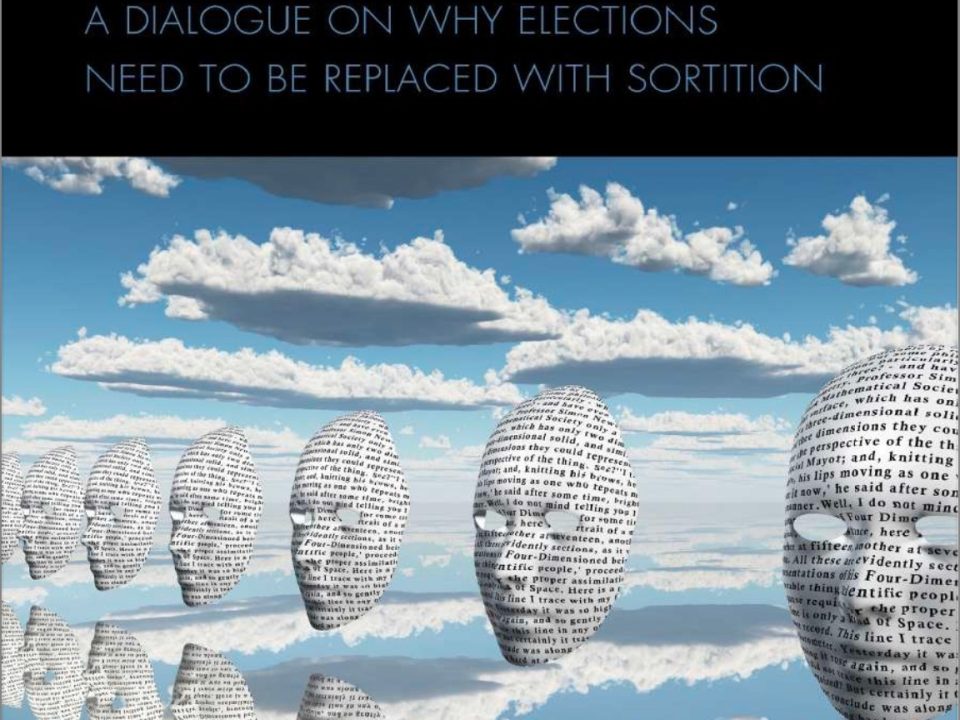Kolonisasi Data, Ekstraksi Kehidupan dan Kolonialisme tahap ketiga
—Dwi R. Muhtaman—
Rimbo Bujang, Jambi
Nanga Pinoh, Kalbar, 20012020
#BincangBuku #38
“Without big data, you are blind and deaf and in the middle of a freeway.”
– Geoffrey Moore
“Capitalism has always sought to reject limits to its expansion, such as national boundaries.
But now, as not only human geography and physical nature but also human experience are being
annexed to capital, we reach the first period in history when soon there will be no domains of life left that remain unannexed by capital.
—Nick Couldry and Ulises A. Mejias, The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for
capitalism (2019).
“Inilah wajah kolonialisme modern.” Demikian kicauan Christopher Wylie, sang whistle-blower yang menyingkap skandal Facebook/Cambridge Analytica, yang memalukan dan mengejutkan, pada bulan Maret 2018. Wylie merujuk pada rencana Cambridge Analytica untuk memperluas operasinya di India menggunakan media sosial dengan target memengaruhi proses politik di sana. Apakah itu sebuah kolonialisasi data? Bagi Nick Couldry and Ulises A. Mejias dalam bukunya, The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism (2019) skala dan ruang lingkup kolonialisme data jauh lebih luas daripada sekedar penyimpangan beberapa penjaja data bersama psikolog in-house mereka yang kelewat bersemangat. Ia bahkan melampaui praktik ekstraksi data dan lisensi data normal Facebook yang menyingkap skandal itu (halaman 3).
Buku yang kita bincangkan ini memperkenalkan beberapa konsep dan neologisme lain, yang dijelaskan secara rinci pada tiga bagian buku 323 halaman ini. Menurut Couldry dan Mejias, Data Kolonialisme, pada dasarnya, adalah tatanan yang muncul untuk perampasan kehidupan manusia sehingga data dapat diekstraksi terus menerus untuk tujuan mencari keuntungan. Ekstraksi ini dioperasikan melalui hubungan data, cara berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia yang difasilitasi oleh alat digital. Melalui keterhubungan data, kehidupan manusia tidak hanya dicaplok oleh kapitalisme tetapi juga menjadi subyek pemantauan dan pengawasan terus menerus. Hasilnya adalah melemahkan otonomi kehidupan manusia secara fundamental yang mengancam hak-hak dasar kebebasan, yang justru merupakan nilai yang digembar-gemborkan oleh kejayaan pendukung kapitalisme.
Penulis yang mendapat banyak pujian bagi bukunya ini menyatakan kegelisahannya atas fakta dan potensi transformasi yang fundamental atas kehidupan manusia karena kolonialisasi data. Karena transformasi mendasar kehidupan manusia ini memiliki konsekuensi dramatis bagi dunia sosial. Mereka memungkinkan terjadinya apa yang disebut sebagai social caching, sebuah bentuk baru pengetahuan tentang dunia sosial yang berdasarkan pada pengambilan data pribadi dan penyimpanannya untuk digunakan kemudian hari untuk meraup keuntungan. Pada saat hubungan sosial berubah dan bertransformasi, kita melihat kemunculan Cloud Empire, sebuah totalisasi visi dan organisasi bisnis di mana perampasan data kolonialisme telah dinaturalisasi dan diperluas di semua domain sosial. Cloud Empire sedang diimplementasikan dan diperluas oleh banyak pemain tetapi utamanya oleh sektor kuantifikasi sosial, sebuah sektor industri yang dicurahkan untuk pengembangan infrastruktur dan diperlukan untuk ekstraksi laba dari kehidupan manusia melalui data (halaman viii).
Bisa jadi Geoffrey Moore, seorang organizational theorist, konsultan manajemen dan pengarang yang dikenal dengan bukunya Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers, benar. Big data adalah kunci yang jadi petunjuk jalan menuju apapun yang diinginkan. Tanpa data seperti seorang buta dan tuli di tengah jalan bebas hambatan. Big data atau mahadata yang dihimpun itu hanya mungkin dihimpun karena keterhubungan pengguna melalui internet. Tanpa kita sadari, atau pun tak menghiraukan, keterhubungan sosok manusia dalam dunia digital ini pada dasarnya menyerahkan diri seluruhnya sebagai alat produksi—alat produksi bagi roda kapitalisme. Hampir semua gerakan-gerakan perlawanan atas kolonialisme baik pada akhir abad keduapuluh, dan lebih-lebih pada abad duapuluhsatu, dengan menggunakan sosial media, justru menimbulkan ambigu seperti yang diungkapkan oleh Couldry dan Mejias. Pada satu sisi sosial media membantu mobilisasi pendukung dalam waktu yang jauh lebih gegas. Tetapi pada sisi lainnya meningkatkan akumulasi kapital bagi korporasi yang menguasai semua perangkat sosial media.
Dengan mengutip Leanne Betasamosake Simpson, seorang akademisi, penulis, dan seniman dari komunitas Nishnaabeg, Couldry and Mejias menulis bahwa setiap tweet, posting Facebook, posting blog, foto di Instagram, video YouTube, dan email yang dikirim saat demonstrasi anti pencaplokan tanah masyarakat oleh korporasi maka membuat perusahaan terbesar di dunia lebih banyak uang untuk memperkuat sistem kolonialisme pada tanah-tanah masyarakat. Simpson pun bertanya-tanya jangan-jangan kita tidak membangun gerakan, tetapi malah membangun kehadiran media sosial yang mengistimewakan individu atas komunitas, validasi virtual atas empati, dan kepemimpinan tanpa akuntabilitas dan tanggungjawab. Data yang dikirimkan kepada para pendukungnya dan khalayak luas adalah sebuah proses produksi yang menangguk keuntungan bagi korporasi teknologi sosial media.
Contoh lain yang berbeda. Bagi Anda yang super sibuk, Anda seringkali lupa menenggak air meskipun terasa haus. Kini Anda tak perlu lupa atau repot lagi untuk mengingatkan saatnya menyeruput air agar tidak dehidrasi. Telah tersedia aplikasi digital untuk itu, Water Minder. Pembuat Water Minder menawarkan sebuah program untuk memotong dan meringkas bagian dari otak yang mengatur rasa haus, dan mengingatkan pengguna untuk menenggak air secara teratur dengan kuota yang ditentukan sambil melacak kemajuan yang dicapai. Seperti banyak aplikasi lainnya, Water Minder telah mengubah secara signifikan tindakan privasi menjadi sebuah perayaan sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dengan kawan dalam jaringan pertemanan.
Dengan mengutip Eve Tuck and K. Wayne Yang, buku yang provokatif ini mengingatkan kita, “..colonization is not an approximation of other experiences of oppression but a highly distinctive exercise of power.”
Couldry dan Mejias berargumen bahwa kolonialisasi data bukanlah sebuah perkiraan belaka. Kehidupan manusia telah dijajah oleh data dan perlu didekolonisasi. Dalam buku ini ditegaskan bahwa tidak ada metafora tentang era kolonialitas baru ini. Dengan menelusuri kontinuitas dari sejarah apropriasi kolonialisme wilayah yang luas, pada negara-negara jajahan pada jaman penjajahan, sampai ke peran data dalam kehidupan kontemporer, kedua penulis ini menyimpulkan, meskipun mode, intensitas, skala, dan konteks perampasan hari ini berbeda, namun fungsi yang mendasarinya tetap sama seperti di bawah kolonialisme historis: untuk memperoleh sumber daya berskala besar dimana nilai ekonomi dapat diekstraksi.
Pada dasarnya buku yang terdiri dari tiga bagian ini (Bagian I: Extraction, Bagian II: Ordering, Bagian III: Reconnecting) adalah tentang kolonialisme dalam bentuknya yang terbaru. Maka mau tidak mau penulis menguraikan dan menelusuri sejarah dan segala aspek tentang kolonilaisme dan kapitalisme. Pada Bagian I banyak mengupas soal sisi kolonialisme dan kapitalisme tersebut.
Kolonialisme adalah bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang didominasi oleh kekuatan kolonial utama seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan kemudian Amerika Serikat. Sekarang biasanya dianggap tertutup secara historis, diakhiri oleh pergerakan dekolonisasi akhir abad kedua puluh, meskipun dalam politik dan daerah lain, bentuk kekuasaan neokolonial masih hidup (aspek ini diuraikan lebih detil pada Bagian II). Buku ini menyingkap kelanjutan dari kolonialisme yang lebih tua itu ke bentuk baru kolonialisme — kolonialisme data. Kolonisasi data inilah yang menjadi kolonialisme tahap ketiga.
Ada empat komponen utama kolonialisme historis: apropriasi sumber daya; evolusi hubungan sosial dan ekonomi yang sangat tidak setara yang menjamin perampasan sumber daya (termasuk perbudakan dan bentuk kerja paksa lainnya serta hubungan dagang yang tidak setara); distribusi global manfaat pemanfaatan sumber daya yang tidak merata besar-besaran; dan penyebaran ideologi untuk memahami semua ini (misalnya, reframing apropriasi kolonial sebagai pelepasan sumber daya “alam,” pemerintah dari orang-orang “inferior”, dan membawa “peradaban” ke dunia), halaman 4.
Jika kolonialisme historis mencaplok wilayah, sumber dayanya, dan tubuh yang bekerja pada mereka, perebutan kekuasaan kolonialisme data lebih sederhana dan lebih dalam: perenggutan dan pengendalian kehidupan manusia itu sendiri melalui apropriasi data yang dapat diekstraksi darinya untuk keuntungan semata. Jika itu benar, kemudian maka serupa kolonialisme historis menciptakan bahan bakar untuk kapitalisme industri akhirnya bangkit, demikian juga data kolonialisme membuka jalan bagi kapitalisme berdasarkan eksploitasi data. Kehidupan manusia secara harafiah sedang dianeksasi menjadi modal.
Dalam tahap kolonialisme, demikian tulis Couldry dan Mejias, kontinuitas antara titik awal pertama dan kedua sudah jelas, tetapi bagaimana dengan yang ketiga? Mungkin tampak berlawanan dengan intuisi untuk membayangkan situs eksploitasi kolonialisme itu saat ini termasuk wajah Barat yang sama yang secara historis memaksakan kolonialisme di seluruh dunia. Tapi bagaimana kalau gudang senjata kolonialisme berkembang? Bagaimana jika cara-cara baru untuk menghisap kehidupan manusia, dan kebebasan tempat bergantungnya, muncul? Yakni kemungkinan yang mengganggu yang dieksplorasi dalam buku ini.
Kembali pada contoh Water Minder itu. Tindakan sehari-hari yang sederhana setiap tubuh individu melakukan pemantauan apakah ia telah minum cukup air tiba-tiba menjadi sesuatu yang terjadi dalam ruang sosial yang kompetitif. Tubuh manusia telah ditata-ulang menjadi sesuatu yang membutuhkan infrastruktur yang jauh, dari mana, secara kebetulan, laba dapat dibuat. Salah satu fungsi penting dari tubuh itu dikerat dan diserahkan pengelolaannya pada sepotong perangkat lunak. Dan ini hanyalah satu contoh kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar: upaya sistematis untuk mengubah semua kehidupan manusia dan hubungan ke dalam input untuk menghasilkan laba. Pengalaman manusia, setiap lapisan dan aspeknya, menjadi target dari ekstraksi untuk meraup keuntungan. Kondisi inilah yang disebut penulis sebagai kolonisasi oleh data, dan ini adalah dimensi utama
tentang bagaimana kapitalisme itu berkembang dewasa ini.
Data yang diekstraksi saat ini bisa dipahami tidak hanya dalam konteks kapitalisme tetapi juga berkaitan dalam relasi antara kapitalisme dan kolonialisme. Eksploitasi terhadap kehidupan manusia demi laba melalui data adalah klimaks dari warisan lima abad upaya untuk mengetahui, mengeksploitasi, dan menguasai dunia dari pusat-pusat tertentu kekuasaan. Kita memasuki zaman kapitalisme baru, pada saat kapitalisme baru saling terkait antara sejarah kembar kapitalisme dan kolonialisme, dan sejarah kekuatan yang saling terkait adalah data.
Apa yang dimaksud dengan data. Buku ini menguraikan dengan gamblang tentang data. Daftar belanja yang dituliskan pada sepotong kertas, bukanlah data yang dimaksud. Tetapi jika daftar itu dimasukkan pada ponsel, mungkin pada aplikasi Google Keep, maka itulah data yang mulai memainkan perannya. Dan itulah yang dimaksud. Selanjutnya jika dipertimbangkan algoritma yang mengumpulkan informasi di semua pengguna Google Keep untuk melihat apa yang didaftar, maka itulah data yang di maksud. Bagi penulis buku ini konsep data tidak dapat dipisahkan dari dua elemen esensial: infrastruktur eksternal di mana ia disimpan dan laba yang bisa diraup. Singkatnya, data yang dimaksudkan adalah aliran informasi yang berpindah dari kehidupan manusia dalam segala bentuknya ke infrastruktur untuk pengumpulan dan pemrosesan. Ini adalah titik awal untuk menghasilkan laba dari data. Dalam pengertian ini, data mengabstraksi kehidupan dengan mengubahnya menjadi informasi yang dapat disimpan dan diproses oleh komputer dan menyesuaikan kehidupan dengan mengonversi itu menjadi nilai untuk pihak ketiga.
Lebih eksplisit didefinisikan, kolonialisme data adalah istilah yang dipakai seluruh deskripsi dalam bukunya untuk menegaskan perpanjangan proses ekstraksi global yang dimulai di bawah kolonialisme dan berlanjut melalui kapitalisme industri, yang lalu berpuncak pada bentuk baru hari ini: sebagai ganti dari sumber daya alam dan tenaga kerja, apa yang sekarang sedang caplok adalah hidup dan kehidupan manusia melalui konversi menjadi data. Hasilnya jelas telah mendegradasi kehidupan, pertama oleh terpaparnya secara terus menerus dengan pemantauan dan pengawasan (sehingga memungkinkan data diekstraksi) dan kedua dengan demikian menjadikan hidup manusia sebagai input langsung untuk produksi kapitalis.
Dengan kata lain, kolonialisme data adalah sebuah orde yang muncul untuk mengambil dan mengekstrak sumber daya sosial untuk mendapatkan keuntungan melalui data, dipraktekkan melalui hubungan-hubungan data. Berbeda dengan kolonialisme historis, yang keuntungan luasnya membantu menciptakan prasyarat bagi apa yang sekarang kita kenal sebagai kapitalisme industrial, kolonialisme data muncul dengan situasi keseluruhan
jalinan sejarah kolonialisme dan kapitalisme. Ini berarti bahwa langkah kolonial dasar untuk mengambil data dari kehidupan manusia (data kolonialisme)
bekerja bersama dengan pengaturan sosial dan infrastruktur teknologi, beberapa yang muncul selama masa awal kapitalisme dan beberapa yang baru,
yang memungkinkan data untuk diubah menjadi komoditas, dan langsung menjadi input untuk produksi kapitalis kontemporer.
Keseharian kita dengan kemajuan internet dan—implikasinya—ekstraksi data, telah menimbulkan ketergantungan kenyamanan. Kolonialisme data dianggap sesuatu yang tak terelakkan, tak terasa dan sekaligus tak berdaya melepaskan diri.
Jadi apa selanjutnya? Banyak yang tergoda untuk mengatakan: jalan ke depan lebih baik kita tinggalkan akun media sosial. Tetapi di hadapan orde kapitalis baru, bentuk perlawanan individu seperti itu tidak memadai, kata Couldry dan Mejias. Data kolonialisme adalah masalah kolektif. Juga tidak akan memadai jika versi kolektif dari tanggapan-tanggapan individual itu hanya memilih sebagian dari masalah untuk direformasi. Untuk orde baru yang hanya itu: Tidaklah cukup untuk memilih keluar dari bit-bit kolonialisme data yang tidak kita sukai.
Tetapi melawan data kolonialisme secara keseluruhan memang sangat merepotkan. Hal ini karena model kolonialisme data untuk mengorganisasikan hal-hal yang mendasari model bisnis dan sumber daya sehari-hari tak terhitung jumlahnya. Pengguna internet di seluruh dunia—dan kita asumsikan juga sebagai downloader, pengguna jutaan aplikasi—mencapai 3,49 miliar (September 2019). Indonesia masuk dalam 10 negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Indonesia berada di peringkat kelima dengan pengguna internet sebanyak 143,26 juta per Maret 2019. Angka tersebut memiliki selisih tipis sebesar 5,8 juta dengan Brasil yang memiliki pengguna internet sebanyak 149,06 juta. Peringkat teratas diperoleh Tiongkok dengan jumlah pengguna internet sebanyak 829 juta. Peringkat kedua India dengan pengguna internet sebanyak 560 juta. Amerika Serikat (AS) menyusul dengan pengguna internet sebanyak 292,89 juta.
Itulah sebabnya, seperti Mark Andreessen, petinggi Facebook, secara tidak sengaja tersirat (dalam kutipan pada bagian pembukaan buku ini), inti menentang kolonialisme tidak pernah sukses secara ekonomi dengan segera. Lebih buruk lagi, selama dua dekade terakhir, miliaran orang sudah mulai banyak mengorganisasikan kehidupan pribadi mereka di sekitar infrastruktur platform digital dan layanan-layanan lain yang bergantung, atau tampak bergantung, pada arus data yang mulus (halaman 192). Penulis pun tidak memberikan solusi yang pasti bagaimana bentuk perlawanan atas kolonialisasi data atau dekolonialisasi data. Nyatanya sistem komunikasi dari sistem yang mapan saat ini malah mengekstrak sesuatu dari mereka yang melakukan perlawanan menggunakan media komunikasi itu. Sehingga jadi agak menggelikan berharap ketika melawan orde sosial politik ekonomi melalui penggunaan sistem yang sama, yang justru kita lawan.
Tetapi kolonialisasi yang menjerumuskan harkat kehidupan manusia harus dilawan, bagaimanapun caranya. Tujuannya adalah mencari dan berimajinasi perlawanan yang paling radikal pada orde tersebut sambil tetap hidup dalam sistem yang ada. Contohnya melalui literasi media. Mendidik kita untuk lebih hati-hati dan lebih baik dalam menggunakan social quantification technologies: unplug alias matikan medsos dan segala aplikasi secara berkala, ubah setting privasi.
Upaya lain misalnya: civic activism. Melakukan protes keras misalnya seperti yang dilakukan melalui hacktivism Anonymous provokatif yang merusak sistem penguasa medsos yang dibangun melalui data secara temporer. Atau aksi yang dilakukan oleh sebuah komunitas di Detroit, Amerika Serikat, yang melarang operasional Airbnb. Tak lupa Couldry dan Mejias juga memberi contoh civic activism ini dari aksi ustadz Felix Siauw yang menyatakan swafoto sebagai haram dengan mengutip ”If we take a selfie and upload it on social media, desperately hoping for views, likes, comments or whatever—we’ve fallen into the OSTENTATIOUS trap” (halaman 195). Swafoto yang diupload dengan berharap pujian dikategorikan sebagai riya’ karena itu haram. Meskipun ucapan ustadz itu mendapatkan reaksi balik yang melawan. Tetapi Couldry dan Mejias menyatakan suatu hari nanti, fatwa lain akan muncul melawan perusahaan media sosial, dan orang akan menggunakannya sebagai medan pertempuran bagi seluruh masyarakat yang merasa bahwa platform media sosial atau segala sosial digital tak lagi untuk kepentingan mereka. Melawan ekstraksi dari dari kehidupan mereka untuk kepentingan korporasi dan kapitalisme, kolonialisme data. Pendiri Apple, Steve Jobs, memahami bukan saja manfaat teknologi tetapi juga bahaya yang melekat pada penggunaan teknologi yang dia sendiri membantu menemukannya. Jobs membatasi akses anak-anaknya terhadap produk-produk Apple. Steve Jobs lebih merupakan orang tua yang bertanggungjawab ketimbang genius marketing visioner (Kagge, 2017).
“We must develop a wider vision of resistance, a vision for connecting with one another on different terms that might provide possibilities for solidarity with resistant data subjects, wherever they are. Who knows, after all, where data colonialism’s great wall will break in the end?,” sebuah optimisme yang patut menjadi catatan penting kita untuk menyambut masa depan yang lebih baik—masa depan yang meletakkan kembali kepentingan publik, dan menghormati privasi individual, menjauhkan dari kolonilisasi data yang mengeruk keuntungan belaka.