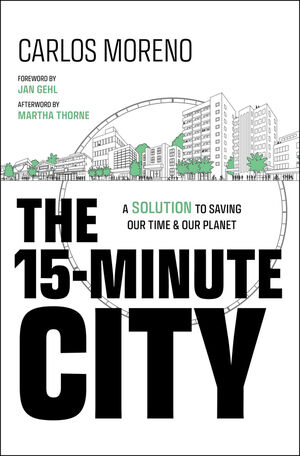Sustainability 17A #59
Konspirasi Belanja: Waste More, Lie More, Control More
Dwi R. Muhtaman,
Sustainability Partner
“Kita tahu seperti apa dunia saat ini:
kekacauan iklim, bahan kimia beracun
di dalam tubuh setiap orang di planet ini
—termasuk bayi yang baru lahir,
ketimpangan sosial yang semakin parah,
hutan dan air bersih yang menghilang,
meningkatnya isolasi sosial,
dan menurunnya kebahagiaan.”
–The Story of Stuff
Annie Leonard; Ariane Conrad
Kita Tidak Pernah Membuang Sesuatu —
Kita Hanya Memindahkan Sampah ke Tempat Lain
—Flora Bagenal
Menjelang hiruk pikuk Black Friday di Amerika Serikat, Netflix merilis sebuah film dokumenter mengejutkan: Buy Now! The Shopping Conspiracy.2 Disutradarai oleh Nic Stacey dan diproduseri Flora Bagenal, film ini bukan sekadar kritik pada konsumerisme—ia adalah seruan keras yang menggugat cara kita hidup, membeli, dan membuang.
Film dengan durasi 1 jam 24 menit ini berargumen bahwa perusahaan-perusahaan menjerat konsumen dalam siklus belanja yang kejam: iklan yang menggoda mendorong orang untuk terus membeli, sementara produk dirancang agar cepat rusak, sehingga memperkuat siklus tersebut. “Waste more, lie more, control more,” kata Sasha, Sang Narator berbasis kecerdasan buatan bernama Sasha itu, salah satu fitur paling unik dari film ini. Sasha digambarkan sebagai asisten virtual ala Alexa yang menyampaikan narasi dengan nada datar dan dingin, mencermin-kan suara korporasi yang manipulatif. Melalui Sasha, film ini menyampaikan pesan-pesannya.
Karyawan dari Apple, Amazon, dan Adidas mengakui bahwa merek tempat mereka bekerja memang berfokus pada konsumsi, dan tugas mereka adalah terus menjual barang. Film dokumenter ini dengan lugas mencantumkan dan menyebut nama-nama besar. Bagenal, Sang Produser, pada awalnya sempat khawatir soal bagaimana perusahaan-perusahaan akan merespons. Tapi berbagai merek itu sengaja ditampilkan untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar persoalan sistem. Bukan salah satu perusahaan saja, tapi seluruh sistem.
Bagi Bagenal satu hal lain yang sangat memengaruhinya selama pembuatan film dokumenter ini adalah menyadari betapa ruang publik dan budaya kita sekarang didominasi oleh iklan. Kita mengizinkannya karena itu menghasilkan uang, dan sangat sulit melepaskannya. Di Inggris, pemerintah lokal mendapat pemasukan dari iklan. Stasiun TV mendapat uang dari iklan. Individu menghasilkan uang dari konten mereka.
Dan dampak dari konsumsi yang tanpa henti itu amat mengejutkan. Bayangkan: setiap minggu, 15 juta pakaian bekas dari seluruh dunia dikirim ke Ghana. Mantan pegawai Apple, Nirav Patel, menyatakan bahwa secara global, sekitar 13 juta ponsel dibuang setiap hari.
Pantai-pantai di Ghana yang dulu bersih kini berubah jadi kuburan tekstil. Stacey menyebutkan, “Away is just another place on Earth”—tempat kita “membuang” sesuatu bukanlah akhir, melainkan hanya perpindahan beban ke belahan bumi lain.
Film ini menyuguhkan testimoni dari mantan karyawan Apple, Amazon, Adidas—orang dalam yang membuka mata tentang bagaimana sistem kapitalisme dirancang bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi menciptakan kebutuhan. Produk dirancang cepat rusak. Iklan dibuat seolah kita tak cukup jika tak membeli. Siklusnya mematikan—bagi dompet kita, dan bagi planet ini.
Namun Buy Now! bukan hanya kelam. Ia menyisipkan harapan lewat sosok-sosok seperti Maren Costa, eks-desainer UX Amazon, yang mencoba melawan sistem dari dalam. Dan lewat visual kreatif—angka-angka produksi seperti “2,5 juta sepatu per jam” divisualisasikan secara mencolok—film ini mengajak kita berpikir ulang: apakah belanja adalah bentuk kebebasan, atau bentuk penjara?
Karena belanja telah menjadi ketagihan maka rumah-rumah penuh sesak dengan aneka barang; barang yang barangkali setahun pun belum tentu digunakan. Berdasarkan berbagai sumber, rata-rata rumah tangga di Amerika Serikat memiliki sekitar 300.000 barang dalam rumah mereka. Mulai dari benda kecil seperti penjepit kertas hingga peralatan besar seperti mesin cuci. Jumlah ini mencerminkan budaya konsumsi yang tinggi dan akumulasi barang yang signifikan di rumah tangga Amerika.3 Menurut penelitian kelebihan barang di rumah tidak hanya mempengaruhi ruang fisik tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mental dan finansial: Stres dan Kecemasan: Sekitar 84% orang Amerika merasa rumah mereka tidak cukup terorganisir, yang menjadi sumber stres signifikan.4 Pemborosan Waktu: Rata-rata orang Amerika menghabiskan 3.680 jam (sekitar 153 hari) dalam hidupnya untuk mencari barang yang hilang.5 Pengeluaran Finansial: Amerika menghabiskan sekitar $1,2 triliun setiap tahun untuk barang-barang yang tidak esensial.
Sementara data spesifik tentang jumlah barang di rumah tangga di seluruh dunia terbatas, beberapa studi memberikan gambaran: India: Sebuah diskusi di India Study Channel menyebutkan bahwa sebuah rumah tangga kecil dapat memiliki sekitar 1.500 barang, termasuk peralatan dapur, pakaian, buku, dan furnitur.6 Inggris: Rata-rata anak berusia 10 tahun di Inggris memiliki 238 mainan, namun hanya bermain dengan 12 di antaranya setiap hari.7
Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam budaya konsumsi, ukuran rumah, dan tingkat pendapatan di berbagai negara. Tetapi hal yang sama adalah bahwa jumlah barang yang dimiliki dalam rumah melimpah meskipun tetap sangat bervariasi tergantung pada budaya, ekonomi, dan gaya hidup. Kelimpahan barang-barang ini yang dimanfaatkan sehari-hari jauh lebih sedikit dari apa yang tersedia.
Tidak ada riset dan keterangan tentang kondisi barang-barang di dalam rumah di Indonesia. Jika kita mengasumsikan bahwa setiap anggota rumah tangga memiliki sekitar 1.000 hingga 2.000 barang pribadi dan rumah tangga memiliki sekitar 5.000 hingga 10.000 barang bersama, maka total barang di sebuah rumah tangga Indonesia dengan 3,8 anggota dapat berkisar antara 8.800 hingga 17.600 barang.
Begitulah kondisi rumah akibat belanja telah menjadi adiktif. Dan adiktif itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Atas gagasan film dokumenter yang menohok ini tak ada perusahaan yang memberi respons. Tapi film ini telah viral di TikTok, membangkitkan diskusi, dan memberikan “izin” pada generasi muda untuk mempertanyakan sistem yang selama ini diterima begitu saja.
Buy Now! bukan dokumenter ramah penonton yang ingin merasa nyaman. Ia mengusik. Tapi justru karena itu, ia penting. Karena perubahan, seperti yang disampaikan Stacey, dimulai dari kesadaran. Dan kadang, satu film bisa menyalakan percikan itu.
Pada sebuah wawancara dengan TIME, produser Flora Bagenal bersama sutradara Nic Stacey mengatakan bahwa dokumenter Buy Now! The Shopping Conspiracy menyuguhkan potret brutal tentang sistem konsumsi global yang rusak. Tapi bagi Bagenal, pesan terbesarnya sederhana: tidak ada yang benar-benar “dibuang”. Semua hanya berpindah tempat — dari pusat-pusat belanja ke pantai di Ghana, dari etalase toko ke tempat pembuangan akhir di negara-negara Global South.
Film dengan animasi visual yang menggetarkan ini menampilkan fakta mengejutkan itu tadi yang setiap minggu, 15 juta pakaian bekas dikirim ke Ghana. Tidak untuk dipakai ulang, melainkan ditimbun, dibakar, atau membusuk di garis pantai. Dan itu baru satu contoh dari siklus global yang memindahkan beban limbah dari negara kaya ke negara miskin.
Bagi Bagenal, sistem konsumsi modern seperti permainan tangan. Kita membeli sesuatu, lalu melepaskannya begitu saja, seolah hilang. Tapi yang hilang hanyalah tanggung jawab kita. Barang itu berpindah tangan, tapi tidak pernah hilang. “Kepemilikan kita sangatlah singkat,” katanya, “dan kita tidak berpikir panjang tentang ke mana semua itu akan berakhir.”
Ia juga menyoroti betapa budaya dan ruang publik kita dikuasai iklan—media, jalanan, layar—semuanya dipenuhi dorongan untuk membeli. “Susah sekali melepaskan itu,” ucapnya. Karena seluruh sistem ekonomi, mulai dari pemerintah lokal hingga individu, bergantung pada uang dari iklan dan konsumsi.
Apa yang bisa dilakukan? Menurut Bagenal, ini bukan hanya tentang individu yang memilih untuk membeli lebih sedikit. Ini soal sistem. Diperlukan regulasi, desain ulang model bisnis, dan yang terpenting, kesadaran kolektif bahwa “membuang” bukanlah akhir—itu hanya memindahkan masalah ke tempat lain di Bumi.
Ada ilusi besar yang kita yakini bersama: bahwa ketika kita membuang sesuatu — sepatu usang, baju lama, ponsel yang retak — benda itu menghilang dari hidup kita. Nyatanya, tidak ada yang benar-benar “hilang”. Seperti diungkap Flora Bagenal dalam film ini, semua yang kita buang hanya berpindah tempat. Dan tempat itu, sayangnya, seringkali adalah tanah milik orang lain yang tak punya suara.
Bayangkanlah 15 juta pakaian bekas dari dunia “maju” dikirim ke Ghana, setiap minggu. Negara-negara Global South menjadi halaman belakang bagi hasrat konsumsi negera-negara yang disebut negara maju. Mereka menyumbang, menghibahkan, atau sekadar membuang dengan perasaan lega — seolah kita telah “berbagi”. Tapi itu bukan kemurahan hati; itu bentuk kolonialisme baru dalam rupa limbah.
Bagenal mengingatkan kita sebuah kenyataan brutal: “Kita tidak pernah membuang sesuatu. Kita hanya memindahkannya.” Dan ironisnya, kita hidup dalam budaya yang dibanjiri oleh iklan—di layar, di jalan, di media sosial—yang terus-menerus menyuruh kita membeli lebih banyak, lebih cepat, lebih sering.
Lalu kita menyalahkan konsumen. Kita beri nasihat: beli lebih sedikit, perbaiki barangmu, beli barang bekas. Tapi sistem yang kita tempati tidak mendukung pilihan-pilihan itu. Produk dirancang untuk cepat rusak. Iklan dirancang untuk menciptakan rasa kurang. Dan ekonomi kita, bahkan ruang publik kita, dirancang untuk memberi panggung bagi iklan, bukan kesadaran.
Apa yang dibutuhkan bukan sekadar pilihan individu, tapi perubahan sistem. Regulasi. Desain ulang ekonomi. Pertanyaan kritis tentang siapa yang bertanggung jawab di akhir siklus hidup sebuah produk. Dan yang lebih penting: keberanian untuk melihat bahwa “jauh” — tempat kita membuang — bukanlah tempat asing. Itu adalah bagian dari dunia yang sama, bumi yang sama, udara yang sama yang kita hirup.
Kita hidup dalam satu planet, bukan dalam satu keranjang belanja.
Ada sesuatu yang sangat ironis dari menonton Buy Now! The Shopping Conspiracy di Netflix — sebuah platform yang juga bergantung pada produksi visual tanpa henti, demi memikat perhatian dalam pasar yang lapar akan konten. Tapi justru dari dalam sistem itulah, film dokumenter ini muncul sebagai semacam “pengakuan dosa” kolektif, yang memaparkan kenyataan brutal di balik kehidupan konsumsi kita sehari-hari.
Sutradara Nic Stacey dan produser Flora Bagenal tak menawarkan kejutan. Kita sudah tahu: barang cepat rusak, iklan memanipulasi keinginan, dan limbah menggunung di tempat-tempat yang jauh dari pandangan mata. Tapi Buy Now! menyusun semua potongan itu menjadi satu narasi tajam yang sulit diabaikan. Mereka tidak hanya menunjukkan akibatnya — seperti pantai di Ghana yang dipenuhi pakaian bekas — tetapi juga memperlihatkan siapa yang membuat sistem ini tetap berjalan: kita, para konsumen, dan tentu saja para korporasi yang menggenggam kendali penuh atas ritme hidup modern.
Mungkin bagian paling kuat dalam film ini adalah kesaksian para mantan orang dalam: dari Amazon, Apple, hingga Adidas. Mereka bukan aktivis sejak awal. Mereka dulunya bagian dari mesin — yang membangun, memoles, dan menjual mimpi. Kini mereka berbicara, dan kita harus mendengarkan.
Yang membuat Buy Now! begitu menggugah bukan hanya karena ia bicara tentang limbah dan krisis iklim, tapi karena ia menunjukkan bahwa akar masalahnya bukanlah kemiskinan atau keterbelakangan teknologi, melainkan keserakahan sistematis. Sebuah model ekonomi yang menyamakan keberhasilan dengan pertumbuhan tak terbatas — sebuah ilusi yang tak lagi bisa kita pertahankan di tengah planet yang terbatas.
Film ini tidak menawarkan jawaban final. Tapi ia memberi amunisi pada percakapan yang lebih besar: bagaimana kita bisa membongkar sistem yang menjadikan “membuang” sebagai kebiasaan budaya? Bagaimana kita bisa menuntut pertanggungjawaban dari merek yang kita kagumi — bukan hanya atas apa yang mereka jual, tapi atas apa yang mereka sisakan di bumi?
Buy Now! adalah film yang tak nyaman. Tapi justru di ketidaknyamanan itu, kita mulai menemukan ruang untuk bertanya, menolak, dan mungkin — suatu hari — berubah.
“Setiap jam, 2,5 juta sepatu diproduksi di dunia.” Pernyataan itu meluncur seperti tamparan dalam film dokumenter itu. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah metafora dari dunia yang sedang kita bangun—dan hancurkan—dalam waktu bersamaan. Kita tidak sedang hidup di zaman konsumerisme, kita sedang tenggelam di dalamnya.
Film garapan Nic Stacey dan Flora Bagenal ini membuka mata: konsumerisme bukan sekadar kebiasaan membeli, melainkan konspirasi sistemik yang menopang seluruh fondasi kapitalisme modern. Melalui testimoni mantan pegawai Amazon, Apple, dan Adidas, penonton diajak menyusuri bagaimana “ilmu manipulasi” dibungkus sebagai inovasi. “You’re being 100 per cent played, and it’s a science,” ujar Maren Costa, mantan desainer pengalaman pengguna di Amazon. Tombol “klik untuk beli” dirancang hingga ke warna untuk menggoda impuls membeli.
Kita tak hanya menjadi konsumen, tapi juga korban. Korban dari siklus rakus produksi dan konsumsi yang saling memperkuat dalam pusaran yang mematikan. Limbah elektronik menumpuk. Pakaian bekas dari Eropa dan Amerika Serikat membanjiri Ghana dalam jutaan ton setiap minggunya. Indonesia menjadi tong sampah dunia karena sejumlah 262.903 ton sampah plastik masuk pada tahun 2024, meningkat dari 252.473 ton pada tahun sebelumnya.8 “Away is just another place on Earth,” ujar Paul Polman, mantan CEO Unilever dalam wawancara film ini—menampar logika “buang ke tempat sampah” yang selama ini kita anggap tuntas.
Tapi ini bukan sekadar soal plastik atau baju yang dibuang. Ini adalah krisis politik dan ekonomi yang dibungkus sebagai kebebasan memilih. Naomi Klein dalam No Logo telah lama menyatakan bahwa “konsumerisme telah menjadi agama baru” dan dalam agama ini, manusia kehilangan makna—digantikan iklan dan algoritma.
Buy Now! adalah cermin retak dari peradaban yang menolak menua. Sebuah sistem yang memproduksi barang dengan masa pakai singkat demi laba jangka pendek. Jargon seperti “go green” dan “sustainability” menjadi kosmetik perusahaan, sementara produk tetap didesain untuk rusak agar kita membeli lagi. Planned obsolescence bukan teori konspirasi, itu model bisnis.
Tidak heran jika The Or Foundation, yang ditampilkan dalam film ini, menyebut pantai Ghana kini seperti kuburan tekstil global. Sampah dari kita yang merasa sudah “membuang” ternyata hanya berpindah ke tubuh negara-negara Global South—sebuah neokolonialisme dalam bentuk pakaian bekas.
Solusinya? Tentu bukan sekadar menyuruh individu membeli lebih sedikit atau membawa tas belanja sendiri. Bagenal menyatakan tegas, “This is a system problem.” Kita butuh kebijakan. Kita butuh revolusi desain dan distribusi. Kita butuh politik yang tidak tunduk pada bursa saham. Jika tidak, seperti dikatakan dalam Plastic Legacies oleh Trisia Farrelly, kita akan mewariskan “toxic permanence” pada generasi mendatang—plastik dan limbah yang tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk.
Sebagai sebuah problem yang sistematik maka perlu dicari solusi yang juga sistematik. Pada sebuah wawancara, TIME bertanya pada Stacey. Mantan pegawai Apple, Amazon, dan Adidas yang ditampilkan dalam film memang bekerja di perusahaan tersebut, memperoleh gaji besar, dan setelah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bekerja, memutuskan untuk berbalik arah. Tapi mereka tetap mendapat manfaat dari sistem itu. Apakah ada cara untuk mengatasi hal ini, khususnya di AS, di mana budaya korporat menjadi bagian besar dari ekonomi? Bagaimana kita bisa membuat lebih banyak orang di perusahaan-perusahaan besar mendorong perubahan?
“Ini memang sulit,” jawab Stacey. Ia menguraikan lebih lanjut, “Tapi Maren Costa, desainer pengalaman pengguna di Amazon, sangat menarik karena dia benar-benar mencoba mengubah sistem dari dalam. [Costa menjalankan kelompok aktivis Amazon Employees For Climate Justice sebelum akhirnya diberhentikan.]. Kami ingin menampilkan pergulatan itu—yang dialami banyak orang ketika mereka bekerja di dalam sistem besar. Memang rumit. Tapi saya ingin menginspirasi orang, mengingatkan mereka bahwa menyuarakan pendapat bisa membawa perubahan. Semoga saja ada orang yang menonton film ini dan jadi lebih terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan dari pegawai mereka di masa depan—itu sudah merupakan kemenangan kecil. Ini tentang memberi keberanian untuk berbicara.”
Buy Now! bukan hanya dokumenter. Ia adalah peringatan. Dan jika kita tidak bertindak, bel yang berbunyi itu bukan alarm, melainkan lonceng kematian untuk dunia yang pernah kita kenal.
Menurut Jonathan Romney, dokumenter karya Nic Stacey ini sebagian membahas seni gelap pemasaran yang memanipulasi kita untuk terus membeli lebih banyak produk. “Kamu sedang 100 persen dimanipulasi, dan ini adalah ilmu pengetahuan,” kata Maren Costa, mantan “desainer pengalaman pengguna” di Amazon, yang turut mengembangkan teknologi persuasi bawah sadar situs tersebut (bahkan warna tombol “klik untuk membeli” pun diteliti secara mendalam).
Costa adalah salah satu dari beberapa orang dalam industri yang menjadi pelapor (whistleblower), mengungkapkan penyesalan pribadi dan rahasia dagang — termasuk mantan CEO Unilever dan mantan eksekutif Adidas. Namun Buy Now! bukan hanya soal mekanisme tipu daya modern. Film ini juga menelusuri akibat dari konsumsi adiktif dan produksi berlebihan yang saling memperkuat dalam lingkaran setan yang menghancurkan ekologi. Film ini menampilkan gambar CGI yang mengerikan dan sugestif — kota-kota yang ditelan oleh gunung sampah yang terus membesar — namun yang lebih menyentuh justru adalah cuplikan nyata dari sebuah pantai di Ghana yang dibanjiri oleh gelombang pakaian bekas.9
Saksi lainnya termasuk seorang pakar perbaikan yang menjelaskan bagaimana perusahaan sengaja membuat produk yang tidak bisa diperbaiki, serta “penjelajah sampah” Anna Sacks, seorang detektif ulung limbah konsumen.
Meskipun tidak banyak pengungkapan yang benar-benar baru, film ini menjadi pengantar yang berguna atas topik-topik yang sudah dikenal seperti keusangan yang direncanakan (planned obsolescence) dan pencitraan hijau palsu (greenwashing), disampaikan dengan gaya cepat dan bersemangat. Naratornya adalah Sasha, asisten pribadi ala Alexa yang dengan nada datar merapal pelajaran utama zaman ini: lebih banyak buang, lebih banyak tipu, lebih banyak kendali…
Karya yang menghibur namun mengganggu ini dirilis di Netflix, yang mungkin terasa ironis: mungkin memang ada film lain yang perlu dibuat untuk membahas dampak lingkungan dan budaya dari begitu banyak produk visual yang terus diproduksi untuk mengisi platform ini dan yang lainnya.
Film dokumenter ini menunjukkan dengan terang benderang apa yang tertulis sangat indah dan cantik dalam laporan-laporan sustainability pada kenyataannya jauh panggang dari api. Bagaimana memasukkan keberlanjutan ke dalam model ekonomi perusahaan besar apalagi yang sudah go public, yang memaksimalkan keuntungan. “Apakah itu realistis?” tanya TIME. Bagi Stacey itu pertanyaan fundamental. Banyak perusahaan besar, brand global paling dikenal sekalipun, pada kenyataannya tidak melakukan apa yang mereka ucapkan dan tulis dalam berbagai media komunikasi dan marketing mereka. Stacey mewawancarai Paul Polman, mantan CEO Unilever, yang memang mencoba mendorong perubahan. Tapi ketika Anda seorang CEO, sangat sulit untuk meyakinkan pemegang saham bahwa Anda mungkin tidak akan tumbuh secepat sebelumnya atau menghasilkan uang sebanyak sebelumnya. Di sinilah menurut Stacey, para pemimpin yang kita pilih harus bertanggung jawab. Ini soal negosiasi; kita harus mulai memikirkan kesehatan jangka panjang peradaban kita.
Bagi Bagenal pertanyaan itu adalah salah satu persoalan besar yang kita hadapi secara global, dan jawabannya membutuhkan pemikiran besar, cara kerja baru, dan semacam dekonstruksi sistem lama sembari membangun sistem yang baru.
Jadi bagaimana kita memperbaiki semua ini? Bagaimana kita mengurangi limbah, selain menyuruh konsumen untuk beli lebih sedikit, memperbaiki, atau membeli barang bekas? Stacey berharap para pemimpin di perusahaan-perusahaan besar menonton film ini, berhenti sejenak, dan menyadari bahwa usia pakai produk adalah persoalan besar. Perusahaan harus mulai berpikir kreatif soal bagaimana memperpanjang masa hidup produk mereka. Kita juga butuh perubahan kebijakan; pemerintah bisa membantu dengan membuat undang-undang untuk mengatur masa akhir pakai sebuah produk. Produsen pakaian di Hong Kong menceritakan bahwa 15 tahun lalu, setiap pakaian baru diuji dengan dicuci sebanyak 50 kali untuk melihat daya tahannya sebelum diproduksi massal. Tapi sekarang itu tidak dilakukan lagi. Ini menunjukkan bahwa kita sudah tidak lagi memikirkan umur barang.
Disadari atau tidak, ketika kita menatap dengan tanpa berkedip pada film ini seperti menyaksikan kita berdiri di depan gerbang pertokoan. Dan menginsyafi inilah konspirasi belanja: kita tidak membeli barang, kita membeli krisis.
“Waste more, lie more, control more,” kata Sasha.
1 We know what the world of today looks like: climate chaos, toxic chemicals in every body on the planet including newborn babies, growing social inequity, disappearing forests and fresh water, increasing social isolation and decreasing happiness.” –The Story of Stuff, Annie Leonard; Ariane Conrad (2010).
2 Black Friday terjadi setiap tahun pada hari Jumat setelah Hari Thanksgiving di Amerika Serikat. Thanksgiving sendiri selalu jatuh pada hari Kamis keempat di bulan November, jadi Black Friday biasanya berlangsung antara tanggal 23 sampai 29 November. Ini peristiwa tahunan, dan dikenal sebagai hari belanja besar-besaran.
Kenapa disebut Black Friday?
Awalnya, istilah “Black Friday” memiliki konotasi negatif. Pada 1960-an di Philadelphia, polisi menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kekacauan yang terjadi saat kerumunan orang membanjiri kota untuk berbelanja dan menonton pertandingan tahunan Army-Navy setelah Thanksgiving. Lalu lintas padat, toko penuh sesak, dan meningkatnya pencopetan membuat hari itu mimpi buruk bagi petugas keamanan—karena itu disebut Black.
Namun, para pebisnis dan retailer kemudian mengubah narasi negatif ini menjadi positif:
Mereka menyebut Black Friday sebagai hari ketika catatan keuangan bisnis berubah dari tinta merah (kerugian) menjadi tinta hitam (keuntungan), karena lonjakan penjualan besar-besaran.
Apa yang terjadi saat Black Friday?
- Diskon gila-gilaan dan penawaran terbatas waktu
- Antrean panjang, bahkan sejak malam sebelumnya
- Dikenal sebagai kick-off musim belanja Natal
Karena popularitasnya, negara lain pun mulai meniru tradisi ini—termasuk Indonesia (meski bukan usai Thanksgiving), lewat marketplace digital.
3 https://www.becomingminimalist.com/clutter-stats/
4 https://notapedestrianlife.com/stuff-and-minimalism-stats/
5 https://www.wavu.io/blog/clutter-stats?
6 https://www.indiastudychannel.com/forum/175860-the-number-of-items-in-our-household?
7 https://notapedestrianlife.com/stuff-and-minimalism-stats/
8 https://mongabay.co.id/2025/04/19/sasaran-limbah-impor-indonesia-tong-sampah-dunia/
9 Film dokumenter Buy Now! The Shopping Conspiracy menampilkan gambar CGI (Computer-Generated Imagery) sebagai cara visual untuk menggambarkan dampak mengerikan dari konsumsi berlebihan dan limbah dalam masyarakat modern. CGI digunakan di film ini bukan hanya sebagai efek visual menarik, tetapi sebagai alat retoris yang kuat untuk:
Menggambarkan realitas yang tak terlihat
- Salah satu adegan paling mencolok adalah visualisasi kota-kota yang tenggelam di bawah gunung sampah — gambaran hiperbolik namun berdasar, yang mengilustrasikan betapa besar volume limbah yang kita hasilkan.
- Misalnya, ada statistik bahwa setiap jam diproduksi 2,5 juta pasang sepatu — angka ini divisualisasikan dengan tumpukan sepatu yang menelan lanskap kota, membantu penonton membayangkan skala sebenarnya dari produksi global.
Menggugah emosi penonton
- CGI dalam film ini bukan sekadar dekorasi, tapi berfungsi sebagai penggugah rasa takut dan kesadaran. Gambar-gambar ini menekankan bahwa jika pola konsumsi kita tidak berubah, maka masa depan kita benar-benar bisa seperti yang ditampilkan dalam simulasi tersebut.
Menyampaikan pesan sistemik
- Visual ini memperkuat argumen bahwa masalah sampah bukan hanya soal pilihan individu, tapi hasil dari sistem ekonomi dan budaya yang menjadikan konsumsi sebagai tujuan utama hidup. CGI membantu merangkum konsekuensi sistemik ini dalam satu gambar besar.
Sutradara Nic Stacey menyatakan bahwa mereka ingin menggunakan “bahasa visual dari dunia periklanan”—yang biasanya digunakan untuk menjual barang—dan membalikkan fungsinya, agar iklan menjadi kritik terhadap dirinya sendiri. CGI dipakai sebagai cermin bagi fantasi kapitalisme konsumtif. Dengan kata lain, CGI di film ini bukan hanya efek, tapi alat politik visual yang mengajak kita membayangkan distopia yang sedang kita bangun diam-diam, setiap kali kita klik tombol “Beli Sekarang.”