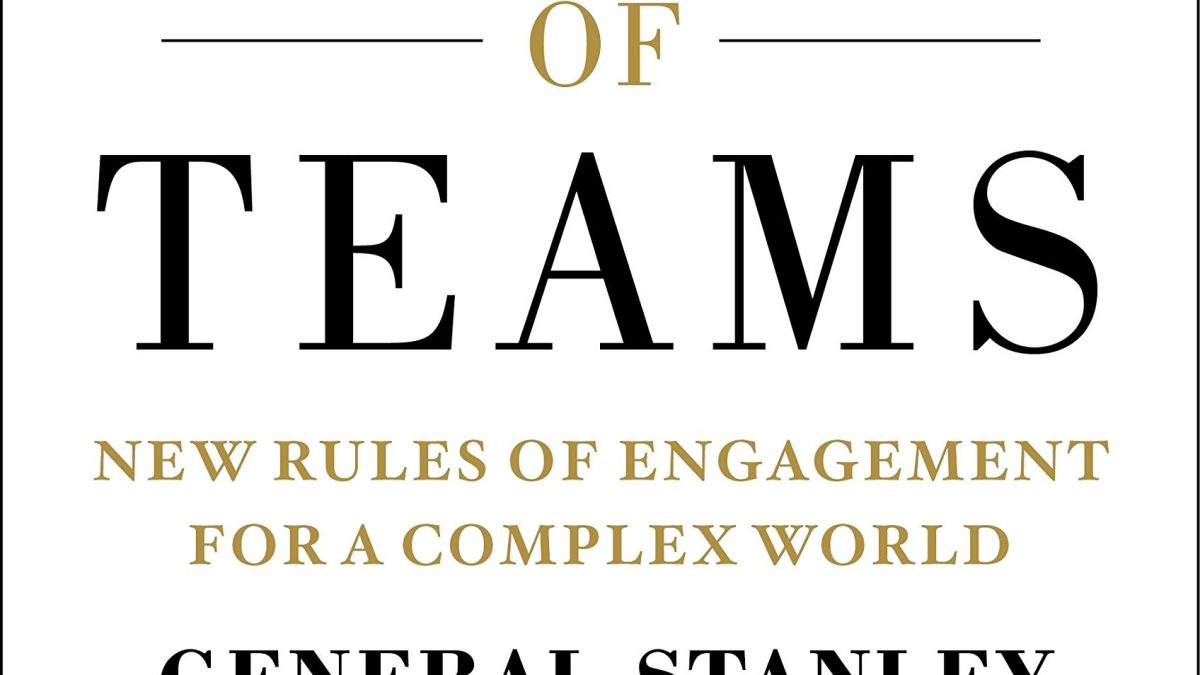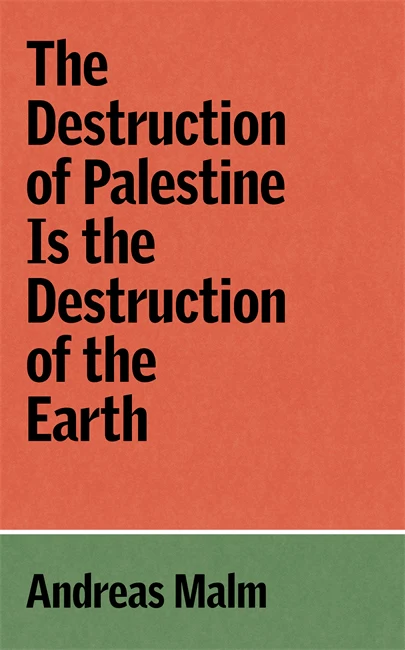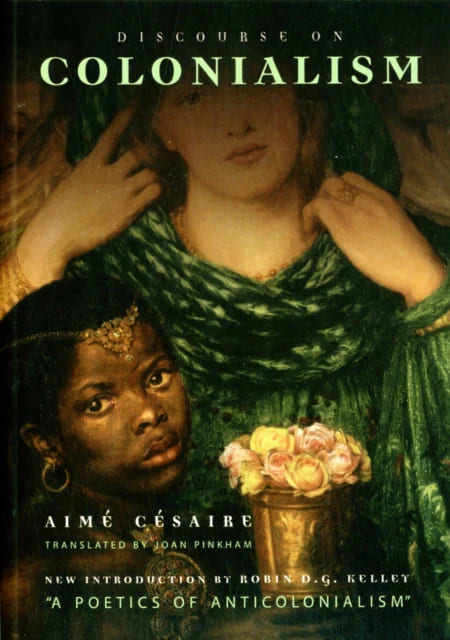Rubarubu #18
Team of Teams: Organisasi dalam Dunia Kompleks
Membongkar Menara Gading: Sebuah Tim Elit Militer Belajar dari Musuh
Pada puncak Perang Irak pasca-2003, pasukan khusus AS yang dipimpin oleh Jenderal Stanley McChrystal adalah yang terhebat di dunia. Mereka adalah tim-tim yang sempurna—seperti unit SEAL atau Delta Force—yang dilatih hingga level tertinggi, dengan perencanaan yang rinci, dan eksekusi yang presisi. Setiap tim adalah mesin pembunuh yang efisien. Namun, mereka kewalahan.
Musuh mereka, Al Qaeda di Irak (AQI) pimpinan Abu Musab al-Zarqawi, adalah sebuah jaringan yang kacau, adaptif, dan terdesentralisasi. Sementara pasukan AS beroperasi dengan rencana yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk disusun, AQI bisa merencanakan dan melaksanakan serangan lintas kota dalam hitungan jam. Setiap kali pasukan AS berhasil membunuh atau menangkap seorang target penting, jaringan AQI langsung bereorganisasi, mengisi kekosongan itu dengan cepat, dan seringkali justru menjadi lebih kuat. Mereka seperti “hidra”—monster mitologi Yunani yang setiap kali kepalanya dipenggal, dua kepala baru tumbuh menggantikannya.
McChrystal dan anak buahnya frustasi. Mereka lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terlatih, tetapi mereka kalah gesit. Masalahnya bukan pada orang-nya, tetapi pada sistem-nya. Dalam bukunya, McChrystal menulis: “We could not combine our talents with other elite teams as quickly and effectively as our enemy combined the talents of his fighters. We were losing to a network that was, by our own standards, disorganized, undisciplined, and even amateurish. But it was faster, more agile, and more creative.” (McChrystal, 2015, p. 8) [1].
Kisah ini adalah titik tolak dari “Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World”. Buku ini adalah sebuah laporan dari garis depan tentang bagaimana sebuah organisasi hierarkis raksasa—militer AS—terpaksa harus membongkar dirinya sendiri dan berevolusi menjadi sebuah “jaringan yang terikat erat” untuk bisa mengalahkan sebuah jaringan. Ini bukan sekadar buku militer; ini adalah sebuah manual untuk bertahan hidup di abad ke-21 yang kompleks.
Dari Efisiensi Menuju Ketangguhan
Buku ini dibangun di atas sebuah narasi transformasi yang powerful. Menurut McChrystal Dunia telah berubah. Ada perbedaan antara “kompleks”(Complex) dan “rumit” (Complicated).
- Sistem yang Rumit: Seperti mesin jam atau roket. Ia memiliki banyak bagian yang bergerak, tetapi ia dapat diurai, dipahami, dan diprediksi. Ia mengikuti rumus sebab-akibat yang linier. Tim yang sempurna adalah solusi untuk masalah yang rumit.
- Sistem yang Kompleks: Seperti cuaca atau ekosistem hutan. Ia terdiri dari banyak elemen yang saling berhubungan dan terus berinteraksi. Perilaku sistem secara keseluruhan muncul (emergent) dari interaksi ini dan tidak dapat diprediksi hanya dengan menganalisis bagian-bagiannya. Perubahan kecil dapat menghasilkan dampak besar (Efek Kupu-Kupu). Inilah dunia yang kita tinggali sekarang, dan ini adalah dunia di mana AQI beroperasi.
Pasukan AS dirancang untuk menghadapi masalah yang rumit. Mereka memiliki “pohon keputusan” untuk setiap skenario. Namun, menghadapi sistem yang kompleks seperti AQI, pohon keputusan itu menjadi tidak berguna. Mereka perlu menjadi sistem yang kompleks pula—tapi satu yang terkoordinasi dan memiliki tujuan bersama.
McChrystal dan timnya tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi mulai merancang dan menerapkan solusi transformatif. Judulnya, “From Many, One” (Dari Banyak, Satu), adalah sebuah paradoks yang elegan. Ini bukan tentang memaksa banyak orang menjadi satu entitas yang homogen (seperti dalam militer tradisional), tetapi tentang menciptakan kesatuan tujuan, pemahaman, dan usaha dari banyak tim yang beragam dan otonom.
McChrystal membongkar mesin birokrasi yang ada dan membangun ulang menjadi organisme yang hidup dan bernapas. Proses ini berdiri di atas tiga pilar utama.
Pilar 1: Membangun Kesadaran Bersama (Shared Consciousness)
McChrystal menyadari bahwa musuhnya, Al Qaeda di Irak (AQI), beroperasi seperti sebuah jaringan saraf—informasi mengalir dengan cepat dan keputusan dibuat secara lokal. Sebaliknya, organisasinya seperti sebuah piramida kuno di mana informasi bergerak naik turun dengan lambat melalui lapisan-lapisan komando. Untuk mengalahkan sebuah jaringan, mereka harus menjadisebuah jaringan.
McChrystal menawarkan resep untuk Transformasi—Membangun “Team of Teams.” Ia memimpin transformasi radikal dari organisasinya. Ia tidak menciptakan satu “tim super,” tetapi sebuah “tim dari tim-tim”—sebuah ekosistem di mana tim-tim yang kecil dan gesit dapat beroperasi dengan otonomi tinggi, namun tetap selaras dengan tujuan strategis yang besar. Transformasi ini berdiri di atas tiga pilar utama:
Ini adalah jantung dari seluruh sistem. Dalam organisasi tradisional, informasi mengalir ke atas, keputusan dibuat di puncak, dan perintah mengalir ke bawah. Ini lambat dan menciptakan “silosis.” McChrystal membongkar ini dengan menciptakan “O&I” (Operational and Intelligence Forum)—sebuah pertemuan via video conference yang diadakan setiap hari, melibatkan ribuan personel dari semua lini dan agensi (militer, CIA, FBI, dll.).
Tujuannya: Bukan untuk memberikan perintah, tetapi untuk berbagi konteks. Setiap orang, dari jenderal hingga operator di lapangan, melihat informasi yang sama, mendengar laporan yang sama, dan memahami “gambaran besar” perang pada saat yang bersamaan.
Kutipan Kunci: “Shared consciousness is the antidote to the silos that complicate and slow system-level effectiveness. It enables speed by pushing context down the chain of command and allowing decisions to be made at the edges.” (McChrystal, 2015, p. 237) [1].
Dengan “Shared Consciousness,” para pemimpin puncak tidak perlu lagi menjadi pusat kendali semua keputusan. Mereka beralih peran dari “pengendali chessboard” menjadi “tuan kebun” (Eyes-On, Hands-Off). Mereka menetapkan tujuan (“kita harus mengalahkan AQI”) dan “mengairi” kebun dengan sumber daya dan informasi.
Hasilnya: Tim di lapangan, yang sekarang memiliki konteks penuh, diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Mereka tidak perlu menunggu perintah. Seorang prajurit yang melihat peluang bisa langsung bergerak, karena ia tahu apa yang diketahui oleh jenderalnya, dan ia percaya bahwa rekan-rekannya di tempat lain akan memahami dan mendukung tindakannya.
Kutipan Kunci: “In a fast-moving, complex environment, waiting for orders is a recipe for failure. We had to empower those on the ground to take initiative.” (McChrystal, 2015, p. 155) [1].
Need-to-Know ke Need-to-Share
Sebuah organisasi sering menghadapi apa yang disebut “The Need to Know.”
- Silosis yang Mematikan: Intelijen, operasi, dan unsur-unsur pemerintah lainnya (CIA, FBI, DIA) bekerja dalam “kerangkeng” mereka sendiri. Mereka memiliki informasi yang vital bagi pihak lain, tetapi tidak membaginya karena budaya “need-to-know” (hanya berbagi jika pihak lain dianggap perlu tahu), kekhawatiran tentang keamanan, dan persaingan antar lembaga.
- Keterlambatan yang Fatal: Intelijen tentang sebuah target bisa memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk sampai ke unit yang bisa bertindak. Pada saat itu, targetnya sudah lama menghilang. McChrystal menggambarkan ini sebagai “pada hari ke-3, kami menyerang target hari ke-1 dengan informasi hari ke-14.”
Karena itu solusinya adalah dengan membangun “The O&I Forum” (Operational and Intelligence Forum). Ini adalah inovasi sentral yang menjadi tulang punggung Shared Consciousness. McChrystal menciptakan sebuah pertemuan via video telekonferensi yang diadakan setiap hari, selama 90 menit, dan melibatkan ribuan personel dari semua lini—dari markas besarnya di Baghdad hingga ke pos-pos terdepan, dan mencakup semua agensi yang terlibat.
- Tujuannya Bukan untuk Memberi Perintah: Ini adalah poin kritis. Forum O&I bukanlah alat komando dan kendali. Tujuannya adalah “to create a shared, fundamental understanding of the situation” (menciptakan pemahaman mendasar yang sama tentang situasi).
- Transparansi Radikal: Dalam forum ini, semua informasi dibagikan secara terbuka. Laporan dari lapangan, analisis intelijen terbaru, bahkan kegagalan, didiskusikan secara terbuka. Semua orang mendengar hal yang sama pada waktu yang sama.
- Membongkar Hierarki: Seorang sersan yang baru saja kembali dari misi bisa langsung melaporkan temuannya kepada seorang jenderal, tanpa melalui rantai komando. Ini memotong lapisan birokrasi dan mempercepat aliran informasi secara dramatis.
Kutipan Kunci McChrystal: “The O&I was not a briefing for the commanders. It was a conversation among the entire force about what was happening and what we were going to do about it… We were building a bird’s-eye view that was accessible to everyone.” (McChrystal, 2015, p. 158).
Hasilnya adalah terjadi perubahan dari “Need-to-Know” ke “Need-to-Share.” Dengan Shared Consciousness, setiap orang dalam organisasi memiliki konteks yang sama. Seorang operator di Mosul memahami bagaimana aksinya berkontribusi pada misi secara keseluruhan di Baghdad. Ini menciptakan rasa tujuan bersama yang kuat dan memungkinkan orang untuk melihat peluang yang tidak akan terlihat jika mereka hanya fokus pada tugas sempit mereka sendiri.
Pilar 2: Pemberdayaan Eksekusi (Empowered Execution)
Memiliki pemahaman bersama saja tidak cukup. Organisasi juga harus mampu bertindak atas pemahaman itu dengan cepat. Di sinilah pilar kedua muncul.
Pada sisi lain organisasi juga sering menghadapi masalah: “The Command-and-Control Bottleneck.” Dalam struktur komando tradisional, keputusan harus naik ke puncak piramida untuk disetujui, lalu turun lagi untuk dilaksanakan. Proses ini, yang McChrystal sebut “pengendali chessboard,” terlalu lambat untuk menghadapi musuh yang bergerak cepat seperti AQI. Seorang prajurit di lapangan yang melihat peluang emas harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan persetujuan, dan peluang itu pun hilang.
Solusinya adalah “Eyes-On, Hands-Off” Leadership. McChrystal secara radikal mendelegasikan wewenang. Peran pemimpin berubah dari “pengendali chessboard” menjadi “tuan kebun” (gardener).
- Pengendali Chessboard: Mencoba mengontrol setiap gerakan dari atas, percaya bahwa hanya dia yang memiliki gambaran lengkap untuk membuat keputusan terbaik.
- Tuan Kebun: Fokus pada menciptakan lingkungan yang subur (dengan Shared Consciousnesssebagai pupuk dan air), lalu mempercayai tim-timnya untuk tumbuh dan berbuah. Dia “melihat” (eyes-on) keseluruhan kebun, tetapi tidak “mengotori tangan” (hands-off) dengan mencabuti setiap tanaman.
Mekanisme yang dibangun adalah “Bersenjata dengan Konteks.” Dengan Shared Consciousness, orang-orang di lapangan (“the edges”) tidak lagi buta. Mereka memiliki konteks strategis yang sama dengan sang jenderal. Oleh karena itu, mereka dilengkapi untuk membuat keputusan taktis yang berkualitas tinggi yang selaras dengan tujuan strategis.
Kutipan Kunci McChrystal: “We came to rely on the principle of ’empowered execution.’ We pushed the power of decision making down the chain of command as far as we could, to those with the best information and proximity to the problem.” (McChrystal, 2015, p. 193).
Ini berarti seorang komandan tim di lapangan bisa memutuskan untuk melancarkan serangan, mengubah rencana, atau bekerja sama dengan unit lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, asalkan tindakannya selaras dengan tujuan yang dipahami bersama.
Transformasi ini terbukti sangat sukses. Jaringan mereka menjadi lebih cepat dan lebih tanggup daripada AQI, yang akhirnya berujung pada penemuan dan pembunuhan al-Zarqawi. Prinsip-prinsip “Team of Teams” kemudian dirumuskan sebagai kerangka untuk organisasi mana pun:
- Kecepatan dan Ketangkasan Mengalahkan Kehebatan dan Kekuatan: Di dunia yang kompleks, kemampuan untuk beradaptasi lebih penting daripada ukuran atau sumber daya.
- Transparansi Radikal: Informasi harus mengalir bebas, bukan sebagai alat kekuasaan.
- Percaya dan Percayai (Trust and Common Purpose): Otonomi hanya bekerja jika ada kepercayaan yang dibangun oleh tujuan bersama dan pemahaman bersama.
Pilar 3: Kepemimpinan yang Melayani (The Leader as a Gardener)
Pilar ketiga ini adalah fondasi yang memungkinkan dua pilar lainnya berfungsi. Transformasi semacam ini tidak mungkin terjadi tanpa perubahan mendasar dalam peran dan mindset kepemimpinan. Peran pemimpin berubah secara fundamental. Bukan lagi sang “pahlawan” yang memiliki semua jawaban, tetapi seorang “arsitek” atau “pengurus kebun” yang bertugas membangun dan memelihara sistem yang memungkinkan orang lain untuk unggul.
Pemikiran ini bergema dengan filosofi Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok kuno: “Pemimpin terbaik adalah mereka yang hampir tidak diketahui oleh orang-orang… Ketika pekerjaannya selesai, tujuannya terpenuhi, mereka akan berkata: kami melakukannya sendiri.” [2]. Ini juga selaras dengan konsep “sayyidul qoum khadimuhum” dalam tradisi Islam, yang artinya “pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” [3]. Seorang pemimpin melayani dengan memastikan sistem berjalan untuk memberdayakan anggotanya.
Setelah McChrystal menjelaskan apa yang diubah (dari organisasi mekanistik ke jaringan adaptif) dan bagaimana mengubahnya (melalui Shared Consciousness dan Empowered Execution), dan, seperti apa peran seorang pemimpin dalam sistem seperti ini? Jawabannya yang powerful dan metaforis adalah: Pemimpin harus berubah dari seorang “Pengendali Catur” menjadi seorang “Tukang Kebun.”
Krisis sebuah metafora: kematian sang pengendali catur. McChrystal mengakui betapa menggodanya metafora pemimpin sebagai “pengendali catur” (chess player). Seorang grandmaster catur melihat seluruh papan, merencanakan langkah-langkah ke depan, dan menggerakkan setiap bidak dengan presisi sesuai kehendaknya. Setiap bidak pasif dan mengandalkan sang master untuk nilai dan arahnya. Ini adalah fantasi kepemimpinan yang klasik: sang pemimpin yang jenius dan visioner di puncak, yang mengendalikan segala sesuatu.
Kutipan Kunci: “The image of the master chess player directing the game from on high is deeply seductive. It promises control, certainty, and the triumph of intellect over chaos.”(McChrystal, 2015, p. 230).
Namun, McChrystal dengan tegas menyatakan bahwa metafora ini sudah mati dalam lingkungan yang kompleks. Dalam peperangan melawan AQI, “papan catur”-nya tidak pernah berhenti berubah; bidak-bidak lawan memiliki kemauan sendiri, terus berlipat ganda, dan mengubah aturan mainnya sendiri. Tidak ada seorang “pemain catur” yang bisa cukup cepat atau cukup pintar untuk mengendalikan permainan seperti itu.
Inilah kelahiran sebuah metafora baru: sang tukang kebun. Sebagai pengganti metafora catur, McChrystal menawarkan metafora yang lebih organik dan rendah hati: pemimpin sebagai “tukang kebun” (gardener). Seorang tukang kebun tidak bisa memerintahkan sebuah tanaman untuk tumbuh. Dia tidak bisa mengontrol matahari atau hujan. Apa yang bisa dia lakukan?
- Mempersiapkan Tanah: Dia memastikan tanahnya subur, gembur, dan penuh nutrisi.
- Menanam Benih: Dia memilih benih yang tepat dan menanamnya pada kedalaman dan jarak yang optimal.
- Menyiram dan Memupuk: Dia memberikan air dan nutrisi yang dibutuhkan pada waktu yang tepat.
- Melindungi dari Hama: Dia membasmi gulma dan melindungi tanaman muda dari serangga dan penyakit.
- Dan yang terpenting: BERSABAR. Dia memahami bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu dan terjadi sesuai dengan proses alaminya sendiri.
Dia memiliki “pengaruh,” bukan “kendali.” Dia menciptakan dan menjaga kondisi yang memungkinkan pertumbuhan terjadi. Kutipan Kunci: “I moved from being a chess player to being a gardener. My job was to create and tend an environment in which the organization could flourish.” (McChrystal, 2015, p. 230). [1].
Apa yang dilakukan “sang tukang kebun” dalam organisasi? Metafora ini diterjemahkan ke dalam tindakan kepemimpinan yang sangat nyata dan konkret:
1. Menciptakan Ekosistem yang Sehat (Shared Consciousness)
Tugas utama “tukang kebun” adalah menciptakan “tanah subur” bagi kolaborasi dan inovasi. Dalam konteks Task Force, ini berarti:
- Merancang dan Memelihara Forum O&I: McChrystal secara pribadi memastikan bahwa forum O&I berjalan efektif. Dia bukan hanya menghadirinya, tetapi secara aktif membudayakan transparansi dan partisipasi. Ini adalah cara utama dia “menyiram” organisasinya dengan informasi.
- Menghubungkan yang Tidak Terhubung: Seperti seorang tukang kebun yang memastikan semua tanaman mendapat sinar matahari, pemimpin aktif menjembatani silo-silo, memperkenalkan orang dari tim yang berbeda, dan mendorong kolaborasi lintas fungsi.
2. Memupuk dan Membuang Gulma (Budaya)
Seorang tukang kebun tidak bisa mengontrol tanaman satu per satu, tetapi dia bisa membentuk keseluruhan kebunnya.
- Memupuk Kepercayaan dan Tujuan Bersama: McChrystal terus-menerus mengomunikasikan “mengapa” di balik misi mereka. Dia memupuk rasa tujuan bersama yang menjadi perekat bagi semua tim yang otonom.
- Membuang “Gulma” Birokrasi: Dia secara aktif mengidentifikasi dan menghilangkan prosedur, aturan, dan lapisan manajemen yang tidak perlu yang menghambat aliran informasi dan kecepatan—ini adalah “gulma” yang merampas nutrisi dari organisasi.
3. Merawat, Bukan Mengendalikan (Empowered Execution)
Ini adalah pergeseran mindset yang paling sulit, tetapi paling penting.
- Eyes-On, Hands-Off: Seorang tukang kebun melihat keseluruhan kebunnya (eyes-on), memperhatikan mana yang kering atau terserang hama. Tetapi dia tidak menarik setiap tunas untuk membantunya tumbuh (hands-off). Demikian juga, McChrystal memantau operasi secara keseluruhan tetapi tidak mencoba untuk mengendalikan setiap keputusan taktis di lapangan.
- Menerima Kegagalan sebagai Bagian dari Proses: Tidak semua benih akan tumbuh. Seorang tukang kebun tidak marah pada benih yang gagal; dia belajar darinya dan menanam lagi. McChrystal menciptakan lingkungan di mana kegagalan yang terhormat (karena mencoba hal baru) dapat diterima, asalkan organisasi belajar darinya. Ini sangat penting untuk mendorong inisiatif dan keberanian.
Metafora “Tukang Kebun” ini bergema dalam banyak tradisi kebijaksanaan:
- Filsafat Taoisme Cina: Lao Tzu dalam Tao Te Ching menulis: “Pemimpin terbaik adalah yang hampir tidak diketahui oleh orang-orang… Ketika pekerjaannya selesai, tujuannya terpenuhi, mereka akan berkata: kami sendirilah yang melakukannya.” Ini adalah esensi dari kepemimpinan tukang kebun—menciptakan kondisi sehingga kesuksesan terasa seperti pencapaian alami dari tim itu sendiri.
- Pemikiran Islam: Terdapat sebuah hadits yang menyatakan: “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (Sayyidul qaumi khadimuhum). Seorang “tukang kebun” pada hakikatnya adalah seorang pelayan bagi kebunnya—dia melayani dengan menyediakan air, pupuk, dan perlindungan, semua untuk memungkinkan kebun itu mencapai potensi penuhnya.
Pemimpin tidak lagi menjadi “orang terpintar” yang memiliki semua jawaban. Sebaliknya, mereka menjadi “arsitek organisasi” yang bertugas merancang dan memelihara sistem—”platform”—di mana orang lain dapat berprestasi.
- Menciptakan Konektivitas: Tugas utama pemimpin adalah memastikan bahwa jaringan komunikasi dan kolaborasi berfungsi dengan baik, seperti yang dilakukan dengan O&I Forum.
- Menjaga Tujuan Bersama: Pemimpin harus terus-menerus mengomunikasikan “mengapa” di balik semua yang mereka lakukan, memastikan bahwa tujuan besar (mengalahkan AQI) tetap menjadi pusat gravitasi bagi seluruh organisasi.
- Memupuk Kepercayaan: Empowered Execution hanya dapat berjalan jika ada kepercayaan yang mendalam. Pemimpin harus mempercayai bawahan mereka untuk membuat keputusan yang tepat, dan bawahan harus percaya bahwa pemimpin akan mendukung mereka bahkan jika ada yang tidak beres.
McChrystal menggambarkan bagaimana mereka membentuk “Joint Task Force” yang benar-benar terintegrasi. Alih-alih hanya “menyewa” spesialis dari agensi lain, mereka menempatkan orang-orang dari CIA, FBI, dan NSA langsung ke dalam tim operasi mereka. Ini menciptakan tim ad-hoc yang sangat luwes dan efektif, di mana seorang analis intelijen sipil bisa langsung memberikan masukan kepada seorang operator Delta Force dalam misi yang sedang berlangsung.
Buku ini menunjukkan bagaimana ketiga pilar ini saling terkait:
- Shared Consciousness memberikan konteks yang sama kepada semua orang.
- Empowered Execution memberikan wewenang kepada orang-orang di lapangan untuk bertindak berdasarkan konteks itu.
- Kepemimpinan yang Melayani menciptakan sistem dan budaya yang memungkinkan kedua hal itu terjadi.
Hasilnya adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuatan dan koherensi dari sebuah organisasi terpusat (“One“), tetapi mempertahankan kecepatan, fleksibilitas, dan kreativitas dari banyak tim yang terdesentralisasi (“Many“). Mereka berubah dari sekumpulan “tim yang sempurna” (yang bekerja sendiri-sendiri) menjadi sebuah “tim dari tim-tim” (yang bekerja secara harmonis dalam sebuah jaringan). Inilah esensi dari transformasi “From Many, One“—sebuah paradigma baru untuk mengorganisir dan memimpin dalam dunia yang kompleks.
Relevansi dengan Dunia Saat Ini dan Masa Depan
Prinsip-prinsip “Team of Teams” bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan di era disrupsi. Menghadapi Disrupsi Digital & AI: Perusahaan-perusahaan mapan (seperti MetaStream dalam cerita pembuka ringkasan Morgan) sering kali kalah dari startup yang lincah karena terjebak dalam struktur hierarkis yang lamban. “Team of Teams” adalah blueprint untuk transformasi digital yang sesungguhnya—bukan sekadar mengadopsi teknologi, tetapi mengubah caraorganisasi beroperasi.
Menanggapi Krisis Global: Pandemi COVID-19 adalah contoh sempurna dari sistem yang kompleks. Negara-negara yang berhasil adalah yang mampu membangun “shared consciousness” (dengan data transparan) dan “empowered execution” (memungkinkan rumah sakit dan pemerintah daerah berinovasi dengan cepat). Sebaliknya, birokrasi yang kaku terbukti fatal.
Masa Depan Kerja: Dengan kerja hybrid dan tim yang tersebar secara global, membangun kohesi dan kecepatan menjadi tantangan. Platform kolaborasi digital modern adalah versi teknologi dari “O&I Forum,” tetapi tanpa budaya transparansi dan kepercayaan, platform itu hanyalah alat yang kosong.
Relevansi dengan Konteks Indonesia
Struktur organisasi di Indonesia, baik di pemerintahan maupun korporasi, sering kali sangat hierarkis dan birokratis—mirip dengan militer AS sebelum transformasi. Prinsip “Team of Teams” sangat kontekstual untuk dilema Indonesia.
Birokrasi Pemerintahan: Birokrasi Indonesia terkenal dengan “silo-silo” K/L (Kementerian/ Lembaga) yang kuat. Masalah kompleks seperti pengentasan kemiskinan atau penanganan sampah laut membutuhkan “Shared Consciousness” melalui pusat data terpadu dan “Empowered Execution” dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, yang memahami konteks lokal mereka secara langsung.
Inovasi di Korporasi Raksasa: Banyak konglomerat Indonesia yang didirikan oleh generasi pendiri yang kuat (seperti “pengendali chessboard”). Untuk bertahan di era digital, mereka perlu beralih ke model “tuan kebun,” memberdayakan tim-tim kecil dan lincah (seperti unit digital) untuk berinovasi tanpa terhambat oleh birokrasi induknya.
Budaya Kekuasaan: Budaya tinggi “power distance” di Indonesia, di mana jarak antara atasan dan bawahan sangat jauh, adalah penghalang terbesar untuk “Empowered Execution.” Perlu perubahan budaya yang mendalam di mana pemimpin lebih percaya dan melayani, sambil membangun tujuan bersama yang kuat, seperti “Bhinneka Tunggal Ika”, sebagai perekat “Team of Teams” nasional.
Catatan Akhir
“Leading Like a Gardener” adalah sebuah penolakan terhadap model kepemimpinan heroik dan individualistik. Ini adalah panggilan untuk sebuah kepemimpinan yang kolaboratif, rendah hati, dan sistemik. McChrystal mengakui bahwa ini membutuhkan ego yang besar untuk memimpin transformasi seperti itu, tetapi juga membutuhkan kerendahan hati yang besar untuk melepaskan kendalisetelah sistemnya berjalan.
Bab akhir buku ini menutup dengan pesan yang powerful: Dalam dunia yang kompleks, keberhasilan bukanlah tentang kepintaran seorang pemimpin tunggal, tetapi tentang kekuatan kolektif dari sebuah ekosistem yang dia bantu ciptakan. Pemimpin masa depan bukanlah seorang jenius yang sendirian di puncak gunung, melainkan seorang tukang kebun yang sabar dan telaten yang bekerja di tengah-tengah kebunnya, memastikan setiap tanaman mendapat apa yang dibutuhkannya untuk tumbuh subur bersama-sama.
“Team of Teams” bukan sekadar buku tentang mengalahkan teroris. Ini adalah sebuah kisah tentang kerendahan hati. Ini tentang sebuah organisasi paling powerful di dunia yang harus mengakui bahwa model operasinya yang selama ini diandalkan sudah usang.
Pesan McChrystal sangat jelas: Baik Anda seorang CEO, pemimpin NGO, atau pejabat pemerintah, Anda tidak bisa lagi hanya mengandalkan tim-tim hebat yang bekerja dalam silo. Anda harus membangun jaringan tim-tim yang saling terhubung, yang digerakkan oleh tujuan bersama, disatukan oleh kesadaran bersama, dan dipercepat oleh pemberdayaan yang penuh kepercayaan.
Di dunia yang semakin terhubung, tidak stabil, dan tidak pasti, kemampuan untuk beradaptasi sebagai sebuah kesatuan—sebagai sebuah “Tim dari Tim-Tim”—adalah satu-satunya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Masa depan bukan tentang menjadi yang terkuat, melainkan tentang menjadi yang paling tanggup belajar dan berubah.
Lumajang-Cirebon, 24 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
[1] McChrystal, S., Collins, T., Silverman, D., & Fussell, C. (2015). Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World. Portfolio/Penguin.
[2] Tzu, L. (n.d.). Tao Te Ching (Chapter 17). (Various translations).
[3] Hadits Riwayat Al-Baihaqi. (n.d.). Syu’ab al-Iman. (Various translations).
[4] Hempel, J. (2015, May 19). What General Stanley McChrystal’s ‘Team of Teams’ Can Teach Corporate America. LinkedIn. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/what-general-stanley-mcchrystals-team-teams-can-teach-jessica-hempel/
[5] Snowden, D. J. (2015). [Review of the book Team of Teams, by S. McChrystal et al.]. Cognitive Edge Blog. Retrieved from https://cognitive-edge.com/blog/team-of-teams-a-review/