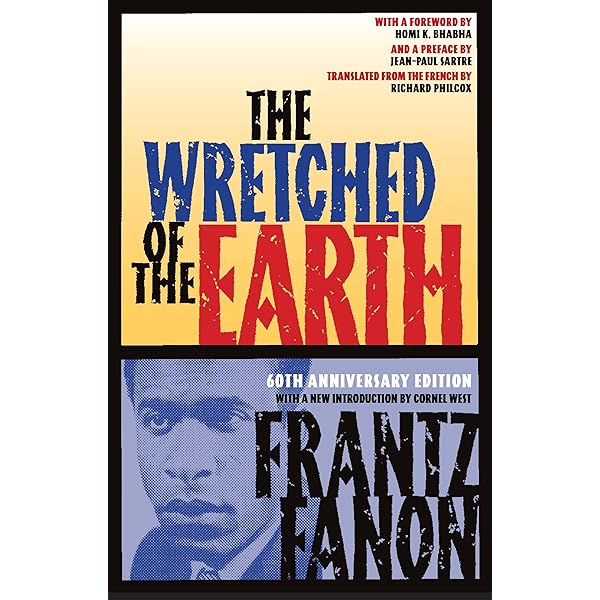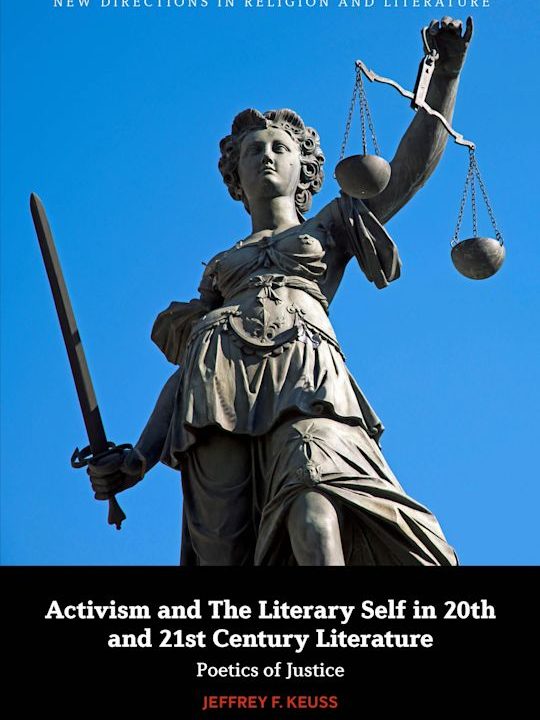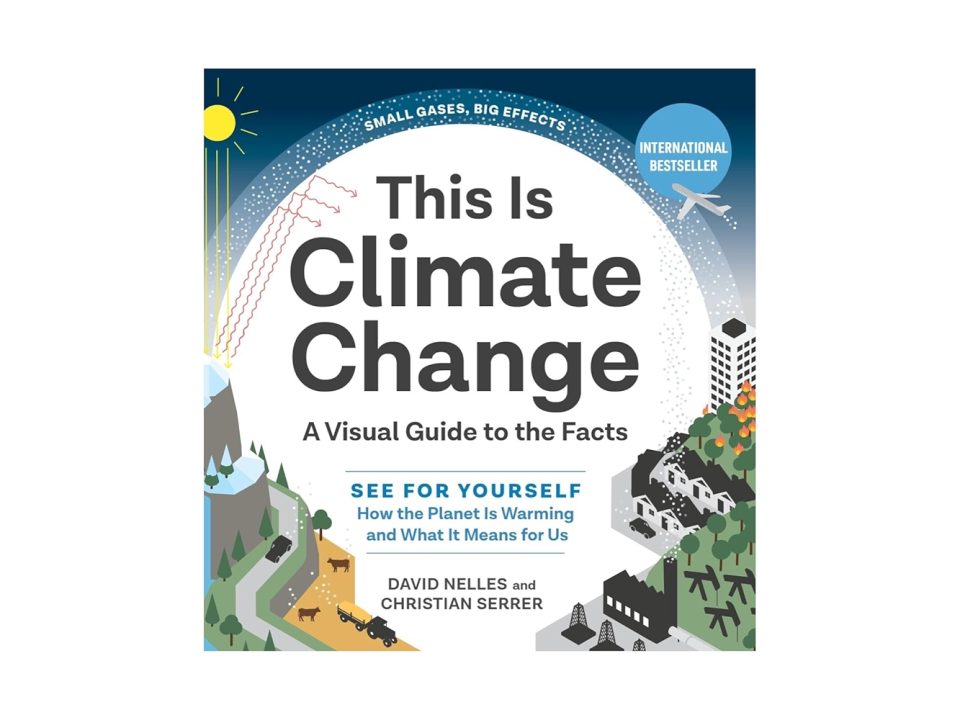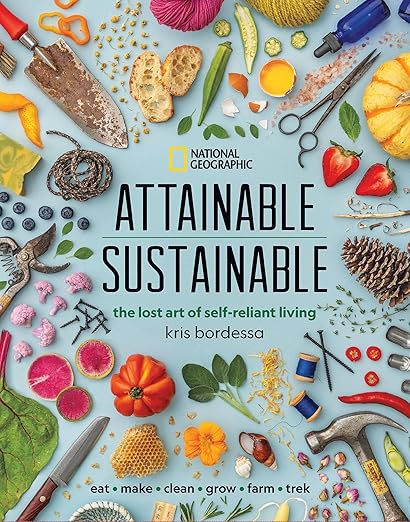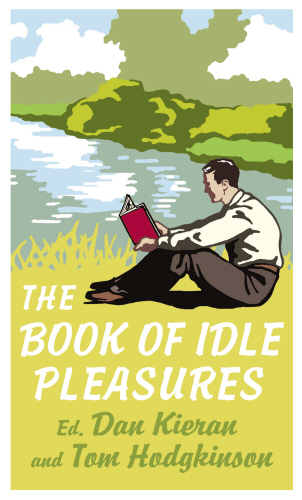# 06 Rubarubu
Luka, Perlawanan, dan Kelahiran Dunia Baru
Di sebuah pagi di Aljazair tahun 1950-an, seorang lelaki muda yang berprofesi sebagai psikiater menyaksikan tubuh-tubuh yang penuh luka datang ke rumah sakit militer di Blida. Mereka bukan hanya korban perang fisik, tapi juga perang batin akibat kolonialisme: trauma, rasa hina diri, dan kehilangan identitas. Lelaki itu nampak lelah menahan api amarah.
Ia hanyalah anak pulau yang kesepian, tetapi ia mampu melawan dunia. Di sebuah pulau kecil di Karibia bernama Martinique, pada tahun 1925, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang hati nurani dunia. Namanya Frantz Omar Fanon. Ia tumbuh di bawah bayang-bayang kolonialis-me Prancis—sebuah sistem yang memecah manusia berdasarkan warna kulit, bahkan di antara mereka yang sama-sama tertindas.
Sebagai remaja, Fanon sudah merasakan getirnya rasialisme: di sekolah menengah, ia belajar dari penyair besar Aimé Césaire, sang pelopor gerakan Négritude yang menanamkan kebangga-an akan identitas kulit hitam. Césaire mengajarinya bahwa kata-kata bisa menjadi senjata. Tetapi Fanon akan melangkah lebih jauh: baginya, luka penjajahan bukan hanya di bahasa, melainkan di jiwa manusia.
Frantz Fanon, penulis buku itu, dan dari luka-luka itu lahirlah salah satu karya paling mengguncang abad ke-20: The Wretched of the Earth. Buku ini bukan sekadar manifesto politik, melainkan juga pembedahan mendalam atas jiwa manusia yang terjajah. Dan dunia yang diatur oleh kekerasan kolonial. The Wretched of the Earth — rekaman atas luka, perlawanan, dan kelahiran dunia baru, yang sialnya hingga kini dunia baru itu masih menganga luka.
Hari ini, 10 November, kita merayakan Hari Pahlawan. Pahlawan yang lahir dari luka dan perlawanan atas penjajahan. Saya merayakan Hari Pahlawan kali ini dengan berbagi buku-buku yang mengupas sola kolonialisme. Buku The Wretched of the Earth adalah pilihan utama. Ini buku lama yang diterbitkan pada 1961. Tetapi pemikiran, kisah dan luka yang diukir dalam lembar-lembar halamannya terasa masih keras hingga saat ini.
Judul “The Wretched of the Earth” aslinya berbahasa Perancis Les Damnés de la Terre. “The Wretched of the Earth” secara harfiah berarti: “Mereka yang terkutuk / yang malang / yang tertindas di muka bumi.” Dalam bahasa Prancis asli: Les Damnés de la Terre
- Les damnés berarti “orang-orang yang dikutuk”, “yang terdampar di neraka”, atau “yang dicampakkan dari rahmat”.
- De la terre berarti “dari bumi” atau “di muka bumi”.
Terjemahan yang paling tepat dalam bahasa Indonesia bisa berbunyi: “Orang-orang yang Terkutuk di Muka Bumi” atau “Yang Tertindas di Bumi”, tergantung penekanan yang ingin kita maksudkan: religius-eksistensial (damned) atau sosial-politik (wretched).
Fanon tidak memilih judul itu secara kebetulan. Ia mengambilnya dari baris pertama lagu “Internationale”, himne revolusi buruh dan sosialisme abad ke-19:
“Arise ye wretched of the earth,
Arise ye prisoners of want…”
(“Bangkitlah, wahai orang-orang terkutuk di bumi,
Bangkitlah, wahai tawanan kemiskinan…”)
Dengan mengambil frasa ini, Fanon langsung menempatkan perjuangan kolonial dalam tradisi universal perlawanan kaum tertindas — bukan hanya perjuangan nasional Afrika, tetapi perjuangan manusia melawan sistem penindasan global.
Bagi Fanon, mereka yang disebut “the wretched of the earth” adalah:
- Petani dan buruh di tanah jajahan;
- Mereka yang hidup di “zona non-being” (daerah yang dihapus dari peta kemanusiaan);
- Mereka yang bahkan kehilangan bahasa untuk menyatakan penderitaannya.
Namun Fanon juga berkata bahwa dari golongan inilah lahir potensi revolusi sejati. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk dipertahankan selain kehidupan, maka mereka mampu memutus rantai kolonial.
Inilah mengapa bab pertama bukunya berjudul “Concerning Violence” —kekerasan revolusioner sebagai jalan untuk memulihkan kemanusiaan yang dicuri.
Judul The Wretched of the Earth adalah deklarasi moral dan politis: Dunia modern dibangun di atas penderitaan miliaran manusia, dan hanya dengan mendengar jeritan “yang terkutuk” itu
kita bisa menemukan kembali kemanusiaan kita bersama. Fanon mengajak pembaca untuk mengakui dan mengambil posisi: Tidak ada “netralitas” di hadapan penderitaan sistemik — entah kita bersama yang terkutuk, atau kita bagian dari sistem yang mengutuk.
Perang, luka, dan kesadaran baru
Ketika Perang Dunia II meletus, Fanon yang baru berusia 18 tahun melarikan diri dari pulau koloninya untuk bergabung dengan Tentara Pembebasan Prancis melawan Nazi. Ironisnya, setelah perang usai, ia melihat kenyataan pahit: di tanah air yang katanya memperjuangkan “kebebasan dan persamaan”, ia tetap dianggap warga kelas dua karena warna kulitnya.
Pengalaman itu menjadi luka pertama dan kesadaran awal: bahwa rasisme bukan sekadar kebencian personal, tetapi sistemik dan struktural. Bahwa kolonialisme hidup bahkan di dalam tubuh republik yang mengaku menjunjung “liberté, égalité, fraternité.”
Setelah perang, Fanon belajar kedokteran dan psikiatri di Lyon, Prancis. Ia meneliti gangguan jiwa pada pasien kulit hitam dan menemukan sesuatu yang mengerikan: penjajahan menciptakan trauma kolektif, luka psikis yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Ia menulis buku pertamanya, Black Skin, White Masks (1952) — analisis tajam tentang bagaimana orang kulit hitam di dunia kolonial “dipaksa memakai topeng kulit putih” untuk diterima. Ia menulis:
“To speak a language is to take on a world, a culture.”
(Berbicara dalam suatu bahasa berarti mengambil alih dunia dan kebudayaannya). Melalui buku itu, Fanon memperlihatkan bagaimana bahasa, citra, dan norma kolonial menginternalisasi inferioritas di benak orang-orang terjajah. Ia menyadari: penjajahan tidak hanya menaklukkan tanah, tapi juga kesadaran. Fanon menjelma dari psikiater menjadi revolusioner.
Aljazair dan kebangkitan radikal
Pada 1953, Fanon ditugaskan sebagai psikiater di Rumah Sakit Blida-Joinville, Aljazair, ketika negeri itu masih di bawah jajahan Prancis. Di sana ia menyaksikan kekerasan kolonial dalam bentuk paling telanjang: penyiksaan, penghinaan, dan penghancuran martabat manusia–sesuatu sangat kita kenal akhir-akhir dengan kebiadaban Zionis Israel atas Palestina, dan ini tengah berlangsung lebih dari 100 tahun.
Ia menulis surat pengunduran diri yang legendaris pada 1956, dengan kata-kata yang membakar: “Saya tidak bisa lagi melayani kegilaan sistem kolonial yang menciptakan penyakit yang kemudian saya harus obati.” Setelah itu, Fanon bergabung dengan Front de Libération Nationale (FLN) — gerakan pembebasan Aljazair. Ia menulis, menyebar pamflet, dan menjadi juru bicara internasional perjuangan anti-kolonial. Dari psikiater, ia berubah menjadi revolusioner.
Selama perang kemerdekaan Aljazair, Fanon menulis dengan amarah sekaligus cinta. Ia menulis A Dying Colonialism (1959) dan kemudian karya terakhirnya, The Wretched of the Earth (1961) — buku yang ia selesaikan dalam keadaan sakit parah akibat leukemia. Dalam buku itu, Fanon menulis dengan kecepatan seorang yang berpacu dengan maut. Ia memanggil “yang terkutuk di bumi” untuk bangkit, bukan hanya melawan penjajahan, tetapi melahirkan kembali kemanusiaan baru.
Ia menulis: “Each generation must discover its mission, fulfill it or betray it.” (Setiap generasi harus menemukan misinya, menunaikannya atau mengkhianatinya). Fanon seperti menulis dari tepi jurang.
Kematian dan warisan
Fanon meninggal dunia pada Desember 1961 di usia 36 tahun, di Amerika Serikat, hanya beberapa bulan sebelum Aljazair merdeka. Jenazahnya dipulangkan dan dimakamkan di tanah yang ia cintai — di perbatasan Aljazair dan Tunisia, di tengah pejuang kemerdekaan.
Tapi gagasannya tidak mati. Karya-karyanya menjadi kitab suci bagi gerakan dekolonisasi dari Afrika hingga Amerika Latin, dari Palestina hingga Taiwan. Para pemikir seperti Paulo Freire, Ngũgĩ wa Thiong’o, Edward Said, Angela Davis, dan bahkan Che Guevara terinspirasi oleh Fanon.
Dalam dunia modern yang masih dipenuhi “penjajahan baru” — lewat ekonomi global, teknologi, dan ekologi — suara Fanon menggema lebih keras dari sebelumnya. Fanon hari ini
seolah memperingatkan kita: Kolonialisme tidak mati, ia hanya berganti wajah — menjadi utang, data, dan karbon.
Di Indonesia, pemikirannya tetap relevan: dalam perjuangan masyarakat adat melawan perampasan tanah, dalam kritik terhadap kapitalisme hijau, dan dalam upaya menemukan kembali kemandirian bangsa yang berakar pada martabat kemanusiaan.
Kisah Frantz Fanon adalah kisah tentang keberanian seorang manusia untuk melawan gila normalitas dunia. Dari dokter menjadi revolusioner, dari penulis menjadi suara jutaan yang tak bersuara. Ia mengajarkan bahwa penyembuhan sejati tidak datang dari kompromi, tetapi dari keberanian memutus rantai.
“For Fanon, to be human is to resist.” (Bagi Fanon, menjadi manusia berarti melawan.)
Maka sudah sepantasnya kita membuka kembali halaman demi halaman, lembar demi lembar pemikiran Fanon dalam The Wretched of the Earth.
Kekerasan sebagai Bahasa Kolonial dan Pembebasan
Fanon membuka bukunya dengan kalimat yang tajam: “Decolonization is always a violent phenomenon.” Ia menolak romantisasi kolonialisme atau imajinasi bahwa kebebasan dapat dicapai lewat negosiasi moral. Baginya, kekerasan kolonial membentuk struktur dunia yang memisahkan manusia menjadi dua: penjajah dan terjajah. Dalam sistem itu, kekerasan bukanlah kecelakaan, melainkan fondasi dari tatanan sosial. Karenanya, bagi Fanon, kekerasan revolusioner adalah bentuk pembalikan historis—bukan balas dendam, tapi pembersihan diri kolektif. Dalam perlawanan, sang tertindas menemukan kembali martabat dan agensinya.
Fanon menulis: “At the level of individuals, violence is a cleansing force. It frees the native from his inferiority complex and from his despair and inaction.” Dari sini kita paham mengapa kaum perlawanan tak pernah lepas dari kekerasan.
Dalam konteks dunia sekarang—di Palestina, Yaman, Kongo, Sudan, atau bahkan di kawasan perkotaan yang dimarginalkan—kata-kata Fanon masih bergema. Kekerasan yang ia maksud bukan semata fisik, melainkan perlawanan terhadap sistem penindasan yang membuat manusia kehilangan kemanusiaannya. Fanon mengajarkan bahwa dekolonisasi adalah proses membangun dunia baru, bukan sekadar mengganti penguasa lama dengan yang baru.
Gagasan-gagasan Frantz Fanon masih sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini: bagaimana kolonialisme muncul kembali dalam wujud-wujud baru (ekologis, ekonomi, digital, keamanan) yang Fanon sudah peringatkan meski dalam konteks abad pertengahan dekolonisasi. Saya akan membahas inti pemikiran Fanon (kekerasan & pembebasan, patologi psikologis penjajahan, nasionalisme dan jebakan borjuis nasional, budaya dan narasi), lalu memetakannya ke fenomena kontemporer — green colonialism, ekstraktivisme, necropolitics, “coloniality of data”, debt/finance, dan kapitalisme rasial — serta mengusulkan arah etis-politik berdasarkan warisan Fanon untuk praktik dekolonial hari ini.
Fanon bukan hanya teoritikus pemberontakan; ia adalah pemikir yang mengajarkan bagaimana relasi kekuasaan membentuk jiwa, institusi, dan wacana. Untuk membaca dunia sekarang melalui kacamata Fanon berarti menaruh perhatian pada 1) siapa yang mendapat manfaat sistem, 2) bagaimana penderitaan diproduksi dan dinormalisasi, dan 3) apa yang diperlukan agar pembalikan kekuasaan bukan sekadar pergantian elite tetapi transformasi struktur.
Fanon menegaskan bahwa deskolonisasi adalah peristiwa yang memutuskan struktur kekuasaan; dalam banyak kasus perubahan politik hanya terjadi melalui konfrontasi. Ia memandang kekerasan revolusioner tidak sebagai glorifikasi brutalitas, tetapi sebagai «pembasuhan» psikologis bagi orang-orang yang lama diinjak: melalui tindakan kolektif mereka mengembalikan martabat. Ini juga menunjukkan bahwa struktur kolonial memelihara ketidakadilan melalui normalisasi — sehingga respon radikal seringkali muncul.
Sebagai psikiater, Fanon membawa perspektif yang jarang disentuh revolusioner lain: kolonialisme juga menjajah alam bawah sadar. Kolonialisme adalah patologi jiwa. Fenomena itu bisa dilihat sebagai psikologi penjajahan. Dalam bab “Colonial War and Mental Disorders,” ia menggambarkan pasien-pasien yang menderita gangguan mental karena kekerasan perang dan penghinaan rasial. Ia menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya perampasan tanah, tapi juga perampasan jiwa, yang melahirkan rasa malu, inferioritas, dan bahkan kekerasan internal di kalangan tertindas.
Dalam Black Skin, White Masks Fanon menganalisis «inferiority complex» yang diproduksi oleh rasialisasi; dalam Wretched of the Earth ia menunjukkan trauma massal akibat kekerasan sejarah. Penjajahan membentuk cara berpikir: internalisasi hina, fragmentasi identitas, dan belajar untuk menduga bahwa martabat hanya bisa diperoleh melalui penerimaan model penjajah.
Konsep ini kemudian menginspirasi banyak pemikir postkolonial seperti Homi Bhabha, Ngũgĩ wa Thiong’o, dan Achille Mbembe—yang melihat bahwa penjajahan modern kini terjadi melalui narasi, ekonomi, dan citra global. Dalam dunia kapitalisme digital saat ini, bentuk kolonisasi baru bisa ditemukan dalam algoritma, ketimpangan data, dan dominasi ekonomi oleh korporasi global.
Nasionalisme, Elit Baru, dan Bahaya Reproduksi Kolonialisme
Fanon memperingatkan bahaya besar pasca-kemerdekaan: munculnya borjuis nasional, kelas elit yang menggantikan penjajah namun meniru cara dan struktur kekuasaannya. Ia menyebut-nya “the pitfalls of national consciousness.” Bagi Fanon, revolusi sejati bukan hanya politik, tetapi transformasi ekonomi dan sosial—pembentukan struktur egaliter di mana rakyat memiliki kendali atas sumber daya dan identitas mereka sendiri.
Fanon memperingatkan bahwa setelah kemerdekaan, kelas borjuis nasional sering mereproduksi struktur kolonial. Kebebasan formal tanpa rekonstruksi ekonomi dan sosial hanya mengganti “wajah” penguasa. Oleh karena itu dekolonisasi sejati harus inklusif dan struktural.
“The national bourgeoisie steps into the shoes of the former European settlement… it is the transmission line between the nation and capitalism, rampant though camouflaged.” Kita di Indonesia, peringatan ini terasa tajam. Setelah kemerdekaan, banyak sektor strategis masih didominasi oleh oligarki ekonomi dan politik yang mewarisi logika kolonial—penjarahan sumber daya, ketimpangan akses tanah, dan marginalisasi masyarakat adat. Fanon mengingatkan bahwa tanpa revolusi struktural dan kesadaran rakyat, kemerdekaan hanya menjadi reinkarnasi kolonialisme dalam bentuk nasional.
Dalam bab “On National Culture,” Fanon menegaskan bahwa kebudayaan bukanlah museum masa lalu, melainkan arena perjuangan. Budaya alat yang bisa digunakan untuk kebangkitan diri. Kolonialisme berusaha memusnahkan memori kolektif agar bangsa jajahan kehilangan akar dan arah. Oleh karena itu, dekolonisasi juga berarti merebut narasi, menulis ulang sejarah, dan menghidupkan ekspresi budaya yang memberdayakan.
“A national culture is not folklore, nor an abstract populism. It is the whole body of efforts made by a people in the sphere of thought to describe, justify, and praise the action through which that people has created itself and keeps itself in existence.” Relevansi bab ini sangat kuat di Indonesia, terutama dalam konteks revitalisasi budaya lokal, bahasa daerah, dan seni yang berpihak pada rakyat. Karya Fanon menginspirasi seniman dan intelektual untuk melihat budaya sebagai alat pembebasan, bukan sekadar komoditas wisata.
Fanon menutup bukunya dengan seruan etis: membangun dunia baru yang humanis dan egaliter. Ia menolak universalisme Barat yang munafik—yang berbicara tentang “hak asasi manusia” sambil melanjutkan eksploitasi global. Baginya, tugas manusia pasca-kolonial bukanlah meniru Eropa, tapi menciptakan bentuk kemanusiaan baru yang menolak kekerasan struktural.
“For Europe, for ourselves, and for humanity, comrades, we must turn over a new leaf, we must work out new concepts, and try to set afoot a new man.” Pesan ini kini bergema di tengah krisis iklim, migrasi paksa, dan ketimpangan global. Dunia masih terbelah antara “yang memiliki” dan “yang dirampas.” Dekolonisasi, menurut Fanon, tetap menjadi agenda moral abad ke-21: keadilan global bukan hanya politik identitas, tapi rekonstruksi kemanusiaan.
Buku ini mendapat pujian luas sekaligus kritik tajam. Jean-Paul Sartre, dalam pengantar edisi Prancis, memuji Fanon sebagai “nabi revolusi dunia ketiga” dan melihat bukunya sebagai panggilan moral untuk menolak kemunafikan Eropa. Namun, sejumlah akademisi menilai Fanon terlalu memuliakan kekerasan dan gagal memberikan strategi konkret untuk membangun demokrasi pasca-kolonial. Hannah Arendt mengkritik gagasannya sebagai “romantisasi kekerasan.” Meski demikian, dalam konteks sejarah kolonial yang brutal, Fanon lebih dimengerti sebagai psikolog kemerdekaan—ia tidak merayakan kekerasan, tetapi memahami bahwa dalam sistem yang tidak adil, kekerasan sering menjadi satu-satunya bahasa yang didengar penindas.
Relevansi untuk Dunia dan Indonesia Hari Ini
Di tengah neokolonialisme global—melalui pinjaman utang, perusahaan multinasional, dan ketimpangan ekonomi digital—The Wretched of the Earth tetap hidup. Dunia kini menyaksikan bentuk baru “kolonisasi hijau,” di mana proyek-proyek energi terbarukan di Selatan justru mengorbankan masyarakat lokal. Di Indonesia, dari tambang nikel hingga proyek IKN, banyak wilayah adat yang menjadi “korban pembangunan.” Fanon memberi lensa moral: bahwa pembangunan tanpa keadilan adalah penjajahan baru dalam bentuk halus.
Secara filosofis, warisan Fanon adalah panggilan untuk etik dekolonial universal—suatu keberpihakan pada martabat manusia, bukan sekadar kebebasan formal. Pemikir kontemporer seperti Achille Mbembe, Ngugi wa Thiong’o, dan Vandana Shiva memperluas warisan Fanon ke ranah ekologis, kultural, dan gender. Dalam Islam, semangat ini sejalan dengan konsep ada (keadilan) dan amanah (tanggung jawab) sebagaimana ditegaskan Fazlur Rahman: “Tidak ada kebebasan sejati tanpa tanggung jawab moral terhadap sesama dan bumi.”
Catatan Akhir
“Each generation must, out of relative obscurity, discover its mission, fulfill it, or betray it.” — Frantz Fanon
Kini, generasi abad ke-21 menghadapi misi yang baru: dekolonisasi iklim, ekonomi, dan kesadaran. Fanon menantang kita untuk tidak sekadar mengeluh atas ketidakadilan, tetapi membangun dunia di mana kemanusiaan tidak lagi memiliki kasta.
Fanon melihat budaya sebagai medan perlawanan: menulis kembali, merestorasi memori, dan mengangkat epistemologi lokal adalah syarat rekonstruksi. Dekolonisasi bukan hanya mengganti peta politik tetapi membangun kembali cara kita memahami dunia — epistemic reconstitution.
Fanon percaya meski negara-negara yang dijajah ratusan tahun telah merdeka namun “kolonialisme baru“ muncul hari ini (peta kontemporer menurut Fanon). Saya gunakan pemikiran Fanon sebagai lensa untuk membaca beberapa fenomena saat ini.
a) Green colonialism / ecological extractivism
Fanon menulis tentang bagaimana sumber daya diambil demi keuntungan penjajah. Hari ini itu muncul sebagai ekstraksi mineral untuk baterai, ladang surya di wilayah yang miskin air, atau pembalakan untuk offset karbon — semua dibungkus dengan narasi «solusi iklim». Pola lama terulang: Selatan menyediakan materi/ruang bagi konsumsi Utara. Fanon akan melihat ini sebagai reproduksi struktur: kolonialisme berubah fungsi (dari penguasaan tanah menjadi penguasaan ekosistem, jasa ekosistem, dan hak atas tanah sebagai aset pasar).
b) Necropolitics dan securitization
Achille Mbembe mengembangkan ide necropolitics yang melanjutkan baca Fanon: negara berdaulat menentukan siapa yang «layak hidup». Kebijakan keamanan, perbatasan, kamp pengungsi, atau relokasi paksa demi proyek infrastruktur menunjukkan cara modern penentuan kehidupan/kematian—seringkali menimpa populasi rentan (pelaut, petani, komunitas adat). Fanon akan menyebut ini sebagai pemeliharaan hierarki kemanusiaan melalui perangkat negara/kapital.
c) Debt, finance, dan governance of scarcity
Keterikatan negara-negara Global Selatan pada mekanisme hutang, conditionalities IMF/Bank Dunia, investor ESG yang menuntut «returns», mengunci kebijakan publik. Fanon mengingatkan bahwa kekuasaan struktur ekonomi memproduksi ketergantungan; hari ini kondisi tersebut membuat negara sulit berorientasi pada kedaulatan rakyat—kebijakan publik dibuat untuk membayar utang, bukan membangun kesejahteraan. Debt becomes new chains.
d) Digital colonialism / data extraction
Fanon tidak bicara tentang data, tetapi prinsipnya berlaku: jika kolonialisme dulu merampas tanah dan tenaga, kini platform dan korporasi memanen data, perhatian, dan behavior. Ekstraksi data menciptakan win-loss baru: kapital platform memonopoli infrastruktur informasi, algoritma menetapkan nilai, sementara subjek disubordinasi. Fanon menuntut pemutusan relasi yang menegasikan martabat — di era digital, itu berarti memulihkan kedaulatan data dan mendemokratisasi informasi.
e) Racial capitalism dan pasar tenaga kerja
Fanon membaca ras sebagai alat revolusi kolonial. Kini ras dan kelas tumpang tindih dalam sistem kerja global—supply chains di mana tenaga kerja murah (sering dari Selatan) menopang konsumsi Utara. Black, brown, Indigenous labor tetap mengalami eksposur risiko lebih tinggi (kesehatan, keselamatan, kerusakan lingkungan). Fanon menuntut rekonstruksi yang mengangkat keseluruhan subjek ini, bukan sekadar redistribusi simbolik.
Dari pandangan Fanon + pembacaan kontemporer, kita bisa menyarikan prinsip etis-praktis:
- Non-sacrifice principle — komunitas tidak boleh dijadikan «zona pengorbanan» demi target global. Proyek apa pun (energi, infrastruktur, offset) harus memenuhi standar hak dan kedaulatan lokal, bukan sekadar cost-benefit investor.
- Epistemic justice — pengetahuan lokal, pengetahuan tradisional dan praktik komunitas harus menjadi dasar kebijakan, bukan tambahan PR. Ini memerlukan revisi proses perizinan dan evaluasi (AMDAL, social impact assessment) agar berbasis pengakuan.
- Redistributive transformation — pembebasan membutuhkan restrukturisasi ekonomi: kepemilikan sumber daya lokal, akses modal tanpa jebakan hutang, dan co-ownership atas rantai nilai hijau.
- Democratize tech & data — kontrol infrastruktur digital, platform, dan data harus didemokratiskan; negara dan masyarakat sipil berperan menjamin akses dan hak penggunaan.
- Remembrance & restorative justice — pengakuan atas sejarah kerugian, mekanisme reparasi (material + simbolik), dan program pemulihan mental/psikososial (Fanon: trauma penjajahan bukan semata individu).
Fanon ingin lebih dari sekadar melawan; ia ingin membangun manusia baru. Dalam konteks modern, strategi harus berlapis:
- Gerakan transnasional (eco-territorial internationalism): jaringan komunitas adat, pekerja, petani, ilmuwan kritis yang berbagi strategi—bukan blueprint-top-down dari Utara. Hal ini sejalan dengan Bringel & Fernandes.
- Kebijakan kedaulatan: reformasi kontrak ekstraksi, syarat lokal content, jaminan benefit sharing, pembatasan mekanisme offset yang merugikan masyarakat—dalam praktiknya negara-negara Selatan perlu menegosiasikan ulang perjanjian.
- Reformasi finansial global: tuntutan terhadap transparansi, pembatalan hutang yang tidak adil, climate finance yang bukan hanya loans tetapi hibah dan investasi untuk kapasitas.
- Ekonomi plural & degrowth: Fanon menentang reproduksi struktur kuasa; beberapa respon modern adalah alternative economics—koperasi, ekonomi solidaritas, agroekologi, degrowth—semua berfokus pada kebutuhan riil manusia, bukan pertumbuhan semata.
Indonesia bisa membaca Fanon sebagai peringatan dan peta tindakan:
- Tinjau ulang kontrak tambang & nikel: pastikan local content, transfer teknologi, royalty redistributive, dan klausul lingkungan yang ketat.
- Larangan offset yang mengorbankan masyarakat: batasi carbon credit schemes yang mengancam ruang hidup adat; bentuk mekanisme partisipatif.
- Kedaulatan data: undang-undang perlindungan data yang menjamin hak komunitas atas pengetahuan tradisional dan data lingkungan.
- Reparative policies: pembebasan lahan yang direbut, dana restorative untuk korban penggusuran, program pemulihan budaya.
- Pendidikan dekolonial: kurikulum yang mengangkat pengetahuan lokal, sejarah kolonial, dan etika lingkungan.
Fanon menuntut perubahan yang radikal dan etis: bukan sekadar menukar warna kapital, tetapi mengubah siapa yang membuat keputusan, siapa yang mendapat manfaat, dan bagaimana kita memikirkan kemanusiaan. Membaca dunia sekarang melalui Fanon berarti menolak bentuk-bentuk halus penjajahan (hijau, digital, finansial) dan menggagas tata dunia yang menghormati martabat—material dan eksistensial—semua orang.
Sebagaimana Fanon menulis: “Each generation must, out of relative obscurity, discover its mission, fulfill it, or betray it.”
Tantangan generasi ini adalah mengakui bahwa solusi teknis tanpa keadilan hanyalah reproduksi kolonialisme berpakaian baru—dan Fanon tetap bernilai sebagai kompas moral untuk memilih jalan yang berbeda.
Bogor, 10 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth. Grove Press.
Sartre, J.-P. (1961). Preface to The Wretched of the Earth. Grove Press.
Ngũgĩ wa Thiong’o. (1986). Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature. Heinemann.
Shiva, V. (2000). Staying Alive: Women, Ecology and Development. Zed Books.
Rahman, F. (1982). Islam and Modernity: Transformation of Religious Thought in the Modern World. University of Chicago Press.