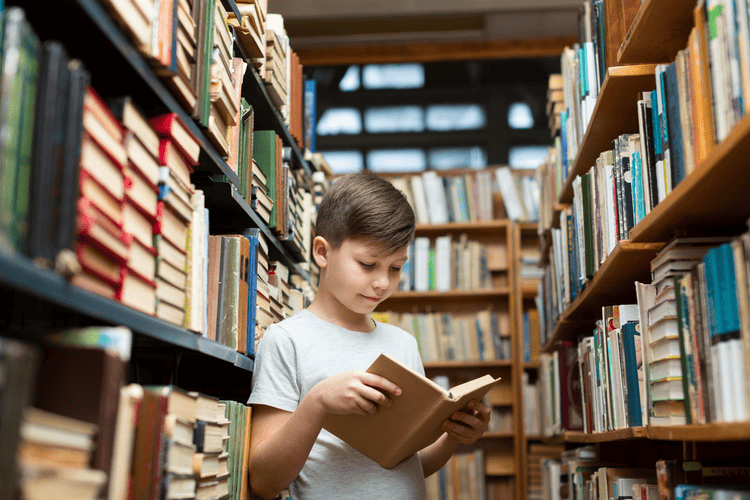“Iqra’!” (“Bacalah!”) (QS. Al-‘Alaq: 1). “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.” Ini adalah wahyu pertama, menempatkan membaca—dalam nama Pencipta—sebagai fondasi pertama peradaban Islam. Membaca di sini bukan hanya aktivitas literer, tetapi juga kontemplasi atas ciptaan.
Mengapa ayat pertama AlQuran ini menegaskan tentang membaca? Ketika ayat “Iqra'” turun di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan kontemplasi mendalam. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Malaikat Jibril mendekati Nabi yang sedang berselimut ketakutan dan memerintahkan: “Iqra’!” (Bacalah!). Nabi menjawab dengan jujur: “Maa ana bi qari'” (Aku tidak bisa membaca). Dialog ini berulang tiga kali sebelum Jibril menyampaikan lima ayat pertama Surat Al-‘Alaq.
Prof. Dr. Quraish Shihab dalam “Tafsir Al-Misbah” menjelaskan bahwa ketidaktahuan Nabi tentang baca-tulis justru menjadi bukti mukjizat Al-Qur’an. Dr. Mustafa al-Maraghi dalam “Tafsir al-Maraghi” menekankan bahwa peristiwa ini menunjukkan transformasi dari ummi (buta huruf) menjadi pemimpin peradaban.
Para ahli melakukan analisis linguistik dan semantik “Iqra.'” Kata “Iqra'” berasal dari akar kata qara’a yang memiliki makna ganda:
- Membaca teks tertulis (reading literacy)
- Menyampaikan, meneliti, dan menganalisis (critical thinking)
Imam al-Raghib al-Isfahani dalam “al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an” menjelaskan bahwa makna dasar qara’a adalah “mengumpulkan dan menghimpun,” yang kemudian berkembang menjadi membaca karena aktivitas membaca melibatkan pengumpulan huruf dan kata.
Sementara dalam tafsir holistik Ayat 1-5 Surat al-‘Alaq disebutkan bahwa Dimensi Teosentris: Membaca dalam Nama Tuhan ”Iqra’ bismi rabbikalladzi khalaq” (Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan). Syekh Muhammad Abduh dalam “Tafsir al-Manar” menegaskan bahwa frasa “bismi rabbik” mengajarkan bahwa segala aktivitas intelektual harus dimulai dengan kesadaran ketuhanan. Dr. Hamka dalam “Tafsir Al-Azhar” menjelaskan: “Membaca dengan nama Allah berarti mengakui bahwa semua ilmu berasal dari-Nya.”
Dari segi Dimensi Antropologis: Penciptaan Manusia dari ‘Alaq ”Khalaqal insana min ‘alaq” (Dia menciptakan manusia dari segumpal darah). Prof. Dr. M. Quraish Shihab menganalisis bahwa penyebutan ‘alaq (zigot, embrio) mengajarkan pentingnya mempelajari ilmu embriologi. Ini sesuai dengan penemuan ilmuwan modern seperti Keith Moore yang mengakui keakuratan Al-Qur’an dalam embriologi.
Dari Dimensi Epistemologis: Sumber dan Metode Ilmu ”Allama bil qalam. ‘Allamal insana ma lam ya’lam” (Yang mengajar dengan pena. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya).
Ibnu Katsir dalam “Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim” menjelaskan bahwa qalam (pena) melambangkan segala sarana pencatatan ilmu. Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam “Kaifa Nata’amal ma’al Qur’an” menekankan bahwa ayat ini mendorong dokumentasi ilmu.
Adrian Johns (2023) mengupas soal ilmu membaca ini. Dalam “The Science of Reading: Information, Media, and Mind in Modern America” Johns mengkaji dengan mendalam tentang evolusi konsep “Ilmu Membaca” sebagai fenomena sosio-kultural. Johns menelusuri bagaimana membaca—yang ia sebut sebagai “penemuan budaya paling berkuasa”—bertransformasi dari keterampilan dasar menjadi subjek ilmu pengetahuan yang kompleks. Buku ini membongkar narasi simplistik tentang membaca dengan menunjukkan bahwa “The Science of Reading” bukanlah kebenaran absolut, melainkan konstruksi historis yang terbentuk melalui pergumulan berbagai disiplin ilmu. “Membaca adalah sebuah craft [kerajinan] yang dipelajari, bukan sebuah naluri,” tulis Johns, menekankan bahwa seperti semua kerajinan, sejarahnya terjalin dengan teknologi dan institusi yang memungkinkannya. Filosof Prancis abad pencerahan, Denis Diderot, dalam Encyclopédie-nya menyatakan, “Hanya pengetahuan yang bebas yang benar-benar berguna,” sebuah prinsip yang bergema dalam upaya Johns membebaskan pemahaman kita tentang membaca dari belenggu pemahaman yang sempit. Membaca adalah sebuah biografi ide yang mengubah peradaban.
Johns secara metodis menguraikan kelahiran gerakan “Ilmu Membaca” dari rahim psikologi eksperimental, ilmu kognitif, dan tekanan industrial Amerika abad ke-20. Buku ini memetakan bagaimana para peneliti pionir seperti Edmund Burke Huey berusaha membongkar “kotak hitam” proses membaca di dalam otak, dan bagaimana upaya ini didorong oleh kebutuhan sosial untuk menciptakan masyarakat yang terstandardisasi dan efisien. “Apa yang kita sebut ‘The Science of Reading’ hari ini adalah produk dari perjuangan panjang untuk otoritas,” papar Johns, menyoroti pertarungan tersembunyi untuk menguasai definisi literasi yang sahih. Ilmuwan dan polimat Muslim abad ke-9, Al-Kindi, berpendapat, “Kita tidak boleh malu mengakui kebenaran dan mengambilnya dari mana pun sumbernya,” prinsip yang mengilhami pendekatan Johns dalam melacak kebenaran yang tersebar dan terkadang bertentangan dalam sejarah ilmu membaca. Johns mengembangkan membaca sebagai anatomi sebuah gerakan ilmiah.
Salah satu kontribusi terbesar buku ini adalah analisis mendalam mengenai perdebatan sengit antara pendekatan phonics (menekankan bunyi huruf) dan whole language (menekankan makna kontekstual) dalam pengajaran membaca. Johns menunjukkan bahwa “perang membaca” ini bukan sekadar perbedaan metodologis, tetapi cerminan dari pertarungan filosofis yang lebih dalam tentang hakikat pembelajaran, kebebasan individu, dan kontrol sosial. Buku ini mengungkap bagaimana masing-masing kubu mengklaim legitimasi ilmiah untuk mendukung posisinya. “Di balik setiap metode mengajar membaca terdapat visi tertentu tentang masyarakat yang diinginkan,”demikian kesimpulan tersirat dari analisis Johns. Seperti dikemukakan penyair dan filsuf Amerika, Ralph Waldo Emerson, “Pikiran, sekali terekspansi oleh sebuah ide baru, tidak pernah kembali ke dimensinya semula,” menggambarkan betapa mendasarnya dampak dari cara kita pertama kali diajar membaca terhadap pembentukan pola pikir kita.
Johns memberikan perhatian khusus pada bagaimana evolusi teknologi—dari mesin cetak bergerak hingga antarmuka digital—telah secara aktif membentuk kembali tidak hanya apa yang kita baca, tetapi juga cara otak kita memproses informasi tertulis. Buku ini berargumen bahwa setiap medium baru membawa serta “ekologi perhatian” yang berbeda, yang pada akhirnya mengkonfigurasi ulang sirkuit neural pembaca. “Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa membaca, tetapi bagaimana kita membaca—dan bagaimana lingkungan media digital yang baru membentuk kembali otak pembaca,” tulis Johns, menawarkan perspektif yang mendesak untuk konteks masa kini. Pakar media Marshall McLuhan pernah menyatakan, “Medium adalah pesan,”dan Johns mengembangkan thesis ini dengan menunjukkan bahwa medium cetak dan digital melahirkan jenis “pikiran pembaca” yang secara fundamental berbeda. Membaca buku ini kita akan mengetahui apa peran teknologi dan media dalam membentuk pembaca.
Maryanne Wolf (Ahli Neurosains) mengatakan bawah, “Kita adalah apa yang kita baca. Kualitas proses berpikir kita tergantung pada kualitas pemikiran yang kita temui.” (Dari “Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain”).
Politik dan Ekonomi di Balik Ilmu Membaca
Tidak berhenti pada aspek teknis, buku ini membongkar dimensi politik-ekonomi dari “Ilmu Membaca.” Johns melacak bagaimana gerakan ini terjalin dengan kepentingan komersial penerbit buku teks, kebijakan pemerintah, dan agenda industrial yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Buku ini mengungkapkan bahwa standarisasi metode membaca seringkali didorong oleh logika efisiensi dan kontrol sosial, bukan semata-mata pertimbangan pedagogis murni. “Standarisasi membaca adalah standarisasi pikiran,” demikian inti dari kritik Johns terhadap komodifikasi literasi. Pemikir Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah-nya mengamati, “Kekuasaan dan pengetahuan adalah saudara kembar,” sebuah pengamatan yang menemukan buktinya dalam narasi Johns tentang bagaimana kekuasaan berusaha mengatur dan mengontrol pengetahuan melalui standarisasi cara membaca.
Buku ini dengan tegas menghubungkan melek huruf dengan proyek keadilan sosial. Johns berargumen bahwa akses terhadap literasi yang bermakna—yang melampaui sekadar kemampuan mengeja—adalah prasyarat untuk partisipasi politik yang setara. Dengan menunjukkan bagaimana metode membaca tertentu secara historis diarahkan kepada kelompok sosial yang berbeda, buku ini membuka mata akan potensi literasi sebagai alat pembebasan atau justru penindasan. “Mengontrol cara seseorang membaca berarti mengontrol cara seseorang berpikir,” sebuah peringatan yang relevan dalam era disinformasi digital. Aktivis hak sipil dan literasi Amerika, Frederick Douglass, yang membebaskan dirinya melalui literasi, menulis, “Setelah saya belajar membaca, saya tidak lagi menjadi budak dalam pikiran,” sebuah pernyataan yang menggemakan urgensi literasi yang membebaskan seperti yang diadvokasikan oleh Johns. Jelaslah membaca berimplikasi untuk keadilan sosial dan masa depan demokrasi. Maryanne Wolf: “Kita tidak sekadar membaca sebuah teks; teks itu juga ‘membaca’ dan membentuk kembali sirkuit neural kita.” (Dari Reader, Come Home).
Menghadapi revolusi digital, Johns tidak bersikap apokaliptik tetapi menawarkan analisis yang bernuansa tentang bagaimana otak pembaca beradaptasi dengan lingkungan media baru. Buku ini membahas tantangan seperti berkurangnya perhatian berkelanjutan (sustained attention) dan meningkatnya kebiasaan skimming, tetapi juga melihat peluang baru untuk jenis literasi yang lebih multimodal dan interkonektif. “Masa depan membaca terletak pada kemampuan kita untuk mengembangkan ‘literasi ganda’—menguasai kedalaman membaca cetak dan kelincahan membaca digital,” demikian tawaran Johns. Dalam konteks ini, wahyu pertama dalam Islam, “Iqra’!” (Bacalah!), dapat dibaca sebagai seruan abadi untuk terus-menerus menegosiasikan kembali makna dan praktik membaca di setiap zaman yang berubah, termasuk zaman digital kita. Kita tahu membaca di era digital mengandung sejumlah tantangan dan peluang.
Catatan Akhir
Pada akhirnya, “The Science of Reading” adalah sebuah panggilan untuk memberdayakan pembaca—baik individu maupun masyarakat—dengan kesadaran kritis tentang sejarah dan politik di balik bagaimana kita diajar membaca. Johns mengajak kita untuk tidak menjadi konsumen pasif dari “metode terbaik” yang diklaim ilmiah, tetapi menjadi partisipan aktif dalam membentuk ekologi literasi yang lebih manusiawi dan demokratis. Tidak menerima begitu saja “cara terbaik” untuk membaca. Ia membongkar sejarah kompleks di balik “Ilmu Membaca” yang kita kenal sekarang. Masa depan membaca, menurut narasi yang dibangun Johns, bukanlah tentang mempertahankan satu metode kuno, tetapi tentang beradaptasi secara cerdas.
“Memahami sejarah ilmu membaca adalah langkah pertama untuk merebut kembali kedaulatan atas pikiran kita sendiri,” demikian pesan penutup yang inspiratif. Seperti kata penyair Indonesia, Sapardi Djoko Damono, “Hidup adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan membaca,” dan buku Johns memberikan kita peta yang lebih kaya dan kritis untuk menavigasi perjalanan tersebut menuju dunia yang lebih adil, di mana setiap pembaca memiliki alat untuk membebaskan diri dan memahami realitas secara mendalam. Ali bin Abi Thalib r.a.: “Ilmu adalah cahaya, dan hati yang tak berilmu adalah gelap gulita.” (Menekankan pentingnya ilmu yang diperoleh melalui membaca).
Di tengah banjir informasi digital, kemampuan membaca kritis—yang dipelajari dari sejarah panjang pergulatan dengan teks—menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Seperti yang diingatkan oleh wahyu “Iqra'” dan para pemikir dari semua tradisi, membaca pada akhirnya adalah tentang pemberdayaan diri, memahami dunia, dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri—baik itu Tuhan, alam semesta, atau kedalaman jiwa manusia.
Membaca adalah sebuah panggilan untuk literasi yang kritis dan memberdayakan. Seperti kata Carl Sagan: “Imajinasi akan sering membawa kita ke dunia yang tidak pernah ada. Tapi tanpanya, kita tidak akan kemana-mana.” Membaca akan memperluas imajinasi.
Bogor, 16 Oktober 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi:
Johns, A. (2023). The science of reading: Information, media, and mind in modern America. University of Chicago Press.