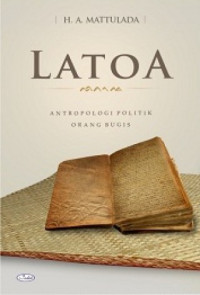halaman drm #40
Albanese dan Korporasi Pendukung Genosida
Dwi R. Muhtaman
“Kapitalisme dan pasar yang
tak mengenal aturan
terus bertahan dengan melibatkan warga
dalam aktivitas kriminal—
bahkan ketika kejahatan itu
begitu terang-terangan—
dengan dalih netralitas..”
— Francesca Albanese.
Daftar Isi
Di sebuah kamp pengungsian yang sempit dan berdebu di Lebanon, tahun 1969, seorang anak laki-laki berusia sepuluh tahun berdiri menatap ke arah tanah air yang tak bisa lagi ia injak. Namanya Naji al-Ali. Ia tak membawa senjata, hanya luka, kehilangan. Dan ingatan tentang rumah yang hancur di Palestina. Di sekelilingnya, tenda-tenda rapuh dan wajah-wajah kelaparan menjadi pemandangan harian. Ia menyaksikan sendiri bagaimana harga diri direnggut dari ayahnya, dan masa depan dirampas dari teman-teman sebayanya oleh penjajahan dan pengusiran.
Namun dari abu-abu pengasingan dan getirnya hidup dalam pengungsian, anak itu tidak tumbuh menjadi pengecut. Ia tidak memilih diam. Ia tidak memilih lupa. Ia memilih menggambar.
Bertahun-tahun kemudian, dari tangannya lahir Handala, seorang anak kecil dengan punggung menghadap dunia. Tanpa wajah. Bertelanjang kaki—lambang dari jutaan pengungsi Palestina yang ditolak keberadaannya, yang tak diberi ruang dalam sejarah resmi. Ruang hidup yang dienyahkan dan dikuasai. Handala bukan sekadar tokoh kartun. Ia adalah bentuk perlawanan. Ia adalah saksi. Ia adalah penolakan terhadap normalisasi penjajahan. Dan hingga hari ini, ia tetap berdiri membelakangi dunia, menunggu keadilan datang.
Dari Handala, kita belajar bahwa perlawanan tidak harus bersenjata. Ia bisa berbentuk gambar, puisi, lagu, bahkan diam yang bermakna. Tapi yang paling penting: ia harus ada. Perlawanan atas penjajahan dan ketidakadilan harus tetap dilahirkan. Perlawanan dalam segala bentuknya tak akan pernah padam. “The memory of oppression will not be silenced,” kata Edward Said, pada sebuah wawancara dan tulisan reflektifnya menjelang wafat.
Dan hari ini, ketika genosida dipertontonkan tanpa malu di Gaza, ketika perusahaan-perusahaan dan negara-negara mendanai pembantaian yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, keheningan bukanlah pilihan. Ketidakpedulian berarti keberpihakan pada penjajah.
Mari kita bersuara, di mana pun kita berada. Menulis, berbagi, berdiskusi, berdonasi, memboikot, turun ke jalan. Tidak ada bentuk partisipasi yang terlalu kecil dalam menghadapi kejahatan besar. Seperti kata Desmond Tutu: “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.”
Saat perusahaan membagikan burger pada penjajah, kita bisa membagikan kesadaran. Dan semoga dunia kelak bisa melihat: bahwa tak ada kebebasan sejati selama ada yang masih dijajah.
Bahwa Palestina—seperti Handala—belum selesai menulis kisahnya.
Saatnya warga dunia mengambil sikap. Dengan suara, dengan karya, dengan boikot, dengan aksi. Kita harus menolak, dan menghukum, mereka yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat yang dijajah. Sebab jika kita diam, kita berdiri di sisi penjagal.
Ketika McDonald’s Berdiri di Pihak Penjajah
Mari kita menyimak beberapa perusahaan yang terlibat dalam genosida. Di tengah debu reruntuhan Gaza yang berhamburan, ketika suara drone mendesis di langit dan suara tangis anak-anak menggema dari puing-puing rumah yang hancur, sebuah foto viral beredar luas: puluhan tentara IOF (Israel Occupation Forces) berbaris rapi, tertawa, memegang sekotak besar makanan cepat saji—burger dan kentang goreng masih hangat di tangan mereka. Di belakang mereka, truk besar berwarna merah mencolok dengan logo ikonik: dua lengkungan emas membentuk huruf M. McDonald’s.
Dalam beberapa unggahan media sosial dan laporan lokal, diketahui bahwa salah satu waralaba McDonald’s di Israel dengan bangga menyumbangkan ribuan paket makanan kepada tentara IOF selama operasi militer brutal mereka di Gaza pada akhir tahun 2023. Aksi itu dilakukan terbuka—dengan banner, dokumentasi foto, dan ucapan selamat dari pemilik waralaba: “Kami bangga mendukung para pahlawan kami di medan tempur. Ini adalah bagian kecil dari rasa terima kasih kami.”
Namun, medan tempur yang dimaksud adalah lingkungan padat penduduk. Tempat sekolah dan rumah sakit dijadikan sasaran. Di balik setiap suapan burger yang mereka lahap, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Di balik setiap gelas cola yang ditenggak sambil tertawa, ada darah anak-anak yang mengering di jalan-jalan Rafah, Khan Younis, dan Jabaliya.
Sementara dunia menyaksikan horor genosida yang ditayangkan langsung melalui media sosial dan laporan saksi mata, merek-merek global yang menjanjikan “kebahagiaan”, “keluarga”, dan “senyum di setiap sajian” memilih untuk berdiri di sisi kekuasaan, penjajahan, pembunuh masal dan pencuri tanah air. Bukan kemanusiaan.
McDonald’s mungkin berpikir mereka hanya memberikan makan siang. Tapi dunia melihat sesuatu yang jauh lebih gelap: kolusi. Apakah satu kentang goreng sebanding dengan nyawa seorang anak? Apakah waralaba makanan cepat saji boleh berdiri di barisan pasukan pendudukan tanpa konsekuensi?
Ketika sejarah menulis bab tentang kejahatan di Gaza, catatan kaki tentang burger yang dibagikan pada para penjajah akan dikenang bukan sebagai kebaikan, tapi sebagai bagian dari infrastruktur moral yang menyokong penindasan. Di zaman ketika setiap keputusan adalah politis, membagi burger pun bisa menjadi bentuk dukungan pada genosida.
Dari Tanah Air Palestina yang diubah jadi concentration camp masif ini kita berkunjung ke Bancelona di Spanyol, negara di tepi Eropa yang memahat jejak sejarah masa lalu yang gelap itu, kini dengan berani berdiri gagah di depan menentang genosida dan memutus hubungan dagang dengan zionis Israel. Mereka memahami dengan baik, sejarah adalah guru terbaik. Menolak melakukan apa yang telah dilakukan pada masa lalu yang gelap.
Seorang warga Spanyok berkunjung ke gerai tempat produk-produk Apple digelar menarik pembeli. Ia sedang berada di salah satu Apple Store terbesar dan terkaya di Barcelona. Kita diajak mengikuti perjalanan dari satu meja ke meja lainnya, dari satu produk ke produk lainnya yang ada di situ. “Di sini ada iPad-iPad yang sangat indah, dan lalu kalian bisa lihat bahwa perusahaan yang “indah” ini menghimpun donasi untuk IDF dan sejumlah organisasi yang mendanai dan mempersenjatai permukiman ilegal,” katanya dengan bersemangat. “Saya pikir, tidak ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan keterlibatan Apple dalam apa yang baru saja kita saksikan selain menunjukkannya langsung lewat perangkat mereka sendiri.”
“Lihatlah ini,” sambil menunjukkan website yang ada dilayar laptop terbaru. Terpampanglah di situ berita dengan judul: Apple Matches Worker Donations to IDF And Illegal Settlements, Employees Allege yang di muat di The Intercept.1 Pada tahun 2018, Tim Cook menerima penghargaan dari ADL, yang merupakan organisasi yang sangat rasis, bukan? Lihat orang ini memberikan pidato tentang betapa dia anti-kebencian di organisasi yang sangat pro-Israel dan penuh kebencian terhadap Palestina. Tim Cook bahkan bertemu dengan Benjamin Netanyahu saat mereka membuka kantor pusat mereka di Yerusalem.
Dan ya, perusahaan yang “indah” ini memiliki kantor pusat di wilayah pendudukan di Yerusalem. Mereka memiliki pusat riset dan pengembangan besar di Yerusalem dan Israel. Itulah sebabnya mereka sangat peduli untuk memastikan tidak ada yang tahu betapa pro-Israel-nya mereka.
“Dan jika kalian tidak percaya semua itu,” katanya makin semangat, “lihat apa yang kami temukan.” Sebuah tangkapan layar internal secara harfiah di perangkat Apple di dalam Apple Store yang menunjukkan bahwa mereka menghimpun (matching fund) 100% donasi untuk “Friends of the IDF“. Dan satu lagi tangkapan layar internal di Apple Store yang menunjukkan kebijakan cuti dinas militer cadangan mereka untuk IDF—bagaimana pada 7 Oktober mereka memulai program baru untuk pasangan tentara IDF agar mendapat tambahan cuti delapan hari.
Itu dimulai pada 7 Oktober. Dan juga, setiap karyawan Apple akan tetap dibayar 100% dari gaji pokok mereka saat mereka bertugas di IDF. Inilah yang membuat organisasi seperti ini menormalisasi rasisme dan kekerasan di Palestina, dan karena itulah semua kekacauan ini terjadi.
Semua kekacauan yang sedang terjadi sekarang antara Iran dan Israel, secara harfiah terjadi karena perusahaan-perusahaan seperti ini menyetujui apa yang dilakukan Israel. Mereka menyetujui apartheid. Mereka menyetujui rasisme.
Apple bersalah besar. Mereka membanggakan betapa indahnya mereka. Mereka menyulap bangunan-bangunan cantik dan merenovasinya. Tapi di balik semua itu, ada rasisme sistemik yang dalam dan tidak dipertanggungjawabkan. Mereka menolak pertanggungjawaban atas rasisme itu. Dan kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengubahnya.
Dan kita akan memastikan bahwa semua orang tahu. Semua orang benar-benar tahu soal omong kosong ini soal Apple yang indah dan kreatif.
Itulah video laporan pandangan mata dari pengunjung Apple Store di Barcelona.
Melawan dengan Partisipasi
Dalam dunia yang kian terhubung oleh informasi dan media, ketidakpedulian bukan lagi karena tidak tahu, melainkan karena memilih untuk tidak peduli. Setiap bom yang dijatuhkan, setiap anak yang dibungkam, setiap rumah yang dihancurkan di Gaza dan Tepi Barat, berlangsung dengan izin dan dukungan—baik eksplisit maupun diam-diam—dari negara-negara besar dan perusahaan-perusahaan global. Mereka menyuplai senjata, mereka bungkam di forum internasional, mereka meloloskan kebijakan impunitas, mereka menjadikan tragedi sebagai peluang bisnis. “It is in collectivities that we find reservoirs of hope and optimism,” tulis
Angela Davis, aktivis Black Liberation, feminis, penentang penjara dan apartheid.
Inilah saatnya bagi kita, warga dunia, untuk tidak lagi menjadi penonton.
Partisipasi dalam menentang genosida bukan hanya soal turun ke jalan, meskipun itu penting. Ini adalah perjuangan multidimensi. Kita bisa:
- Melawan dengan dompet kita. Boikot perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pendanaan penjajahan dan genosida. Perusahaan seperti HP, Puma, Caterpillar, dan lainnya telah disebut oleh berbagai koalisi internasional karena keterlibatan mereka dalam pendudukan ilegal.
- Melawan dengan suara kita. Tanda tangani petisi, sebarkan informasi, lawan narasi dominan yang membungkam Palestina dengan dalih “keamanan”, “perang melawan teror”, atau “netralitas palsu”. Ingat: netralitas di tengah penindasan adalah keberpihakan pada penindas.
- Melawan dengan seni dan budaya. Seperti Naji al-Ali yang menggambar Handala, setiap seniman, penulis, musisi, fotografer, dan pekerja kreatif memiliki peran penting dalam merawat ingatan kolektif dan menyebarkan empati lintas batas.
- Melawan melalui institusi. Dorong universitas, serikat pekerja, dan lembaga masyarakat sipil untuk menerapkan kebijakan pemutusan hubungan dengan entitas yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan. Kampanye Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) bukan sekadar strategi, tapi juga bentuk konsistensi moral.
Membela Palestina adalah Membela Kemanusiaan
Perjuangan membebaskan Palestina bukan hanya tentang satu wilayah. Ini adalah cermin dari perlawanan terhadap sistem global yang menormalisasi kolonialisme, apartheid, dan eksploitasi atas nama keamanan atau kemajuan. Ketika kita berdiri untuk Palestina, kita berdiri untuk Rohingya, untuk Uyghur, untuk masyarakat adat yang dilucuti tanahnya, untuk setiap manusia yang ditindas karena identitasnya.
Seperti Handala yang tak pernah menoleh ke arah dunia, kita juga tak boleh menoleh dari ketidakadilan. Karena ketika anak-anak kecil di kamp pengungsian menggambar perlawanan, maka tugas kita yang hidup dalam kebebasan relatif adalah memperkuat suara mereka.
Sebab yang membungkam kita bukan peluru, melainkan rasa nyaman yang menyesatkan. Kita sering mendengar retorika negara-negara Barat yang mengklaim mendukung “demokrasi” dan hak azasi manusia, padahal sejatinya mereka berkoar-koar soal itu semua sambil tetap mendukung penjajahan, pembunuhan, otoriterianisme.2 Atau menggulingkan negara-negara lain yang demokratis jika tidak sejalan dengan agendanya. Persis yang disampaikan Edward Said dalam Culture and Imperialism: “Namun, setiap Empire meyakinkan diri sendiri dan dunia bahwa ia berbeda dari semua Empire lain, bahwa misinya bukan untuk menjarah dan menguasai, melainkan untuk mendidik dan membebaskan.”3 Palestina membuka topeng wajah kebohongan mereka.
Francesca Albanese dan Keadilan
Muhammad Hassan dalam Big Picture Podcast mengundang Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina.4 “Kita masih menjadi bagian dari sebuah sistem yang mengobarkan perang demi keuntungan—menghancurkan kehidupan serta menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga bagi kita semua. Negara-negara anggota seperti Amerika Serikat, Israel, dan lainnya telah merancang agar genosida ini menjadi usaha yang menguntungkan. Mereka harus membayar reparasi,” kata Francesca dengan penuh percaya diri. “Kapitalisme dan pasar yang tak mengenal aturan,” cetusnya, “terus bertahan dengan melibatkan warga dalam aktivitas kriminal—bahkan ketika kejahatan itu begitu terang-terangan—dengan dalih netralitas. Kini, Palestina menjadi momen penentu berikutnya yang harus mengarah pada pertanggungjawaban. Jika bukan sekarang, kapan? Jika bukan kita yang mendorong perubahan ini, siapa lagi?”
Hanya dua hari setelah wawancara Francesca Albanese, ia dikenai sanksi oleh pemerintahan Trump, 9 Juli 2025. Mereka menuduhnya melancarkan perang ekonomi terhadap Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan AS. Albanese menyebut sanksi tersebut sebagai “teknik intimidasi ala mafia” dan bersumpah akan terus melanjutkan pekerjaannya—mengingatkan negara-negara akan kewajiban hukum mereka untuk menghentikan dan menghukum genosida, serta menuntut pertanggungjawaban mereka yang mengambil untung darinya.
Mengapa Amerika Serikat mengambil langkah drastis ini? Semua ini berkaitan dengan laporan tajam yang baru saja diterbitkan oleh Albanese, berjudul The Economy of Genocide (Ekonomi Genosida).
Berikut ini beberapa cuplikan wawancara Muhammad Hassan dengan Francesca Albanese dalam Big Picture Podcast.
Kita berbicara hanya beberapa hari setelah Anda menerbitkan laporan eksplosif yang menyebut lebih dari 60 perusahaan yang Anda tuduh menopang dan mengambil keuntungan dari pendudukan, apartheid, dan genosida yang dilakukan Israel. Beberapa perusahaan tersebut termasuk Google, Amazon, Hyundai, Booking.com, dan bank Barclays. Tuduhan ini serius, ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang kita gunakan sehari-hari. Mengapa perusahaan-perusahaan ini, dan mengapa sekarang?
Mari saya mundur sedikit. Jika laporan ini hanya dibaca sebagai daftar perusahaan yang dituduh, maka saya telah gagal. Tujuan laporan saya adalah untuk mengungkap sebuah sistem yang telah memungkinkan pendudukan bertahan selama puluhan tahun, alih-alih dibongkar sebagaimana mestinya.
Pendudukan—yang kini telah berubah menjadi genosida terhadap rakyat Palestina—masih ada karena beberapa faktor: ambisi teritorial Israel yang tak henti terhadap sisa wilayah Palestina; sebuah ideologi yang telah meracuni banyak orang, termasuk anak muda Israel; dan pandangan orientalis-rasis di beberapa negara Barat yang menganggap Israel sebagai pelaksana “pekerjaan kotor” bagi kita semua. Ini patut dibahas tersendiri.
Namun ada juga faktor ekonomi—banyak perusahaan yang meraup keuntungan dari situasi ini. Saya mengungkap sebuah ekonomi pendudukan yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang menopang pengusiran dan penggantian warga Palestina. Pengusiran terjadi melalui penghancuran sumber penghidupan dan ruang hidup mereka, melalui senjata dan bahan-bahan penggunaan ganda seperti buldoser dan mesin konstruksi lainnya yang digunakan untuk merobohkan rumah dan mencabut pohon.
Peralatan ini, ditambah pengawasan, menciptakan sistem segregasi berupa tembok, pos pemeriksaan, dan pagar yang membatasi warga Palestina dalam ruang-ruang yang bisa dikontrol. Sementara itu, pilar lainnya—penggantian—dibiarkan berkembang. Perusahaan membangun kota dan permukiman bagi warga Yahudi Israel saja. Ini mencakup rumah, infrastruktur, jaringan listrik dan air, pembangkit listrik, jalan raya, rel kereta api.
Ada juga ekstraktivisme—mengeksploitasi tambang, sumber air, sumber daya alam, dan cadangan minyak lepas pantai di Gaza. Lalu ada industri barang dan jasa: kurma, produk Laut Mati, anggur, dan lainnya yang dijual ke pasar internasional. Termasuk pula industri pariwisata dan rantai pasok. Semua saling terkait.
Kedua pilar ini tidak akan bertahan tanpa jaringan pendukung: bank, dana pensiun, lembaga keuangan, universitas, dan lembaga amal. Seluruh jaringan ini telah memberi legitimasi, kredibilitas, dan dana kepada Israel untuk mempertahankan ekonomi pendudukannya.
Saya bisa saja menulis laporan ini 10 tahun lalu dan isinya tetap valid. Tapi kini, kerangka hukum sudah sangat jelas. Segala keterlibatan dengan pendudukan adalah ilegal. Telah ada proses pidana atas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap negara Israel dan para pejabatnya.
Kita juga memiliki Opini Penasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang bukan sekadar menarik garis merah, tapi membuat jalan tol yang memisahkan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Keterlibatan dengan pendudukan yang telah dinyatakan ilegal—yang diperintahkan untuk dibongkar total dan tanpa syarat—melanggar hak penentuan nasib sendiri. Ini mengarah pada aneksasi, pendudukan permanen, pembunuhan di luar hukum, pengusiran paksa, dan perampasan.
Inilah yang membuat perusahaan dan sektor swasta terlibat. Dalam 20 bulan terakhir, ekonomi pendudukan telah bertransformasi menjadi ekonomi genosida. Laporan saya menyoroti pergeseran ini. Perusahaan-perusahaan yang disebut hanyalah contoh—ilustrasi betapa sektor swasta terjalin erat dalam desain kriminal ini.
Anda menyebut dalam laporan bahwa Anda telah menghubungi 45 perusahaan dan 15 di antaranya merespons. Apa tanggapan mereka?
Saya tidak menyebutnya sebagai tuduhan. Saya memberikan pemberitahuan kepada 48 entitas swasta—termasuk lembaga amal, dana pensiun, dan universitas. Akhirnya, 18 merespons, termasuk beberapa setelah laporan diajukan.
Sebagian besar tidak memberikan tanggapan. Mereka yang merespons sebagian menyangkal fakta, sebagian mengatakan saya salah menafsirkan hukum. Saya memberi mereka kesempatan untuk membantah atau memperbaiki informasi. Saya bahkan membuat analisis hukum khusus untuk setiap entitas. Beberapa mencoba berdialog dengan itikad baik, tapi kebanyakan hanya ingin nama mereka dihapus dari laporan—tanpa memberikan komitmen tertulis untuk menghentikan keterlibatan mereka.
Ketika laporan itu dipublikasikan, semua 18 kembali memberi respons pada intinya menyatakan, “Kami tidak akan mengubah praktik bisnis kami.” Menariknya, mereka seakan tidak memahami, atau pura-pura tidak memahami. Mereka berkata, “Kami hanya menyediakan komponen kecil. Kami tidak bisa disalahkan atas apa yang dilakukan Israel.”
Tapi perusahaan memiliki kewajiban due diligence—apalagi dalam konteks konflik. Dan wilayah pendudukan Palestina bukan sekadar zona konflik. Ini adalah wilayah yang telah didokumentasikan mengalami pelanggaran berat selama puluhan tahun. Perusahaan-perusahaan ini telah lama diberi tahu. Beberapa bahkan terdaftar dalam basis data PBB.
Mereka tetap beroperasi dengan sadar dan sengaja. Argumen bahwa mereka tidak berkontribusi pada pelanggaran karena tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindakan Israel tidak bisa lagi diterima. Sejak Januari 2024, sudah ada pemberitahuan resmi bahwa Israel mungkin sedang melakukan genosida. Ada bukti nyata tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan—termasuk kelaparan massal.
Dalam ekosistem ilegal ini, due diligence menuntut perusahaan menggunakan pengaruh mereka untuk menghentikan pelanggaran. Misalnya, perusahaan pembangun jalan dapat berkata, “Kami tidak akan bekerja sama jika Anda terus membangun infrastruktur di wilayah pendudukan.” Tapi bahkan itu pun tidak membebaskan mereka dari pengawasan jika pengaruh mereka terbukti tidak efektif.
Faktanya, sebagian besar perusahaan tidak berusaha sama sekali. Konteks ini bukan tempat di mana pengaruh sektor swasta bisa bekerja. Laporan saya juga menunjukkan bahwa kita harus berhenti percaya pada fiksi tentang “Israel yang baik” di dalam perbatasan resminya, dan “Israel yang buruk” di wilayah koloni.
Permukiman bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Itu melayani kepentingan negara Israel—menguasai tanah, sumber daya Palestina, dan menindas mereka secara politik dan ekonomi. Negara lah yang melakukan kejahatan ini.
Bayangkan hari ini seperti lebih dari 30 tahun lalu saat menghadapi Afrika Selatan dalam rezim apartheid. Haruskah kita menghentikan hubungan dengan apartheid Afrika Selatan? Tentu saja. Mengapa? Bukan hanya karena apa yang mereka lakukan dalam bantustan, tapi karena mereka mempertahankan sistem apartheid.
Hal yang sama berlaku saat ini. Bahkan lebih serius, karena apartheid Israel telah melangkah lebih jauh dari apa yang pernah dilakukan Afrika Selatan. Israel kini melakukan, atau sangat mungkin melakukan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ini adalah saatnya untuk memberlakukan sanksi dan memutuskan hubungan dengan Israel. Tuntutan ini tidak hanya datang dari masyarakat sipil Palestina atau masyarakat sipil global internasional, tetapi juga dari banyak warga Israel yang saya ajak bicara, yang terus bertanya: mengapa belum ada sanksi?
Jawabannya terletak pada aliansi politik, tetapi juga karena banyak orang belum memahami betapa dalam keterlibatan kita semua dalam kejahatan-kejahatan Israel. Dan bukan hanya kejahatan Israel, sebab saat ini kita melihat banyak negara Barat dan bahkan beberapa negara Arab yang secara aktif mendukung apa yang dilakukan Israel.
Jika Palestina adalah tempat kejadian perkara hari ini, maka sidik jari kita semua ada di sana. Palestina menjadi cermin yang memperlihatkan seberapa terjalinnya kita satu sama lain. Karena keterikatan ini, kita harus menggunakan kekuatan kita—baik secara individu maupun kolektif—untuk mengubah keadaan.
Ini adalah momen penentu dalam sejarah, seperti saat runtuhnya apartheid di Afrika Selatan. Dari sejarah itu pula lahir prinsip-prinsip panduan tentang bisnis dan hak asasi manusia. Sebelumnya, dunia juga telah memeriksa dan mengadili para pelaku bisnis dan produsen senjata pasca-Holocaust atas peran mereka dalam kejahatan terhadap orang Yahudi dan lainnya. Sekarang, Palestina adalah momen penting berikutnya yang harus mengarah pada akuntabilitas.
Jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kita yang mendorong perubahan ini, siapa lagi?
Saya memikirkan beberapa perusahaan yang disebut dalam laporan ini, dan menyadari bahwa saya sendiri telah menggunakan banyak dari mereka selama seminggu terakhir. Bahkan untuk wawancara ini, saya harus menggunakan Google. Setelah selesai, wawancara ini akan diunggah ke YouTube, anak perusahaan Alphabet, pemilik Google. Jika perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam ekonomi genosida, apakah itu berarti kita semua juga turut bersalah?
Saya akan mengubah cara memandangnya: itu berarti kita semua punya kekuatan untuk memengaruhi sistem.
Jika kita melihat gerakan-gerakan lain, kita perlu saling belajar. Acuan saya berasal dari dunia lingkungan hidup—satu-satunya bidang tempat saya pernah menjadi aktivis. Di sana saya belajar bahwa kita tidak bisa mengubah hidup kita 100% dalam semalam. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua sektor.
Kita harus mulai dari langkah kecil yang mudah dicapai. Secara individu, kita bisa mulai dari apa yang kita beli. Mengganti kopi lebih mudah daripada mengganti alat teknologi atau platform pariwisata yang kita gunakan.
Saya, seperti jutaan orang lainnya di dunia, pernah menggunakan Airbnb dan Booking.com. Namun dalam 16 bulan terakhir, saya berhenti menggunakannya. Dan kini saya akan menutup akun saya di kedua platform tersebut. Saya tidak ingin menjadi bagian dari sistem itu, setidaknya selama mereka masih mempromosikan properti di Tepi Barat—dan bisa jadi di Gaza juga jika rencana Israel untuk mengambil alih wilayah itu berhasil.
Ini kontribusi paling sederhana yang bisa dilakukan oleh banyak orang musim panas ini: jangan mendukung pendudukan ilegal hanya dengan satu klik. Jangan mendukung ekonomi yang telah menjadi genosidal hanya dengan satu klik.
Bisakah Anda tidak menggunakan Airbnb dan Booking.com selama tiga bulan? Itu bukan pengorbanan besar.
Selain itu, ada tindakan lain yang bisa dilakukan. Ada orang-orang yang menjadi pemegang saham atau karyawan di perusahaan seperti Microsoft dan Google. Para pekerja ini sendiri yang pertama kali mengungkap bahwa sistem cloud yang mereka gunakan disediakan untuk Israel dan digunakan untuk menargetkan ratusan ribu warga Palestina secara sembarangan.
Para pemegang sahamlah yang harus pertama-tama didengar, bahkan sebelum para pengguna. Dalam beberapa minggu terakhir saya berbicara dengan para bankir dan profesional keuangan yang benar-benar terkejut. Tidak semua bankir jahat. Ini adalah saatnya kita menetapkan aturan tambahan.
Bukan untuk menghancurkan pasar, tapi untuk membuat pasar lebih ramah manusia—dan bebas dari genosida.
Tentu saja tak semua tindakan bisa dijabarkan di satu wawancara, dan itu pun bukan sepenuhnya tugas saya. Apa yang saya lakukan juga dibangun di atas kerja para jurnalis investigatif, pengacara, dan gerakan masyarakat sipil—terutama gerakan BDS, yang telah membuka mata banyak orang terhadap kenyataan ini. Dan karena itulah BDS sangat diserang dan dikriminalisasi. Sebab BDS benar-benar didasarkan pada hukum internasional.
Saya sendiri dulu nyaris terintimidasi. Apakah saya harus mendukung BDS? Kampanye melawan BDS sangat agresif. Tuduhan yang sering muncul adalah bahwa BDS berusaha mengisolasi satu-satunya negara Yahudi di dunia secara ekonomi dan budaya. Ini argumen yang juga dulu dipakai melawan gerakan boikot terhadap apartheid Afrika Selatan.
Sekarang saya tinggal di negara Arab, dan saya lihat ada gerakan yang jauh lebih radikal daripada BDS. Setelah memahami sistem yang coba mereka bongkar, saya rasa BDS sebenarnya sangat moderat. Gerakan ini damai, anti-diskriminasi, dan inklusif. Banyak warga Yahudi dari seluruh dunia, termasuk Israel, yang mendukungnya.
Saya dulu berpikir institusi akademik tidak perlu diboikot. Tapi setelah genosida Februari 2024, saya berubah. Saat itu saya melihat universitas Israel diam total terhadap penghancuran universitas-universitas di Gaza. Bahkan lebih dari itu, mereka menyerang siapa pun yang menunjukkan solidaritas. Akademisi Palestina, mahasiswa, dan seluruh fakultas menjadi sasaran.
Kini saya melihat para sarjana hukum terkenal di bidang saya sendiri justru mendukung kekerasan Israel, bahkan terhadap warga Lebanon dan Iran. Saya pun mendalami lagi, termasuk membaca karya para cendekiawan Israel anti-apartheid seperti Maya Wind, yang menunjukkan bagaimana sistem pendidikan tinggi Israel menjadi pilar penghapusan institusi budaya Palestina.
Universitas-universitas Israel terlibat dalam kolonisasi—baik melalui kerja sama dengan universitas di permukiman ilegal maupun dalam mendukung sistem militer Israel, yang merupakan tulang punggung negara itu. Mereka mengembangkan mitos “startup nation”, padahal semua saling terhubung: militer, pendidikan, dan ideologi negara kolonial sekuler Israel.
Hari ini kita harus memahami bahwa negara Israel sebagai entitas politik perlu dihadapkan pada akuntabilitas. Ini mengejutkan, tapi penting.
Namun saya juga ingin menyoroti kesadaran yang menyakitkan bagi banyak warga Israel dalam beberapa bulan terakhir. Saya berbicara dengan seorang kolega Israel tadi malam, dan dia mengatakan bahwa banyak anak muda di Israel tidak ingin kembali berperang di Gaza. Tapi mereka takut dianggap pengkhianat karena menjadi bagian dari IDF adalah identitas nasional.
Saya tidak membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh warga Israel, tetapi dari sudut pandang saya sebagai pengamat luar, banyak anak muda Israel juga menjadi korban sistem yang telah mencuci otak mereka—meyakinkan bahwa mereka sedang melawan teroris, bahwa semua warga Gaza bersalah atas serangan 7 Oktober.
Kini mereka mulai menyadari bahwa keyakinan itu runtuh. Tapi mereka belum mampu memikul tanggung jawab itu secara kolektif, apalagi melawan IDF. Akibatnya, mereka depresi atau bahkan bunuh diri. Ini tragis.
Lebih tragis lagi adalah survei yang dilakukan oleh media seperti Haaretz, yang menunjukkan bahwa 80% responden masih mendukung penghancuran total Gaza atau pembersihan etnis warga Palestina dari sisa wilayah yang mereka miliki.
Dalam situasi seperti ini, kita semua harus bertindak—dari semua jalur dan posisi—melawan negara Israel yang saat ini menjadi ancaman bagi warga Palestina, warga Israel sendiri, kawasan, dan dunia.
Lihat saja bursa saham Tel Aviv yang terus meningkat, mencapai nilai $220 miliar sejak awal genosida, dan $70 miliar hanya dalam sebulan terakhir.
Di sinilah letak masalah yang sebenarnya. Bukan hanya orang Israel yang mendapat keuntungan dari genosida, melainkan korporasi—serta oligarki yang berhubungan dengan industri pertahanan, baik di Eropa maupun AS—yang kaya raya karena genosida tersebut. Orang Israel sendiri pun terjebak dalam sistem ini.
Mereka yang tidak mendapatkan keuntungan dari aliansi ini—mereka yang tak ambil untung dari produsen senjata maupun industri pengawasan dan intelijen—harus bersatu dan menolaknya.
Mari ambil satu contoh konkret. Anda menyebut institusi pendidikan. Baru-baru ini, kami menghubungi Universitas Oxford, yang dituduh menggunakan bagian dari dana abadi (endowment)-nya untuk berinvestasi dalam dana yang dikelola BlackRock—salah satu perusahaan dalam laporan Anda. BlackRock mengelola sekitar $10 triliun—angka yang sungguh luar biasa. Masalahnya, dana yang diinvestasikan Oxford mencakup 36 perusahaan yang tercantum dalam database PBB, yang berarti mereka terkait atau mendukung permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Saat kami mengonfrontasi Oxford, mereka menjawab bahwa investasi itu bersifat pasif. Mereka menyatakan: “Investasi pasif umum digunakan di industri investasi, oleh banyak institusi, dana pensiun, dan kumpulan modal lainnya. Diperkirakan 50% industri investasi dilakukan secara pasif.”
Apa tanggapan Anda terhadap argumen Oxford ini? Mereka berdalih: “Kami hanya berinvestasi pasif. Kami memiliki mekanisme pengawasan agar dana tidak digunakan secara salah. Tapi beginilah dunia berjalan.”
Saya akan mengatakan: berhenti berinvestasi secara pasif—sekarang juga.
Terlibat dalam ekosistem yang sarat dengan kejahatan, bahkan secara pasif, sudah menjerat Anda dalam tanggung jawab hukum. Saya telah menerima data tentang endowment Oxford, dan ini sudah masuk dalam database saya yang berisi 10.000 perusahaan. Saya akan membahas ini lebih lanjut dengan universitas tersebut, karena ada masalah nyata. Alasan mereka, dengan hormat, sangat tidak masuk akal. Mereka bersembunyi di balik dalih.
Universitas—tempat mencetak generasi sekarang dan masa depan—tak bisa bertahan dengan tingkat kemunafikan semacam ini. Dan ini bukan hanya soal Oxford. Ini berlaku untuk seluruh sektor produksi ilmu—terutama universitas di Barat.
Ada hubungan langsung antara penindasan agresif pihak kampus terhadap protes mahasiswa—pengawasan, penutupan kamp, intervensi rektorat, serta tekanan terhadap staf administrasi—dengan keterlibatan mereka dalam pendudukan ilegal. Gerakan mahasiswa menyoroti portofolio investasi kampusnya. Upaya mereka brilian.
Salah satu penyesalan saya: saya belum mampu mengungkap lebih banyak keterlibatan universitas dalam sistem ini. Banyak kampus akan bangkrut jika kehilangan dana dari program Horizon Uni Eropa atau dari industri pertahanan domestik dan khususnya yang berhubungan dengan Israel. Ini mengungkap realitas kelam: universitas tak hanya membentuk murid untuk pasar, melainkan untuk pasar tertentu—yang terkait industri pertahanan.
Saat mahasiswa menyuarakan nilai, prinsip, dan hukum internasional, mereka dikritik. Inilah kenyataan zaman kita.
Universitas harus berubah. Mahasiswa perlu yakin bahwa mereka berdiri di jalan yang benar—damai dan non-kekerasan—dan terus maju. Sebab setiap kesalahan atau kehilangan kontrol akan digunakan untuk menyerang mereka dan gerakan masyarakat sipil yang menentang apartheid dan genosida.
Namun masyarakat sipil juga perlu memfokuskan perhatian pada universitas. Tidak ada netralitas dalam mendukung pendudukan ilegal yang telah meresmikan rezim apartheid dan kini berujung pada genosida.
Dan ini bukan hanya masalah Palestina. Banyak perusahaan yang disebut juga terlibat dalam pelanggaran HAM di Kongo, Sudan, dan wilayah lain.
Anda menyebut kapitalisme rasial dan hubungan historis antara perluasan kekuasaan secara paksa dan kekuatan swasta. Beberapa orang mungkin berargumen ini apa adanya kapitalisme. Jadi, bagaimana kita melepaskan diri tanpa meruntuhkan tatanan? Apakah ini cara tepat saat menghadapi krisis seperti genosida di Gaza?
Pertanyaan yang sangat kuat.
Pertama, kita harus pahami: ini bukan hal baru. Sektor swasta sejak dulu mendorong atau mendukung proyek kolonial dan kolonial pemukim. Ada literatur luas tentang ini—yang kini disebut kapitalisme kolonial rasial. Kapitalisme selalu memiliki komponen rasial. Ini juga cara perusahaan menghindar dari akuntabilitas historis.
Ambil contoh kasih batas tanggung jawab (limited liability)—prinsip ini memungkinkan aktor swasta menentukan aturan sendiri tanpa diperlakukan sama seperti warga negara. Dan hasilnya: korporasi multinasional kini memiliki kekayaan dan pengaruh lebih daripada negara. Mereka hak-hak tetapi tak punya kewajiban setara—karena kewajiban hanya dikenakan pada negara. Sektor swasta hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham.
Itulah realitas saat ini. Negara-negara berkolaborasi dengan perusahaan besar. Mungkin terlihat seperti pemerintah mengendalikan, tapi faktanya sering terbalik—perusahaan senjata atau minyak justru lebih berpengaruh daripada pemerintah. Dan kita—rakyat—kita semakin tidak berdaya.
Palestina membuka semua ini dengan jelas. Saya telah berbicara dengan negara anggota PBB yang bertanya, “Di mana batasnya agar sistem ini tidak runtuh seperti susunan Menara Jenga?”5 Jawaban saya: Saya bukan mengusulkan sistem dihentikan total—ini seperti gerakan nol sampah. Kita tak akan berhenti pakai plastik sepenuhnya, dan bukan plastiknya yang masalah, melainkan plastik sekali pakai, konsumsi berlebihan, produksi berlebihan.
Saya tidak menentang kapitalisme per se. Saya menolak kapitalisme tanpa kontrol. Pasar tanpa aturan yang membuat warga terjebak dalam aktivitas kriminal demi keuntungan, dicamkan sebagai netral.
Mari kembali ke Kongo—contoh sempurna. Negara ini kaya sumber daya, tapi hancur karena eksploitasi berbasis keuntungan. Kita harus mengalihkan fokus dari keuntungan ke penentuan nasib sendiri. Ini yang sangat jelas dari kasus Palestina. Opini penasihat ICJ adalah momen penting—bukan hanya bagi Palestina, tapi juga Kongo. Opini itu menegaskan hak atas penentuan nasib sendiri sebagai prioritas utama.
Perusahaan yang beroperasi di Kongo harus menghormati hak rakyat Kongo—beragam suku dan kelompoknya. Ini mungkin butuh waktu, tapi jika kita membangun gerakan berbasis HAM, saat ini bisa menjadi titik balik dari keterpurukan hukum. Saya tidak bilang hedge fund harus tutup. Tapi saya katakan: apakah satu-satunya cara kalian menghasilkan uang adalah dengan mata tertutup terhadap kerusakan dan kehancuran—terutama anak-anak yang menjadi sasaran hidup? Gaza adalah mesin penghancur manusia hidup. Bisakah kalian benar-benar tidak melihat itu? Apa kalian akan tetap diam—atau itu akan jadi norma baru?
Saya percaya banyak orang di sektor swasta siap—tak hanya untuk melangkah, tapi menyatakan komitmen etis. Dalam 72 jam terakhir, saya menerima puluhan pesan—email dan DM media sosial—dari orang di sektor keuangan yang berkata, “Saya tidak tahu. Terima kasih. Apa yang bisa saya lakukan?”
Tak ada tongkat sihir, tapi langkah pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan. Selama 30 tahun, pengetahuan itu racun oleh bahasa “keamanan” dan “pembelaan diri.”
Keamanan penting—demikian pula keselamatan—tapi itu tak bisa dipakai alasan pembelaan diri. Harus melalui penentuan nasib sendiri. Ini berlaku bagi Palestina, Israel, maupun warga di Inggris dan Eropa.
Mari kita tanyakan pada diri kita: bagaimana perasaan warga Inggris atau Italia melihat pemerintahnya alokasikan 6–7% anggaran untuk senjata, sementara pemotongan terjadi di bidang sosial, sekolah, pendidikan, dan kesehatan? Kenapa saya harus peduli soal senjata baru? Melawan apa? Perdamaian dibangun dengan cara damai—bukan senjata.
Dalam dua tahun terakhir, diplomasi damai dikubur. Pemerintah tak melayani warga. Mereka menjadikan warga pendukung ekonomi perang, sambil merampas sumber daya penting. Kita jauh lebih terhubung daripada yang disadari.
Namun negara-negara—seperti Inggris—masih mengulang mantra “solusi dua negara.” Bagaimana bisa mereka bicara soal itu saat belum mengakui Palestina? Dan Inggris punya andil—bukan hanya sebagai negara, tapi melalui figur seperti Tony Blair. Saya terkejut—tapi tak heran—melihat Blair, dua dekade kemudian, masih terseret dalam proyek-proyek bermasalah di Timur Tengah. Dia seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kehancuran Irak.
Dan kini dia—melalui institusinya—berperan dalam rencana rekonstruksi Gaza bersama Boston Consulting Group sejak 2024. Tapi rencana itu bukan untuk membangun—melainkan untuk mengusir dan mengganti penduduk. Laporan mereka berbicara soal relokasi “sukarela”—bahwa sampai 25% penduduk Gaza memilih pergi.
Tidak ada yang sukarela. Mereka dipaksa keluar karena bom—tanpa pilihan.
Hanya rakyat Palestina yang berhak menentukan cara membangun kembali Gaza—bukan Israel, AS, Tony Blair, atau negara lain. Mereka yang mengubah genosida menjadi peluang bisnis harus membayar reparasi kepada rakyat Palestina.
Tapi kita masih hidup dalam sistem yang mengobarkan perang demi laba—menghancurkan nyawa, menebar ketidakstabilan global. Penghancuran Irak membuat kita semua lebih rentan.
Dalam pidato saya di Dewan HAM PBB, saya berkata: “Saya dulu kira masalahnya adalah kebodohan—kekurangpahaman tentang sejarah Palestina. Kemudian saya menyadari bahwa masalahnya adalah ideologi—keterikatan politik mendalam antara banyak negara dan elit dengan Israel.”
Misalnya, kanselir Jerman baru-baru ini berkata terkait agresi Israel ke Iran: “Israel melakukan pekerjaan kotor bagi kita semua.”
Ini sangat memprihatinkan. Pertama—siapa ‘kita semua’? Bukan saya, bukan jutaan warga Eropa yang turun ke jalan menuntut penghentian kekerasan. Kedua—apa pekerjaan kotor itu?
Israel mengklaim sedang menjalankan “perang peradaban,” membela nilai Barat dari “barbarisme.” Retorika ini menumbuhkan Islamofobia yang sudah lama ada. Reagan dulu menyebut ekspansi Soviet “barbarisme.” Kini yang dianggap “barbar” adalah Arab dan Muslim.
Ini bukan hanya merugikan warga Palestina—tapi memecah belah masyarakat kita sendiri. Menciptakan retakan berbasis agama. Meningkatkan Islamofobia—dan mengangkat antisemitisme—dengan menjadikan Israel satu-satunya pembela Yahudi. Padahal Israel tidak mewakili semua orang Yahudi; banyak Yahudi secara pribadi menolak klaim itu.
Eropa masih penuh rasisme—banyak orang bersikap rasis secara pasif, akibat indoktrinasi. Mereka diajarkan untuk takut pada orang “lain”—Muslim, imigran—sebagai ancaman keamanan, sosial, dan gaya hidup Eropa.
Padahal keberagaman adalah kekayaan. Untuk meraihnya, kita harus bersatu—sebagai keluarga manusia. Itulah cara melawan doktrin rasis yang dipupuk para oligark yang menyulut permusuhan antar kita.
Saat ini sudah 21 bulan genosida berlangsung. Selama bertahun-tahun kita mengandalkan hukum internasional untuk melindungi yang rentan. Tapi waktu demi waktu, institusi-institusi—pengadilan PBB, ICC, gerakan protes—gagal total.
Sebagai ahli hukum hak asasi, apakah saya masih percaya hukum internasional?
Ya—tapi bukan sebagai tongkat ajaib. Bukan Tuhan. Hukum internasional memberi HAM yang bisa digunakan sebagai perisai dan pedang.
Kita juga harus melihat kegagalannya di banyak bidang—hak pekerja, hak gender, perlindungan atas alasan politik di Barat. Di Inggris, seorang lansia 80 tahun ditangkap. Sementara buronan perang bebas terbang. Dan Inggris masih menjual senjata ke negara yang dituduh melakukan genosida.
Ada hubungan langsung antara runtuhnya norma internasional dan terkikisnya hak-hak kita di dalam negeri. Jika kita hubungkan kehancuran kehidupan Palestina dengan terkikisnya kehormatan dan hak kita sendiri, kita akan memahami lawan kita—dan menemukan kekuatan bersama.
Kita punya standar hukum. Kita punya mekanisme penegakan—meski saat ini gagal. Itu sebabnya kita harus menuntut akuntabilitas dan merebut kembali arena politik untuk agenda baru. Beberapa anggota parlemen dan dewan lokal sudah berusaha—meski melawan kebijakan pemerintah.
Litigasi strategis juga membantu. Kadang kita menang meski secara hukum kalah—seperti kasus F-35 melawan pemerintah Inggris oleh Al-Haq, dll. Putusan pengadilan yang konservatif justru menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut—dan itulah tujuan laporan saya: membuka mata, bahkan hakim, terhadap sistem ini.
Akhirnya, saya mengatakan: Palestina adalah cermin dunia.
Cermin itu menunjukkan kita berada di persimpangan sejarah. Gelombang global pun muncul—bersatu mencari tujuan akhir: akhir genosida, akhir pendudukan permanen, akhir apartheid.
Bagaimana menuju ke sana? Dengan strategi holistik. Setiap orang—jurnalis, pensiunan, pelajar, intelektual, akademisi—punya peran. Lakukan bagian Anda.
Inilah saat yang tepat menciptakan dunia yang lebih baik—tempat genosida terakhir terjadi, dan kejahatan terakhir yang dilakukan Israel diwakili rakyatnya, tanpa melibatkan rakyat Yahudi lainnya.
Namun kita harus bersatu melawan ketidakadilan. Jika tidak, ketidakadilan akan jadi norma.
Momen ini menuntut solidaritas internasional—dan aksi nyata. Tidak pernah terlambat bagi pegawai negeri, hakim, pejabat, banker, universitas—untuk sadar.
Jika bukan sekarang, kapan?
Jika bukan Anda, siapa?
Jika tidak sekarang—keadilan akan datang juga, entah bagaimana.
Demikianlah Francesca Albanese, suara utama yang menggertarkan dunia. Mewakili milyaran penduduk bumi. Dialah kini sosok yang menjadi tumpuan harapan menegakkan Hukum Internasional. Harapan keadilan dunia dan menghapus segala penjajahan. Harapan untuk membawa pelaku kejahatan perang ke pengadilan.
Bagaimanapun seperti kata Angela Davis, “Palestine is the moral litmus test of the world.” Kita harus memastikan dunia memegang teguh nilai-nilai moralitas, keadilan dan kemanusiaan. Kita harus menunjukkan keteguhan mendengar suara hati nurani. Dan menyuarakannya dengan lantang.
***
Malinau, 25 Juli 2025
1 https://theintercept.com/2024/06/11/apple-donations-idf-israel-gaza-illegal-settlements/
2 Baca misalnya buku oleh Matt Kennard, The Racket: A Rogue Reporter vs the American Empire (London: Zed Books, 2015), p. iii. Kutipan awal buku ini: Psikolog evolusioner Harvard, Steven Pinker, pernah mengatakan kepada saya bahwa kekuasaan itu sendiri mendistorsi pemahaman manusia tentang moralitas dan keadilan:
“Dominasi, keadilan, dan kebersamaan adalah tiga cara berpikir yang sangat berbeda tentang hubungan sosial. Seseorang yang berkuasa cenderung tidak memandang hubungannya dengan orang lain—baik bawahan maupun pihak luar—dalam kerangka keadilan,” ujarnya. Elit Amerika, termasuk para pengusaha besar yang berkuasa dan pemerintah sekutu (terlepas dari partai politik), termotivasi oleh dominasi, bukan keadilan. Orang-orang yang berkuasa menyadari hal ini—yang dibohongi adalah rakyatnya. Tentu, kebutuhan untuk menembus gelembung propaganda bukanlah hal baru. Setiap kaisar, orang kaya, dan negara adidaya sejak zaman dahulu dengan senang hati memelihara mitos tentang tindakan mereka agar bisa memanfaatkan niat baik rakyat untuk menjalankan agenda kriminal mereka sendiri. Sejarawan Cornelius Tacitus mengungkapkannya dengan sangat tepat pada puncak kekuasaan Romawi: “Orang Romawi menciptakan padang gurun,” tulisnya, “dan menyebutnya perdamaian.”
Mitos-mitos yang disuguhkan kepada orang Amerika sejak kecil—dan indoktrinasi ideologis ini melampaui batas-batas AS—masih menggambarkan AS sebagai kekuatan yang istimewa dalam dunia politik kekuasaan. Tidak seperti semua negara adidaya sebelumnya, Amerika Serikat dianggap sebagai kekuatan “moral”, yang digerakkan oleh prinsip dan nilai-nilai, bukan dominasi dan keserakahan.
Kita diberi tahu bahwa Amerika itu “luar biasa”—bukan luar biasa dalam kekerasan (yang itulah kenyataannya), tetapi luar biasa karena memiliki “tujuan yang lebih luhur”; ia adalah “kota yang bercahaya di atas bukit”.
Sekilas menjelajahi dunia dengan mata terbuka akan segera membuat Anda sadar bahwa ini bertolak belakang dengan kebenaran. Namun, menjaga mata tetap terbuka selalu lebih sulit daripada mencari penghiburan dalam superioritas moral ilusif sendiri dan keburukan musuh. Maka, mitos pun mengakar.
Ulangi setelah saya:
Ketika AS melakukannya,
Teror disebut Mencari Perdamaian;
Dominasi disebut Kemitraan;
Ketakutan disebut Stabilitas.
Mudah, bukan?
3 Edward W. Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage Books, 1994). “Every empire, however, tells itself and the world that it is unlike all other empires, that its mission is not to plunder and control but to educate and liberate.”
4 https://youtu.be/UXITQ-Zjnps?si=SOmrfwE7Z0XmDbGu
5 Jenga Tower atau Menara Jenga adalah menara balok kayu yang dibangun secara berlapis dalam permainan Jenga.Cara Main: Pemain secara bergiliran menarik satu balok dari lapisan mana pun (kecuali lapisan paling atas) dan menaruhnya di puncak menara. Tujuan: Menjaga menara tetap stabil tanpa roboh. Pemain yang kalah jika menara roboh saat gilirannya.