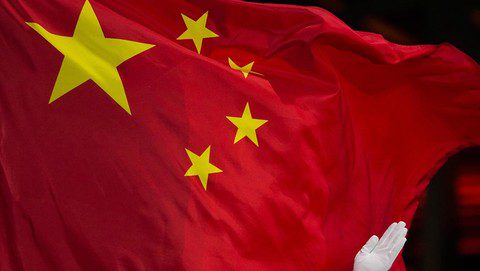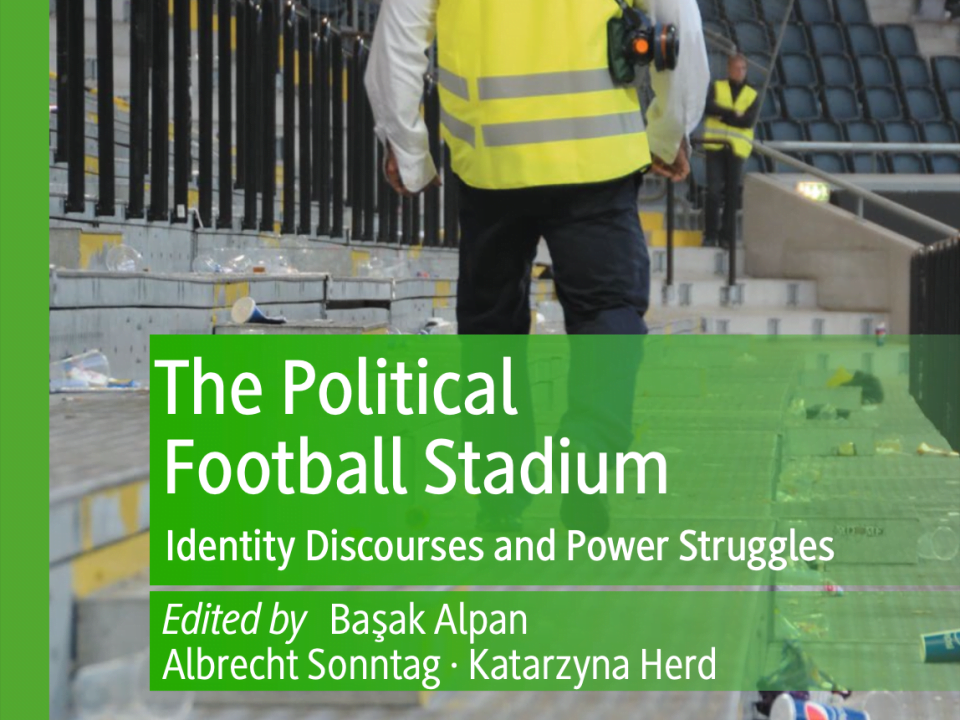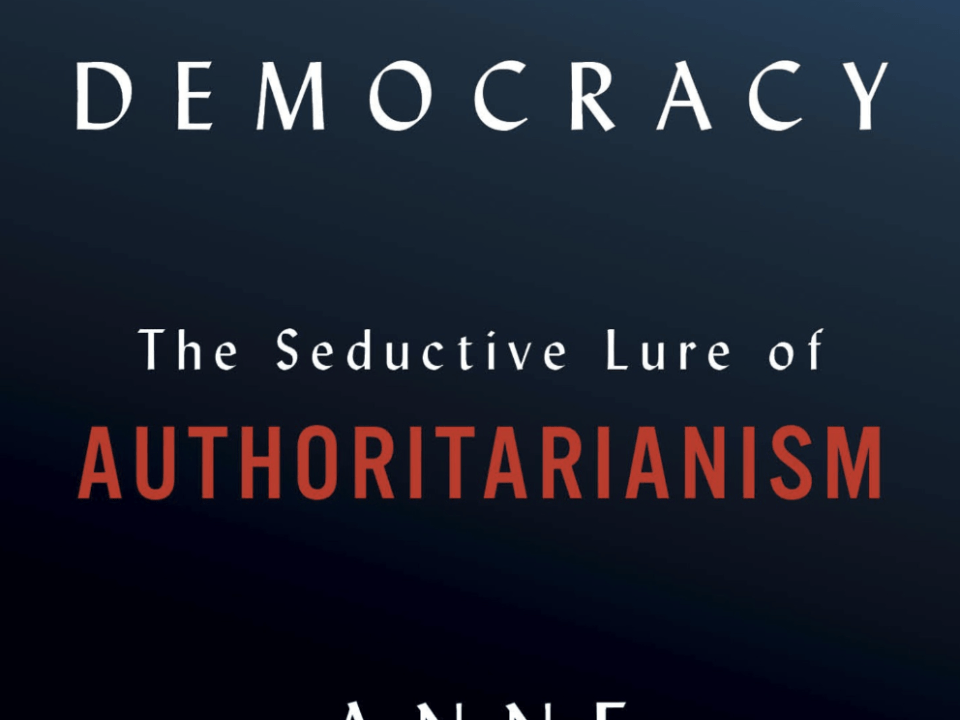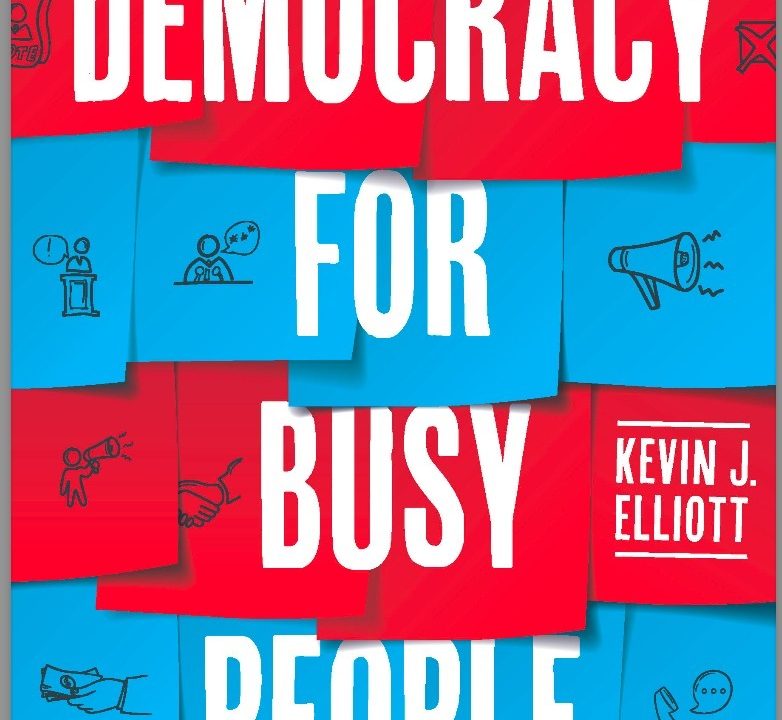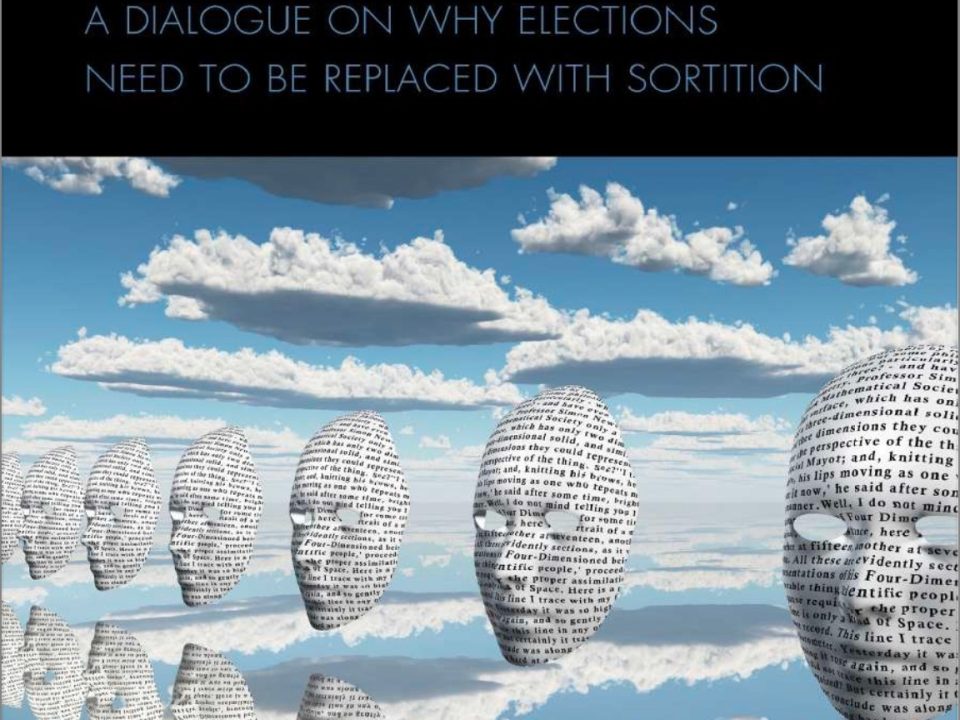Bagaimana Cina Menguasai Dunia?
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor-Cirebon-Pekanbaru, 31.12.2019
#BincangBuku #35
“If we shrink from the hard contests where men must win at hazard of their lives and at the risk of all they hold dear, then the bolder and stronger peoples will pass us by and will win for themselves the domination of the world.”
—THEODORE ROOSEVELT “The Strenuous Life,” 1899.
Kutipan dari Dambisa Moyo. “Winner Take All: China’s Race for Resources and What It Means for the World.”
“Alas, journey upon journey
upon journey, we’re separated
with thousands and thousands
of miles between us, each stranded
at the other end of the world.
The roads so difficult and long,
when can we possibly see each other again? The horse
from the north still yearns
for the northern wind, the bird
from the south clings, like
before, to the southern branch …
—From “Journey Upon Journey,” Author Unknown. Han Dynasty China. Translated By Qiu Xiaolong.”
Kutipan dari: French, Howard W. “China’s Second Continent: How a Million Migrants Are Building a New Empire in Africa.”
Pengantar:
Beberapa waktu yang lalu banyak kehebohan berkaitan dengan maraknya tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia. Mereka ada yang berada di proyek-proyek industri di pelosok Sulawesi, Banten dan propinsi-propinsi lainnya. Ada juga yang nyempil di pojok-pojok pelosok Kabupaten Bogor, Cianjur; beternak dan berkebun. Kita tidak tahu berapa jumlah tepatnya. Pemerintah mengeluarkan data resmi. Publik tidak mudah percaya. Kedatangan mereka, bersama proyek-proyek investasi Cina dan juga entah datang dengan cara dan kepentingan yang berbeda, serta merta menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Seolah-olah Cina bak monster yang siap mengunyah sumberdaya alam nusantara dan mencampakkan rakyat Indonesia dari mendapatkan akses kesempatan kerja dan berusaha.
BincangBuku #35 ini mengupas enam buku sekaligus yang berkaitan dengan Cina dari beberapa aspek, terutama berkaitan dengan potensi penguasaan suatu wilayah.
- Howard W. French: China’s Second Continent, How a Million Migrants Are Building A New Empire in Africa (Alfred A. Knopf, 2014)
- Dambisa Moyo: Winner Take All, China’s Race for Resources and What It Means for the World (Basic Books, 2012)
- Clive Hamilton: Silent Invasion, China’s Influence in Australia (Hardie Grant Books, 2018)
- Robert Spalding: Stealth War, How China Took Over While America’s Elite Slept (Penguin Random House, 2019)
- Martin Jacques: When China Rules the World, The End of Western World and the Birth of the New Global Order (The Penguin Press, 2009)
- Olayiwola Abegunrin dan Charity Manyeruke: China’s Power in Africa: A New Global Order (Palgrave Macmillan, 2020)
Suatu saat seorang jurnalis Amerika menelusuri pojok-pojok Afrika. “Di Afrika akhir-akhir ini, saya sangat terpana oleh kehadiran migran Cina di hampir semua tempat yang saya kunjungi: berbicara panjang lebar dengan pedagang kaki lima di Dar es Salaam, Tanzania, peternak unggas dan pedagang di Lusaka, Zambia, dan para penambang tembaga liar di Republik Demokratik Kongo, dan mengenal mereka dengan baik, telah begitu kuat membentuk kesan yang berbeda tentang Tiongkok,” demikian tulis, Howard W. French, Sang Wartawan dalam bukunya “China’s Second Continent: How a Million Migrants Are Building a New Empire in Africa (2014).”
Fenomena tsunami migrasi warga Cina ke belahan lain dunia bukan hanya terjadi di Indonesia. Terjadi di Australia, Srilanka, Papua Nugini, dan hampir di semua negara Afrika. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak akhir Perang Dingin, kehadiran Cina di Afrika telah berkembang pesat. Hubungan yang makin intim China dengan Afrika makin erat saat iklim bisnis meningkat di seluruh Afrika dan minat terhadap Afrika sebagai pasar telah tumbuh sangat pesat.
Bagi Cina, Benua Afrika bukan hal yang baru.
Olayiwola Abegunrin dan Charity Manyeruke dalam buku terbarunya “China’s Power in Africa: A New Global Order (2020) mencatat bahwa penyebutan pertama Afrika dalam sumber-sumber Cina adalah dokumen Yu-yang-tsa-tsu oleh Tuan Ch’eng-shih (meninggal pada tahun 863) yang menulis tentang tanah Po-pa-li, merujuk ke Somalia zaman modern. Zhu Siben dari Dinasti Yuan adalah tokoh Cina pertama yang diketahui melakukan pelayaran ke Samudra Atlantik. Sedangkan Laksamana Dinasti Ming Zheng He dan armadanya yang terdiri dari lebih 300 kapal melakukan tujuh pelayaran terpisah ke daerah di sekitar Samudra Hindia dan mendarat di pantai Afrika Timur (halaman 1).
Menurut Abegunrin dan Manyeruke meskipun jejak sejarahnya cukup lama tetapi hubungan Tiongkok-Afrika modern dimulai dengan kunjungan pertama Perdana Menteri Zhou Enlai di Afrika, yang dikenal sebagai Zhuo’s African Safari. Ini adalah kunjungan serial kenegaraan ke sepuluh negara Afrika merdeka. Dilakukan antara Desember 1963 dan Februari 1964. Tujuan safari di Afrika adalah meningkatkan profil Cina di benua itu yang pada saat itu pula terjadi kontestasi terbuka dengan Uni Soviet atas arah gerakan Komunis global.
Kunjungan ini banyak merupakan perjuangan ideologis, tidak seperti penekanan saat ini pada pembangunan ekonomi dan investasi di Afrika. Penekanan ideologis ada pada kesepakatan untuk menentang imperialisme, kolonialisme, rasisme, dan ekspansionisme, menjaga perdamaian dunia, dan memperkuat persatuan di antara Tiongkok dan negara-negara Afrika.
Kebijakan Tiongkok terhadap Afrika saat ini adalah bagian dari Kebijakan Pintu Terbuka yang dirancang oleh reformasi Deng Xiaoping. Secara virtual mencakup semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Tiongkok mulai dari 1978. Memulihkan negara ke stabilitas domestik dan pertumbuhan ekonomi setelah ekses Revolusi Kebudayaan, dan mengurangi ketimpangan. Deng Xiaoping memandu Tiongkok keluar dari isolasi selama puluhan tahun dan stagnasi ekonomi.
Meski demikian seperti dirasakan oleh Howard W. French, ketika kita berpikir tentang hubungan China dengan Afrika, umumnya yang terbayangkan adalah satu hal: memastikan akses ke sumberdaya alam yang melimpah, di mana Afrika adalah gudang terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara penghasil tembaga terbesar, Zambia, negara yang terkurung daratan di Afrika Selatan, tak diragukan lagi merupakan bagian yang sangat besar dari kisah soal sumberdaya alam itu. Saat ini, demikian French, Cina sendiri menyumbang 40 persen dari permintaan tembaga global. Tetapi ada motif yang lebih jauh ke depan, yang sering diabaikan dalam banyak spekulasi tentang ambisi Cina di Afrika: untuk mengolah, atau mungkin bahkan menciptakan, pasar masa depan untuk industri berorientasi ekspor Cina, pasar yang suatu hari nanti dapat menggantikan pasar saat ini yang makin melemah karena proses penuaan konsumen dan ekonomi yang dililit utang di Barat dan Jepang (halaman 83). Suatu pandangan yang sangat kapitalistik dari sebuah negara komunis. Dan bisa dipastikan inilah juga motif masa depan dari banyak investasi yang dibenamkan ke Indonesia. Pasar domestik 270 juta mulut yang menganga siap disuapi dengan aneka produk Made in China.
Karena itu ambisi yang luar biasa Cina menguasai Benua Afrika bak tsunami dengan ombak putih bergulung tiada henti datang mengisi seluruh pelosok Afrika. Baca juga soal ini, misalnya, yang dipaparkan oleh Martin Jacques: When China Rules the World, The End of Western World and the Birth of the New Global Order (2009).
Menurut catatan French, Zambia berada di barisan depan dari pergerakan manusia yang sangat besar ini (halaman 84). Orang Cina telah datang ke sini dalam jumlah besar sejak tahun 1990-an, lebih awal daripada hampir di semua negara lain di benua itu. Sekarang mereka berjumlah 100.000 atau lebih dan menjadikan mereka salah satu komunitas migran terbesar Cina di Afrika. Hanya waktu yang akan membuktikan, tentu saja, apakah pertaruhan Cina pada masa depan benua ini akan membuahkan hasil. Faktanya, menurut catatan jurnalistik French ini, adalah bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa kekayaan sejumlah besar orang Afrika membaik secara dramatis dan kemungkinan akan terus berlanjut selama satu atau dua dekade mendatang, bahkan lebih cepat.
Keberadaan Cina tidak hanya berhenti di situ. Senegal, seperti Zambia, menempati tempat tertentu dalam kisah migrasi China ke Afrika. Jika Zambia berada jauh di depan dalam hal emigrasi Cina untuk mencari kekayaan mereka di bidang pertambangan dan pertanian, Senegal, di Afrika Barat, telah menjadi tujuan perintis dalam perdagangan kecil dan komersial, sebuah sektor yang akan terbukti sangat populer di kalangan orang Cina pendatang baru, dan memang adalah sektor yang paling populer.
Penguasaan masif sumber-sumber bahan tambang oleh Cina tidak hanya berhenti di Afrika, tentu saja. Dambisa Moyo: Winner Take All, China’s Race for Resources and What It Means for the World (2012) mengurai dan menganalisis begitu dalam sepak terjang Cina dalam menguasai tambang dimanapun di seluruh dunia dan mengamankan kepentingannya.
Dalam buku yang terdiri dari Dua Bagian dan 10 Bab ini Moyo menuliskan hal ihwal penguasan aneka komoditi tambang dari aspek sumberdaya, geopolitik, ekonomi, lingkungan hingga aspek-aspek kotor yang melibatkan korupsi. Segala cara akan dilakukan oleh Cina untuk penguasaan sumber-sumber vital tambang tersebut.
Pada musim panas 2007, sebuah perusahaan Cina membeli sebuah gunung di Peru. Ya sebuah gunung. Lebih khusus lagi, ia membeli hak mineral untuk menambang sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pada ketinggian lima belas ribu kaki (empat puluh enam ratus meter), Gunung Toromocho adalah daratan yang mengesankan — lebih dari setengah ketinggian Gunung Everest. Toromocho mengandung dua miliar ton tembaga, salah satu deposit tembaga tunggal terbesar di dunia. Dengan bayaran US$ 3 miliar, hak penguasaan Gunung Toromocho ditransfer dari rakyat Peru ke tangan orang Cina.
Menurut catatan Moyo dalam buku setebal 375 halaman ini kampanye komoditas Cina sangat menakjubkan. Hanya dalam lebih dari satu dekade, dari posisi relatif Cina yang tidak penting telah meningkat ke posisi terdepan dalam penjaminan banyak transaksi terkait sumber daya di seluruh dunia. Chinalco China, perusahaan yang membeli hak untuk mengeksploitasi gunung Peru itu, juga menghabiskan hampir US$ 13 miliar pada 2008 untuk saham di sektor aluminium Australia (halaman 13).
Pada Juni 2009 Sinopec — perusahaan petrokimia Tiongkok terkemuka — membeli Addax Petroleum, yang memiliki aset cukup besar di Irak dan Nigeria, senilai US$ 7,2 miliar. “Sinopec juga membeli 40 persen saham di Rep-sol Brasil, sebuah perusahaan energi Spanyol, senilai US$ 7 miliar pada Oktober 2010 dan kepemilikan sebagian di sebuah perusahaan minyak patungan dengan Rosneft Rusia (sebuah perusahaan minyak dan gas terkemuka) untuk US$ 3,5 miliar pada Juni 2006.
Secara kolektif, input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa ini dikenal sebagai komoditas, dan komoditas menyerap setiap aspek kehidupan sehari-hari dunia modern: energi yang memberi tenaga pada mobil, truk, dan jaringan listrik; air untuk keberlangsungan semua bentuk kehidupan; tanah subur yang menghasilkan biji-bijian dan bahan makanan lainnya; dan daftar panjang mineral yang digunakan dalam segala hal mulai dari telepon seluler hingga layar televisi dan sebagai input untuk semua jenis mesin.
Sayangnya, menurut analisis Moyo yang juga menulis buku “How the West Was Lost,” tren pertumbuhan cepat dan ekstensif ini hanya akan berlanjut hingga tahun 2050, ketika prakiraan populasi global menyentuh angka lebih dari sembilan miliar. Berdasarkan analisis yang disajikan dalam buku Moyo ini, bumi sama sekali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung populasi sejumlah ini, terutama tidak pada standar hidup di mana ratusan juta orang telah terbiasa. Berita baiknya adalah, ketika merujuk pada konteks sejarah, ledakan berkelanjutan dalam populasi dunia dapat dipandang sebagai episode unik — yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dan begitu tren saat ini berjalan dengan sendirinya, sangat kecil kemungkinan bahwa peningkatan populasi seperti itu, dalam hal kecepatan dan besarnya, akan terjadi lagi. Perkiraan terbaik PBB menyebutkan bahwa populasi dunia akan mulai menurun pada tahun 2075 begitu menyentuh 9,2 miliar.
Dengan kata lain, demikian pemaparan Moyo (halaman 327), populasi dunia tidak akan tumbuh ad infinitum—tanpa batas—, dan ada kemungkinan tekanan permintaan komoditas. Cina sendiri berisiko menjadi tua sebelum menjadi kaya, dengan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa setengah dari populasi Cina akan berusia lima puluh tahun atau lebih pada tahun 2050. Hal ini dapat mengurangi permintaan komoditas, karena yang biasanya memicu konsumsi adalah kaum muda (bukan orang tua). Inilah masalah yang tak terhindarkan, meskipun: perubahan komposisi yang dramatis seperti itu belum akan terjadi untuk beberapa waktu.
Bagi Moyo, fakta ini berarti bahwa kita menemukan diri kita di bumi pada waktu yang unik dengan tantangan luar biasa dalam mengelola dan menavigasi terpaan angin kencang kekurangan komoditas yang dihadapi dunia selama dua dekade mendatang. Saat ini kita tidak siap untuk menghadapi kemungkinan ini. “Namun tantangan yang kita hadapi melampaui standar kehidupan kita untuk kelangsungan hidup planet ini seperti yang kita kenal. Pertarungan ini adalah tentang hidup atau mati,” Maka gemuruh jejaring Cina di Afrika adalah juga bagian dari ekspansi dimanapun di muka bumi ini.
Toko-toko Cina telah menjadi pemandangan biasa di jalan-jalan kota besar dan kecil di seluruh Afrika, tetapi keberadaan mereka bisa menipu; itu hanya kedok betapa pesat pembangunan dicapai, dan betapa cepat menyebar. Dakar, Ibukota Senegal, agak berbeda. Kehadiran pedagang kecil dari Cina sudah mulai dirasakan sejak akhir 1990-an, tahun-tahun mendatang sebagian besar kota-kota besar Afrika lainnya. Dan seperti di Zambia, kenaikan tajam dan tiba-tiba dalam jumlah pendatang baru ini telah memprovokasi reaksi cepat dari penduduk setempat.
Senegal selalu membuat salah satu budaya pedagang paling bersemangat Afrika. Para pedagang yang mengenakan boubou di negara itu telah lama menjajah sudut-sudut jalan di New York dan banyak kota di Eropa, tempat mereka menjual pakaian, gadget, dan berbagai macam pernak pernik wisata. Tapi di tahun 2004, para pedagang Dakar ini bangkit tiba-tiba dan mulai khawatir bahwa mereka pada gilirannya dijajah oleh Cina yang tampaknya mengambil alih sektor ritel. Protes besar terjadi di Dakar, pedagang Senegal menuntut tindakan pemerintah untuk melindungi mereka dari pendatang baru Cina (Halaman 132).”
Di Senegal, Namibia, Malawi, dan Tanzania, protes oleh pedagang lokal baru-baru ini pecah karena masuknya sejumlah besar pedagang Cina kelas bawah. Di daerah penghasil emas di Ghana Selatan, penduduk setempat mengeluh keras tentang kedatangan sejumlah besar penambang liar Cina, yang mengambil alih tanah yang kaya dan merusak lingkungan, menebangi hutan dan menuangkan merkuri ke tanah dan sungai. Dan di Zambia, di mana kedatangan Cina baru-baru ini telah merasuk di hampir setiap sektor ekonomi yang menguntungkan, termasuk pedagang unggas yang bersaing ketat dengan penduduk setempat di pasar bergaya Afrika. Kehadiran para imigran baru ini telah menjadi masalah yang diperdebatkan di pemilihan umum nasional.
Seperti yang dikatakan Ed Brown, seorang eksekutif senior Ghana di salah satu lembaga think tank independen terkemuka di negaranya seperti yang dikutip oleh French bahwa hubungan Cina-Afrika akan menentukan masa depan Afrika untuk lima puluh tahun ke depan. Pertanyaan besarnya adalah apakah negara-negara Afrika cukup dinamis untuk mampu mengambil manfaatnya, atau apakah mereka akhirnya akan menjadi budak orang lain lagi. Sebuah pernyataan yang penting untuk dipikirkan secara mendalam tidak saja bagi Afrika tetapi bagi negara-negara lain yang sudah dibanjiri oleh jaring-jaring tentakel monster oktopus.
Cina tentu tidak saja ingin menguasai Benua Afrika. Ambisi utama Tiongkok adalah menjadi negara penguasa tunggal dunia pada 2050. Benua Australia juga menjadi sasaran empuknya.
Pada 24 April 2008, ketika obor olimpiade tiba dan diarak di Canberra sebagai persiapan menuju Beijing ada demonstrasi Pro-Tibet digelar. Menuntut pembebasan Tibet dari penjajahan Cina. Tidak lama berselang puluhan ribu mahasiswa Cina menggeruduk demo Pro-Tibet. Karuan saja mereka kocar kacir. Yang menjadi pertanyaan darimana para mahasiswa itu datang? Siapa yang mengorganisasikan? Mengapa mereka menghalau demonstran Pro-Tibet yang sebagian juga adalah warga Australia? Itulah sejumput pertanyaan yang menggelayuti pikiran Clive Hamilton dalam bukunya: “Silent Invasion: China’s influence in Australia (2018). “Delapan tahun kemudian, pada Agustus 2016, badai politik melanda Senator Sam Dastyari (yang setahun kemudian keluar dari kursi parlemen). Dalam beberapa minggu kemudian baru diketahui adanya segelintir pengusaha Cina dan Cina-Australia yang sangat kaya telah menjadi donor terbesar bagi partai-partai politik utama di Australia. Mereka telah membeli banyak pengaruh; politisi berselingkuh di tempat tidur bersama mereka.
Demokrasi China dan Australia berbenturan. Buku Hamilton yang berjumlah 903 halaman ini adalah sebuah investigasi atas hubungan antara Cina dan Australia. Infiltrasi penting Cina di Australia dimulai pada Agustus 2004. Sekretaris Partai Komunis Hu Jintao mengatakan pada sebuah pertemuan dengan para tokoh Cina Australia di Beijing bahwa Komite Pusat yang sangat berkuasa di partai telah memutuskan bahwa Australia harus dimasukkan ke dalam ‘periferal’ China. Menurut Hamilton China selalu mencurahkan perhatian khusus kepada negara-negara yang memiliki perbatasan darat dengannya—negara periferi. Tetapi kini Australia tidak lagi dianggap jauh karena ia bagian periferi Cina. Australia akan dijadikan sebagai basis pasokan yang dapat diandalkan dan stabil untuk pertumbuhan ekonomi China yang berkelanjutan selama dua puluh tahun ke depan. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mendorong pecahnya aliansi Amerika-Australia. Mereka yang hadir diberi tugas untuk mengetahui bagaimana China dapat secara paling efektif mencapai apa yang disebut ‘pengaruh komprehensif’ terhadap Australia secara ekonomi, politik, budaya, dalam segala hal.
Hamilton dalam bukunya ini juga menguraikan pandangan berbagai ‘teman China’ yang mendorong debat publik soal Cina di Australia. Ia mencatat: betapa sedikit nilai demokrasi yang mereka miliki. Banyak tokoh berpengaruh di antara para elit politik, birokrasi, media, dan akademis tampaknya percaya bahwa demokrasi adalah sebuah kemewahan, dan sering kali menjadi gangguan. Atau mereka melihat demokrasi sebagai sandiwara saja dan bahwa ekonomilah (bukan demokrasi) yang benar-benar penting (seperti halnya di China). Dan ketika warga negara Australia menuntut agar pemerintah menghormati hak asasi manusia dan mengikuti aturan hukum, mereka merasa seperti bunuh diri. Hugh White, Profesor Strategic Studies at the Strategic and Defence Studies Centre of the Australian National University di Canberra, Australia, menasihati, ‘Tidak perlu lagi memberi kuliah tentang pembangkangan, Tibet, atau kebebasan beragama di Cina, nasihat itu diberikan bukan karena menceramahi China tentang hak-hak itu tidak efektif, tetapi karena hak dan kebebasan itu merupakan hal yang sepele dalam permainan strategis besar sejarah dunia. Ketika Geoff Raby mengeluh bahwa Australia mengadopsi ‘pendekatan idealis’ ke China, terlalu fokus pada nilai-nilai dan hak asasi manusia, dia mengatakan kepada warga Australia bahwa ‘pendekatan pragmatis yang bertujuan meningkatkan ikatan ekonomi’ adalah hal yang sangat penting. (halaman 687). Demikianlah para tokoh itu sangat pragmatis dengan kondisi kepentingan ekonomi. Bandingkan fenomena ini dengan kaum elit penguasa di Indonesia: politisi, rezim, pengusaha, LSM, think tanks, dan sejumlah antek-antek lainnya. Adakah bedanya?
Buku Hamilton yang sangat ekstensif dalam menguliti merasuknya darah Cina ke dalam jantung dan sendi-sendi politik ekonomi Australia ini barangkali juga seperti apa yang dituliskan dengan garang oleh Robert Spalding pensiunan Brigadir Jendral the U.S. Air Force setelah 25 tahun bertugas. Judulnya: Stealth War, How China Took Over While America’s Elite Slept (2019). Spalding mengingatkan pemerintah Amerika dan seluruh aliansinya, politisi, lembaga keuangan dan kelompok kepentingan untuk waspada pada perang siluman yang sedang dijalankan dengan cantik oleh China.
Dalam pengamatan Spalding yang adalah mantan China strategist for the chairman of the Joint Chiefs of Staff and the Joint Staff at the Pentagon, dan juga sebagai senior Atase Pertahanan untuk Cina, dan dia memperoleh doktorat bidang ekonomi dan matematik dari the University of Missouri dan piawai berbahasa Mandarin, selama empat puluh tahun terakhir, Partai Komunis Tiongkok (PKC) telah memainkan permainan yang indah. Canggih namun sederhana. Ini adalah kompetisi untuk mendapatkan kendali dan pengaruh di seluruh planet ini — dan untuk mencapai hasil itu tanpa menggunakan keterlibatan militer. Terbang diam-diam di bawah radar, PKC telah memperoleh teknologi tanpa membayar sepeser pun untuk mengembangkannya, dengan hati-hati mengambil kendali bisnis pelayaran dunia, menyusup ke perusahaan-perusahaan Amerika dan laboratorium sains, dan menggunakan dolar investor Amerika untuk membiaya pabriknya sendiri dan perusahaan — dan kemudian, sambil mengolok-olok bersikeras uang yang dihasilkan itu harus berada di Cina.
Perang antara negara-bangsa di abad ke-21 nampak jauh berbeda dari perang di abad ke-19 dan ke-20. Alih-alih bom dan peluru, ini tentang satu dan nol dan dolar dan sen: ekonomi, keuangan, informasi data, manufaktur, infrastruktur, dan komunikasi. Mengendalikan itu semua hari ini, dan Anda dapat memenangkan perang tanpa melepaskan tembakan. “Ini strategi yang sederhana dan logis,” tulis Spalding mungkin dengan begitu geram.
Strategi PKC, bagaimanapun, adalah bertarung dengan cara lain, memanfaatkan berbagai taktik. Ini mengadvokasi dan mensponsori terus menerus pada pencurian, pemaksaan, sabotase ekonomi, dan monopolisasi infrastruktur di tingkat global — semua untuk meningkatkan lingkup pengaruh China. Dimana mana. Tentu ini adalah pandangan seorang Spalding yang melihat kecenderungan Cina dan mengamatinya bertahun-tahun.
“Saya ingin mengingatkan dunia akan perang siluman Tiongkok dan strateginya untuk mendominasi planet ini dengan berfokus pada enam bidang pengaruh: ekonomi, militer, diplomasi global, teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. Cina hampir mencapai tujuannya untuk mempengaruhi para politisi dan perusahaan Amerika Serikat. Jika ini terjadi, kebebasan mendasar yang kita anggap remeh — kemampuan untuk mengkritik politisi atau kebijakan, menerbitkan pernyataan politik, melaporkan penyalahgunaan atau ketidakefisienan pemerintah, menyanyikan lirik yang Anda inginkan, mempelajari secara harfiah setiap subjek apapun yang ada di bawah matahari, untuk mengunjungi situs web mana pun, tidak peduli ideologi apa yang didukung — akan diserang,” pungkas Spalding.
Kita tidak tahu kepastian 10, 30, 50 tahun mendatang. Tetapi ilmu pengetahuan mampu memperkirakan apa yang akan terjadi. Dengan mencermati, menganalisis beragam faktor-faktor dan kecenderungan perkembangan Barat dan Cina. Inilah yang dilakukan Jacques (2009) dalam bukunya. Buku sejumlah 993 halaman ini menggunaan sumber-sumber informasi yang amat kaya yang terangkum dalam 49 halaman bibliography. Jacques mengelaborasi bukunya dari sejarah Barat, kebangkitan dan gerbang kebangkrutannya. Pada Bagian 2: The Age of China, Jacques memaparkan juga dari aspek sejarah dan kebangkitan sebagai sebagai negara adidaya ekonomi. “There are, thus, already strong indications that China’s rise will be hastened by the global crisis,” tulis Jacques menutup bukunya.
Target Cina menjadi negara superpower baru mengalahkan Amerikat Serikat pada 2049 nampak tak terelakkan. The Hundred-Year Marathon—sebuah perjalanan panjang Cina yang dimulai sejak Mao Zedong, untuk membalas satu abad dendam kesumat yang mendorong Cina meneguhkan cita-citanya untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia pada bidang ekonomi, militer, dan politik pada tahun 2049 (ini adalah tonggak ulang tahun yang ke seratus tahun Revolusi Komunis).
Sekedar mengingatkan Goldman Sachs memprediksi pada 2050 Cina bercokol sebagai negara dengan ekonomi terbesar mengalahkan Amerika (pada 2025 posisi Amerika masih di puncak dan diikuti Cina posisi kedua). Sementara itu PriceWaterhouseCooper juga menempatkan Cina sebagai top scorer negara dengan ekonomi terkuat. Indonesia masuk pada posisi ke enam. Revolusi Kebudayaan Cina tahun 1960-an dan 1970-an hampir menghancurkan ekonomi. Reformasi pemimpin Deng Xiaoping menyelamatkan Cina dan membuka Cina bagi ekonomi pasar sosialis dan membuatnya mulia untuk menjadi kaya. Seperti pepatah Cina: you leap forward if there’s an empty space. Empty spaces are there to be filled. “Alas, journey upon journey/upon journey, we’re separated/with thousands and thousands/of miles between us, each stranded/at the other end of the world….
Enam buku itu menegaskan satu hal: Cina sudah ada di dalam rumah kita. Mereka mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Mungkin mendesak yang sudah penuh agar mendapatkan ruang untuknya. Mereka bekerja. Mereka menguasai. Maraknya investasi Cina, besarnya utang yang diberikan, dan Natuna adalah bagian dari The Hundred-Year Marathon menuju negara adidaya, ketika Cina menguasai dunia. Perlukah diributkan? Jika kekuasaan itu menghisap, jika kekuasaan itu menjajah, jika kekuasaan itu menginjak kedaulatan, jika kekuasaan itu membungkam hak-hak asazi manusia, maka bukan saja harus diributkan. Tetapi dilawan. Dan kata Roosevelt:”…the bolder and stronger peoples will pass us by and will win for themselves the domination of the world.”